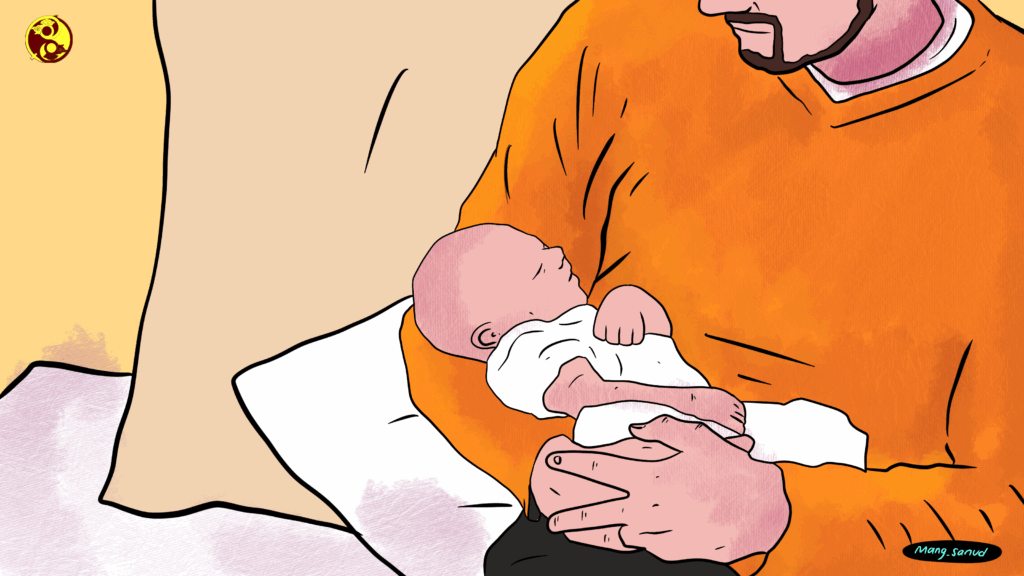Mubadalah.id – Beberapa waktu lalu, jagat media sosial ramai oleh berita tentang seorang pria yang memiliki 11 orang anak, tidak bekerja, dan menolak vasektomi. Sementara itu, istri dan anak-anaknya justru harus turun tangan mencari nafkah demi menghidupi keluarga. Suami pengangguran itu memilih untuk berleha-leha, tak merasa bersalah. Bahkan mengklaim bahwa anak banyak sama dengan banyak rezeki.
Pernyataan ini tentu mengundang respons beragam. Ada yang menyoroti sisi kemiskinan struktural, ada pula yang menegaskan bahwa ini bukan hanya soal ekonomi. Tapi soal tanggung jawab dan keadilan gender dalam keluarga. Apakah pantas seorang kepala keluarga justru tidak mengambil peran aktif dalam menghidupi dan mendidik anak-anaknya?
Peran Suami dalam Islam
Sementara itu jika kita tarik ke dalam perspektif Islam, khususnya dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir peran suami sebagai qawwam dalam QS. An-Nisa ayat 34 tidak bisa kita maknai secara otoritatif atau dominatif. Justru, tafsir ini menawarkan pemahaman baru bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah bentuk tanggung jawab yang bisa dipertukarkan, tergantung siapa yang lebih mampu—bukan siapa yang lebih “laki-laki”.
Jika realitanya istri bekerja keras demi ekonomi keluarga, sementara suami pengangguran berleha-leha dan bahkan menolak program KB, maka bukan hanya beban rumah tangga yang timpang, tapi juga melanggar nilai-nilai keadilan Islam.
Menurut Faqihuddin, kata qawwam memiliki arti “penanggung jawab” yang penuh kasih, bukan sebagai pemimpin yang merasa lebih tinggi atau berhak mengatur sesuka hati. Qiwamah dalam hal ini adalah tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan kesejahteraan keluarga secara adil dan setara, bukan alat untuk mempertahankan kekuasaan dalam rumah tangga.
Tanggung jawab menafkahi dalam ayat tersebut bukan berarti untuk mengukuhkan superioritas laki-laki, tetapi sebagai bentuk peran kolaboratif dalam membangun keluarga. Maka, ketika seorang suami tidak menjalankan fungsi qawwam-nya, apalagi malah membebankan semuanya kepada istri dan anak-anak, maka telah terjadi pengingkaran terhadap nilai ajaran Islam: keadilan dan kesalingan.
Lebih lanjut, Faqihuddin juga mengkritisi pemaknaan patriarkal atas ayat ini yang sering kali mengabaikan konteks dan realitas sosial. Ia menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan milik satu jenis kelamin, tapi milik siapa saja yang mampu menjalankan tanggung jawab dengan adil, penuh kasih sayang, dan tidak menzalimi pihak lain.
Dengan sudut pandang ini, kita bisa melihat bahwa membiarkan istri dan anak-anak bekerja keras, sementara suami sendiri tidak menjalankan tanggung jawabnya, bukanlah bentuk kepemimpinan dalam Islam. Itu justru pengabaian terhadap amanah, dan sangat jauh dari nilai rahmah (kasih sayang) yang menjadi fondasi keluarga.
Vasektomi
Selain itu, menolak program vasektomi dengan alasan agama atau budaya tanpa memahami konteks maslahatnya juga menjadi masalah tersendiri. Islam sebenarnya memberikan ruang yang luas dalam perencanaan keluarga, selama tidak bersifat permanen dan tidak membahayakan.
Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahas tentang azl (coitus interruptus) yang pada masa itu menjadi metode pengaturan kelahiran, dan beliau tidak menyalahkannya selama hal tersebut terjadi atas kesepakatan bersama.
Maka, dalam konteks hari ini, program vasektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi laki-laki seharusnya masuk secara terbuka dalam bingkai musyawarah suami-istri. Apalagi jika kondisi ekonomi sangat tidak mendukung dan anak-anak justru tidak mendapatkan hak dasarnya—pendidikan, kesehatan, hingga hak bermain dan tumbuh secara layak.
Double Burden Pada Perempuan
Naasnya, dalam kasus seperti ini, perempuanlah yang sering menjadi korban paling nyata. Dalam teori gender, beban ganda (double burden) menjadi fenomena yang umum: perempuan dituntut mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Ketika suami tidak menjalankan peran ekonominya, istri terpaksa mengisi kekosongan itu. Ini bukan hanya soal ketidakadilan dalam pembagian peran, tapi juga tentang relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga.
Anak-anak pun tak lepas dari dampaknya. Banyak dari mereka akhirnya harus putus sekolah, bekerja di usia dini, atau kehilangan masa kecil yang seharusnya diisi dengan belajar dan bermain. Dalam perspektif Islam, anak adalah amanah yang memiliki hak atas pengasuhan, cinta, pendidikan dan kehidupan yang aman serta terjamin. Rasulullah Saw. bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya…”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Benarkah Banyak Anak Banyak Rezeki?
Kepemimpinan bukan berarti otoritas semata, tapi tanggung jawab moral dan sosial. Maka, ketika seorang ayah dengan santainya berkata “anak banyak adalah rezeki,” tanpa adanya upaya menafkahi dan mendidik, ini menjadi ironi. Sudah seharusnya, seseorang menjadi dan memelihara rezeki, bukan hanya menghitung jumlahnya.
Beberapa ulama tafsir juga menegaskan pentingnya maslahah (kebaikan) dalam setiap keputusan berkeluarga. Prof. Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Mishbah, sering kali menekankan bahwa Islam selalu mengutamakan kemaslahatan, termasuk dalam hal perencanaan keluarga. Jika memiliki anak terlalu banyak justru menimbulkan kemudaratan, maka menahan diri adalah bagian dari kebaikan yang diajarkan agama.
Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menilai kejantanan laki-laki dari berapa banyak anak yang ia hasilkan. Bukan dari bagaimana ia mencintai dan merawat mereka. Masyarakat patriarkal, sering kali menempatkan maskulinitas di atas tanggung jawab, dan ini justru merugikan semua pihak—terutama perempuan dan anak-anak.
Sebagai generasi muda, kita harus mulai membangun narasi baru tentang keluarga: keluarga yang adil, setara, dan saling mendukung. Menjadi ayah tidak cukup dengan menjadi “kepala” rumah tangga—harus ada aksi nyata untuk menjadi “pelindung” yang sesungguhnya. Begitu pula menjadi ibu bukan berarti harus memikul beban sendirian. Keluarga adalah kerja sama.
Kita juga perlu mendukung program-program kesehatan dan perencanaan keluarga dengan lebih terbuka. Vasektomi bukanlah ancaman terhadap maskulinitas. Ia adalah bentuk tanggung jawab yang sejajar dengan kontrasepsi perempuan. Jika selama ini perempuan rela menggunakan berbagai metode KB dengan efek samping fisik yang tak ringan, maka sudah sepatutnya laki-laki pun mau mengambil bagian.
Sudah selayaknya kita berefleksi diri kembali, jangan sampai kita menciptakan generasi yang lahir tanpa cinta, tanpa perhatian, dan tanpa masa depan yang layak. Anak bukan sekadar angka. Mereka adalah titipan, yang akan menjadi saksi apakah kita pernah benar-benar menjadi orang tua yang bertanggung jawab. []