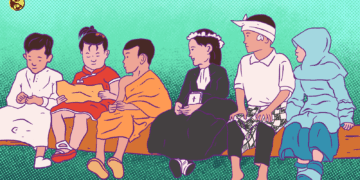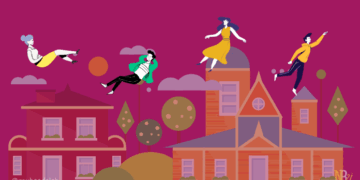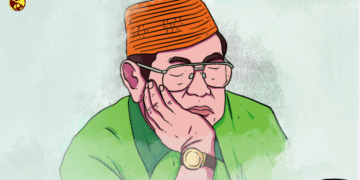Mubadalah.id – Beberapa waktu lalu, viral sebuah video yang menyebutkan bahwa ada sejumlah pihak, ditengarai dari salah satu ormas Islam, yang merasa patung Bunda Maria di Kulon Progo Yogyakarta mengganggu ketentraman di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, patung tersebut selanjutnya mereka tutup terpal biru untuk menghormati umat Muslim yang sedang berpuasa.
Kasus Penutupan Patung Bunda Maria
Sontak, kejadian penutupan patung Bunda Maria tersebut memantik kontroversi di lini masa. Banyak yang melihat tindakan tersebut berlebihan dan harus kita tengahi agar tidak memicu kegaduhan yang berkepanjangan.
Dan, ternyata apa yang video pendek tersebut sampaikan keliru adanya. Pihak yang menutup patung tersebut bukanlah ormas berbasis agama Islam. Yang berinisiatif menutup patung Bunda Maria di Rumah Doa Sasana Adhi Rasa ST Yacobus, Dusun Degolan, Kalurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, adalah pihak pengelola sendiri. Mereka sengaja menutup patung Bunda Maria setinggi enam meter itu karena ada persoalan administrasi yang belum selesai. Jadi, bukan karena desakan pihak luar.
Oleh karenanya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghimbau agar kejadian tersebut tidak kita politisasi. Terlebih, tidak semua orang mengetahui fakta dan latar belakang di balik kejadian sebenarnya. Sehingga, hal ini bisa memicu kericuhan dan polarisasi massa terutama di media sosial.
Fenomena Konten Intoleransi dan Propaganda Jelang Tahun Politik
Maraknya konten-konten yang memicu kontroversi dan propaganda intoleransi utamanya yang berkaitan dengan relasi antar umat beragama. Di mana akhir-akhir ini perlu semakin kita waspadai. Bagaimana tidak, konten-konten tersebut akan membuat lini masa kian keruh dengan ujaran kebencian.
Belum selesai dampak yang tertinggal akibat Pilkada DKI periode silam, kini kita akan berhadapan dengan narasi polarisasi yang sama karena pemilihan umum 2024 semakin dekat. Meski masih setahun mendatang, para politisi nampaknya siap mencari celah untuk memanfaatkan momen ini untuk mencari apresiasi massa.
Melihat kondisi itu, sebagai warga negara, kita sebaiknya tidak mudah terpancing, apalagi sampai menghujat pihak lain yang berbeda pendapat. Sebab, kericuhan ini tentu akan menjadi peluang bagi mereka yang untuk tampil sebagai pahlawan kesiangan dan mendapatkan simpati publik. Jika melihat konten yang bernada provokasi, jangan mudah membagikannya meski itu menarik. Cek dulu kebenarannya apalagi jika kita tidak berada di lokasi dan tidak memahami budaya setempat.
Seperti nasihat dalam buku Gus Nadir, “saring sebelum sharing”, di era media sosial di mana informasi yang kita dapat begitu cepat. Perlu ada ‘rem’ diri untuk menahan emosi dan jempol agar tidak mudah terjebak dengan perangkap oknum-oknum tertentu. Terlebih, para oknum ini memahami bahwa masyarakat Indonesia mayoritas memiliki sense aktualisasi diri yang tinggi. Semakin banyak konten yang viral, kita harus tahu, dan jika ada kesempatan, kita dapat terlibat dalam dinamika keviralan tersebut.
Memang, apa yang kita lakukan dapat menaikkan persona kita, namun membagikan konten viral tanpa mengecek kebenarannya juga akan berbuah simalakama. Dan, fenomena memanfaatkan polarisasi masyarakat menjelang tahun politik bukan hanya terjadi di tanah air semata. Tak terbilang banyak negara dalam satu dekade terakhir mengalami hal yang sama.
Berkaca pada Peristiwa di Amerika
Di Amerika sana, politisi yang memanfaatkan perpecahan di masyarakat untuk mendapatkan simpati sudah berulang kali terjadi. Ditilik dari sejarahnya, hal tersebut pertama kali terjadi pada tahun 1950an. Ketika itu, dua partai besar di sana, yakni Republik dan Demokrat memiliki ideologi dan prinsip yang hampir sama. Sehingga masyarakat kesulitan memilih mana yang terbaik.
Akhirnya, sejumlah kandidat memilih kebijakan yang ‘ekstrem’ atau memanfaatkan celah dari polarisasi masyarakat dengan mendukung salah satu pihak untuk mendapatkan dukungan dari konstituen pendukungnya.
Kini, dengan kian runcingnya ideologi dan kebijakan yang diusung oleh Republik dan Demokrat, makin terlihat bahwa banyak politisi di negeri Paman Sam yang lihai melihat peluang untuk ‘tampil’ dan mendapatkan simpati agar menang dalam pemilihan. Sebelas dua belas, dengan yang terjadi di sini.
Beberapa kali kita diperlihatkan bagaimana politisi melemparkan propaganda untuk menyerang lawan politik mereka saat pemilu. Namun sikap tadi hanyalah bersifat sementara saja saat kampanye. Usai kompetisi politik terselenggara, mereka saling merangkul, makan bersama, dan bahkan terlihat tertawa-tawa rileks.
Bandingkan yang terjadi di akar rumput. Akibat tak sependapat dengan pilihan politik, orang tak lagi menyapa, perkawanan di media sosial putus total hingga menolak untuk berkata maaf. Dari pengalaman tersebut, kiranya kita perlu mengikuti saran Bang Napi untuk lebih berhati-hati menyikapi konten viral terkait intoleransi di media sosial, “waspadalah.. waspadalah!” []