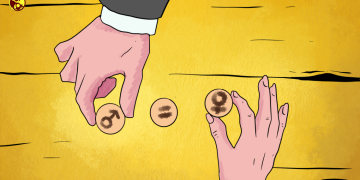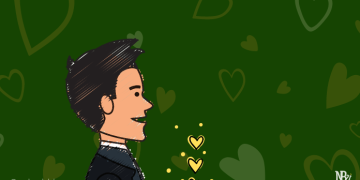Mubadalah.id – Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat termasuk di antara suku dengan jumlah maskawin yang melangit. Apalagi para perempuan berdarah biru. Mereka yang bergelar ‘lale’ atau ‘baiq’ itu nyaris membuat banyak pria Sasak geleng-geleng kepala. Terutama, bagi yang tak menyandang gelar ‘raden’ atau ‘lalu’.
Gelar ‘raden’ adalah gelar bangsawan yang diberikan kepada mereka yang memiliki jasa besar terhadap kerajaan di Pulau Lombok, dan keturunan perempuannya bergelar ‘lale’. Sedangkan ‘lalu’ adalah gelar bangsawan untuk mereka yang sekadar membantu raja dan mengabdi untuk kerajaan. Keturunan perempuannya bergelar ‘baiq’. Secara kasta, ‘raden-lale’ menyandang posisi tertinggi, lalu diikuti kasta ‘lalu-baiq’ di bawahnya.
Untuk masyarakat dengan strata sosial yang tinggi, maskawin 50 juta itu masih tergolong standar. Ini realita. Lebih-lebih, menggenap dengan pria yang berkasta rendah. Belum lagi melihat jenjang pendidikan perempuan tersebut yang tak sekufu dengan calon suaminya. Ini hanya maskawin, lain dengan pisuke-nya (Uang yang diberikan kepada orang tua calon istri sebagai rasa terima kasih sekaligus permintaan maaf karena telah menculik putrinya).
Penting digaris di sini, kami tak mempersoalkan apakah maskawin itu membumbung tinggi ke langit atau masih jongkok di bumi. Karena itu bukan ranah kami. Tetapi, yang meresahkan yaitu saat maskawinnya melangit dan tak ramah kantong sama sekali. Masyarakat kita seperti tiba-tiba gelap mata dari melihat realita. Kebijakan-kebijakan yang keluar tampak tak bersumber dari akal-budi. Melainkan muncul dari egoisme. Katanya sih, demi mempertahankan pangkat sosial warisan leluhur. Tapi benarkah demi mempertahankan pangkat sosial sampai-sampai tak ramah sosial? Ini perlu dikoreksi.
Lebih parah lagi, ketika masyarakat dengan kasta yang tak tinggi, hanya karena ada pihak yang tak merestui, akhirnya maskawin dan pisuke dibebankan seberat mungkin. Tak ubahnya seperti sanksi sosial. Padahal, pernikahan sebagai salah satu cara memuliakan perempuan. Tapi mengapa malah dihujani penderitaan. Yang susah bukan hanya pihak laki-laki, pengantin perempuannya pun banyak yang turut menangis melihat sikap keluarganya.
Baik, biar lebih enjoy saya akan bercerita. Mari kita membuka hati menelaah cerita ini. Di salah sebuah desa di Lombok, ada salah seorang ayah yang berpendirian kokoh dalam hal maskawin putrinya. Jumlah yang ia tetapkan tak ada peluang tawaran. Pandangannya benar-benar gelap, ia bersikap seolah kepada orang asing yang tak dikenal. Padahal yang turut menanggung derita tak lain adalah putrinya sendiri. Sang ayah menetapkan ‘harga’ yang amat mahal. Kondisi ekonomi pihak pria tak mampu menjangkau itu. Antara langit dan bumi.
Jalan satu-satunya adalah utang. Pinjam sana-sini, keluar masuk bank. Sedangkan, kalkulasi pendapatan harian dan bulanan tak bisa melunasi utang tersebut. Harapannya hanya satu, tanah warisan sebagai jaminan tumpukan utangnya. Bahkan, tak sedikit yang sampai memunculkan kesenjangan sosial berkepanjangan antar dua keluarga tersebut. Di sini, sengaja tak disebutkan detail ihwal ceritanya. Demi menghindari ketersinggungan pihak-pihak tertentu. Sudah maklum bersama bahwa pembenahan budaya tak seperti goreng pisang. Kita butuh waktu yang panjang.
Lalu, bagaimanakah teladan baginda Nabi yang harus kita tiru terkait maskawin ini? Mari kita kaji perlahan dengan hati nurani.
Adalah penggalan surah an-Nisa’ ayat 20, termasuk di antara teks syariat yang berbicara tentang jumlah maskawin. Lebih tepat pada lafal Qinthar(an) dalam frasa ‘Wa ataitum ihdahunna qinthar(an)’. Rata-rata, para ulama tafsir memaknai lafal tersebut dengan al-Mal al-Katsir (jumlah harta yang banyak). Ini sebagai bukti bahwa pernikahan adalah salah satu cara menghormati perempuan, mengangkat martabat sosialnya. Mengingat di masa jahiliah, para perempuan melulu dipandang sebagai komoditas rendahan. Sehingga, al-Qur’an menegaskan bahwa maskawin yang diberikan kepada mereka itu mesti tinggi.
Apa yang diajarkan surah an-Nisa’ ayat 20 ini adalah tentang sebuah idealitas. Umat Islam sedang dididik menjadi pribadi yang idealistis dalam urusan ini. Dan, ini benar. Namun, untuk tepat memahami agama, kita tidak bisa hanya dengan al-Qur’an. Kita sangat butuh hadist Nabi sebagai mubayyin (penjelas) dan mufassir (penafsir) kalam ilahi itu.
Baginda Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, yang mana ucapan (aqwal), tingkah langkah (af’al), dan sikap pembiarannya (taqrirunnabi) sebagai wahyu Tuhan dari jalur lain, tak hanya bicara maskawin dari sudut pandang idealitas. Tetapi juga sesekali turun ke bumi realitas. Dalam banyak kesempatan, guru kami di Ma’had Aly Situbondo, KH. Afifuddin Muhajir kerap kali menyampaikan statement indah yang berbunyi:
التنزيل من السماء العلى إلى الأرض الواقع
Artinya, “Turun dari langit idealitas menuju bumi realitas.”
Sikap semacam ini memiliki peran penting dalam eksistensi nilai luhur ajaran yang dibawa baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia harus elastis seperti balon yang mempu menampung banyak air. Laiknya sikap Nabi yang mampu selentur mungkin di hadapan hukum-hukum parsial (al-ahkam al-juziyah).
Syekh Iqbal dalam syairnya yang dikutip syekh Yusuf al-Qardhawi dalam al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa at-Tajdid (hal. 48), menyampaikan makna elastisitas (al-murunah) dalam beragama:
مرحبين بكل جديد نافع # ومحتفظين بكل قديم صالح
Artinya, “Selamat datang udara baru yang segar nan sejuk kuucapkan, mutiara-mutiara lama yang berkilap indah tetap kupertahankan, takkan kubuang.”
Syair indah ini semakna dengan kaidah Al-muhafadhzatu ‘ala qadim(in) shalih wa al-akhdzu bi jadid(in) nafi’, (Menjaga tradisi lama yang masih relevan sekaligus terbuka untuk hal baru yang bermanfaat besar).
Kembali ke maskawin, bagi diri Nabi sendiri maskawinnya tidak murah untuk ukuran masanya. Bahkan lumayan mahal. Dalam sebuah Hadits, Abu Salamah bin Abdirrahman bertanya kepada sayyidah Aisyah terkait jumlah mahar Nabi. Ia menjawab:
كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه
Artinya, “Maskawin Nabi untuk (sebagian besar) istrinya adalah 12 tambah setengah uqiyah. Dan jumlah semuanya adalah 500 dirham. Itulah maskawin yang diberikan pada sebagian besar istrinya.”
Syekh Abu Abdillah Abdissalam Allausy dalam Ibanatul Ahkam Syarh Buluq al-Maram (juz 3, hal. 314) mencoba mengkalkulasi 500 dirham bila dibelanjakan hari ini. Ternyata, setara dengan harga 50 ekor kambing. Dalam konteks Indonesia sekarang-dengan nilai mata uang yang lebih rendah dari Arab Saudi yang berkonsekuensi lebih mahal-harga seekor kambing dewasa lebih kurang tiga juta (Ini ketika harga kambing sedang naik). Berarti untuk 50 ekor bisa mencapai harga 150 juta. Apakah maskawin ini tergolong murah? Tentu tidak.
Kendati demikian, Nabi sangat realistis. Sang sayyidus sadat tak berkenan memberatkan umatnya dengan harus memiliki maskawin mahal. Masih ingat kisah seorang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi? Lantaran tak berkenan, si perempuan pun akhirnya menikah dengan seorang sahabat yang miskin papa. Sahabat yang hanya punya satu buah sarung. Jangankan cincin perak, dari besi pun ia tak punya. Kemudian, Nabi menikahkan mereka dengan mahar sedikit hafalan al-Qur’annya. Riwayat lain bilang, ia bermaskawinkan jasa mengajarkan 20 ayat al-Qur’an.
Artinya, jalan syariat itu sangat lebar. Tak bisa lewat jalan itu, lewat jalan lain. Tidak perlu repot oleh konstruk budaya yang kejam, tak ramah sosial, bahkan sampai menabrak norma agama. Dalam hal ini yaitu raf’ul haraj (memudahkan umat). Saat agama ingin memudahkan, norma adat malah bermaksud menyusahkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bisshawab. []