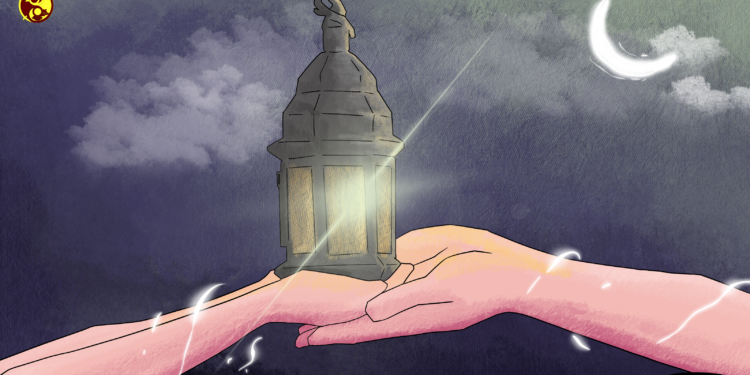Mubadalah.id – Dalam sejarah umat Muslim, Al-Qur’an turun di bulan Ramadan, atau terkenal dengan peristiwa malam Nuzulul Qur’an, ketika ibadah puasa menjadi kurikulum utamanya. Jika berkaca pada kehidupan Kanjeng Rasul Muhammad Saw, pada hakikatnya ilmu puasa terpendar dari hampir seluruh aspek dan perilaku beliau.
Peristiwa Thaif, rumus kesehatan lintas dimensi yang berbunyi “makan saat lapar berhenti sebelum kenyang”, wejangan agar tidak marah, nasihat agar tidak berlebihan dan kekurangan, serta semangat egalitarianisme beliau adalah beberapa keping dari keseluruhan wajah utuh lelaku puasa.
Etos kerja yang amanah, sarat nilai kejujuran, kebersahajaan dan empati terhadap kaum miskin papa beserta cuplikan hidup yang lain. Semua itu sejatinya secara implisit bermuatan nafas puasa sebagai thariqoh batin beliau.
Terutama saat kita sadar di era itu terbuka lebar peluang untuk bertindak manipulatif, curang, mendominasi, dan memonopoli. Namun Kanjeng Nabi Muhammad memilih untuk mentidakkan semua itu. Bukankah yang demikian adalah bentuk kecil dari semesta puasa?
Sewaktu hampir seluruh jazirah Arab berada dalam kepemimpinannya, tirakat berperih-pedih Nabi Muhammad menjadikannya tidak kalap dan terjebak pada euphoria semu. Beliau masihlah seorang nabi yang rela tidur di atas sesobek pelepah kurma hingga ada jejak goresan di pipinya. Kemudian membuat Ibnu Mas’ud yang sedang melintas terheran,
“ini orang menguasai seantero jazirah Arab, tapi hidupnya seperti ini.”
Kemuliaan itu adalah semesta agung dibandingkan debu-debu kerdil nan hina dari sikap kita yang sedemikian ngebet akan jabatan dan kekuasaan.
Bulan Puasa sebagai Madrasah
Membaca puasa nabi sebagai Muslim tidak lagi menjadi suatu kemewahan melainkan kebutuhan elementer dan paling mendasar. Usaha inilah yang memungkinkan manusia mampu terbebas dari jebakan nafsu, lepas dari jerat rasa ketidakcukupan yang menjurus kepada keserakahan dan menyelamatkan dari anasir demonic sejenisnya.
Dalam labirin historiografi dan celah-celah potensial kehidupan Nabi di atas, kita dapat mencerap mata-air nilai. Yakni telaga hikmah dan tetes embun rahasia puasa sebagai strategi manajemen atau bahkan jalan hidup.
Bahwa pada momentum Ramadan sebagai bulan penggemblengan (madrasah), puasa Allah wajibkan atas kita karena kandungan manfaat yang sangat dibutuhkan oleh diri manusia itu sendiri. Ialah suatu metode penjernihan yang dapat membebaskan manusia dari perbudakan hedonistik, berahi ekonomi, hasrat pemilikan Qarun, angkuhisme Namrud dan Fir’aun, serta melepaskan kita dari kemungkinan diperkuda oleh politik Iblis.
Dengan puasa, peningkatan kualitas spiritual transendental akan mungkin terlaksana seiring dengan usaha menerapkan tiga rukun tazkiyatunnafs, yakni: takhalli, tahalli, dan tajalli.
Pertama, dengan takhalli manusia mendisiplinkan diri untuk senantiasa membuang ‘sampah rohani’ berupa kecenderungan menyuplai hoax, tindakan manipulatif, adu-domba, khianat, dusta, iri-dengki, dan buruk sangka hingga kemunafikan sosial—baik di dunia nyata maupun jagat maya.
Sedangkan tahalli mendorong kita menghias diri dengan akhlak baik, kesantunan, keterlibatan sosial dalam mengupayakan kebermanfaatan, husnudzon, dan sefamilinya.
Setelah kedua rukun itu tertunaikan, maka atas izin Allah, potensi tersingkapkannya percik-percik cahaya Ilahiah berupa tajalli akan mungkin tercapai. Ketika melihat daun, engkau akan ingat akar, lalu ingat tanah, ingat bumi, ingat matahari yang membantunya tumbuh merimbun dan berujung kepada ingat kepada Sang Penciptanya.
Segala fenomena alam, saat kita cermati dan kita hayati, ternyata berhulu dan bermuara hanya padaNya. Sebuah pencapaian rohaniah yang mengaktivasi kesadaran sangkan paraning dumadi dalam setiap jengkal dan ruas-ruas gerak hidup kita.
Iqra’: Membaca yang Bukan Huruf
Perlu kita tengarai juga bahwa hal tersebut, akan baru mungkin terkabul sepanjang kita mau mengindahkan firman pertama Allah kepada sang kekasihNya: iqra’. Bacalah! Sontak Nabi bingung dan bertanya pada waktu itu: apa yang dibaca?—sedang beliau sendiri seorang ‘ummi, tak bisa membaca. Al-Quran? Belum turun secara utuh dan justru baru itulah ayat pertamanya.
Maka Nabi Muhammad gemetar ketakutan. Siapa gerangan bisikan itu? Hingga beberapa jenak kemudian Nabi Muhammad nyaris frustrasi dan ingin meloncat saja dari puncak bukit. Namun dicegah ‘suara’ itu lagi, “Hai, Muhammad, engkau memang utusan-Nya. Jangan takut.”
Lantas beliau berusaha meneguhkan diri, bersama perempuan pejuang di sisinya, Siti Khadijah. Sejak itu, Nabi Muhammad cermat membaca situasi masyarakatnya, ikut bergumul dengan kesulitan tetangga-tetangganya, bersikukuh untuk egaliter sesama manusia, terlibat persoalan sosial dan turut berprihatin sampai masa sepuh dan ajal menjemput.
Iqra’ di Malam Nuzulul Qur’an
Berpijak dari sanalah lelaku puasa dan tadabbur malam Nuzulul Qur’an menjadi penting agar kita tumpukan pada semangat iqra’. Bahwa membaca bukan hanya menyangkut buku, kitab, atau segala informasi tulis yang tertuang di jagat maya dan sekadar menggunakan indera mata atau potensi intelektual-kognitif.
Namun bahkan melampaui itu, membaca adalah juga mendayagunakan multipotensi instrinsik dalam diri agar sanggup menangkap fenomena, isyarat iklim dan cuaca, membaca diri kita sendiri, situasi sosio-antropologis dan psikologis. Bahkan sampai ke penjelajahan belantara batiniah yang penuh rahasia dan dapat menambah ketakjuban kita kepada Allah.
Dengan begitu, membaca puasa dan iqra’ di malam Nuzulul Qur’an tentu merambah ke spektrum makna yang berlapis-lapis dan gradasi level pengertian yang luas sekaligus dalam. Jika tidak, maka cita-cita kita meraih “idulfitri” akan menjadi utopis belaka. Keinginan agar terlahir kembali dengan kesadaran utuh disertai keterbimbingan dan ketercerahan spiritual, tentu hanya akan berakhir sebagai angan-angan.
Kalau sudah begitu, apa yang membedakan diri kita hari ini dengan yang kemarin? Pada titik mana perbedaan antara kita—yang berpuasa menekuni lapar dan dahaga tapi tak merubah apa-apa selain upgrade baju—dengan ular yang setelah berpuasa lantas berganti kulit dan kembali pergi mencari mangsa baru? []