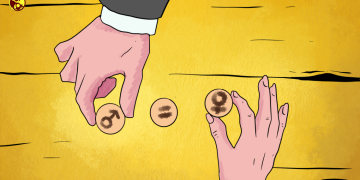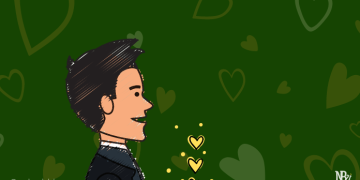Mubadalah.id – Film Tilik ini tentang gender stereotyping atau film memperkokoh gender stereotyping? Begitu perdebatan di publik saat ini merespon hadirnya film dokumenter berdurasi 30 menit tersebut. Saya tertarik membuat tulisan respon subyektif saya terhadap film ini. Secara alur film ini sederhana sekali dimana serombongan ibu-ibu dari sebuah desa yang memiliki kepedulian kepada Bu Lurahnya yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit yang letaknya jauh di kota.
Mereka terpaksa harus travel menggunakan mobil truk untuk mengangkut para ibu yang hendak “tilik” Bu Lurah. Percakapan sepanjang menuju Rumah Sakit inilah yang menjadi fokus film ini dimana tokoh utama Bu Tejo, Yu Ning, Yu Sam, Bu Tri dan yang lain terlibat dalam pro dan kontra menyikapi informasi dari media sosial.
Percakapan menjadi seru ketika Bu Tejo membawa sosok Dian menjadi topik hangat diskusi. Dian digambarkan sebagai perempuan single, punya pekerjaan, karir cukup menjanjikan, tetapi justru di mata Bu Tejo dan beberapa ibu yang lain menjadi ancaman karena sifatnya yang “semanak” (mudah bergaul) dianggap potensi menggaet suami-suami mereka.
Saya tertarik mengupas film ini dengan menggunakan kacamata alumni Sastra Inggris UNEJ dan juga seorang feminis. Yang ingin saya sampaikan pada publik, bahwa untuk menganalisis sebuah karya sastra seperti ini, pendekatan observasi sangat kuat, dan kemudian memberikan penilaian dengan menggunakan perspektif kita masing-masing. Jangan buru-buru jatuh pada konklusi.
Nah, ini perspektif saya yang Melihat film ini 2 kali dan cukup menikmati karya Wahyu Agung Prasetyo, sutradara muda yang saya rasa terbuka. Apakah ini tentang atau mengukuhkan gender steretyping? Kedua-duanya sangat mungkin, karena pada dasarnya publik punya tangkapan beragam terhadap film ini.
Saya lebih melihat bagaimana gender stereotyping diperburuk oleh kehadiran media sosial dan individu yang tidak kritis. Di Film ini sangat jelas penggambarannya, apalagi dengan kehadiran tokoh seperti Bu Tejo yang punya kemampuan persuasif sangat tinggi mempengaruhi opini publik dengan dukungan data-data dari internet.
Pada awal percakapan para ibu ini,sangat kelihatan kalau internet dan media sosial menjadi sumber berita yang diyakini kebenarannya. Internet diyakini betul oleh Bu Tejo dan kawan-kawannya sebagai temuan orang pintar maka dari itu seluruh informasi yang disuguhkan oleh internet adalah kebenaran hakiki.
Menjadi single, bekerja dan cukup umur menikah, seperti Dian, di masyarakat tidak gampang. Sejumlah stereotyping yang dilekatkan mulai dari:
- memiliki pekerjaan yang dianggap tidak halal karena berbagai fasilitas yang dimiliki
- penggoda suami tetangga
- Cap gonta ganti pasangan, meskipun konteks Dian karena pekerjaan pariwisata yang bertemu banyak orang
- Direndahkan karena karir lebih penting dari status menikah
- menggunakan susuk pemikat karena hampir semua laki-laki terpikat oleh Dian
- muntah-muntah dan menghindar bertemu orang lain disimpulkan hamil
- jalan-jalan di mal dengan seseorang yang lebih tua, dianggap tidak pantas atau kalau jalan sama pacar kok ya udah tua, harusnya cari yang lebih sepadan
Semua gender stereotyping yang dilekatkan oleh Dian semakin kuat dan menyakinkan dengan hadirnya Facebook di mana unggahan Dian menjadi perhatian Bu Tejo, dan kemudian dijadikan bukti pembenaran prasangka selama ini. Yu Ning, sosok yang selalu berusaha mengcounter narasi Bu Tejo, adalah sosok kritis yang berusaha untuk selalu mengingatkan bahwa fakta-fakta sepihak itu belum tentu kebenarannya.
Informasi yang ada di media sosial juga tidak seharusnya dijadikan kebenaran tunggal. Begitu Yu Ning selalu membantah semua ucapan Bu Tejo. Ada tokoh lain Yu Sam yang sedikit banyak mendengarkan Yu Ning, dan Bu Tri yang acapkali selalu membenarkan ucapan Bu TEjo dan membumbui dengan fakta-fakta baru untuk melengkapi referensi bahwa Dian Perempuan Nakal.
Nah komplit sudah stereotyping single, bekerja, banyak teman, cantik, cukup sukses karirnya, diasosiasikan dengan perempuan nakal. Jadi, semua gambaran stereotyping yang dilukis oleh Bu Tejo dan Bu Tri, juga ditimpalin yang lain, sangat “relate” atau nyambung dengan kondisi real di masyarakat. Saya yakin kalian pasti sependapat dengan saya bahwa masyarakat kita punya stereotyping seperti gambaran Bu Tejo.
Apakah Masyarakat Melakukan Resistensi pada Gender Stereotyping?
Di Film ini, perlawanan Yu Ning yang begitu sengit dengan berkali-kali agar tidak begitu saja percaya dengan media sosial dan umbaran Bu Tejo diwakili dengan narasi-narasi “jangan suka menyimpulkan”, atau “kok seperti wartawan saja”, “sok tahu kahanan lian” (seolah tahu orang lain) adalah gambaran bahwa masyarakat kita tidak seragam.
Orang seperti Yu Ning, itu saya gambarkan para feminis yang merasa tidak sreg dengan semua obral image tentang seorang perempuan cantik dan single. Perjuangan Yu Ning tidak sia-sia, buktinya Yu Mas perempuan berjilbab merah yang berdiri dekat Bu Tejo, juga mengiyakan sanggahan Yu Ning tentang fitnah. Bahkan Yu Mas sendiri mengatakan “fitnah lebih kejam dari pembunuhan”.
Gimana dengan ibu-ibu yang diam? Saya rasa mereka mewakili silent majority yang tidak mau bersikap terbuka terhadap pro dan kontra yang sedang berjalan. Mereka mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan Bu Tejo, tapi tidak punya keberanian untuk melawan.
Ingat ekspresi seorang ibu yang muntah karena mabuk kendaraan, ekspresi wajahnya yang kesal kepada Bu Tejo cukup jelas mengatakan pada kita, bahwa apa yang digambarkan oleh Bu Tejo tentang muntah berasosiasi dengan hamil itu tidak benar. Saya rasa kemungkinan juga ada beberapa ibu yang benar-benar tidak seide dengan Bu Tejo.
Yu Ning memberikan gambaran kepada kita bahwa resistensi pada hal-hal yang dianggap tidak benar membutuhkan energi yang panjang dan daya lenting yang luar biasa untuk tidak emosi dan mengambil sikap diam. Ekspresi Yu Ning berkali-kali menimpali dengan guyonan dan santai adalah cara unik menghadapi teman se kampung yang memiliki ekstra energi negatif seperti Bu Tejo.
Kita bisa bayangkan kalau orang seperti Yu Ning patah arang dan kemudian diam. Maka gender stereotyping ini bisa berubah menjadi menggiring pada diskriminasi, marginalisasi, dan bahkan bentuk kekerasan lain pada Dian. Bayangkan jika perempuan-perempuan di kampung kita yang memiliki wawasan lebih kritis tidak angkat bicara? atau mundur dengan pelan-pelan dari percakapan publik?
Apakah film ini memperkokoh gender stereotyping?
Adegan bagaimana gosip dibangun, direproduksi dalam percakapan sesama ibu-ibu ini serta sentralistik tema Dian sangat berasosiasi erat dengan cara perempuan membangun conversation. Apalagi adegan Bu Tejo dan Yu Ning berdebat keras tentang akurasi informasi tentang Dian yang dituduh memakai susuk, sangat memperlihatkan realitas perempuan bertengkar.
Itu realitas. Perempuan beradu pandangan dengan bicara karena kekuatan oral mereka. Tapi adegan ini sangat nice karena tidak berujung pada adu fisik. Bagi saya ini percakapan bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki, tentu saja dua jenis kelamin ini punya kekhasan cara membangun cerita, krena mereka memiliki latar belakang dan karakter berbeda.
Tapi mungkin inilah yang ditangkap sebagian kawan bahwa film ini melanggengkan gender stereotyping dengan mengambil aktor perempuan, setting, dan pembicaraan yang dibangun. Ada benarnya, tetapi kita juga tidak bisa denial pada realita yang masih kuat di masyarakat.
Saya merasa mungkin sutradara tidak bermaksud begitu. Semua bentuk-bentuk gender stereotyping pada Dian disuguhkan dengan lugas dan dibumbui media sosial yang powerfull, sehingga dari ide senyap Bu Tejo awalnya kemudian berubah menjadi ide banyak orang, apalagi dengan bukti foto-foto dan fakta-fakta yang dianggap ganjil terkait reaksi Dian pada komunitas.
Di adegan terakhir film ini ketika mobil truk sudah sampai di Rumah Sakit dan akhirnya ibu-ibu kecewa karena tidak bisa “tilik” Bu Lurah yang sedang di ICU dan tidak boleh dikunjungi. Sosok Bu Tejo sekali lagi memainkan pengaruh yang luar biasa dengan menawarkan “solusi” atas kekecewaan para ibu yaitu pergi ke pasar Gede. Bagi perempuan ini solusi banget karena mereka bisa berbelanja dan melepaskan penat perjalanan dan juga perasaan kecewa.
Di sinilah, saya merasa Sutradara mengalami dilema apakah mengakhiri film dengan memenangkan Bu Tejo atau Yu Ning. Pada akhirnya semua bersepakat untuk mengikuti Bu Tejo krena tidak ada alternatif lain yang lebih menarik untuk melampiaskan kekecewaan.
Begitu naik truk, terlihat sekali wajah Yu Ning yang kecewa dan malu karena niat baiknya untuk peduli kepada Bu Lurah, tanpa informasi yang detil, kandas begitu saja karena ternyata bu Lurah tidak bisa ditengok. Disinilah pemirsa bisa melihat, bagaimana Bu Tejo mengambil peran dominan untuk menghibur ibu-ibu yang kecewa dengan menawarkan “pergi ke pasar gede (Bringharjo)”.
Sontak itu diaminin oleh semua ibu-ibu, termasuk Yu Ning yang masih dalam pergulatan batin ini ikut mengamini ide Bu Tejo. Sindiran Bu Tejo “jadi orang yang solutif” …. ini begitu telak seolah mengatakan kalau Yu Ning tidak solutif. “Jadi menyebarkan kabar yang belum jelas itu fitah bukan?”, Bu Tejo sekali lagi memberikan pukulan telak kepada Yu Ning yang sekali lagi hanya terdiam.
Disinilah, saya merasa sedih, karena segala upaya Yu Ning sebagai defender untuk kritis, runtuh seketika. Masyarakat lebih mengamini suara keras Bu Tejo yang sekali lagi ingin mengukuhkan bahwa dirinyalah yang benar.
Melihat wajah sedih Yu Ning, saya berdoa semoga orang-orang seperti Yu Ning tidak gampang patah arang dan akan kembali menjadi ke masyarakat dengan bangga sebagai si topi hitam, orang yang kritis.
Menutup ulasan ini, baik Bu Tejo yang termakan media sosial, ternyata seorang yang kritis seperti Yu Ning juga bisa kepleset melakukan hal yang sama yaitu tidak check dan recheck kebenaran informasi. Mungkin saja dalam kenyataan hidup kita, kita pernah diposisi Yu Ning atau Bu Tejo.
Setajam apapun perbedaan kita, akan tetap disatukan dalam sebuah kepentingan bahwa mereka hidup satu desa dan akan terus mengalami peracakapan seperti itu. Yang terpenting bagaimana mengelola orang-orang seperti Bu Tejo dan orang-orang yang diam.
Apakah film ini relate dengan kehidupan saya?
Iya. Waktu saya kecil, sebuah pertengkaran antar ibu-ibu tetangga terjadi di sebuah Warung kelontong, dimana si A menyindir-nyindir keluarga saya yang punya utang di warung dan si B membela mati-matian keluarga saya. Masalah utang di Warung adalah hal biasa di kampung kita, karena mamang kadang nggak punya uang sementara harus makan setiap hari.
Si pemilik warung sangat paham itu dan sangat percaya bahwa perempuan-perempuan ini, termasuk ibuku pasti akan membayar hutang mereka. Karena ini masalah relasi jangka panjang. bukan sekedar jual beli saja. Sosok Bu Tejo ada dalam real di masyarakat. Pun sosok Yu Ning yang membela orang yang dianggap lemah juga ada. Saya merasa melihat film ini begitu dekat dengan kehidupan saya waktu kecil, apalagi keluarga saya pernah jadi perbincangan di suatu pagi, oleh orang seperti Bu Tejo.
Kami beruntung memiliki Mbak Mi yang memiliki warung kelontong yang bijak dan selalu memproteksi para pelanggan setia dia. Juga para tetangga yang merasakan kebaikan keluarga kami. Sehingga pertengkaran itu tidak berkembang.
Akhirnya saya katakan, bahwa karakter Bu Tejo akan sangat bisa menuai mobilisasi masa kalau masyarakat tidak kritis dan menggunakan nalarnya. Oleh karenanya, Jika anda seperti Yu Ning, anda tidak boleh menyerah. []