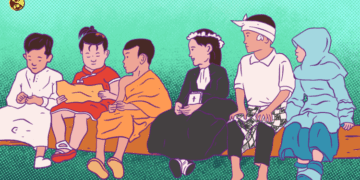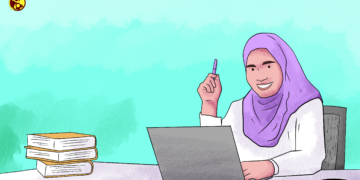Teman saya yang tomboi itu, sebut saja Sita, dia harus membiasakan kedua kupingnya dari sindiran picik orang-orang di sekitarnya yang saban hari ia dapatkan karena sifat tomboinya. Itu pula sebab mengapa ia lebih sering dipanggil dengan nama “Stela”—akronim dari “setengah laki-laki” sebagai sindirian untuk karakternya yang tomboi itu.
Sindiran tersebut ia dapatkan karena mereka menganggap Stela telah gagal sebagai seorang perempuan; Perempuan dalam pengertian lemah lembut, gemulai, ayu, dan hobi bergumul dengan perkakas-perkakas kecantikan demi memikat laki-laki sebagai simbol feminitasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak di antara kita yang getol mengategorikan segala hal; karakter sampai pada penampilan dengan kompas budaya gender yang saya nilai sudah begitu usang ini.
Gender merupakan kontradiksi logis, bagaikan hitam dan putih. Defenisi ini terbilang ambigu karena gender sebagai konstruk “budaya” hampir tak tersentuh sama sekali dalam diskusi-diskusi kita. Alih-alih didekati sebagai konstruk budaya, gender cenderung didekati sebagai divine creation yang wajib diikuti tanpa ba bi bu.
Sewaktu duduk di bangku sekolah dasar, pun hal serupa juga pernah terjadi kepada saya; Saya dilarang keras bermain dengan anak-anak perempuan karena orang tua saya khawatir saya akan menjadi banci jika ikut bergabung dengan mereka. Seolah sifat keperempuanan itu akan menulari suatu penyakit kepada saya laiknya sebuah pandemi.
Kebingungan seperti ini muncul dari anggapan awam bahwa ada yang tidak alamiah dari seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Ditambah lagi, anggapan ini juga mendapat pembenaran dari agama dan budaya populer kita—yang mana kemudian menciptakan jurang yang bias dalam membedakan antara yang alamiah dan kultural; dan jurang ini ditutupi dengan menyatakan bahwa adalah aneh bagi siapapun yang kealamiahannya tidak sesuai dengan “kealamiahan” ala budaya dan agama.
Apa yang terjadi di atas memicu beragam pertanyaan; apakah perempuan atau laki-laki harus menyesuaikan diri dengan defenisi-defenisi gender yang sudah digariskan budaya kepada mereka demi membuktikan identitasnya sebagai seorang laki-laki atau perempuan?
Lalu apa sebenarnya arti menjadi laki-laki atau perempuan? Atau haruskah kita meninjau kembali defenisi gender tersebut dan menempatkannya sebagai realitas historis yang dapat dikritik, alih-alih sebagai sebuah kealamiahan yang final?
Sejarawan Yuval Noah Harari, dalam buku terkenalnya “Sapiens” pernah menerangkan hal ini. Ia mulai dengan sebuah pertanyaan tentang: apa yang disebut alami dan bukan alami? Pastinya sains dan budaya punya defenisinya tersendiri. Dia menulis:
“Kenyataannya, konsep-konsep alami dan tidak alami kita bukan diambil dari biologi (sains), melainkan dari teologi (agama). Dalam agama, alami adalah “apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan….“
Dalam pandangan Harari, “alami” dan “tidak alami” adalah merupakan bahasa agama atau budaya, bukan bahasa biologi. Dalam biologi, jika sesuatu hal masih dapat atau mungkin terjadi maka hal tersebut dapat dikatakan alami; singkat kata, tidak ada yang tidak alami.
Di lain sisi agamawan percaya bahwa Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu. Gagasan klasik seperti inilah yang menciptakan kategori tersebut; Artinya, bila kita menggunakannya sesuai dengan tujuan yang digariskan Tuhan, maka itulah yang disebut “alami,” jika digunakan selain daripada itu, maka hal tersebut dikatakan “tidak alami.”
Andai kata Stela tidak tomboi, tunduk pada laki-laki, tidak kasar, lemah lembut, berdandan, dan bermanja ria laiknya apa yang budaya populer kita ajarkan melalui standar-standar keperempuanan, maka itu disebut perempuan normal. Jika Stela menolak untuk melakukannya, maka ia tidak pantas disebut perempuan normal walaupun secara biologis ia berjenis kelamin perempuan.
Harari menyebutkan bahwa—kategori-kategori gender tersebut tak lebih dari sekadar kategori-kategori sosial, namun bukan biologis. Dalam biologi, kita hanya mengenal laki-laki atau perempuan tanpa memiliki standar atau kategori sifat (tertentu) yang diharuskan untuk mereka miliki agar disebut normal, seperti feminin untuk perempuan dan maskulin untuk laki-laki; karena alih-alih sebuah kealamiahan, istilah-istilah gender tersebut tak lebih dari sekadar apa yang masyarakat dan budaya bebankan kepada kita.
Dalam biologi, untuk menjadi seorang laki-laki itu cukup mudah, kita hanya membutuhkan satu kromosom X dan satu kromosom Y saja, sementara untuk menjadi perempuan kita hanya memerlukan dua kromosom X. Tapi untuk menjadi laki-laki atau perempuan dalam kacamata budaya diperlukan hal yang lebih kompleks daripada seongok kromosom-kromosom tersebut—yang meliputi banyak aspek, termasuk peran, tugas, dan sifat seseorang; bahwa perempuan atau laki-laki normal harus seperti ini dan/atau seperti itu. Olehnya, tak heran jika Harari berkata: “Jenis kelamin adalah perkara mudah; namun gender adalah perkara serius.”
Saya tidak tahu bagaimana rasanya memiliki dua kromosom X. Tetapi saya hidup dengan beberapa orang yang memiliki dua kromosom X; Ibuku dan sebagian besar sahabat saya adalah perempuan. Dan ketika saya memikirkan hal tersebut, saya menyadari bahwa hal-hal yang selama ini kita percayai dan diwajibkan masyarakat atas kita bukan lah takdir.
Perempuan masih terjebak dan tertindas di banyak bagian dunia karena keperempuananya yang katanya alami itu, ia dipaksa untuk tunduk pada laki-laki. Tapi laki-laki pun juga sama, ia terjebak dan dipaksa melakukan peran yang ditentukan oleh budaya. Meskipun secara hirarkis, laki-laki cenderung lebih diuntungkan oleh budaya, namun pada dasarnya keduanya—laki-laki dan perempuan—sama: bahwa kita semua adalah tawanan dari budaya kita sendiri.
“Mitos-mitos kebudayaan menetapkan laki-laki peran-peran maskulin tertentu, seperti—hak dan tugas maskulin. Serupa dengan itu, perempuan juga dibebankan mitos-mitos kebudayaan tertentu yang mewajibkannya memenuhi peran-peran feminin tertentu….” Tulisnya.
Apa yang terjadi pada Stela dan mungkin sebagian di antara kita (yang dinilai tomboi atau banci) menunjukkan bahwa perbedaan biologis itu nyata. Baik laki-laki atau perempuan, tubuh biologis kita mewakili sifat yang oleh budaya sebut sebagai sifat alamiah yang wajib diikuti—kita semua pada dasarnya tengah berada dalam posisi yang sama: terjebak dan dipaksa melakukan apa yang budaya ingin untuk kita perankan. Dalam hal ini budaya sama seperti apa yang oleh Chip Brown sebut sebagai: Making a Man.
Laki-laki dan perempuan sama-sama hidup dalam kekhawatiran yang terus menerus; Laki-laki didesak untuk tangguh bak pegulat papan atas demi memenuhi standarisasi klasik kejantanan ala budaya: laki-laki harus tegap, maco, dan pantang menangis. Sementara perempuan sibuk untuk meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa dia adalah perempuan tulen dengan scin care dan alat make up tanpa sepak bola dan jersei Ronaldo-nya.
Jika manusia maju karena kekuatan imajinasi atau fiksinya, seperti yang dikatakan Harari, maka kita seharusnya dapat membayangkan sebuah dunia di mana gender tidak selalu dapat mendefinisikan seseorang lebih daripada biologis mereka dan tanpa pembebanan ekspektasi atau kategori tertentu. Kita masing-masing—perempuan dan laki-laki—dapat mengembangkan diri kita sendiri sesuai dengan apa yang kita anggap pantas dan nyaman bagi diri kita.
Tujuan akhirnya, tentu saja, adalah membiarkan semua orang mendefinisikan diri mereka sebagai manusia, untuk keluar dari kategori yang ditetapkan dan mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini mereka terima. Di sisi lain, kita juga musti sadar bahwa kita adalah pencipta, korban, dan juga pelaku dari budaya kita sendiri.
Jadi, bisakah kalian melihatnya, Sita atau siapapun kalian? Budaya itu imajiner. Tapi kamu tidak. Kamu sangat nyata. Jadilah diri sendiri. []