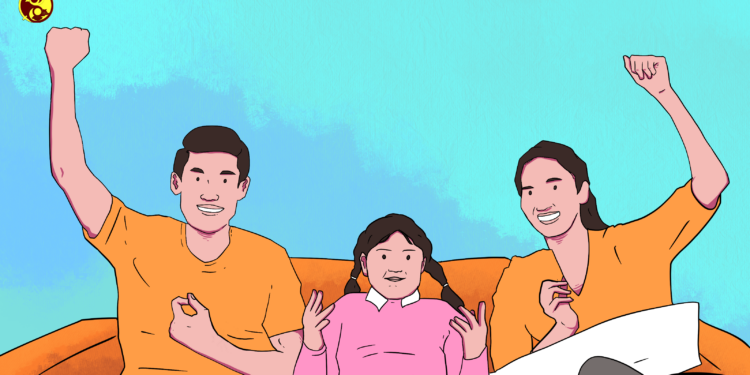Mubadalah.id – Kita mungkin sudah sering mendengar Birrul Walidain. Berbuat baik pada kedua orang tua. Pesannya jelas sekali ada dalam hadis Nabi, tentang 3 amal yang tidak pernah putus, salah satunya berbakti pada orang tua. Selain itu ada shadaqah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat.
Lalu ada pesan lain dari Al Quran dalam surat Lukman yang melarang kita bilang “hussh/cih” pada orang tua, kata lain adalah berkata kasar. Sehingga kadang, mohon maaf, narasi di atas menjadi alat orang tua untuk mengendalikan kehidupan anak.
Sebagaimana yang berapa kali aku temukan dalam kesempatan menjadi konselor Posyandu Remaja di salah satu kampus di Indramayu dua pekan kemarin. Orang tua, atau aku sendiri yang kini juga berperan sebagai orang tua kadang lupa, ada hak anak yang seringkali terabaikan. Yaitu birrul awlad, atau berbuat baik pada anak tanpa syarat.
Sementara untuk birrul awlad belum banyak yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus memperlakukan anak-anak dengan baik. Aku semakin paham setelah lama nyemplung mengelola media Mubadalah.id, dan membaca buku Qiraah Mubadalah. Ada lagi tambahan referensi lainnya ada di buku Fiqh Perwalian terbitan Rumah Kitab.
Bakti Anak Bukan Membayar Hutang Jasa Orang Tua
“Saya harus bagaimana menghadapi orang tua, terutama ayah yang seperti itu Bu?”
“Kadang-kadang saya ingin menghilang saja dari dunia ini, kalau ibuku sudah marah-marah di rumah, karena aku tidak memberinya uang”
“Saya pernah bersembunyi di kolong tempat tidur, ketika para penagih hutang datang ke rumah, jadi saya takut pulang”
Isakan kecil peserta Posyandu Remaja yang pernah aku dampingi proses konselingnya, masih teringat jelas dalam ingatan. Tidak hanya satu orang, tapi lebih dari tiga peserta yang bercerita dengan problem sama. Relasi yang kurang baik dengan orang tua, terutama ibu.
Di mana berdasarkan cerita yang mereka sampaikan, orang tua seakan menuntut anak untuk membayar apa yang sudah orang tua berikan. Sehingga banyak fakta yang aku temui di Indramayu, anak perempuan seringkali menjadi aset keluarga untuk berangkat bekerja di luar negeri.
Jadi ketika ada anak yang selepas SMA belum ingin bekerja, tapi lebih memilih kuliah atau melanjutkan pendidikan, anak seakan mendapatkan perlakuan berbeda dari orang tua. Ketiadaan dukungan dari orang tua dan keluarga menjadi beban tersendiri bagi mereka untuk bisa meraih mimpi serta cita-cita. Sayang sekali, padahal pendidikan adalah salah satu kunci untuk bisa mengubah nasib mereka di kemudian hari.
Tentu aku kurang sepakat dengan pernyataan di atas. Bakti anak pada orang tua bukan untuk membayar hutang jasa, karena telah melahirkan anak ke dunia. Tetapi karena sebagai orang tua telah memperlakukan anak secara baik, memberikan segala hal terbaik, dengan penuh dukungan, cinta serta kasih sayang.
Terlebih jika kita berpegang pada prinsip birrul awlad tadi, yakni berbuat baik pada anak tanpa syarat. Tanpa mengharap kompensasi dan imbalan apapun, dan biarkan anak menemukan jalannya sendiri menuju masa depan.
Patahkan Stigma Generasi Strawberry
Mengutip artikel Ratih Prihatina dalam laman djkn.kemenkeu.go.id yang menjelaskan bahwa istilah strawberry generation pada mulanya muncul dari negara Taiwan. Istilah ini ditujukan pada sebagian generasi baru yang lunak seperti buah strawberry.
Pemilihan buah strawberry untuk penyebutan generasi baru ini juga karena buah strawberry itu tampak indah dan eksotis, tetapi begitu kita pijak atau kita tekan ia akan mudah sekali hancur.
Sementara itu menurut Prof. Rhenald Kasali dalam salah satu kesempatan kuliah online melalui streaming youtube beliau, strawberry generation adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati.
Definisi ini dapat kita lihat melalui laman-laman sosial media. Begitu banyak gagasan- gagasan kreatif yang dilahirkan oleh anak-anak muda, sekaligus juga tidak kalah banyak cuitan resah penggambaran suasana hati yang mereka rasakan.
Dengan melihat, dan mendengar langsung realitas curhatan sebagian besar peserta Posyandu Remaja, aku yakin telah mematahkan stigma generasi strawberry. Terutama jika anak-anak itu terlahir dari keluarga kelas menengah ke bawah, yang secara ekonomi masih serba terbatas. Sehingga beban keuangan keluarga ikut dilimpahkan pada anak-anak.
Untuk mengurai persoalan ini, saat sesi konseling tak banyak yang bisa aku sampaikan pada mereka. Aku lebih banyak memberinya dukungan moral, agar tak mudah menyerah untuk mengajak orangtuanya bicara. Selain itu mereka juga tak segan untuk segera minta tolong pada orang dewasa, seperti layanan pendamping, ketika kondisi mental mereka memicu depresi berat.
Menjadi generasi apapun seorang anak, tergantung pada bagaimana pola asuh yang orang tuanya terapkan. Alih-alih membebani anak dengan sekian tuntutan, ada baiknya kita refleksi bersama. Sudahkah kita mengajaknya bicara, dan mendengarkan ceritanya? []