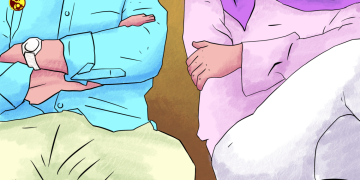Mubadalah.id – Literasi Indonesia hari ini perlahan-lahan mulai mengangkat isu-isu disabilitas sebagai objek tulisan. Hal ini juga terlihat dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Novel ini menceritakan bagaimana penyandang disabilitas bertahan hidup.
Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini adalah novel kedua yang saya baca yang membahas tentang penyandang disabilitas emosional. Jika pada novel Seberapa Candu cinta itu dari Disabilitas Emosional hingga Kritik Sosial dalam ‘Seberapa Candu Cinta itu’ penulis novel tidak menyebutkan secara spesifik inspirasi penulisan novel. Brian Khrisna, penulis novel ini menyebutkan bahwa kisah ini dia tulis berdasarkan wawancara dengan kawan penyintas depresi akut.
Novel ini menceritakan tentang Ale – seseorang yang terkucilkan oleh lingkungan dan mengidap depresi akut. Ia berniat bunuh diri dan ambang hidupnya berada dalam pencarian semangkuk mie ayam.
Dari mie ayam ini kemudian dia bertemu banyak orang, mengetahui banyak sisi kehidupan, realitas sosial, dan beragam kejadian spele namun ternyata memiliki makna yang dalam.
Secara umum, novel ini memaparkan filosofi kehidupan penyandang disabilitas utamanya disabilitas emosional, sementara sisanya disabilitas fisik.
“Maybe Life is worth living again”
Pertemuan Ale dan Jipren (penyandang disabilitas netra) merupakan titik krusial yang paling menentukan terhadap sudut pandang Ale tentang hidup dan (memilih) mati.
Ini juga memperlihatkan pada kita bagaimana penyandang disabilitas terkadang menganggap bunuh diri sebagai alternatif “paling baik”. Pikiran seperti ini muncul ketika mereka telah mencapai titik depresi dan merasa menjadi orang paling tidak berguna dan paling sial di dunia.
Jipren mengatakan, “Menjadi orang cacat jauh lebih buruk ketimbang menjadi mayat”. Dan Ale memprotesnya dengan, “Apa yang menarik di dunia ini sampai Bapak tetap bertahan? Dunia ini jahat sama kita, Pak. Bukankah mati jauh lebih baik?” (h. 180).
Terdapat banyak fakta menarik yang mereka jadikan jawaban terhadap pertanyaan itu, setelah berkali-kali jatuh dan terpuruk.
Keinginan dalam hidup, harapan bahwa keadaan – atau kita bisa sebut sebagai sistem dalam lingkup yang lebih besar – berubah, dan kesetaraan agar mereka dilihat selayaknya manusia biasa adalah jawaban-jawaban yang mereka temukan dalam proses pencarian itu.
Stoikisme sebagai Falsafah Hidup
Sebagai pengalaman langsung pengidap depresi akut, novel ini menceritakan bagaimana penyandang disabilitas memiliki stok penerimaan yang lebih banyak daripada orang dengan non-disabilitas.
Stoikisme mereka jadikan sebagai metode survival oleh penyandang disabilitas di tengah dunia yang jarang sekali memihak mereka.
Mereka mengandalkan penerimaan atas segala hal yang terjadi di kehidupan mereka. Selaras dengan prinsip stoikisme, mereka juga menekankan pentingnya ketenangan batin dan pengendalian sikap kita terhadap hal-hal di luar kendali kita; dalam cerita novel ini, sikap orang lain, segala hal yang di luar kendali kita seperti disabilitas, dan bahkan lingkungan yang tidak asssesibel.
Dalam novel ini, para tokoh memandang kehidupan “orang di bawahnya”, di bawahnya lagi, dan seterusnya lalu menganggap lebih beruntung daripada mereka yang lebih susah.
“Sebagai orang buta, kami Cuma bisa menganggap semua orang itu baik. Sebab, hanya itu yang dapat kami lakukan. Kalaupun mereka ternyata jahat dan curang seperti orang di jembatan penyeberangan tadi, kami hanya bisa menerima. Gimana Tuhan aja… ” (h. 176)
Dalam beberapa bagian seperti pada penggalan percakapan Ale dengan Jipren di atas, bagi saya, sikap penerimaan seperti itu terjebak dalam toxic positivity.
Sebab sebetulnya ada hal yang bisa kita usahakan bersama, yaitu, sikap kita sendiri sebagai “orang lain” dalam kehidupan orang difabel dan menganggap mereka sebagai kawan yang setara.
Pemerintah sebagai “orang lain” juga dapat mengubah hal itu dengan kebijakan yang lebih inklusif.
Isu Disabilitas dan Literasi Indonesia
Hal lain yang menjadi perhatian saya pada buku-buku yang secara acak saya beli, namun ternyata memiliki sedikit kesamaan dalam membahas orang depresi.
Fakta Ini menunjukkan bahwa literasi sastra kita hari ini, mulai naskah akademik, teks keagamaan, hingga sastra mulai menganggap pentingnya isu-isu disabilitas kita bicarakan untuk menjangkau khalayak yang lebih banyak. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang mencoba untuk menjadikan isu ini mainstream.
Hal ini tentu saja patut kita apresiasi. “Cahaya kecil” ini semoga semakin terang dan berdampak langsung terhadap penyandang disabilitas. Brian Khrisna, penulis novel ini, berharap bahwa orang lain dapat menemukan alasan-alasan kecil untuk hidup sekali lagi.
Namun demikian, isu ini masih jauh panggang dari api. Literasi yang secara serius membahas isu disabilitas masih sangat minim. Kita perlu mengupayakannya bersama-sama. []