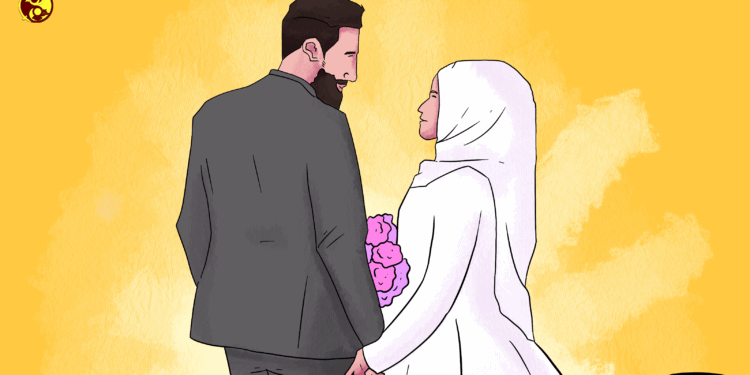Mubadalah.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam acara nikah massal di Masjid Istiqlal pada Sabtu (28/06/2025) menyambut baik sekaligus mengutarakan keresahan ihwal perjalanan pernikahan di Indonesia mutakhir. Progam ini mendapat sokongan dari kementerian yang beliau pimpin, tepatnya dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Mendengar kata “massal”, mengingatkan kita akan kegiatan keagamaan serupa sewaktu kecil, yakni sunatan massal. Dan, biasanya, kegiatan yang terikuti diksi ini tidak berbayar, alian cuma-cuma. Bahkan, mungkin bakal mendapat benefit lebih di luar fasilitas gratis yang terberikan.
Sorotan mengenai keresahan Menag Nasarudin ialah menyindir generasi Milenial (lahir pada 1981 hingga 1996) agar lekas menikah, jangan melulu pacaran atau kumpul kebo. “Di luar negeri, banyak yang memilih pacaran tanpa ikatan resmi. Tapi ini Indonesia, negara Pancasila yang berketuhanan.” jelas Menag Nasarudin.
Ungkapan tersebut memang pantas terucapkan oleh seorang pejabat, apalagi beliau adalah menteri yang berurusan dengan agama dan kepercayaan. Ada unsur nasihat moralitas dan penganjuran terhadap umat Islam, umumnya, untuk tak tergoda atau berlama-lama pacaran.
Lebih baik menikah, berbuhungan sesuai syariat dan patuh pada hal-hal administratif negara. Kita tahu, segala bentuk administratif di Indonesia kadang memiliki dampak nyata dalam mengurus dokumen lainnya, termasuk pernikahan. Ringkasnya, negara memudahkan ihwal hal-hal bersifat resmi.
Nikah Massal sebagai Solusi?
Namun, Menag Nasaruddin seakan melihat sebuah pernikahan dalam kanon agama semata. Maksudnya menganggap bahwa nikah massal sebagai solusi dari pelbagai persoalan yang generasi Milenial hadapi. Pun, kedudukannya sebagai pejabat publik perlu mendapat garis tanya, karena dasarnya kebijakan program lembaga negara, lalu segala anggarannya terserap dari sana, apakah gelaran nikah massal itu tulus atau malah tendensius?
Saya paham dan mengerti, program nikah massal ini Kemenag tuju agar dapat membantu pasangan yang terkendala secara ekonomi dalam melangsungkan pernikahannya, kan? Dan, ternyata biaya pernikahan—yang Rp600 ribu, sekaligus maharnya pun Kemenag tanggung.
Selain itu, tiap pasangan mendapat Rp2,5 juta sebagai bantuan ekonomi mikro untuk modal usaha. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang konon bakal memantau bantuan yang terberikan pada pasangan pengantin itu.
Jangan hanya karena melihat setitik celah alasan lalu mendasarkannya untuk menguatkan dalih sebuah program, tetapi dengan sengaja menafikan hal-hal lain di sekitarnya. Menag Nasuruddin mesti paham juga bagaimana pemaknaan menikah dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Kita tak bisa menyederhanakan urusan (kebijakan) agama sat set sekali jadi tapi menegasikan unsur-unsur penyokongnya, yang menguatkannya.
Ada yang tak boleh Menag Nasaruddin lewatkan dari program nikah massal bisa menjadi pemicu ketergantungan masyarakat soal finansial pada pemerintah. Mereka yang hendak menikah tetapi masih kesulitan biaya boleh jadi akan berharap penuh pada progam nikah massal Kemenag. Mereka menanti negara memberi bantuan, sementara mereka tak punya sedikitpun upaya dan usaha untuk benar-benar mandiri sebagai pasangan dalam membentuk penyangga finansialnya. Ironis!
Konsepsi negara memberi Rp2,5 juta bernada bantuan dalam kasus di atas tentu terbilang murah. Rakyat tak mendapat didikan dari negara untuk bagaimana mendapat finansial lewat jalan kreativitas dan kerja keras. Namun, negara selalu hadir terlambat, menunggu di ujung kenestapaan berharap mendapat sanjungan dan ampresiasi karena berusaha “membantu” rakyatnya.
Kearifan Memerintah
Inilah gaya pemerintahan yang, bagi saya, kurang kreatif. Sedikit-sedikit dan terlihat gampang sekali memberi bantuan. Ini bukan soal negara harus welas asih pada rakyatnya saja, tetapi mendidik rakyat melalui sumbangan, bantuan, dan bentuk cuma-cuma lainnya adalah konsep yang buruk. Semestinya ada upaya dan jalan usaha yang masyarakat tempuh sebelum akhirnya ia mendapatkan bantuan itu.
Demikian halnya, Kemenag tampaknya perlu menerapkan seleksi ketat dalam memilih calon pengantin yang bakal mendapat tiket nikah massal. Misal, salah satu syaratnya, calon pengantin seminimal memiliki penghasilan sebagai penguat pondasi keberlangsungan kehidupan rumah tangganya kelak. Dengan begitu, ia terdidik untuk tak menggantungkan harapannya pada bantuan pemerintah.
Ini termaksudkan agar mereka yang betul-betul mendaftar, menyiapkan berkas, menjalani proses, dan sampai akhirnya mendapat tiket nikah massal memaknainya sebagai penghargaan—bukan bantuan—dari pemerintah atas usahanya selama ini.
Walau dalam proses pernikahan segala biaya dan mahar pemerintah tanggung, lalu mungkin mendapat biaya tambahan lain, itu mereka maknai bukan sebagai dana primer, tetapi menjadi dana sokongan untuk kemudian ditabung. Karena dari awal mereka mendaftar nikah massal, pondasi finansialnya sudah aman dan kokoh.
Sebagai penutup, saya jadi teringat ucapan Dr. Sidik Hasan, penguji tugas akhir saya semasa kuliah sarjana, mengatakan bahwa pernikahan itu sangat kompleks, sehingga berhubungan dengan berbagai aspek, ia tak sepenuhnya tunggal berjalan.
Dalam pada itu, paradigma yang oleh Menag Nasaruddin dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, khususnya, mesti pegang soal program nikah massal adalah keterpojokan momentum masa pernikahan tidak mesti menjadi alasan sebuah lembaga negara memberikan bantuan cuma-cuma kepadanya. []