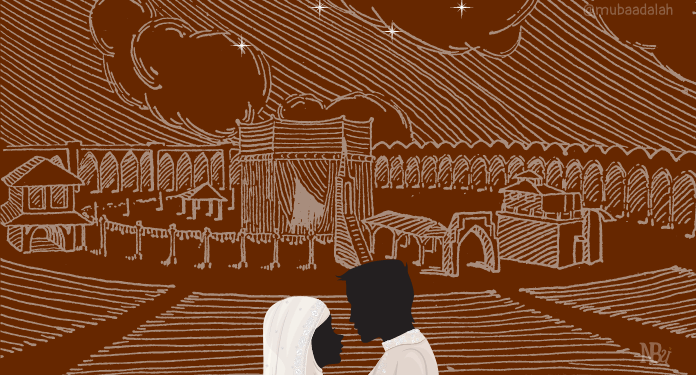Mubadalah.id – Seseorang mengaku mengenal Fulan di hadapan Khalifah Umar RA. Maka Umar bertanya, “Apakah kamu pernah menemaninya dalam sebuah perjalanan, sehingga kamu yakin atas akhlaknya yang terpuji itu?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Umar berkata, “Jika demikian, maka aku menganggapmu belum mengenalnya.” Saya nukil dari buku Rahasia Haji dan Umrah karya Imam Al-Ghazali.
Dalam momen berhaji kemarin, saya berada dalam satu rombongan bersama banyak pasangan suami istri. Saya tertarik menuliskan kisah salah satu pasangan yang usianya sudah lebih dari 75 tahun. Saya memanggil mereka “Ajengan dan Ibu Nyai”. Kebetulan, pasangan ini bersuku Sunda, dengan logat yang kental dan halus, terutama Ibu Nyai.
Sejak rombongan kami berangkat dari Islamic Center Serpong, saya mengira Ajengan berangkat sendirian karena tidak pernah melihat ia beraktivitas bersama pasangannya. Begitu pula saat rombongan sudah tiba di Mekah dan memulai aktivitas umrah hingga puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, ia selalu berjalan lenggang sendirian. Sementara saya dan pasangan lainnya tidak pernah terpisahkan jaraknya.
Laki-laki berpostur tinggi dengan kumis tebal dan jenggot putih panjang itu selalu berjalan tegak, menatap jauh ke depan tanpa menoleh ke kanan maupun kiri. Mulutnya tidak berhenti berzikir di sepanjang jalan. Ciri khas lainnya: setiap kali bersalaman dengan laki-laki lain, ia akan mencengkeram sangat kuat.
Setelah si “korban” kesakitan, barulah cengkeraman itu dilepas, lalu ia tertawa lebar. Hanya pada momen inilah ia tertawa. Selebihnya, ia diam dan hanya berzikir.
Kisah di Tenda Mina
Saat berhaji kami menetap di dalam tenda di Mina, setiap hari kami harus berjalan kurang lebih 4,5 kilometer menuju Jamarat untuk melempar jumrah. Kami memilih berangkat pukul 03.00 dini hari agar tenaga masih fit dan bisa mengakhiri ritual itu dengan salat Subuh, lalu kembali ke tenda saat matahari mulai terbit dan suhu udara mulai menyengat. Ritual ini ia lakukan sebanyak tiga kali, selama tiga hari berturut-turut.
Pada hari pertama, seperti biasa, Ajengan memilih berjalan sendiri, terpisah dari istri maupun rombongan. Langkahnya tegak, tanpa menoleh, hingga sampai di tujuan dan menyelesaikan lempar jumrah. Dalam perjalanan pulang ke tenda, ia mengalami kendala karena adanya penutupan akses jalan oleh tentara Arab, yang memang kerap dilakukan untuk mengatur arus jutaan jemaah yang lalu-lalang.
Ajengan tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti arus ribuan manusia yang terus membludak. Ajengan terpaksa oleh petugas untuk kembali ke Jamarat, menempuh jarak kurang lebih 4,5 kilometer lagi, padahal tadi pagi ia sudah melaluinya.
Di usia yang sudah lebih dari 75 tahun, berbekal air mineral seadanya, ia terus berjalan kembali sendirian menyusuri terowongan yang padat, berdebu, dan panas menyengat, bersama ratusan ribu jemaah lainnya. Agar tidak dehidrasi, ia terus-menerus meneguk air minum.
Apes, tiba-tiba keinginan buang air kecil muncul, sementara tidak ada toilet di sepanjang terowongan Mina. Ribuan orang terus meringsek dari kanan-kiri, depan-belakang tanpa bisa terbendung. Alhasil, ia tidak mampu lagi menahan hajat itu. Terpaksa ia akhirnya buang air kecil membasahi kain ihram yang tetap ia kenakan sambil terus berjalan gontai.
Hilang Kontak
Di tenda yang panas dan sesak, Ibu Nyai menunggu dengan cemas. Udara panas dan terik membuat tubuhnya semakin lunglai. Mulutnya pahit, perutnya terasa mual, hingga hanya bisa meminum air kemasan. Hingga usai salat Zuhur, kabar tentang suami tercinta pun tak kunjung ia dapatkan. Perangkat handphone yang seharusnya sangat membantu tidak menolong sama sekali. Ajengan jarang sekali membuka handphone, apalagi media sosial.
“Alat itu berisik dan mengganggu zikir dan ngaji saya,” ujarnya.
Hingga pukul 15.00, kabar tentang Ajengan belum juga diperoleh. Kecemasan Ibu Nyai memuncak, tangisnya pecah berkali-kali, napasnya terasa sesak, jantungnya berdegup kencang, dadanya berat seperti tertindih beras.
Pukul 16.30, tiba-tiba muncul kabar melalui ketua rombongan bahwa Ajengan sedang dirawat di ruang kesehatan pintu 201. Saya dan Mas Jaka S. Suryo (Direksi ANTARA) segera meluncur ke sana. Kami mendapati Ajengan tengah berbaring lunglai di kasur tipis dengan wajah sangat pucat. Sementara kain ihramnya basah kuyup.
Setibanya di tenda, Ibu Nyai menangis sejadi-jadinya, mencium wajah Ajengan yang pucat, memberikan air minum, dan menyuapinya pisang kesukaannya agar tenaganya pulih. Pandangan mata Ajengan tetap kosong, tanpa ekspresi, tanpa sepatah kata pun, kecuali hanya meminta pisang—dan pisang. Jamaah lain ramai-ramai menyodorkan berbagai makanan apa saja agar bisa ia santap.
Ibu Nyai berlinang air mata, bersujud syukur di tenda itu juga. Berkali-kali menciumi wajah Ajengan yang datar, lalu ambruk tertidur hingga beberapa jam kemudian.
Cinta Sejati
Pemandangan yang saya saksikan itu adalah wujud nyata dari ekspresi cinta sejati yang sungguh mendalam kepada seorang pasangan. Cinta yang letaknya begitu dalam, berada jauh di dalam hati, terkadang memang muncul dalam berbagai bentuk.
Ada yang keluar lewat kata-kata manis namun manipulatif. Kadang juga telah disederhanakan dengan kata-kata bersayap, seperti: “sayang”, “beb”, “honey”, “habibi”, dan puluhan kata lainnya, namun tetap terasa kering dari substansi jika diucapkan dengan tidak tulus.
Kali ini sungguh berbeda. Cinta tulus itu telah direpresentasikan oleh Ibu Nyai kepada Ajengan secara telanjang. Ia begitu dalam maknanya. Setiap sentuhan tangan dan kaki, dengan mimik muka tulus dan jujur. Setiap gerakannya menjadi penuh makna dan dapat kita rasakan kedalamannya.
Saya kehabisan kata-kata untuk merangkainya dengan kalimat apa pun di dalam tulisan ini. Namun saya bisa merasakannya dari jarak 3–5 meter. Kulit-kulit saya terasa merinding karena ikut merasakan ketulusan cinta Ibu Nyai kepada Ajengan, suaminya.
Setelah kejadian saat berhaji itu, saya menyimpulkan sendiri—dan cukup di batin saja—bahwa sikap keras kepala Ajengan tampaknya telah membentur batu besar yang sangat dahsyat efeknya. Sikap kakunya seharusnya perlahan mulai mencair. Sekuat apa pun prinsip hidupnya, setangguh apa pun hatinya, Ajengan yang selama ini kerap meninggalkan pasangan dan memilih untuk berjalan sendirian, ternyata kurang bijaksana.
Berjiwa mandiri memang mutlak, namun tetap tidak dengan cara mengabaikan pasangan, apalagi meninggalkannya sendirian. Surga harus tetap kita upayakan untuk diraih bersama pasangan, dalam keadaan suka maupun duka.
Saya teringat pesan Imam Al-Ghazali bahwa perjalanan, yang dalam bahasa Arab disebut safar, merujuk pada yasfiru ‘an al-akhlaq (membuka sesuatu yang tertutup). Perjalanan sejatinya adalah membuka kedok manusia yang selama ini tertutup rapat—menjadi lebih terbuka, telanjang, dan apa adanya di hadapan manusia lain. Meski tidak ada yang sama sekali bisa ditutupi di mata Allah. []