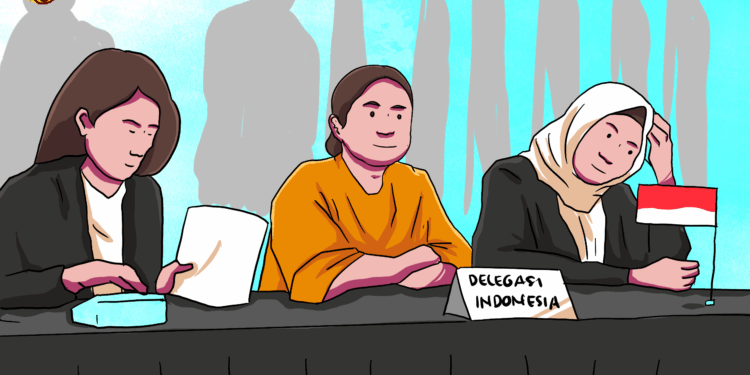Mubadalah.id – Dalam setiap rencana pembangunan, selalu ada peta. Jalan mana yang akan kita bangun, jembatan mana yang akan kita perkuat, sekolah mana yang akan kita renovasi, bendungan mana yang akan kita perluas. Tapi ada satu hal yang sering luput dari peta-peta itu: suara perempuan.
Padahal, dalam kehidupan nyata, perempuan adalah pihak yang paling pertama dan paling dekat merasakan dampak pembangunan—baik yang berhasil maupun yang gagal.
Mereka tahu seberapa jauh anak-anak harus berjalan ke sekolah, bagaimana kondisi air bersih di musim kemarau, atau seberapa berbahaya jembatan tua yang terlalui setiap hari. Tapi dalam forum-forum musyawarah desa atau penyusunan anggaran pembangunan, suara mereka nyaris tak terdengar.
Bila pembangunan hanya menjadi urusan teknis dan formalistik, maka yang terjadi bukan kemajuan, tapi ketimpangan yang semakin terpoles. Perempuan dan pembangunan sering kali dianggap sebagai penerima manfaat, bukan perancang kebijakan.
Mereka ditampilkan dalam dokumentasi program, tetapi tidak pernah benar-benar diminta pendapatnya dalam tahap perencanaan. Bahkan dalam pembangunan infrastruktur sekalipun—yang dampaknya sangat langsung terhadap kehidupan perempuan—peran mereka nyaris tak masuk hitungan.
Padahal, membangun jalan bukan hanya soal menurunkan angka kemacetan. Ia berkaitan dengan akses layanan kesehatan, pendidikan, pasar, dan ruang-ruang aman bagi semua warga, termasuk perempuan, anak, dan lansia. Tapi terlalu sering, jalan terbangun hanya agar kendaraan lebih cepat lewat, bukan agar perempuan lebih mudah mengakses posyandu.
Penerangan jalan terbangun untuk estetika kota, bukan untuk mengurangi risiko kekerasan seksual di jalanan gelap. Bahkan trotoar pun sering terbangun tanpa mempertimbangkan ibu yang mendorong stroller, perempuan hamil, atau penyandang disabilitas.
Pembangunan yang Bermakna
Dalam konteks inilah, penting sekali menempatkan perempuan dan pembangunan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari inti pembangunan. Kehadiran perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan bukanlah bentuk belas kasih, tapi keharusan etis sekaligus strategis. Sebab, hanya dengan mendengar suara yang paling dekat dengan denyut kehidupan, pembangunan bisa sungguh-sungguh bermakna.
Islam sendiri tidak menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Dalam Surah At-Taubah ayat 71 ditegaskan:
“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar…”
Ayat ini memperlihatkan bahwa dalam kerja-kerja sosial, termasuk pembangunan, perempuan dan laki-laki adalah mitra. Keduanya punya tanggung jawab kolektif dalam menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan. Maka dalam kerangka pembangunan, tidak ada alasan untuk mengecualikan perempuan dari meja perencanaan.
Sayangnya, dalam praktiknya, banyak perempuan desa yang bahkan tidak tahu bahwa mereka bisa bersuara dalam forum Musrenbang. Tidak sedikit pula yang datang hanya untuk memenuhi kuota kehadiran, bukan untuk bicara.
Ada yang sudah menyusun proposal kebutuhan sanitasi dan air bersih, tetapi kemudian terkalahkan oleh usulan pengaspalan jalan ke tempat wisata. Ini bukan sekadar soal prosedur, tapi bukti bahwa kebutuhan hidup perempuan masih belum dianggap sebagai kebutuhan publik.
Kapan Pembangunan Mendengarkan Suara Perempuan?
Lebih jauh, kita juga harus jujur bahwa pembangunan sering kali tidak peka terhadap kerja-kerja domestik perempuan. Misalnya, kerja mengurus anak, merawat orang tua, memasak, dan menjaga kebersihan rumah.
Semua itu masih dianggap sebagai beban personal, bukan tanggung jawab negara. Padahal, semua pembangunan fisik akan sia-sia jika perempuan tetap hidup dalam keletihan yang tidak terlihat, dalam kerja tanpa upah, dan dalam pengabdian yang tidak dihargai.
Maka pembangunan yang sejati bukan hanya membangun jalan atau gedung, tetapi juga membangun struktur sosial yang adil. Struktur yang mengakui kerja perempuan sebagai kerja produktif. Memamastikan perempuan punya akses yang sama terhadap sumber daya, pelatihan, dan peluang. Struktur yang membuka ruang partisipasi perempuan sejak awal, bukan sekadar saat pelaporan.
Sudah saatnya pendekatan pembangunan bergeser: dari yang maskulin dan teknokratis, menuju yang partisipatif dan kontekstual. Perempuan tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Mereka hanya perlu ruang yang setara. Mereka tidak minta kita hormati sebagai simbol ibu bangsa, jika dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap tersisihkan dari ruang pengambilan keputusan.
Kita tahu bahwa pembangunan adalah proyek jangka panjang. Tapi jika sejak awal sudah bias gender, maka hasil akhirnya tidak akan adil. Ketika perempuan tak terlibat dalam membangun, maka separuh dari kekuatan bangsa ini tersia-siakan. Dan ketika kebutuhan mereka terus-menerus terabaikan, maka tak heran jika hasil pembangunan terasa jauh dari kehidupan rakyat kecil.
Maka pertanyaannya hari ini bukan lagi: apakah perempuan boleh ikut membangun? Tapi: kapan pembangunan akan benar-benar mendengarkan perempuan?