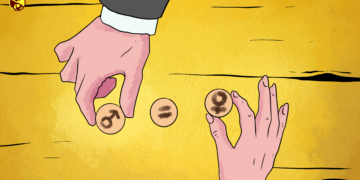Mubadalah.id – Beberapa bulan menjelang akhir tahun ini kasus-kasus kekerasan dalam dunia Pendidikan yang melibatkan bullying antar pelajar, dominasi dan kekerasan, amat menakutkan. Tingginya kasus kekerasan di lingkup pendidikan sangat nyata dan celakanya menciderai nilai luhur pendidikan itu sendiri.
Mengingat Lembaga Pendidikan menjadi tempat utama mentransfer nilai-nilai pengetahuan dan kebaikan. Ironisnya kasus-kasus kekerasan dalam pendidikan sudah seperti fenomena gunung es.
Jika menelisik data WHO, hampir tiap tahunnya, sebanyak 200.000 pembunuhan terjadi pada kelompok remaja usia 10-29 tahun. Sebanyak 84 persen korban pembunuhan remaja adalah laki-laki dan sebagian besar pelakunya juga dari laki-laki.
Bahkan di Indonesia sendiri, laki-laki lebih rentan menjadi pelaku dan korban kekerasan baik di sekolah maupun luar sekolah. Hingga Desember 2022 Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) mencatat terdapat 440 anak laki-laki dan 326 anak perempuan sebagai pelaku perundungan di sekolah. Sedangkan korbannya, 574 anak laki-laki dan 425 anak perempuan.
Angka di atas mengartikan bahwa laki-laki menjadi pelaku dan korban tertinggi dalam kekerasan di ranah pendidikan. Termasuk kasus beruntun akhir-akhir ini yang terjadi pada anak remaja laki-laki.
Berita Kekerasan Kembali Marak
Beberapa minggu yang lalu saya membaca berita pilu yang mengabarkan kasus kematian mahasiswa baru saat mengikuti pengkaderan jurusan di Gorontalo. Ini terjadi lantaran praktik dominasi golongan tertentu terhadap golongan lain (baca: senior kepada junior), penindasan, dan penganiayaan.
Sebelum itu berita juga datang dari video yang viral di media sosial yakni adanya aksi kekerasan pelajar di Cilacap. Penyebabnya karena ketersinggungan ucapan korban kepada pelaku. Dan masih banyak lagi kasus perundungan terhadap remaja.
Pada akhirnya situasi ini memunculkan anggapan dan pertanyaan. Anggapan yang melabeli bahwa laki-laki adalah seseorang yang identik dengan perkelahian dan kekerasan. Sebab jika tidak berkelahi, tidak kuat, tidak tegas, ya itu artinya tidak jantan.
Situasi ini yang kemudian menandakan bahwa ada maskulinitas toksik ada dalam diri laki-laki. Sehingga menimbulkan pertanyaan: kenapa mesti remaja laki-laki berkelahi? Bagaimana menghentikan fenomena dari budaya patriarki ini? Apa yang menjadi evaluasi dan tindakan solutif dari Lembaga Pendidikan dalam stabilitas geraknya?
Stereotip Gender dan Toxic Masculinity
Seksualitas dan gender pada hakikatnya memang berbeda. Seksualitas sebagai karakter biologis yang melekat pada manusia, sementara gender merupakan konstruksi sosial. Anggapan karakter perempuan yang feminin sebagai karakter yang lunak dan bergantung pada laki-laki. Sementara laki-laki sebagai individu yang kuat dan kompetitif. Jika tidak memenuhi konstruksi ini maka individu dianggap tidak normal.
Konstruksi sosial ini membawa dampak buruk yakni maskulinitas toksik. Komponen inti dari maskulinitas toksik adalah laki-laki harus kuat secara fisik, tidak memakai perasaan, dan agresif.
Dampak maskulinitas ini berbahaya sebenarnya karena merugikan baik laki-laki maupun perempuan. Misal, menghambat upaya laki-laki merawat kesehatan fisik dan psikologisnya yang cenderung menyembunyikan perasaan saat memiliki emosi, bisa menyebabkan depresi hingga bunuh diri, serta ketergantungan pada minuman beralkohol dan narkotika.
Mengutip Richardo Pranata Salim bahwa Sculos dan Bryant dalam Who’s Afraid of Toxic Masculinity, Class, Race, and Corporate Power menjelaskan bahwa maskulinitas toksik ada dalam dominasi laki-laki yang berlebihan seperti kepemimpinan dengan intimidasi dan kekerasan, hiper-maskulinitas yang seakan memaksa terhadap orang-orang di sekitarnya.
Maka dengan itu, laki-laki yang memiliki karakter maskulinitas toksik akan menggunakan “keistimewaannya” untuk melakukan apa saja termasuk tindak kekerasan.
Lemahnya Upaya Pendidikan Tanpa Kekerasan
Pendidikan tanpa kekerasan pada dasarnya berlandaskan pada tertib dan damai, tata-tentram (orde en vrede). Hal ini selaras dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara dalam memaknai pendidikan yang merupakan daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak.
Maka hakikatnya, sekalipun ada yang memahami bahwa hukuman dan perintah dapat menjadi alternatif memberikan efek jera, akan tetapi coba kita renungkan kembali. Bahwa apa yang anak rasakan saat mendapatkan perlakuan tersebut akan meninggalkan kesan negatif, ingatan melekat, trauma, hingga peniruan perilaku.
Bahkan parahnya kekerasan (bullying) yang terjadi di lingkungan sekolah seringkali dilegitimasi dengan dalih menegakkan peraturan untuk membangun kedisiplinan peserta didik. Sehingga kekerasan seakan menjadi budaya dan mekanisme yang seolah legal dalam ruang pendidikan.
Menyedihkan ketika ada yang menganggap bahwa anak yang menjadi korban bully adalah hal biasa untuk dunia anak. Padahal secara prinsip bullying tak boleh hadir dalam dunia pendidikan. Sebab lagi-lagi dalam hal ini terkadang kebanyakan orang masih menganggap bahwa ini hanyalah guyonan anak-anak. Bukankah ini yang menjadi faktor merebaknya problem kasus bullying banyak terjadi hingga kini? Bahkan kasus yang hadir malah semengerikan itu.
Atau dalam permasalahan yang mirisnya masih terjadi adalah bahwa anak mendapat kekerasan dalam masa orientasi siswa baru tak jarang karena adanya norma tak tertulis. Ejekan, dipermalukan, pemukulan, mirisnya dianggap sebagai hal yang lazim, meski sejatinya tak senafas dengan perlindungan untuk peserta didik. Fatalnya pula korban tak menyadari bahwa hal tersebut bukan sebagai bentuk pelanggaran, namun sebagai hal yang patut dan menjadi budaya.
PR Kita Bersama
Lebih ironi lagi terkadang ketika fenomena mulai sudah merebak, barulah evaluasi, dan tindakan preventif mulai gencarkan lagi. Sedangkan peraturan awal jikapun sudah ada mungkin hanya menyinggung sedikit tanpa ada penegasan aturan dan tindak edukasi untuk para siswa maupun guru.
Khittah sekolah hingga perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang dijujug, harus menyemai nilai-nilai luhur, nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pikiran dan tindakan. Sebab setiap peserta didik memiliki hak untuk berproses dan bertindak sesuai kemampuannya.
Bukan semua harus seragam, baik pikiran, tindakan, serta kemampuan. Sehingga di situlah kemudian melanggar hak anak. Mencari solusi permasalahan pendidikan saat ini melibatkan tiga lingkup yang sangat kompleks, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan pun juga sangat susah dalam praktiknya.
Kembali pada maskulinitas toksik, Nur Hasyim, founder Aliansi Laki-Laki Baru, mengubah maskulinitas toksik atau maskulinitas patriarki bisa mengarah ke arah yang lebih fleksibel dan manusiawi. Bahwa saat perbincangan maskulinitas masuk ke dalam konteks dan kompleks tabirnya, muncul fakta bahwa maskulinitas tidak hanya berdampak pada perempuan, tapi juga laki-laki, seperti halnya dalam kasus di atas.
Secara prinsipnya, maskulinitas manusiawi ini maksudnya adalah menyebarkan pemahaman baru tentang maskulinitas yang tak selalu mengukur kekuatan, superioritas, dominasi, tapi lebih menekankan pada kebutuhan emosional. Bukankah pemahaman seperti ini yang seharusnya kita pelajari dan ambil kemaslahatannya? []