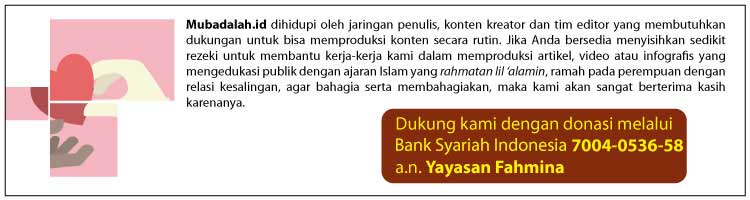Mubadalah.id – Sebagaimana yang terjadi pada beberapa orang di sekitar saya, mereka sebagai orang tua lebih memilih untuk menjauhkan anak dari ayah maupun ibu yang tidak memiliki hak kewalian atas pola asuh di pengadilan. Tentu mereka melakukan ini bukan tanpa dasar.
Barangkali karena masih adanya perasaan dendam di antara mantan pasangan, sehingga takut akan kalut jika harus tetap berhubungan atas dasar kepentingan anak. Atau bisa jadi ada kesedihan mendalam di antara salah satu pihak sehingga enggan melepaskan anak kepada mantan pasangan.
Lantas hal ini harusnya tidak bisa dibenarkan juga. Kepentingan pribadi antar mantan pasangan yang telah bercerai hanyalah urusan yang harusnya bisa dikompromikan berdua. Bukan malah menjadikan anak sebagai korban yang tidak tahu apa-apa, tapi mendapatkan imbasnya hingga dewasa.
Kecuali, andaikan kedua belah pihak, entah ibu maupun ayah, memang tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik lagi. Misalnya salah satu pihak memang meninggalkan keluarga tanpa tanggung jawab, sehingga ia tidak mau lagi memikirkan urusan anaknya sama sekali.
Kedua adalah masalah keamanan. Misalnya karena salah satu pihak orang tua memiliki memiliki potensi untuk melakukan kekerasan, perbudakan, maupun pemaksaan yang berujung pada ancaman nyawa anak. Maka berlaku hukum درء المفاسد مقدم على جلب المصالح demi menjaga anak dari suatu hal yang membahayakan dan merugikan.
Anak Jadi Korban
Kebetulan saya memiliki seorang teman, sebut saja Agus (nama samaran). Ia merupakan korban perceraian kedua orang tuanya. Kala itu usianya masih tiga tahun saat orang tuanya memilih untuk berpisah. Karena pertimbangan usia yang masih balita, hak asuhnya pun diberikan kepada sang ibu.
Hal ini selaras dengan tuntunan di Kompilasi Hukum Islam yang mana pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Moh Soleh Shofier dalam tulisannya juga sempat menyinggung bahwa hak asuh berada pada orang tua perempuan ketika anak masih balita / kecil dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikisnya.
Kendati demikian, kedua saudaranya yang lain harus berpisah dan ikut kepada sang ayah. Walaupun usia mereka saat itu belum melewati batas 12 tahun. Hal ini tidak lain mempertimbangkan kemampuan finansial orang tua untuk mengasuh anak yang lebih ayahnya miliki.
Harusnya, selaras dengan Kompilasi Hukum Islam, saat orang tua bercerai, ayah tetap memiliki kewajiban untuk biaya pemeliharaan anak. Nahasnya nafkah lahir ini tidak Agus dapatkan dari ayahnya selama bertahun-tahun. Ibunya lah yang berusaha jungkir balik untuk menghidupinya sejak kecil.
Kehilangan Ayah
Tak hanya itu, pada urusan kepengasuhan, ayahnya tidak pernah turun tangan sejak kedua orang tuanya bercerai. Bahkan ia mendapati dirinya memiliki ayah lain buah pernikahan baru ibunya dengan seorang lelaki. Ibunya sendiri tak pernah memperkenalkan sosok ayah kandung pada Agus. Sehingga bertahun-tahun lamanya Agus tidak paham, bahwa yang hidup bersamanya adalah ayah tiri.
Sayapun bertanya-tanya apa pertimbangan kedua orang tua Agus hingga membesarkan lelaki itu dengan kebohongan orang tua, dijauhkan dari ayahnya, dan mengapa ayahnya tidak memiliki usaha untuk menghadirkan diri sebagai sosok orang tua yang utuh kepada Agus? Sayangnya pertanyaan itu cukup sampai di sini, ia pun tak bisa menjawabnya.
Saat Agus beranjak dewasa dan mulai memahami kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, ia pun mencoba untuk melakukan pendekatan kepada sang ayah. Sayangnya belasan tahun bukanlah waktu yang sebentar. Selama itu mereka telah jauh dan hampir tidak pernah berkomunikasi aktif.
Melakukan pendekatan selayaknya anak dan ayah kepada orang asing tidaklah mudah bagi Agus. Baginya yang tidak benar-benar mendapatkan peran ayah dalam hidupnya. Sedangkan ayahnya juga tidak pernah menunjukkan diri bahwa ia bersalah atau ingin mendekat diri, membuat Agus semakin canggung dan kebingungan.
Belajar dari Co-Parenting Gading Marten
Melihat kisah Agus yang memprihatinkan karena keputusan orang tuanya yang tidak mempertimbangkan dengan baik keberlanjutan pengasuhan anak, saya jadi beralih pada kisah Gading Marten dan Gisel.
Meskipun mereka sudah menempuh kehidupan masing-masing, namun antara keduanya sepakat untuk tetap mengasuh Gempi bersama-sama. Mereka melakukan co-parenting yang berfokus pada kepentingan, kebahagiaan, dan kesejahteraan anak.
Dasar tujuan co-parenting adalah meminimalisir gejolak emosi anak ketika orang tua berpisah. Anak yang mengalami stres dan cemas karena keadaan keluarga bisa merasa lebih tenang karena kedua orang tua masih hadir di sampingnya. Mereka masih utuh untuk membesarkan anak dengan baik.
Hubungan pasangan, selayaknya Gading dan Gisel, boleh jadi gagal. Mereka bisa saja memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing. Tapi mereka sadar, bahwa anak adalah milik keduanya, bukan salah satu saja. Mereka paham, bahwa keduanya penting memberikan peran secara seimbang untuk kebaikan sang anak.
Tentu hal ini perlu kompromi yang begitu berat, karena harus melepaskan masalah perasaan pribadi yang barangkali masih terluka atau sedih karena berpisah dengan mantan pasangan.
Perlu proses panjang, bahkan keduanya sama-sama tetap belajar untuk memecahkan masalah bersama, berkomunikasi dengan baik, saling berbagi tugas, dan saling mendukung atas berbagai hal yang menyangkut dengan anak. Sehingga, bagaimanapun hubungan sebagai pasangan telah gagal, setidaknya masih bisa berhasil untuk menjadi orang tua yang baik dan tidak melepas tanggung jawab pengasuhan pada anak. []