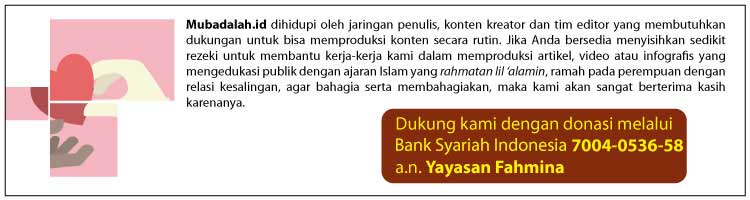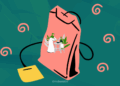Berapa kali dalam seminggu Anda memesan makanan melalui aplikasi ojek online? Mungkin ada orang-orang yang melakukannya hingga lebih dari sepuluh kali dalam seminggu, apapun alasannya. Bisa jadi karena mereka memang loyal terhadap warung langganan, atau karena ada niat murni untuk membantu kesejahteraan para driver. Alasan lain yang juga sering muncul adalah karena memasak makanan sendiri bukan keahlian yang dikuasai, sehingga membeli makanan jadi merupakan jalan keselamatan agar tidak keracunan sebab tidak bisa menakar bumbu.
Terkait alasan terakhir di atas, pembahasan tentang keahlian masak-memasak itu sendiri tidak pernah sederhana. Isu masak-memasak bisa jadi sangat rumit ketika jatuh pada bahasan tentang bagaimana majikan memperlakukan juru masaknya dan seberapa pantas gaji yang harus diberikan.
Bahasan lain yang juga bisa jadi sangat rumit adalah tentang peran istri atau ibu di dapur yang sering tidak dianggap sebagai faktor penentu kesuksesan suami di tempat kerja atau prestasi anak-anak di sekolah, sehingga tidak wajib diapresiasi. Sudah dituntut bisa memasak, eh, ketika bisa pun dianggap remeh karena katanya sudah qodrati.
Mengenai tuntutan perempuan bisa memasak, beberapa hari yang lalu seorang teman membagikan cuplikan percakapan Whatsapp dua sejoli yang sedang viral, yang membicarakan rasa dari masakan yang dibuat oleh pihak perempuan, yang kemudian diantar ke rumah pihak laki-laki. Pihak laki-lakinya berkata bahwa sang ibu berpesan agar pihak perempuan tidak usah lagi mengirimkan makanan buatan sendiri ke pihak laki-laki, karena rasanya tidak enak. Pihak laki-laki pun lanjut berkata, “Makanya belajar masak, biar aku yakin buat ngelamar kamu.”
Gagasan patriarkal ini terus beredar, seolah tak lekang oleh waktu. Padahal sudah banyak sekali pemuka agama dan cendekiawan Islam yang menantang serta membongkar salah kaprahnya gagasan ini. Contoh dari “pembongkaran” ini bisa dibaca di sebuah artikel yang berjudul “Memasak dan Mencuci Bukan Kewajiban Istri” di situs NU Online.
Artikel tersebut mengibaratkan istri sebagai “objek penderita” karena adanya tuntutan-tuntutan patriarkal dalam relasi berumah tangga yang tidak setara, salah satunya tuntutan perdapuran. Sementara jika kita boleh memaknai nafkah suami untuk istri secara kaku, nafkah pangan itu bukan termasuk kewajiban istri untuk mengolahnya; istri berhak mendapatkan nafkah pangannya dalam bentuk siap santap di meja makan. Adalah suatu kerelaan jika seorang istri bersedia mengolah pangan di rumah, maka seharusnya tidak ada tuntutan atasnya.
Sayangnya, meski pencerahan-pencerahan seperti ini sudah bukan hal yang baru lagi, tetap saja ada segolongan masyarakat yang terus melanggengkannya. Mungkin karena mereka belum terpapar informasi tersebut, yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah ulama arus utama yang membawa topik ini dalam bahasan tausiyahnya. Selain itu, mungkin saja mereka yang perempuan sudah menginternalisasi patriarki dalam diri, dan yang laki-laki memang sudah telanjur menikmati buaian patriarki ala Indonesia.
Mengapa saya menyebutnya patriarki ala Indonesia? Karena di belahan dunia lain, kemampuan memasak dianggap sebagai genderless survival skill. Seorang teman laki-laki saya yang menempuh pendidikan S-2 di sebuah kota di negeri kincir angin pernah menceritakan pengalamannya diolok-olok teman-teman kuliahnya karena tidak bisa memasak. Mereka betul-betul heran, bagaimana bisa seorang mahasiswa rantau tidak bisa memasak.
Salah satu dari mereka bertanya, “So, you have takeouts all the time? Wait, are you, like, super rich or something?” Sejak saat itu, teman saya ini mengubah cara pandangnya terhadap keterampilan memasak. Kini dia sering mengunggah hasil kreasi masakannya di insta story.
Memasak adalah suatu keterampilan yang bisa dipelajari dan dikuasai lewat praktek, tidak ada bedanya dengan kemampuan membetulkan rantai motor bebek yang lepas dari geriginya di tengah perjalanan. Baik perempuan maupun laki-laki tentu bisa menguasainya, sebab tidak ada batasan qodrati yang menghalangi siapapun untuk memiliki keterampilan itu.
Jadi, keahlian memasak sudah sepantasnya dinormalisasi sebagai suatu kualitas seseorang terlepas identitas gendernya. Sementara kita masih belajar menciptakan masakan yang aman dan lezat untuk dikonsumsi, banyak Mas-mas atau Mbak-mbak, akang atau teteh ojek online yang siap mengatasi kelaparan kita, bahkan saat tengah malam. []