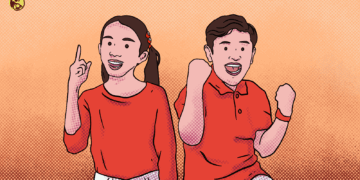Mubadalah.id – Sabtu 13 Juli 2019 saya melakukan perjalanan seorang diri ke ibu kota, Jakarta. Sebenarnya bukan kali pertama saya berkunjung, namun perjalanan kali ini saya benar-benar merasakan gambaran kehidupan di sana. Seperti halnya kota metropolitan, Jakarta tidak jauh berbeda dengan kota besar lainnya, padat, panas, dan macet. Saya terbayang dengan gagasan Fiqih Metropolitan.
Dalam perjalanan minim dana ini, saya harus menghemat pengeluaran dengan memastikan semuanya bernilai ekonomis. Sebenarnya mudah sekali jika bepergian menggunakan layanan ojeg online (Grab/Gojek) untuk mengantar ke tempat tujuan.
Namun untuk meminimalisir pengeluaran, akhirnya saya dan kawan saya memilih jalan kaki, atau menggunakan KRL dan angkutan kota jika masih memungkinkan. Jasa Ojol hanya sebagai opsi terakhir manakala tidak bisa dijangkau oleh ketiganya.
Sekitar pukul 17.00 WIB, kawan saya dan teman-temannya hendak menghadiri resepsi pernikahan di Bekasi, saya pun diajaknya. Kami menggunakan KRL dari stasiun Juanda menuju stasiun Bekasi. Kereta Rel Listrik tersebut sesak dan penuh karena bertepatan dengan jam pulang kerja.
Pukul 18.20 WIB KRL sampai di stasiun Bekasi, kami berempat bergegas menuju mushala stasiun. Bukan hanya kami, para penumpang lainnya pun bergegas ke mushala karena waktu shalat maghrib akan segera berakhir. Mushala stasiun kecil tersebut padat, bahkan untuk sekedar berwudhu saja sulit, tidak ada celah sama sekali.
Kami maju mundur untuk ikut berdesakkan, tapi jika diperkirakan waktu mengantre akan menghabiskan waktu maghrib. Kebimbangan kami tak cukup sampai di situ, dalam antrean yang bercampur laki-laki dan perempuan, juga tempat shalat yang sempit, akhirnya kami memutuskan keluar stasiun dan memesan Grabcar untuk mencari lokasi hajat dan tempat shalat.
Cukup lama kami menunggu di jalanan yang padat merayap tersebut, namun beberapa kali Grabcar membatalkan pesanannya. Batin kami mulai resah saat tidak menemukan mushala di tempat tunggu. Sempat ada pembahasan di antara kami mengenai bagaimana melaksanakan shalat Maghrib yang sudah hampir Isya.
Bagi saya selaku musafir, jarak Indramayu-Jakarta (sekitar 221 KM) sudah lebih dari 2 marhalah (sekitar 81-119 KM menurut ikhtilaf madzahib), juga perjalanan saya tidak bertujuan untuk bermaksiat sama sekali. Maka dalam perjalanan tersebut sah bagi saya untuk berniat dan melakukan shalat qashar dan jama’ takhir. Namun bagaimana dengan ketiga teman saya yang sudah bisa dianggap sebagai mukimin di Jakarta?
Status muqimin dalam istilah fiqih digunakan oleh orang yang melakukan perjalanan lebih dari 80 KM namun berencana untuk menetap di suatu tempat lebih dari 3 hari. Domisili selama lebih dari 3 hari ini bukan untuk menjadi penduduk setempat, karena memungkinkan untuk pulang kembali ke kampung halaman.
Mengenai status muqimin, para ulama madzhab berbeda pendapat, mayoritas mengatakan tidak bisa melakukan qashar maupun jamak. Namun Ibnul Qayyim lebih memilih pendapat bahwa iqamahnya seorang musafir di sebuah negeri tidak mengeluarkan status dia sebagai musafir, baik waktunya lama atau pendek.
Para ulama yang memperbolehkan jamak sepakat bahwa sebab yang memperbolehkan jamak adalah bepergian (lebih dari 2 marhalah). Sedangkan bagi orang yang tidak bepergian dan tentang syarat-syarat memperbolehkan jamak saat bepergian pun berbeda-beda.
Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh Shahih Muslim, “Sekelompok Imam berpendapat, diperbolehkan menjamak shalat saat tidak bepergian karena adanya kebutuhan tertentu dan tidak menjadikannya kebiasaan.” Pendapat ini pun dikuatkan oleh ucapan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan umatnya.
Kebolehan ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Sirrin, Asyhab murid Imam Malik. Al-Khaththabi menghikayatkan pendapat ini dari al-Qaffal, al-Syasyi al-Kabir, murid As-Syafi’i dari Abu Ishaq al-Mawarzi dari sekelompok ulama ahli hadist.
Dengan penjelasan di atas dan dikuatkan dengan kaidah fiqih “al-masyaqqah tajlib at-taysir” kesulitan dapat menarik kemudahan, maka dalam keadaan ini kawan saya diperbolehkan untuk jamak asal dalam keadaan darurat sekali dan tidak dibiasakan,
Namun, saat menunggu kedatangan Grabcar di tepi jalan. Saya berkali-kali berpikir dan mengamati orang-orang berkendara yang terjebak macet. Jika kemacetan tersebut terjadi berulang-ulang dan pengemudi merupakan penduduk asli dan muqimin yang mungkin saja belum menunaikan shalat maghrib saat adzan Isya tiba, apakah prinsip masyaqah juga masih bisa diterapkan? Dan bagaiaman mengukur kadar masyaqah tersebut agar tidak disepelekan?
Saya teringat pendapat yang viral kala itu, saat salah satu pengasuh pesantren di Jombang mengimbau shalat tiga waktu. Kemudian diklarifikasi bahwa imbauan tersebut diperbolehkan hanya untuk pekerja yang sibuk, seperti sopir, tukang becak, dan buruh tani, karena mereka tidak bisa tepat waktu dalam melaksanakan shalat lima waktu. Pendapat ini berlandaskan pada surat Al-Isra’ ayat 78 dan beberapa hadist mengenai jama’ shalat.
Mungkin saja pendapat ini merupakan hasil ijtihadnya, Namun jika melihat ulama Kuffah, maka bisa saja shalat tersebut bukanlah jamak, hanya saja melakukan shalat Zuhur di akhir waktu zhuhur, lalu disambung dengan salat Asar di awal waktu Asar, begitupun dengan Maghrib dan Isya dilakukan secara berdekatan, sehingga terlihat seolah-olah menjamak.
Bukan hanya permasalahan shalat saja, dari perjalanan ini saya juga berfikir tentang wudhu laki-laki dan perempuan yang berdesakkan tersebut. Jika menggunakan mazhab Syafi’i maka akan batal jika tersentuh, kecuali dengan pemahaman “Lams” madzhab lain. Begitu pun mengenai tempat shalat, kesucian pakaian, dan lain-lain.
Dalam permasalahan-permasalahan ini, unsur dan alasan masyaqah bisa saja dipakai, namun seberapa kadarnya juga perlu diperhatikan agar tidak keluar dari batas-batas aturan syariah. Kadar tersebut dapat diukur dengan usaha dan kemampuan setiap pelakunya.
Dalam perjalanan ini, saya sempat mengingat tentang fiqih minoritas yang lahir di kalangan muslim yang berada di negara mayoritas nonmuslim, saya pun terfikir tentang ‘Apakah juga perlu fiqih metropolitan’ mungkin saja diperlukan sebagai panduan amaliah di kota-kota besar yang memiliki permasalahan yang kompleks. Hal ini berdasarkan pengalaman saya yang merasakan berbagai kebimbangan dan keresahan dalam berfiqih di Ibu Kota.[]