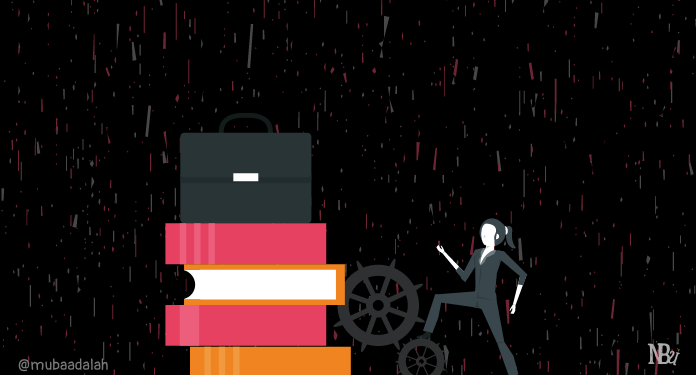Kitab Ta’lim Al-Muta’allim telah memaparkan dengan jelas bahwa menuntut ilmu atau pengetahuan diharuskan bagi laki-laki dan perempuan. Secara eksplisit tanpa harus dijelaskan tafsirannya pun, siapapun juga bisa memahami bahwa menuntut ilmu itu tidak terikat jenis kelamin dan gender. Bahkan, tentu tidak terikat pula dengan waktu dan jarak, hal ini juga dijelaskan dalam kitab yang sama.
Di sini saya memahami bahwa menuntut ilmu bisa di mana saja, baik di bangku ruang-ruang kuliah, seminar, diskusi, majelis-majelis, pengajian-pengajian, atau bahkan nongkrong di warung-warung kopi selama mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Jelas sudah di sini bahwa landasan agama sudah ada, akan tetapi konsep ideal tersebut berbanding terbalik dengan pandangan masyarakat kita.
Sementara di Indonesia, banyak masyarakat yang memberikan label negatif (stereotype) kepada perempuan yang menempuh pendidikan lebih tinggi khususnya di bangku-bangku kuliah. Banyak anggapan bahwa perempuan yang sekolah tinggi adalah hal yang sia-sia atau muspro (tahsilul hasil), karena seberapa lama atau tinggipun perempuan menempuh pendidikan akan balik lagi ke kodrat perempuan yaitu ke dapur, kasur, dan sumur.
Lagi, banyak missunderstanding terhadap interpretasi antara kodrat dan konstruk sosial. Dua konsep yang berbeda namun sering tumpang tindih. Padahal, kodrat adalah sesuatu yang dibawa dari lahir, sederhananya sudah ketentuan, seperti perempuan bisa hamil, menyusui, menstruasi, melahirkan, sementara laki-laki bisa membuahi, dan hal tersebut tidak bisa dipertukarkan.
Sedangkan konstruk sosial adalah label yang dilekatkan kepada seseorang secara sosial maupun budaya, seperti bekerja itu kewajiban seorang suami, sementara istri di rumah. Konstruk sosial yang dibentuk, dilekatkan bahkan dilanggengkan untuk laki-laki maupun perempuan ini sering disebut sebagai peran gender.
Konstruk sosial yang berbeda tersebut melahirkan diskriminasi hak-hak pendidikan terhadap perempuan. Adanya konstruk bahwa perempuan adalah makhluk yang diciptakan untuk melayani dan mengurus kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti mengurus suami, anak, bersih-bersih rumah, memasak, dan bejibun pekerjaan teknis rumah tangga lainnya menjadikan perempuan tidak dapat meraih pendidikan dan mimpi-mimpi mereka.
Mirisnya lagi, perempuan yang tidak bisa melakukan bejibun pekerjaan rumah tangga tersebut dianggap keperempuanannya kurang sempurna atau kalau boleh dikatakan kurang sholehah. Sering saya bertemu orang ketika dia tahu ada teman perempuan saya bisa memasak atau pas lagi mencuci piring, “wah sholehah sekali!”, lho, apakabar kita-kita yang belum bisa masak?
Konstruk yang sudah dijalankan turun-temurun ini menjadi seolah-seolah kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Padahal jika konstruk tersebut melemahkan salah satu pihak harusnya bisa didekonstruk. Tidak hanya laki-laki yang turut melanggengkan konstruk tersebut, perempuan juga turut berpartisipasi, karenanya banyak perempuan yang turut mencibir perempuan lainnya karena dianggap tidak normal dalam standar mereka.
Banyak perempuan yang sekolah tinggi kemudian dikendor-kendori kalau percuma sekolah tinggi-tinggi toh baliknya juga di dapur. Tidak sedikit mereka juga dari orang-orang terdekat. Heran juga kalau ada orang ingin sekolah malah disebut-sebut akan mendominasi dalam rumah tangga kalau sudah berumah tangga.
Kita bisa kembali mendengar pepatah yang mengatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama (al-madrasah al-ula) bagi anak-anaknya. Meskipun tugas mengasuh anak adalah tugas kedua orang tua, bukan ibu saja, kodrat ibu adalah hamil, tapi untuk mengasuh dan mendidik anak adalah tugas bapak ibu.
Analoginya, jika seorang ibu memiliki wawasan dan pendidikan yang luas maka akan berimplikasi kepada pola pikir dan karakter anak-anaknya, juga sebaliknya jika seorang ibu memiliki wawasan yang terbatas anak-anaknya juga tidak akan jauh berbeda. Setidaknya ia akan membuktikan bahwa pendidikan tidak terikat jenis kelamin dan gender.
Idealnya, bukan hanya laki-laki saja yang boleh berwawasan luas, tapi perempuan juga harus berwawasan luas.
Mungkin di luar sana banyak perempuan yang mengalami stereotype semacam ini “nanti jodohnya takut lho mbak!”. Mirisnya, kalimat semacam ini sering keluar dari seorang yang memiliki jenjang pendidikan tinggi menurut standar masyarakat kita.
Saya tidak habis pikir apa yang ditakutin dari seorang perempuan yang mempunyai pengalaman sekolah di bangku-bangku kuliah atau mereka yang aktif di luar sana. Keresahan ini pun terjawab ketika ada teman laki-laki di media sosial menimpali ia berdalih mengkoreksi dari perspektif ia sebagai laki-laki, bahwa laki-laki pada dasarnya mempunyai jati diri sebagai pemimpin, khususnya di dalam rumah tangga.
Dalam pandangan laki-laki, perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan merasa lebih unggul yang kemudian akan memimpin dan menguasai dalam keluarga. Jadi, sepertinya ada kekhawatiran jika akan menikah dengan perempuan yang lebih tinggi pendidikannya secara formal, perempuan akan mendominasi kepemimpinan dalam keluarga.
Hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki pandangan seperti ini memang tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Memang sangat tidak adil bagi perempuan yang menerima pelabelan seperti ini. Kenapa laki-laki yang sekolah tinggi justru mendapat prestise, sementara perempuan mendapat pelabelan, nanti jodohnya takut lho mbak, atau halah toh nanti balik ngurus rumah. Baiklah, memang perempuan yang baik akan mendapat laki-laki yang baik juga lho. Percaya deh! []