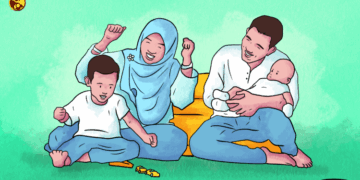Mubadalah.id – Setiap kali kita membicarakan tentang posisi perempuan dalam Islam, kita seakan berhadapan dengan sebuah persimpangan. Di satu sisi, ada Al-Qur’an yang secara harfiah terkesan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Mulai dari masalah kepemimpinan laki-laki, warisan yang cenderung tidak adil, hingga masalah kesaksian yang terkesan meremehkan perempuan.
Di sisi lain, kita juga terbiasa dengan paradigma modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, yang membikin kita merasa miris dengan pemahaman harfiah tersebut. Hal ini sering kali menggiring kita pada dua pilihan yang sama-sama dilematis: Menelan mentah-mentah tafsir tradisional dan mengorbankan rasa keadilan, atau menolak teks tersebut dan mengorbankan keimanan demi keadilan dan kesetaraan.
Di tengah dilema inilah, seorang pemikir Muslim abad ke-20, Fazlur Rahman, menawarkan jalan keluar. Bagi Rahman, masalahnya bukan terletak pada teks Al-Qur’an, melainkan pada cara kita membaca atau menafsirkannya.
Selama berabad-abad, banyak Muslim memperlakukan Al-Qur’an layaknya kitab hukum yang kaku dan statis, yang turun dari langit dan hampa sejarah. Pandangan inilah yang, menurut Rahman, telah “membekukan” pesan-pesan Al-Qur’an yang dinamis dan progresif.
Metode Tafsir Fazlur Rahman
Untuk mencairkan kembali kebekuan itu, Rahman memperkenalkan metode tafsir yang ia sebut “double movement” (gerak ganda). Metode tafsir ini mengajak kita melakukan perjalanan waktu. Gerakan pertama adalah perjalanan kembali ke masa lalu, tepatnya ke Jazirah Arab abad ke-7 saat Al-Qur’an diwahyukan.
Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya membaca teks Al-Qur’an, tetapi juga mencoba untuk hidup di dalamnya. Kita harus bertanya: Apa masalah sosial, ekonomi, dan moral yang sedang masyarakat hadapi saat itu? Mengapa sebuah ayat tertentu turun? Apa konteks spesifik yang melatarbelakanginya?
Bagi Rahman, Al-Qur’an bukanlah serangkaian pernyataan abstrak, melainkan respons Tuhan—melalui pikiran dan kesadaran Nabi Muhammad—terhadap situasi historis di zamannya.
Setelah kita memahami konteks historis dan masalah spesifik yang dijawab oleh sebuah ayat, kita kemudian melakukan gerakan kedua. Dari solusi spesifik yang diberikan Al-Qur’an untuk masalah partikular saat itu, kita harus mengekstrak prinsip moral atau nilai universal yang mendasarinya.
Rahman menyebut ini dengan “ratio legis”—spirit atau ruh di balik hukum tersebut. Prinsip moral atau “ratio legis” inilah yang abadi, bukan bentuk hukum spesifiknya yang terikat oleh ruang dan waktu.
Setelah menemukan prinsip universal itu, kita lalu kembali ke masa kini dan bertanya: Bagaimana kita akan mewujudkan prinsip moral yang sama dalam konteks masyarakat kita yang sudah sangat berbeda? Dengan metode gerak ganda inilah, Rahman membongkar kembali isu-isu perempuan yang selama ini dianggap problematis. Mari kita lihat bagaimana ia menerapkannya.
Membongkar Kembali Isu Perempuan
Pertama, isu poligami. Banyak kalangan yang memandang izin poligami dalam Al-Qur’an (Surat An-Nisa’ ayat 3) sebagai hak istimewa laki-laki yang bersifat universal dan mutlak. Rahman menolak pandangan ini. Dengan gerakan pertamanya, ia membawa kita pada konteks pasca-Perang Uhud, di mana banyak laki-laki Muslim gugur dan meninggalkan banyak janda serta anak yatim.
Poligami, dalam konteks ini, bukanlah tentang memuaskan hasrat laki-laki, melainkan sebagai sebuah solusi praktis untuk masalah sosial yang mendesak saat itu: Melindungi para janda dan anak yatim dari ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan, terutama terkait harta warisan
Kemudian, dengan gerakan keduanya, Rahman mencari prinsip moral di baliknya. Ratio legis dari Surat An-Nisa’ ayat 3 adalah keadilan sosial (social justice). Al-Qur’an bahkan memberikan syarat yang sangat berat: “Jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja.”
Ayat ini, menurut Rahman, sebenarnya menunjukkan bahwa Al-Qur’an sedang bergerak menuju sebuah ideal, yaitu monogami, karena berlaku adil dalam poligami adalah sesuatu yang mustahil.
Poligami diizinkan sebagai solusi darurat saja, tetapi cita-cita moral jangka panjangnya adalah monogami. Jadi, jika di zaman sekarang poligami sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak, maka mempraktikkannya justru bertentangan dengan spirit keadilan yang menjadi ruh (ratio legis) dari ayat tersebut.
Rahman menerapkan metode serupa pada ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan (“qawwamun”, dalam Surat An-Nisa’ ayat 34). Tafsir tradisional sering kali memaknainya sebagai superioritas bawaan laki-laki atas perempuan yang inferior. Rahman membantahnya dengan tegas. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan ini bersifat “fungsional”, bukan “hakiki”.
Dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, laki-laki adalah satu-satunya penopang ekonomi keluarga. Kepemimpinan itu melekat pada fungsi ekonomi mereka. Prinsip moralnya adalah siapa yang bertanggung jawab secara finansial, dialah yang memegang fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga.
Logikanya, jika dalam konteks modern seorang perempuan juga menjadi pencari nafkah dan berkontribusi pada ekonomi keluarga, maka superioritas fungsional laki-laki itu akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali! Jadi, ayat ini bukan tentang superioritas jenis kelamin, melainkan tentang tanggung jawab ekonomi.
Isu Kesaksian dan Warisan
Begitu pula dengan isu kesaksian (dua perempuan setara dengan satu laki-laki) dan warisan (perempuan mendapat separuh bagian laki-laki). Bagi Rahman, semua ini harus dipahami dalam bingkai masyarakat Arab saat itu.
Aturan kesaksian tersebut (Surat Al-Baqarah ayat 282), muncul karena pada masa itu perempuan umumnya tidak terbiasa dengan urusan bisnis dan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan akurasi, bukan karena perempuan tidak bisa dipercaya.
Demikian pula dengan hukum waris. Bagian yang lebih kecil untuk perempuan mencerminkan struktur masyarakat kesukuan di mana laki-laki memikul seluruh beban ekonomi keluarga.
Namun, yang revolusioner pada masanya adalah Al-Qur’an memberikan hak waris kepada perempuan, hak yang sebelumnya tidak pernah ada. Ini menunjukkan “spirit progresif”. Bagi Rahman, ketika struktur sosial berubah, di mana perempuan juga memiliki tanggung jawab ekonomi, maka aturan hukumnya pun harus berubah agar tetap sejalan dengan ratio legis-nya, yaitu keadilan.
Al-Qur’an Arah Menuju Kesetaraan
Melalui analisisnya, Fazlur Rahman menunjukkan bahwa Al-Qur’an bukanlah kitab yang melegalkan patriarki. Sebaliknya, ia adalah dokumen suci yang melakukan reformasi besar-besaran untuk mengangkat derajat perempuan dalam konteks masyarakat yang sangat patriarkal saat itu.
Lebih jauh, Al-Qur’an, dalam pandangan Rahman, menunjukkan “arah” atau “vektor” menuju kesetaraan. Kesalahan para ahli fiqih klasik, menurutnya, adalah mereka membekukan hukum-hukum spesifik dan menganggapnya final, tanpa melihat konteks historis dan arah moral yang dituju oleh Al-Qur’an. Mereka lebih fokus pada bunyi harfiah teks daripada spirit progresif yang terkandung di dalamnya.
Pemikiran Rahman ini membebaskan kita dari keharusan memilih antara iman dan akal budi. Ia menunjukkan bahwa menjadi Muslim yang taat tidak berarti harus menerima ketidakadilan gender. Sebaliknya, justru dengan memahami spirit keadilan dalam Al-Qur’an, kita didorong untuk terus memperjuangkan kesetaraan di zaman kita.
Ia mengajak kita untuk tidak lagi memandang Al-Qur’an sebagai fosil dari masa lalu, tetapi sebagai sumber inspirasi moral yang terus hidup dan dinamis, yang berbicara dan menantang kita untuk membangun dunia yang lebih adil bagi semua, laki-laki maupun perempuan. []
Daftar Pustaka
Ali Akbar. ‘Contemporary Perspectives on Revelation and Qur’ānic Hermeneutics’. Edinburgh University Press: Edinburgh, 2020.