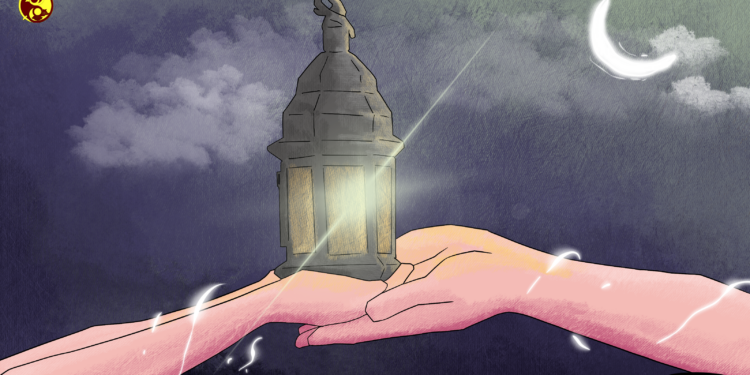Mubadalah.id – Tatkala kita (berkenan) mengunjungi saudara-saudara kita sesama muslim, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), di dalam tempat mereka kita akan segera menemukan tulisan: Love for All Hatred for None. “Cinta kasih untuk semuanya, tanpa kebencian (atas) satu dan apapun”. Begitulah kira-kira saya pribadi memahami maknanya.
Barangkali makna yang terkandung dalam tulisan tersebut adalah mimpi besar refleksi kemanusiaan yang kita inginkan terjadi selama ini. Tak bisa dielak, bahwa kita sesungguhnya amat mendambakan cinta kasih dalam kepengapan kemanusiaan yang terus menderu dalam paru-paru kehidupan batin kita.
Keruh mata air kemanusiaan yang tak kunjung bening, semakin memperburuk nuansa silaturahmi kita—baik dalam koordinat keberagamaan atau kemanusiaan itu sendiri. Kita memimpikan cinta kasih kemanusiaan yang serius, tulus, dan suci.
“Love for All Hattred for None”—yang saya pahami sebagai semacam adagium—boleh jadi sangat Ahmadi (sebutan lain dari: JAI) sentris, layaknya NU dengan komitmen tawasuth-nya, atau Muhammadiyah dengan semangat fastabiqul khairat-nya, maupun Indonesia dengan Pancasila serta “Bhinneka Tunggal Ika”-nya.
Kendati sangat Ahmadi sentris, mari kita pahami maksud nilai adagium tersebut dalam komitmen mereka terhadap soal-soal kemanusiaan.
Komitmen Kemanusiaan Ahmadi
JAI sendiri, sebagai “ormas” Islam, misalnya, mungkin tidak cukup familiar bagi kebanyakan telinga kita. Lebih-lebih tentang adagium “Love for All Hattred for None” yang memang identik Ahmadi itu. Bertambah posisinya sebagai minoritas, sekaligus, adanya stereotipe “politis” yang melekat pada Ahmadi semakin susah tergapai oleh mata pandang pemahaman “tolerantif” kebanyakan kita.
Sebaliknya, Ahmadi malah kebanyakan kita kenal sebagai “sekte” Islam yang menyimpang. Padahal, saya, memahami banyak hal tentang komitmen kemanusiaan, baik secara konkret dan teoritis-filosofis. Justru ketika berkesempatan bertukar pikiran dengan saudara-saudara Ahmadi.
Komitmen yang seyogyanya tidak hanya harus dilakukan pula oleh “sekte-sekte” Islam lain, tetapi juga oleh siapapun yang memang memberikan klaim dirinya: manusia. Layaknya tugas dasar kemanusiaan itu sendiri. Bahwa kita mesti selalu memanusiakan manusia.
Berkesempatan bertemu, sekaligus berdiskusi, bersama saudara-saudara Ahmadi—pertama kali di Solo, kemudian di Semarang—menjadi pengalaman yang menarik bagi perjalanan kemanusiaan, khususnya bagi saya pribadi.
Ada hal baru yang lebih membuka mata pikiran saya terkait arti penting kemanusiaan. Keramahan, toleransi, rasa damai, dan cinta kasih itu sendiri menjadi jalan pilihan saudara-saudara Ahmadi yang saya pribadi pahami. Untuk tidak menyebutnya kita semua—dalam setiap gerak dakwah “spritualitas” mereka semenjak Mirza Ghulam Ahmad dirikan di India pertama kalinya hingga masa kepemimpinan Mirza Masroor Ahmad hari ini.
Kiprah JAI
Tentu saja, kita boleh tidak setuju, bahkan berhak memberikan argumentasi tandingan dengan paham keagamaan yang saudara-saudara Ahmadi tafsirkan. Terutama dalam hal-hal yang sifatnya “teologis” yang mereka bawa.
Akan tetapi, dalam hal sosial-kemanusiaan, rasa-rasanya kita agaknya perlu banyak belajar kepada kiprah dan perjuangan mereka. Kita perlu sedikit banyak meniru apa yang telah masif dilakukan oleh saudara-saudara Ahmadi kepada saudara-saudara sesama yang lain dalam urusan kemanusiaan.
Sebagai contoh, persis yang Bapak Muhaimin sampaikan di Jemaat Ahmadi Solo dan Bapak Syaifulloh di Jemaat Ahmadi Semarang, JAI dalam kiprahnya telah banyak memberikan kontribusi sosial bersama Humanity First, Giveblood Community, dan Clean The City.
Bahkan, JAI juga memperoleh penghargaan dari MURI di tahun 2017 sebagai komunitas dengan jumlah calon donor mata terbanyak se-Indonesia. Hal-hal yang, tentu saja, mesti pula kita semua lakukan demi tumbuhnya kemanusiaan yang lebih masif. Dan, JAI mempelopori itu.
Alteritas JAI sebagai Refleksi Kemanusiaan
JAI, adalah satu dari sekian banyak tipologi tafsir keagamaan Islam yang beragam. Kemudian—sebutlah—menjadi: salah satu ormas Islam. JAI bukan mayoritas dominan. Karena itu, dalam konstelasi peta aliran keagamaan (Islam) di Indonesia, JAI adalah minoritas. Hidup dalam lingkup komun kecil, tak banyak kita kenal, tak cukup kita pahami. Sebaliknya, keberadaannya justru amat sering “disalahpahami”, bahkan dipersekusi.
Kita bisa mencari sendiri berbagai macam berita masa lalu yang sering menyuguhkan bagaimana saudara-saudara Ahmadi terdiskriminasi dan dipersekusi keberadaannya. Pembakaran masjid, misalnya, menjadi hal umum mereka alami.
Tapi, yang sungguh menarik, dalam kondisinya yang sering dipersekusi semacam itu mereka justru menyikapinya dengan cinta kasih yang arif dan damai. Tidak ada keinginan terbesit menyerang balik. Setidaknya itu yang Bapak Muhaimin katakan sebagai ketua JAI Solo.
Mereka sering kali menjadi korban dari keganasan tata kelola perpolitikan nasional kita—khususnya, dalam isu-isu keagamaaan yang notabene memang amat sensitif. Dan, tidak masuknya kiprah arah gerak mereka dalam domain-domain politik. Saya pikir, juga menjadi hal yang amat penting kita pahami dari “misi dakwah” mereka.
Barangkali itulah “jalan suci” yang mereka tempuh untuk menyukseskan “misi kemanusiaan” mereka agar terhindar dari bias conflict of interest. Sesuatu hal yang agaknya perlu pula kelompok-kelompok Islam lain refleksikan, tumbuhkan, dan realisasikan.
Berjumpa dengan Wajah yang Lain
Maka itu, di tengah-tengah keringnya kita dalam hal toleransi dan cara pandang sikap yang multikultural, JAI sesungguhnya adalah sekian dari banyaknya alteritas yang—(Wajah)—eksistensinya perlu kita pahami sungguh-sungguh. Alteritas itu, sebagaimana dalam istilah Levinas, merupakan sebuah “sapaan”.
Artinya, ketika kita berjumpa dengan “Wajah Yang Lain”, secara otomotis, Wajah tersebut akan membuka ruang yang harus kita sapa dan pahami. Yakni, alteritas “Orang Lain” tersebut.
Melalui alteritas itu, keberadaan JAI sejatinya tidaklah ingin menegasikan suatu kesamaan. Tetapi lebih untuk mengundang kita agar berani mencoba keluar dari kejumudan “imananesi” sikap dan cara pandang. Tujuannya supaya lebih berkenan “mentransendensikan” diri kita bersama “Wajah Yang Lain” tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks ini, “Wajah Yang Lain” itu, adalah JAI.
Keberadaan JAI sejatinya mengundang kita untuk menyediakan diri berkenan memahaminya—mengambil pelajaran darinya. Hal inilah yang kemudian menuntut kita untuk berinteraksi dengan JAI tersebut melalui percakapan atau dialog. Dan dalam dialog itu kita mesti “menyapa” JAI.
Upaya Dialog
Dalam upaya dialog tersebut, apa yang kita bicarakan (tema percakapan) harus selalu dimulai oleh orang yang kita sapa. Artinya, dalam konteks ini, kita tidak semestinya memaksakan apa yang ingin kita bicarakan kepada JAI.
Biarkan JAI mengungkapkan terlebih dahulu pikirannya, sesudah itu barulah kita berbicara. Jadi, inisiatif percakapan, dalam logika dan etik dialog ini, mestilah selalu datang dari mereka (saudara JAI), bukan dari kita. Hal demikian menjadi sangat penting untuk mengkritik asumsi-asumsi negatif kita, yang barangkali, selalu melekat secara stereotipe dalam cara kita memandang mereka-mereka yang berbeda dengan kita.
Itulah yang sejatinya hendak Levinas tekankan, dalam alteritas “Wajah Yang Lain”, sehingga dalam saat kita memahami kelompok-kelompok minoritas berarti kita menyapa mereka dan membiarkan mereka mengungkapkan apa yang ia pikirkan terlebih dahulu.
Bukan sebaliknya. Ini pulalah sesungguhnya basis nilai filosofis yang beririsan sama sekali dengan prinsip cara pandang multikulturalisme. Entah dalam domain ko-eksistensi maupun pro-eksistensi, di mana kita terkadang teramat terburu-buru menilai bahkan menghukumi orang-orang lain layaknya: “polisi moral”.
Saling Silaturahmi
Dalam kebutuhan multikulturalisme di Indonesia, saya pikir, kita amat mendambakan sikap saling silaturahmi demikian itu. Menyemai cara pandang tolerantif terhadap “yang lain”. Mereka “yang lain” itu adalah mereka yang mesti pula kita pahami tanpa memberikan intervensi penilaian, tanpa diskrimiasi cara pandang, tanpa persekusi eksistensial.
Karena, mereka-mereka itu—kelompok minoritas—sebagai “Wajah Yang Lain”, sesungguhnya hadir sebagai ajakan etis agar kita berkenan berlaku adil dan melakukan kebajikan demi kebajikan dalam segal hal-ihwal kemanusiaan.
Lebih dari itu, selain sebagai undangan moral, kehadiran “Wajah Yang Lain” sejatinya bertujuan pula mengeliminasi potensi kekerasan dalam diri kita terhadap yang lain. “Wajah Yang Lain”, dalam setiap keberadaannya dalam kehidupan kita, sesungguhnya selalu membawa pesan perdamaian.
Betapapun mereka tidak mengatakan apa-apa kepada kita, tetapi tatapan keberadaannya sejatinya bermakna: mencegah kita untuk tidak memperlakukan mereka-mereka (yang lain) dengan kekerasan.
JAI hanyalah contoh, dan masih ada banyak lagi kelompok-kelompok yang tidak cukup mendapatkan cara pandang tolerantif dalam konstelasi silaturahmi kemajemukan masyarakat kita. Maka itu, mari kita mulai benih-benih menyemai kemanusiaan, dengan memandang siapapun dan apapun jenisnya, dalam posisinya yang sama-sama sebagai: manusia. Urusan kemanusiaan adalah urusan kita bersama, entah dari golongan mana dan apapun. []