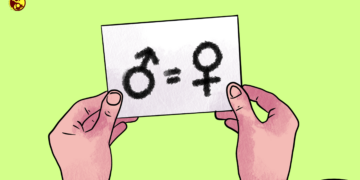Mubadalah.id – Berbagai negara, seperti Sri Lanka, India, Jerman, dan Indonesia, telah berhasil memilih perempuan sebagai kepala pemerintahan di berbagai era. Sri Lanka membuka jalan pada 1960 dengan Sirimavo Bandaranaike sebagai perdana menteri perempuan pertama di dunia, diikuti oleh Margaret Thatcher di Inggris dan Angela Merkel di Jerman, yang memimpin untuk waktu yang lama.
Bahkan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Pakistan dan Indonesia, telah memiliki pemimpin perempuan, menunjukkan bahwa tantangan budaya dan agama bukanlah penghalang mutlak bagi perempuan untuk mencapai posisi tertinggi. Namun, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, fakta ini mengungkap paradoks dalam lanskap demokrasi global.
Mengklaim sebagai salah satu negara demokrasi paling maju, Amerika Serikat ternyata belum pernah memilih seorang perempuan sebagai presiden. Kegagalan Hillary Clinton pada 2016 dan Kamala Harris pada 2024 menggambarkan betapa kandidat perempuan masih menghadapi hambatan yang kompleks, baik dari segi gender maupun narasi politik yang kurang mendukung, meskipun secara teknis mereka memiliki peluang yang sama.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun AS telah mencapai banyak kemajuan dalam kesetaraan gender, terutama di bidang politik, masih ada resistensi yang mendalam terhadap kepemimpinan perempuan pada posisi tertinggi, yang kontras dengan pencapaian negara-negara lain.
Donald Trump dan Kemenangannya
Kemenangan Donald Trump atas Kamala Harris dalam pemilu 2024, yang sekali lagi menghalangi Amerika Serikat memiliki presiden perempuan, dapat kita analisis penyebabnya. Pertama, kegagalan Harris untuk mencapai posisi tertinggi dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki mencerminkan adanya bias gender yang kuat dalam politik elektoral.
Feminisme menunjukkan bahwa perempuan seringkali kita nilai dengan standar yang lebih ketat dibandingkan laki-laki, termasuk dalam hal penampilan, sifat keibuan, dan komitmen terhadap keluarga. Dalam konteks ini, bias gender menjadi hambatan struktural yang mengurangi peluang perempuan untuk mencapai jabatan eksekutif tertinggi, meskipun mereka telah berpartisipasi penuh dalam ranah politik.
Selain itu, perspektif demokrasi yang berfokus pada representasi menyoroti ketimpangan dalam representasi perempuan dalam pemerintahan. Gagalnya Harris untuk memenangkan pemilu memperkuat pandangan feminis radikal, yang menyatakan bahwa demokrasi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, masih memihak laki-laki karena berakar pada sistem patriarki yang kuat (MacKinnon, 1989).
Demokrasi seharusnya memberikan representasi yang adil. Tetapi dengan terpilihnya kembali kandidat laki-laki yang lebih tradisional seperti Trump, terlihat bahwa sistem ini tidak sepenuhnya netral gender dan cenderung mendukung status quo.
Terakhir, fenomena “glass ceiling” masih membatasi akses perempuan pada posisi kekuasaan tertinggi. Dalam pandangan feminisme struktural, meskipun perempuan memiliki hak formal yang sama, budaya patriarki masih membuat masyarakat Amerika enggan untuk mempercayakan posisi presiden kepada perempuan.
Glass ceiling ini mencerminkan adanya hambatan kultural dan psikologis dalam sistem demokrasi, di mana kandidat perempuan sering mereka anggap kurang kompeten atau kurang kuat untuk memimpin daripada laki-laki. Akibatnya, struktur kekuasaan di Amerika Serikat, yang tampaknya terbuka, sebenarnya tetap membatasi representasi perempuan pada jabatan politik tertinggi.
Kekalahan Kamala Harris dan Hillary Clinton: Sebuah Perbandingan
Kekalahan Kamala Harris dalam pemilu 2024 melawan Donald Trump memiliki kesamaan dan perbedaan dengan kekalahan Hillary Clinton pada 2016. Terutama kita lihat dari perspektif tantangan politik gender, pengaruh narasi politik, dan persepsi publik terkait identitas kandidat. Dari sisi tantangan politik gender, baik Clinton maupun Harris menghadapi hambatan serupa.
Clinton pada 2016 menerima banyak kritik berdasarkan aspek gender seperti karakter keibuan, penampilan, dan citra “hangat” yang dianggap penting bagi kandidat perempuan (Paxton & Hughes, 2017). Demikian pula, Harris, meski lebih muda dan mewakili kelompok minoritas, tetap menghadapi kendala gender yang mendalam, menunjukkan keberlanjutan adanya “glass ceiling” dalam politik Amerika Serikat (Crenshaw, 1991).
Fenomena ini mencerminkan bias struktural dalam masyarakat yang mengklaim sebagai demokrasi maju, namun masih menghalangi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan tertinggi.
Narasi politik yang dominan turut memberikan perbedaan dalam pengalaman kekalahan keduanya. Clinton, yang sudah lama berada dalam panggung politik nasional sebagai mantan Senator dan Menteri, menjadi sasaran berbagai teori konspirasi dan narasi negatif yang kerap dikaitkan dengan posisinya.
Di sisi lain, Harris lebih terkenal sebagai tokoh progresif yang dianggap sebagian pihak belum memiliki “pengalaman” yang cukup, meski telah menjabat sebagai Wakil Presiden. Narasi ini menunjukkan adanya preferensi publik yang berdasarkan pada persepsi keterlibatan dan stabilitas, di mana kandidat yang lebih muda atau dianggap terlalu “progresif” sering dihadapkan pada keraguan atas kompetensi mereka.
Pendekatan Feminisme Interseksional
Perbedaan yang signifikan juga terlihat dari persepsi publik terkait identitas kandidat yang mencakup ras dan etnis. Clinton, sebagai perempuan kulit putih, menghadapi bias gender; namun Harris, sebagai perempuan keturunan India dan Jamaika, berhadapan dengan interseksionalitas kompleks yang mempertemukan bias gender dan ras (Hooks, 2000).
Pendekatan feminisme interseksional menekankan bahwa perempuan dari ras minoritas menghadapi tantangan yang lebih berat dalam dunia politik daripada perempuan kulit putih. Hal ini berdampak pada persepsi publik terhadap Harris sebagai calon pemimpin.
Kekalahan Harris dan Clinton, karenanya, mencerminkan bahwa bias gender-struktural dan rasial masih berakar kuat dalam sistem demokrasi Amerika Serikat, dan bahwa perjuangan untuk representasi perempuan, khususnya dari kelompok minoritas, masih menghadapi hambatan yang besar (Collins, 2009; Crenshaw, 1991).
Perbandingan Pemilu 2016 dan 2024: Demokrasi, Gender, dan Bias Struktural
Perbandingan hasil pemilu 2016 dan 2024, yang keduanya dimenangkan oleh Donald Trump atas kandidat perempuan—Hillary Clinton pada 2016 dan Kamala Harris pada 2024—mencerminkan kompleksitas dalam demokrasi yang masih menghadapi bias gender struktural. Demokrasi menekankan prinsip representasi setara, idealnya setiap kandidat memiliki peluang adil dalam pemilihan umum.
Namun, baik pemilu 2016 maupun 2024 menunjukkan kesulitan kandidat perempuan untuk mencapai jabatan tertinggi. Khususnya karena faktor Electoral College yang dapat menguntungkan kandidat konservatif yang mengusung nilai tradisional (Levitsky & Ziblatt, 2018).
Ini relevan dalam konteks kekalahan Clinton, yang meski memenangkan tiga juta suara populer, tetap kalah di Electoral College. Hal serupa terjadi pada Harris pada 2024, di mana struktur ini mempertahankan dominasi kandidat pria.
Diskriminasi yang Clinton alami dan Harris memiliki lapisan yang berbeda. Identitas gender dan ras selalu mempengaruhi tantangan yang perempuan hadapi, terutama dalam peran kepemimpinan publik (Crenshaw, 1989; Collins, 2000).
Clinton menghadapi hambatan utama terkait bias gender yang menekankan pada “karakter feminin,” sedangkan Harris, sebagai perempuan kulit berwarna, menghadapi diskriminasi berlapis yang mencakup gender dan ras, yang memperburuk penerimaan publik atas perannya (Carroll & Fox, 2018).
Diskriminasi yang dialami Harris menunjukkan tantangan yang lebih besar bagi kandidat perempuan dari latar belakang minoritas dibandingkan perempuan kulit putih.
Narasi Patriarkis
Dinamika elektoral dalam kedua pemilu ini juga memperlihatkan kesinambungan narasi patriarkis, yang mengarahkan opini publik untuk mendukung kandidat pria. Narasi yang didorong Trump, yang menekankan ketidakpercayaan pada kandidat perempuan dan menyerang karakter Clinton maupun Harris secara personal, menyoroti bahwa kesetaraan demokratis dalam pemilu masih terhalang oleh stereotip gender (Dittmar, 2018; Jamieson, 1995).
Peran narasi ini menegaskan bagaimana sistem elektoral dan budaya politik Amerika Serikat masih jauh dari representasi yang sepenuhnya adil bagi perempuan.
Pada kampanye 2016, Trump menyebut Clinton sebagai “politisi umum” yang banyak berbicara tanpa aksi nyata. Fakta ini menegaskan bahwa Trump memiliki “sifat yang lebih baik,” untuk memperkuat persepsi bahwa pria lebih cocok sebagai pemimpin yang tegas (Carroll & Fox, 2018). Strategi ini tidak hanya menekankan pada “kelemahan” kandidat perempuan dalam hal ketegasan tetapi juga menciptakan bias publik yang merugikan.
Selain serangan akan kompetensi, Trump menggunakan narasi yang berfokus pada skandal untuk mengurangi kredibilitas Clinton. Pada 2016, Trump sering kali mengaitkan Clinton dengan berbagai skandal yang melibatkan suaminya, Bill Clinton. Terutama tuduhan pelecehan seksual, yang digunakan untuk merusak reputasi Clinton baik sebagai politisi maupun sebagai figur perempuan.
Retorika Bias Gender
Taktik ini secara efektif memanfaatkan stereotip gender negatif dan narasi kultural tentang dukungan pada sesama perempuan. Meskipun tidak ada skandal serupa yang dapat dimanfaatkan melawan Harris pada 2024, Trump tetap menggunakan retorika bahwa pandangan progresif Harris adalah “berbahaya” dan “radikal,” menggambarkannya sebagai ancaman bagi nilai-nilai tradisional (Burns, 2020; Sides, Tesler, & Vavreck, 2019).
Terakhir, Trump sering kali mempertanyakan legitimasi proses pemilu dengan retorika yang bias gender. Pada 2016, ia menggambarkan kekalahan Clinton sebagai kegagalannya dalam politik dan mengaitkan kekalahan Harris pada 2024 sebagai bukti resistensi publik terhadap kepemimpinan perempuan di posisi tertinggi.
Melalui strategi ini, Trump menggunakan bias budaya untuk merusak citra Clinton dan Harris, mempertegas pandangan bahwa kekalahan mereka adalah hasil “kekurangan” karakter kepemimpinan mereka yang terkait dengan stereotip gender (Valentino, Wayne, & Oceno, 2018).
Kesimpulan
Tanpa adanya perempuan yang bisa mendobrak glass ceiling, Amerika Serikat akan terus berada dalam kontradiksi demokrasi yang mendalam. Sebagai negara yang mengklaim sebagai pemimpin demokrasi global, AS tetap menghadapi kegagalan mendasar dalam menciptakan akses sejati yang inklusif dan setara bagi semua, terutama pada level tertinggi kepemimpinan.
Hambatan-hambatan struktural dan kultural masih mengakar kuat dalam proses pemilihan. Di mana perempuan terus menghadapi bias gender yang menahan potensi mereka untuk berpartisipasi secara setara.
Dalam sistem demokrasi yang sesungguhnya, setiap individu, terlepas dari gender, berhak atas peluang yang sama dalam mencapai jabatan tertinggi. Kegagalan kandidat perempuan di AS, mulai dari Hillary Clinton hingga Kamala Harris, menunjukkan bagaimana norma patriarkal masih menjadi penghalang dalam pemilihan presiden. Situasi ini membuat sistem demokrasi AS tidak sepenuhnya merepresentasikan prinsip-prinsip keterwakilan yang inklusif.
Hal ini kontras dengan negara-negara lain yang telah memiliki pemimpin perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa glass ceiling ini lebih dari sekadar hambatan individual, tetapi merupakan cerminan dari bias dalam sistem demokrasi itu sendiri.
Secara keseluruhan, kemenangan Trump melawan Harris menunjukkan bahwa masih ada hambatan sistemik dan kultural yang harus perempuan hadapi dalam arena politik. Bahkan di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat.
Selama struktur politik AS tidak memberi ruang yang adil bagi perempuan untuk melampaui batasan ini. Negara ini tidak akan mencapai demokrasi yang benar-benar representatif. Demokrasi yang hanya menampilkan suara laki-laki pada tingkat eksekutif tertinggi mengingkari esensi kesetaraan, yang seharusnya menjadi dasar dari sistem politik negara. Oleh karena itu, hanya dengan menghancurkan glass ceiling ini, AS dapat membuktikan komitmennya sebagai negara demokrasi yang inklusif dan benar-benar setara. []
Daftar Pustaka
1. Carroll, S. J., & Fox, R. L. (2018). Gender and elections: Shaping the future of American politics. Cambridge University Press.
2. Collins, P. H. (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Routledge.
Routledge
3. Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum.
4. Hooks, B. (2000). Feminist theory: From margin to center. Pluto Press.
5. Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown. Penguin Random House
6. MacKinnon, C. A. (1989). Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press.
7. Paxton, P., & Hughes, M. M. (2017). Women, politics, and power: A global perspective. SAGE Publications.
8. Sides, J., Tesler, M., & Vavreck, L. (2019). Identity crisis: The 2016 presidential campaign and the battle for the meaning of America. Princeton University Press.
9. Valentino, N. A., Wayne, C., & Oceno, M. (2018). “Mobilizing sexism: The interaction of emotion and gender attitudes in the 2016 US presidential election.” Public Opinion Quarterly, 82(S1), 213-235.