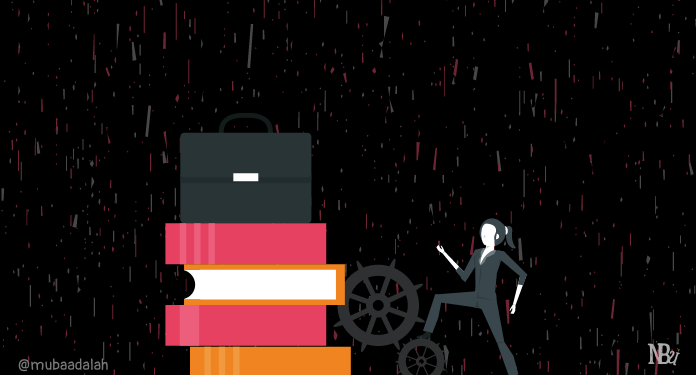Sebelummya, saya memiliki—beberapa teman perempuan di kelas filsafat, dan selama saya duduk di kelas tersebut, saya merasa bahwa mereka nampaknya kurang menikmati diskursus—yang mendalam seperti filsafat. Ini ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam kelas filsafat itu tak seaktif ketika mereka mengikuti kelas-kelas lain, seperti kelas fiqih atau sejarah.
Ini membuat saya berpikir, bahwa mungkin perempuan memang—kurang menaruh perhatian pada persoalan-persoalan filosofis. Perempuan mungkin cenderung tertarik—pada masalah-masalah yang lebih praktis dan mudah dipahami dengan cara yang (seharusnya) jua lebih sederhana.
Seperti apa yang pernah dikatakan oleh penulis eksistensialis, Mary Warnock bahwa “perempuan memang cenderung lebih mudah bosan dengan persoalan filosofis dibanding laki-laki, karena filsafat tampaknya kurang menarik di mata perempuan ketika ia mulai menjadi serius.”
Menurut saya, kurangnya filsuf perempuan hari ini sebenarnya bukan karena ketidakadaan bakat mereka tetapi karena kerapuhan semangat filsafat itu sendiri. Berbeda dari masa-masa awal, filsafat kini pada praktiknya mungkin hanya sekadar menjadi bacaan kering di dalam kelas.
Hal ini juga tak terlepas dari fakta bahwa buku teks filsafat kita memiliki kesadaran relasi gender yang buruk; dari semua penulis-penulis filsafat, hanya sedikit saja dari kalangan perempuan yang menjadi penulis atau kritikus filsafat seperti Sachiko Murata atau Nawal El-Saadawi. Inilah jawaban mengapa kita lebih banyak mengenal filsuf laki-laki daripada perempuan.
Apakah perbedaan tersebut mencerminkan fakta yang tidak dapat diubah tentang sejarah filsafat kita? Saya kira tidak. Itu bisa diperbaiki apabila kesadaran dan pengetahuan kita akan kesetaraan kualitas setiap orang (terlepas dari gender) bertumbuh.
Namun begitu, ini bukan berarti bahwa perempuan secara inheren tidak memiliki kualitas dalam berpikir filosofis. Saya kira ini hanya sekadar persoalan minat—antara suka atau tidak suka sahaja, laiknya kurangnya minat laki-laki pada urusan dapur—karena saya percaya bahwa setiap orang memiliki kualitas kognitif yang sama meskipun dengan minat yang berbeda. Bahkan mungkin saya lebih banyak memiliki teman laki-laki yang tidak menyukai filsafat, daripada teman perempuan yang tidak menyukai filsafat.
Terlepas dari itu, meskipun tampak bahwa hanya laki-laki saja yang getol membicarakan persoalan filosofis (olehnya dunia memiliki sejarah patriarki yang pantas untuk disalahkan).
Namun dalam sejarah, ada beberapa perempuan pemberani, brilian, dan menginspirasi yang pernah melakukan dobrakan masif dan berpengaruh pada wacana filsafat kita bahkan sampai terasa hingga hari ini, meskipun perempuan-perempuan ini jarang terabadikan dalam buku standar filsafat pada umumnya. Kita boleh menyebut mereka sebagai “filsuf perempuan yang terlupakan” atau apapun itu. Berikut adalah enam filsuf perempuan yang saya kira perlu untuk diketahui.
1. Hypatia (350-370 M)
Ia merupakan pengikut mazhab Neo-Platonisme yang banyak mengembangkan ide Plotinus di Alexandria. Olehnya dia begitu terkenal di masanya.
Selain filsuf, ia juga adalah seorang matematikawan dan ahli astronomi. Dia—telah mengajarkan beragam ide yang berkaitan dengan realitas dan bagaimana cara manusia dalam memahami realitas. Sebagaimana para pengikut Neo-Platonis lain, dia juga percaya bahwa segala sesuatu—berasal dari “yang satu”—dan bahwa manusia tidak akan dapat memahami segala realitas dunia secara lengkap.
Pada Maret 415, Hypatia dibunuh oleh sekelompok Kristen yang dipimpin oleh seorang lektor yang bernama Petros. Pembunuhan Hypatia tersebut mengguncang kekaisaran dan menjadikannya sebagai seorang “martir filsafat” yang digadang-gadang setara dengan leluhur filsafat, Socrates. Kematian Hypatia tersebut, tentu saja, menyebabkan tokoh-tokoh Neo-Platonis sesudahnya, termasuk Damaskios, marah dan berubah masif dalam mengkritik agama Kristen.
2. Tullia d’Aragona (1510-1556 M)
Tullia d’Aragona, ia merupakan putri tidak sah dari seorang kardinal dan pelacur. Ia dikenal di seluruh Italia karena kecantikannya dan keahlian retorikanya, mulai dari sastra hingga filsafat.
Teks filsafat terkenalnya adalah ‘Dialogues on the Infinity of Love’ (1547), sebuah karya yang berbau Neo-Platonis yang membahas tentang perlunya kebebasan seksual dan juga emosional perempuan dalam cinta romantis.
Dalam buku tersebut ia berpendapat bahwa semua dorongan seksual itu tidak terkendali dan juga bukan sebuah kecacatan. Ia menilai bahwa dorongan seksual merupakan kombinasi dari spiritualitas yang dapat menciptakan—moral cinta.
Olehnya, satu-satunya cara agar cinta menjadi mulia, menurutnya, adalah jika pria dan wanita saling menerima dan mengakui hasrat seksual dan spiritual mereka (tubuh dan jiwa mereka).
3. Anne Conway (1631-1679 M)
Terlahir sebagai Anne Finch, dia belajar filsafat secara langsung—bersama saudara tirinya John Finch—di bawah bimbingan Henry More di Cambridge. Selain saudaranya, suaminya pun juga tertarik pada filsafat. Namun demikian, Conway tetap jauh melampaui suaminya dalam hal filsafat, baik dalam hal kedalaman pemikiran maupun keragaman minatnya.
Karena kecerdasannya tersebutlah, More pernah mengatakan bahwa ia “jarang bertemu dengan seseorang, pria atau wanita—yang lebih baik daripada Lady Conway.” Tak heran, ide filsafatnya kemudian banyak mempengaruhi gagasan-gagasan filsafat setelahnya, salah satunya berpengaruh pada tokoh penting mazhab Rasionalisme: Gottfried Leibniz (1646-1716).
4. Marry Wollstonecraft (1759-1797 M)
Ia lahir dari keluarga yang boleh dikata amburadul; ayah dengan sifat kasar yang suka memukul saat mabuk, dan seorang ibu yang tidak bisa apa-apa. Hal itu membuatnya kabur dari rumah, dan mulai bergelut di dunia kepenulisan sembari menjadi seorang guru.
Karyanya yang paling terkenal ialah ‘A Vindivcation of the Rights of Woman’ (1792). Pada buku ini, sangat jelas terlihat kebenciannya terhadap pemikiran orang-orang yang menilai perempuan sebagai perhiasaan rumah tangga yang tidak berdaya. Ia juga menulis bahwa wanita secara alamiah setara dan tidak lebih rendah dari laki-laki.
Menurutnya, perempuan terlihat lebih rendah karena mereka tidak memperoleh pendidikan yang layak. Maka, tak jarang ia menegaskan agar laki-laki dan perempuan musti dianggap setara, dan untuk menyukseskan kesetaraan tersebut—adalah penting untuk mengubah sistem pendidikan yang ada dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki.
5. Simone de Beauvoir (1908-1986 M)
Jika kita membuka buku-buku sejarah pemikiran eksistensialisme pada umumnya, adalah lazim terjadi apabila filsuf yang satu ini jarang kita temukan. Padahal dia merupakan satu dari sekian banyak tokoh yang paling berpengaruh dalam mazhab ini, yang bahkan tak kalah hebat dari sang kekasih Jean Paul Sartre, atau tokoh-tokoh eksistensialis lain seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Albert Camus, dan Martin Heidegger.
Mengapa ini bisa terjadi? Apa sebenarnya perbedaan antara Beauvoir dan para filsuf laki-laki tersebut yang karyanya diidentifikasikan sebagai pemikiran eksistensialisme? Jawabannya dapat Anda temukan dengan membaca secara kritis sejarah filsafat kita.
Namun demikian, meskipun ia kurang kesohor sebagai filsuf eksistensialisme, Simone sangat masyhur dalam barisan feminisme melalui bukunya ‘The Second Sex’ (1949) yang menguraikan dasar teori eksistensialisme feminis.
Dalam buku tersebut, ia percaya bahwa pria menjadikan wanita sebagai sesuatu ‘yang lain’ atau the second sex, agar supaya mereka menjadikan diri mereka seolah lebih tinggi dan mulia dari perempuan—menempatkan perempuan di sudut sejarah—dan di balik bayang-bayang laki-laki.
Bagi Beauvoir, pemahaman laki-laki yang menindas itulah yang menyebabkan perempuan rentan mengalami perbudakan, penganiayaan, intimidasi dan bahkan kekerasan dalam masyarakat atau bahkan rumah tangga. Ide yang cukup menohok dan indah, namun tidak untuk pembela nilai-nilai patriarkal yang dogmatik. Tak heran kemudian, gereja Vatikan saat itu memasukkan buku ini ke dalam daftar buku terlarang mereka.
6. Iris Murdoch (1919-1999 M)
Iris Murdoch mungkin lebih dikenal sebagai seorang novelis dan penulis drama. Namun, tak dapat dinafikkan bahwa ia juga merupakan seorang filsuf. Ia memiliki banyak karya yang berkenaan dengan filsafat. Ia banyak dipengaruhi oleh ide Plato dan gagasan filsuf Prancis Simone Weil. Ide filsafatnya banyak berkutat pada persoalan etika.
Seperti Plato, dia sangat fokus pada moralitas dan kebaikan. Ia pernah menyatakan bahwa mengenali diri sendiri dan kehidupan orang lain merupakan hal penting untuk hidup secara bermoral.
***
Itulah beberapa “filsuf perempuan” yang dapat saya rangkum pada tulisan singkat ini. Tentu, masih banyak filsuf perempuan lain yang (terus terang) tidak dapat saya terangkan di sini satu per satu, karena berbagai alasan.
Terlepas dari itu, apa yang terpenting untuk saat ini adalah kita musti menjauhkan diri dari perfeksionisme atas nama gender. Karena laki-laki ataupun perempuan memiliki kelebihan yang sama, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Menurut saya, apa yang membuat filsuf perempuan ini kurang terkenal dan membuat semangat mereka tak tersampaikan kepada perempuan-perempuan saat ini adalah dominasi budaya maskulinis dan kurangnya kesadaran kita akan relasi gender—yang cenderung mengklaim bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan berpikir yang sama seperti laki-laki.
Saya kira, dengan membaca sejarah pemikiran dan perjuangan perempuan secara adil dan kritis, kita dapat mematahkan klaim perfeksionisme maskulinis, bias, dan sepihak tersebut.
Tentu saja, pengalaman saya dan teman-teman saya dalam kelas-kelas filsafat hanyalah satu bagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar—karena selain pendidikan, berbagai macam kekuatan seperti sosial dan budaya juga memengaruhi keputusan, nilai, dan bahkan karir perempuan di semua aspek kehidupan. Tujuan akhir tulisan ini ialah, membiarkan setiap orang untuk memilih apa yang mereka sukai atau minati.