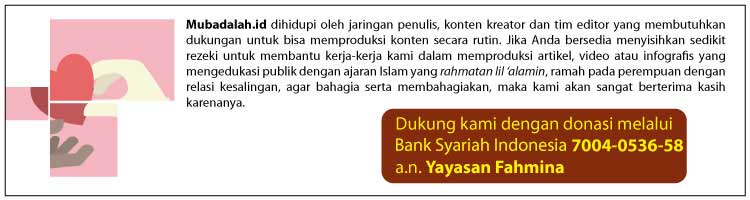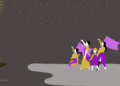Mubadalah.id – Dalam surat an-Nur (QS. 24: 33), Allah Swt meminta mereka yang belum mampu menikah untuk menjaga diri (isti’faf). Kemudian seringkali hanya diartikan dengan menjauhi dari zina, agar bersih dari dosanya (‘afif dan ‘afifah). Menjaga diri dari zina adalah penting dan wajib, tetapi mengartikan perintah isti’faf hanya mejauhi zina adalah kurang lengkap. Mengapa?
Cara pandang terhadap relasi laki-laki dengan perempuan yang hanya sebatas dimensi seksual semata akan berpengaruh pada pemaknaan berbagai anjuran adab dalam relasi tersebut, seperti pada perintah isti’faf. Padahal, dimensi dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah luas dan tidak sebatas seksual. Pernikahan yang menjadi alternatif dari isti’taf juga tidak melulu berdimensi seksual.
Nah, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi relasi laki-laki dan perempuan yang luas, terutama dalam ranah sosial, kita bisa mengajukan pemaknaan isti’faf dalam bingkai akhlak relasi mubadalah. Dimensi relasi yang luas ini bisa menjadi ruang implementasi dari teks-teks berkaitan akhlak relasi dan adab sopan santun.
Dengan bingkai akhlak relasi mubadalah, makna isti’faf tidak ekslusif pada, namun termasuk juga, hal-hal yang bersifat seksual-fisikal tersebut.
Memaknai isti’faf yang tercantum dalam al-Qur’an (QS. An-Nur, 24: 33) dengan menjauhi zina, tentu saja relevan pada konteks literal dari ayat ini. Namun, ini tidak harus menjadi satu-satunya makna. Karena zina juga tetap bisa terjadi pada saat seseorang sudah dalam relasi perkawinan, di mana ia juga tetap diperintahkan untuk isti’faf.
Relasi Akhlak yang Terpuji
Apalagi jika merujuk pada makna asal dari kalimat ini. Yaitu adalah menjauhkan diri dari segala yang haram, dan menghiasi diri dengan rasa cukup pada yang halal. Dengan makna asal ini, jika kita letakkan pada akhlak relasi, antara dua pihak, laki-laki dan perempuan, maka perintah isti’faf bisa menjangkau hal yang lebih fundamental.
Yaitu, bahwa perintah isti’faf adalah mengenai relasi akhlak yang terpuji (mahmudah) dan menjauhi akhlak yang tercela (madzmumah). Yaitu disiplin diri dalam berelasi agar konstruktif dan tidak destruktif. Yang destruktif itu adalah segala relasi yang mendorong pada kejahatan, kezaliman, keburukan, dan dosa, termasuk zina. Yang konstruktif itu segala relasi yang mendorong pada kebaikan dan kemaslahatan. Termasuk relasi perkawinan yang sehat dan saling menguatkan.
Seseorang yang menjalankan isti’faf, biasa kita sebut sebagai ‘afif (laki-laki) dan ‘afifah (perempuan), adalah ia yang memiliki karakter terpuji dalam berelasi antar jenis kelamin, tidak hegemonik, tidak dominatif, dan tidak menjebak atau mengkondisikan orang lain pada dosa, seperti kekerasan seksual dan zina. Baik dalam relasi sosial sebelum dan di luar perkawinan, maupun relasi pasutri yang sah dalam ikatan perkawinan.
Orang yang berzina tentu saja tidak ‘afif (laki-laki) dan tidak ‘afifah (permepuan). Di samping itu, laki-laki yang melampiaskan nafsu syahwatnya dengan istrinya, dengan kekerasan dan menyakiti, sekalipun dalam perkawinan, adalah juga secara akhlak relasi tidak ‘afif (bersih, suci, atau sehat). Sementara perempuan yang menjadi korban perkosaan di luar perkawinan tidak bisa dianggap bukan ‘afifah, hanya karena hubunagn seksual itu terjadi di luar perkawinan.
Memaknai perintah isti’faf seperti ini penting agar alternatif menjauhi zina itu tidak hanya dengan menikah. Apalagi relasi menikahnya justru menyakitkan. Menjauhi zina adalah dengan tidak berzina, yang bisa dengan berbagai aktivitas positif, mulai dari ibadah, belajar, kerja-kerja sosial, olahraga, dan banyak lagi yang lain.
Perintah Ghaddul Bashar
Begitupun perintah ghaddul bashar, dalam konteks akhlak berelasi, adalah bukan penundukan mata fisik. Melainkan kontrol atas cara pandang kita terhadap orang lain, terutama terhadap perempuan: agar tidak sebatas makhluk/objek seksual.
Sekalipun mata tertunduk, jika cara pandang seseorang pada lawan jenis masih sebatas objek seksual maka bisa jadi ia tetap berpikir mencari peluang melakukan aktivitas seksual. Termasuk dengan paksaan dan kekerasan sekalipun. Di sinilah, mengapa perempuan yang sudah menutup aurat sekalipun masih menjadi korban kekerasan seksual dan perkosaan.
Namun, jika cara pandanganya terhadap orang lain, terutama perempuan sebagai manusia utuh, yang memiliki dimensi intelektual, sosial, bahkan spiritual, maka dia akan berelasi dengannya sebagai subjek penuh kehidupan. Yakni menghormati, mengapresiasi, bekerjasama dan saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan dan takwa, serta saling menghindari dari segala dosa dan kejahatan.
Dengan membiasakan diri ghaddul bashar terkait kontrol cara pandang seperti ini, seseorang akan mudah mendisiplinkan diri dalam berelasi dengan akhlak yang mahumdah. Bukan yang madzmumah, menjadi laki-laki yang ‘afif dan perempuan yang ‘afifah.
Ghaddul Bashar, dan Berpuasa
Cara pandang terhadap relasi laki-laki dengan perempuan yang hanya sebatas dimensi seksual semata juga berpengaruh pada pemaknaan berbagai anjuran adab dalam relasi tersebut.
Misalnya, anjuran isti’faf seringkali kita pahami hanya sebagai kesucian diri dari zina. Yakni dengan menjauhi segala pertemuan fisik dengan lawan jenis. Ghaddul bashar kita maknai sebagai penundukan mata fisik dari lawan jenis; dan anjuran berpuasa kita galakkan untuk menurunkan syahwat seksual.
Namun, jika mempertimbangkan berbagai dimensi relasi laki-laki dan perempuan yang begitu luas, terutama dalam ranah sosial, maka pemaknaan hal-hal tersebut di atas harus dengan bingkai akhlak relasi. Dimensi relasi yang luas ini, sebagaimana sudah ditegaskan adalah nyata adanya. Di mana memiliki presedan pada masa Nabi Saw, dan menjadi ruang implementasi dari teks-teks berkaitan akhlak relasi dan adab sopan santun.
Dengan bingkai akhlak relasi dalam dimensi yang lebih luas, makna isti’faf dan ghaddul bashar tidak ekslusif pada, namun termasuk juga, hal-hal yang bersifat fisikal tersebut. Bahkan, ketika sudah dalam relasi perkawinan, yang secara seksual sudah halal, kedua terma isti’faf dan ghaddul bashar masih memiliki makna yang relevan untuk penguatan relasi tersebut.
Sebagaimana terbahas dalam tafsir dan fiqh, perintah isti’faf tercantum dalam al-Qur’an (QS. An-Nur, 24: 33) bagi orang yang belum mampu untuk menikah. Karena itu, tafsir mainstream atas kalimat ini adalah mendisiplinkan diri agar tidak terjerumus pada zina. Makna ini tentu saja relevan pada konteks literal dari ayat ini.
Namun, ini tidak harus menjadi satu-satunya makna. Karena zina juga tetap bisa terjadi pada saat seseorang sudah dalam relasi perkawinan. Padahal ia juga tetap diperintahkan untuk isti’faf. Apalagi jika merujuk pada makna asal dari kalimat ini.
Yaitu adalah menjauhkan diri dari segala yang haram, dan menghiasi diri dengan rasa cukup pada yang halal. Dengan makna asal ini, jika kita letakkan pada akhlak relasi, antara dua pihak, laki-laki dan perempuan, maka perintah isti’faf bisa menjangkau hal yang lebih fundamental.
Cara Pandang yang Bermartabat, Adil dan Maslahah
Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan berdimensi yang lebih luas, perintah isti’faf adalah mengenai relasi akhlak yang terpuji (mahmudah) dan menjauhi akhlak yang tercela (madzmumah). Yaitu disiplin diri dalam berelasi agar konstruktif dan tidak destruktif.
Di mana yang destruktif itu adalah segala relasi yang mendorong pada kejahatan, kezaliman, keburukan, dan dosa, termasuk zina. Yang konstruktif itu segala relasi yang mendorong pada kebaikan dan kemaslahatan. Termasuk relasi perkawinan yang sehat dan saling menguatkan.
Seseorang yang menjalankan isti’faf, biasa kita sebut sebagai ‘afif (laki-laki) dan ‘afifah (perempuan). Keduanya adalah yang memiliki karakter terpuji dalam berelasi antar jenis kelamin. Yakni tidak hegemonik, tidak dominatif, dan tidak menjebak atau mengkondisikan orang lain pada dosa, seperti kekerasan seksual dan zina. Baik dalam relasi sosial sebelum dan di luar perkawinan, maupun relasi keluarga dalam ikatan perkawinan.
Begitupun perintah ghaddul bashar, dalam konteks akhlak berelasi, adalah bukan penundukan mata fisik, melainkan kontrol atas cara pandang kita terhadap orang lain, terutama terhadap perempuan: agar tidak sebatas makhluk/objek seksual.
Sekalipun mata tertunduk, jika cara pandang seseorang pada lawan jenis masih sebatas objek seksual maka bisa jadi ia tetap berpikir mencari peluang melakukan aktivitas seksual, termasuk dengan paksaan dan kekerasan sekalipun. Di sinilah, mengapa perempuan yang sudah menutup aurat sekalipun masih menjadi korban kekerasan seksual dan perkosaan.
Namun, jika cara pandangnya terhadap orang lain, terutama perempuan sebagai manusia utuh, yang memiliki dimensi intelektual, sosial, bahkan spiritual, maka dia akan berelasi denganya sebagai subjek penuh kehidupan: menghormati, mengapresiasi, bekerjasama dan saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan dan takwa, serta saling menghindari dari segala dosa dan kejahatan.
Dengan membiasakan diri ghaddul bashar terkait kontrol cara pandang seperti ini, seseorang akan mudah mendisiplinkan diri dalam berelasi dengan akhlak yang mahumdah, bukan yang madzmumah, menjadi laki-laki yang ‘afif dan perempuan yang ‘afifah.
Puasa sebagai Laku Spiritual
Anjuran berpuasa juga demikian. Sekalipun anjuran ini muncul dalam konteks seseorang yang belum mampu menikah. (Sahih al-Bukhari, no. hadits: 5120). Tetapi seharusnya tidak hanya terhenti pada meninggalkan makan dan minum untuk mengurangi syahwat seksual. Karena bagi orang yang sudah dalam perkawinan, sekalipun berpuasa di siang hari, masih tetap diperbolehkan untuk berhubungan seksual di malam hari.
Artinya, berpuasa itu tidak serta merta, atau tidak secara khusus untuk mengontrol nafsu syahwat seksual. Apalagi, jika merujuk pada hadits lain (Sahih al-Bukhari, no. hadits: 1937). Berpuasa juga secara spiritual ingin mendisiplinkan seseorang agar mampu mengontrol diri dari relasi buruk dengan orang lain, baik keburukan verbal (qawl az-zur) maupun tindakan (‘amal az-zur).
Dengan makna demikian, anjuran berpuasa juga merupakan laku spiritual bagi seseorang untuk mengasah karakter diri. Tujuannya agar memiliki akhlak relasi yang mahmudah, membuang segala akhlak relasi yang madzmumah, memiliki cara pandang yang bermartabat, adil, dan maslahat. Selain itu, mengajak dan mewujudkan segala kebaikan-kebaikan hidup, serta menghindari dan menolak segala keburukanya.
Dengan bingkai akhlak ini, semua perintah isti’faf, ghaddul bashar, dan berpuasa adalah relevan untuk menguatkan karakter diri dan karakter relasi. Baik sebelum menikah, sedang dalam pernikahan, maupun paska pernikahan. []