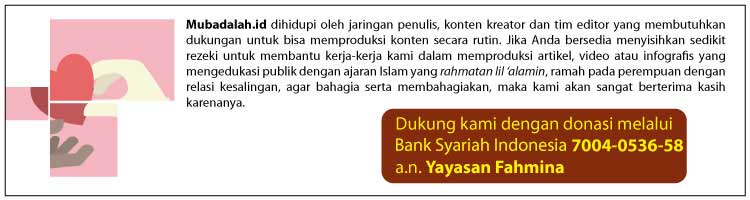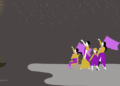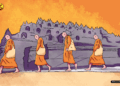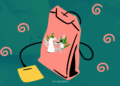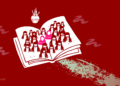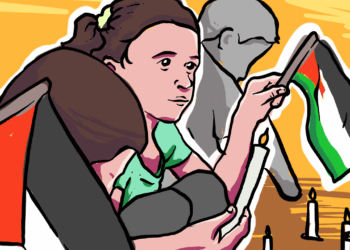Mubadalah.id – Sungguh saya bersyukur bisa hadir di ruang belajar ini—sebuah majelis ilmu yang semoga menjadi taman cahaya. Kita berkumpul untuk membahas sebuah tema yang kerap berbisik di balik teks agama dan bergema di ruang-ruang sosial kita: Perempuan adalah fitnah.
Kalimat ini terdengar begitu akrab. Ia datang dari mimbar ke mimbar, dari ruang keluarga hingga diskusi fiqh. Perempuan, katanya, adalah sumber fitnah bagi laki-laki. Lalu perempuan diminta menunduk, dibatasi geraknya, dipinggirkan suaranya, dan dimintai tanggung jawab atas kekacauan hasrat sebagian laki-laki.
Tapi benarkah? Apakah benar ajaran Islam meletakkan perempuan sebagai biang kerusakan sosial? Ataukah kita sedang membebankan beban dosa sosial kepada tubuh perempuan, dan melupakan satu hal paling mendasar dari ajaran Islam—bahwa kehidupan ini adalah ujian bagi setiap manusia, laki-laki dan perempuan?
Mari kita mulai dari akar katanya: fitnah
Dalam bahasa Arab, fitnah bukan sekadar berita bohong atau provokasi. Fitnah adalah ujian, cobaan, bahkan sesuatu yang mempesona dan menggiurkan. Al-Qur’an menggunakan kata ini berkali-kali, dan nyaris tak satu pun mengarahkannya secara eksklusif kepada perempuan.
Allah berfirman dalam surat al-Mulk (67: 2):
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
“Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa yang terbaik amalnya.”
Ayat ini menegaskan bahwa ujian itu bersifat universal. Bukan hanya tentang perempuan, bukan hanya tentang tubuh, tetapi tentang kehidupan itu sendiri.
Dalam surat al-Furqan (25: 20), Allah juga menyatakan:
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
“Kami jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar?”
Begitulah kehidupan itu, pada praktiknya, satu sama lain adalah: saling menguji, saling menjadi fitnah. Karena itu, fitnah sesungguhnya bersifat relasional. resiprokal. timbal balik. Adalah tidak benar secara qur’ani, jika hanya perempuan yang dipandang fitnah bagi kehidupan, sementara laki-laki tidak.
Maka, ketika Rasulullah Saw bersabda:
“Tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berat bagi laki-laki daripada perempuan.” (HR. Bukhari).
Hadis ini sesungguhnya sedang menyapa laki-laki, mengingatkan mereka agar menjaga diri dari pesona perempuan.
Tetapi sayangnya, sebagian kita membacanya secara sepihak: seolah perempuanlah masalahnya, seolah tubuh perempuanlah biang kerusakannya. Lalu tubuh itu disembunyikan, suaranya dibungkam, langkahnya dibatasi, hingga yang tersisa hanya “perempuan rumah”—bukan perempuan masyarakat, apalagi perempuan pemimpin.
Padahal, jika kita membacanya dengan perspektif mubadalah, kita akan sampai pada pemahaman lain: bahwa sebagaimana laki-laki bisa terfitnah oleh perempuan, perempuan pun bisa terfitnah oleh laki-laki. Bahwa fitnah bukan hanya tubuh—tapi juga harta, kekuasaan, kehormatan, bahkan ilmu.
Jadi, benar perempuan itu fitnah, seperti yang dinyatakan Nabi Saw, tetapi yang penting adalah respon kita lalu apa? Karena laki-laki juga fitnah, respon kita apa?, harta, jabatan, anak, adalah tentu fitnah, respon kita apa? Bahkan, seluruh kehidupan ini adalah sejatinya juga fitnah, lalu respon kita apa?
Sesungguhnya, fitnah itu pada awalnya adalah netral. Yang membuatnya berbahaya adalah respons kita. Maka yang harus kita jaga bukanlah tubuh orang lain, tetapi diri kita sendiri: hati kita, niat kita, akhlak kita.
Sayangnya, realitas tak seindah itu
Stigma “fitnah” justru sering menjadi alat untuk membatasi partisipasi perempuan.
Ketika perempuan ingin belajar—dibilang fitnah.
Lalu, ketika perempuan tampil dan bersuara—dibilang aurat.
Dan, Ketika perempuan memimpin—dibilang melampaui kodrat.
Lalu diciptakanlah dunia yang sempit, tempat perempuan harus terus-menerus membuktikan bahwa ia bukan penggoda, bukan pemicu dosa, bukan ancaman bagi kehormatan lelaki.
Kita lupa, bahwa suara Sayyidah Aisyah ra menjadi rujukan ilmu. Bahwa Fatimah ra berdiri dan bersuara membela haknya. Bahwa perempuan-perempuan sahabat berperan dalam pasar, perang, pendidikan, bahkan fatwa.
Dan kita lupa, bahwa laki-laki pun bisa menjadi fitnah. Bahwa tubuh laki-laki juga bisa menggoda. Bahwa kuasa, jabatan, dan kedudukan mereka bisa menjadi ujian besar bagi perempuan dan masyarakat luas.
Inilah pentingnya pendekatan mubadalah
Mubadalah tidak membalikkan ketimpangan, tapi menyeimbangkannya. Ia menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama. Sama-sama berakal, sama-sama bertakwa, dan sama-sama memikul amanah kekhalifahan.
Mubadalah mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu “Bukan satu penggoda, dan yang lain penjaga, tapi dua-duanya penjaga—dan sekaligus potensi penggoda”.
Dengan perspektif mubadalah, kita melihat bahwa:
Pertama, “Tubuh (bukanlah) sumber dosa, tetapi amanah yang harus terjaga”. Artinya, tubuh bisa sumber dosa dan bisa sumber amanah, kitalah yang merespon, dan menentukan dan harus bertanggung-jawab atasnya.
Kedua, “Suara (bukanlah) fitnah, tapi medium dakwah dan kebaikan”. Artinya: suara kita, laki-laki maupun perempuan adalah bisa menjadi pendorong keburukan (fitnah), tetapi bisa menjadi medium segala kebaikan.
Ketiga, “Perempuan (bukan) sumber kekacauan, tapi sumber ilmu, berkah, bahkan jalan surga”. Artinya, perempuan baik tubuh, suarah, tindakan, dan peran sosialnya, sebagaimana persis laki-laki, bisa menjadi sumber kekacauan, dan pada saat yang sama banyak yang menjadi sumber ilmu, kebaikan hidup, berkah, dan surga.
Maka, pertanyaannya bukan lagi: apakah perempuan fitnah bagi laki-laki?
Tapi: bagaimana kita memaknai fitnah itu?
Apakah ia menjadi alasan untuk mengkerangkeng perempuan?
Atau menjadi peluang untuk mendidik umat—agar semua insan menjaga diri, saling menghormati, dan membangun relasi yang berkeadaban?
Dan pertanyaan lebih dalam lagi: Apakah kita siap meninggalkan narasi-narasi yang menakut-nakuti atas nama agama, demi membangun narasi kasih sayang, keadilan, dan kesalingan yang sejati?
Islam hadir bukan untuk membebani yang sudah berat, atau menyudutkan yang lemah. Islam hadir untuk memuliakan semua manusia. Dan relasi antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat, adalah relasi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bukan fitnah yang menakutkan, tetapi fitrah yang saling menenteramkan.
Karena itu, mari kita tegakkan pemahaman yang adil. Mari kita jaga tubuh dan akal kita, bukan semata-mata membatasi tubuh orang lain. Dan mari kita pahami bahwa perempuan bukan sumber fitnah. Tapi manusia mulia, seperti juga laki-laki:
- yang bisa menginspirasi,
- yang bisa menyesatkan,
- yang bisa menjadi ujian,
- sekaligus bisa menjadi rahmat bagi semesta.
Akhirnya, mari kita bertanya pada diri sendiri: benarkah kita takut pada perempuan, atau sesungguhnya kita takut menghadapi nafsu dan kelemahan kita sendiri?
Mengapa lebih mudah menyalahkan tubuh perempuan, daripada mendidik mata dan akal kita sendiri? Bukankah menjaga diri adalah tanggung jawab pribadi, bukan alasan untuk membatasi hidup orang lain?
Jika kita ingin membangun masyarakat yang sehat, maka kita harus mulai dari kejujuran hati: bahwa perempuan bukan musuh yang harus dijaga jaraknya, melainkan sahabat hidup, berkah yang perlu dirangkul, dan mitra sejati dalam membangun peradaban.
Saatnya kita menanggalkan ketakutan yang lahir dari prasangka, dan menggantinya dengan keberanian untuk saling memuliakan. Karena hanya masyarakat yang melihat perempuan sebagai berkah—bukan fitnah—yang akan mampu melangkah menuju keadilan dan kebaikan yang sejati.
Demikianlah mubadalah menawarkan. Bagaimana menurut Anda? []