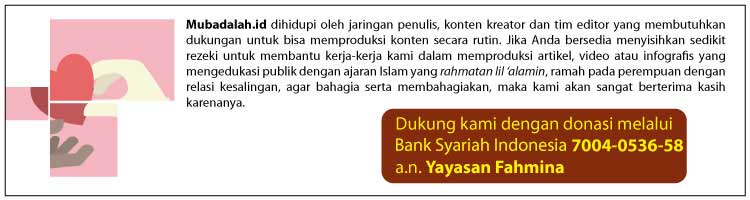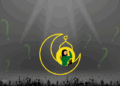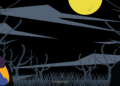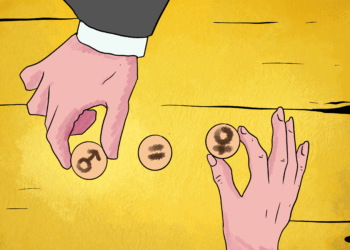Serat yang terdiri dari 12 jilid dan berbentuk tembang ini banyak digubah kembali oleh para sejarawan dan cendekia, seperti Pustaka Centhini (Ringkasan 12 Jilid Serat Centhini) oleh Ki Sumidi Adisasmita (Bahasa Jawa), Ringkasan Centini (Suluk Tambanglaras) oleh R.M.A. Sumahatma, Serat Centhini oleh Agus Wahyudi (Bahasa Indonesia). Pun kajiannya mewujud dalam telaah luas termasuk di antaranya “Gender dalam Karya Sastra Jawa (Studi Kasus pada Serat Centhini Episode Centhini)” oleh Siti Muslifah (2008).
2008, tahun yang sama ketika penerbit Babad Alas menerbitkan (kembali) buku Elizabeth dengan judul Centhini: Kekasih yang Tersembunyi. Elizabeth D. Inandiak adalah mantan jurnalis negara Perancis yang terpesona pada Serat Centhini yang dianggapnya sakral –karya sastra yang sarat makna religiusitas dan erotisme– hingga kemudian ia membuat tafsir atasnya dalam Centhini: Les Chants de Lile a’ Dormir Debout, Le Livre de Centhini (2002) dan meraih penghargaan sebagai buku Asia terbaik berbahasa Perancis di tahun berikutnya.
Adaptifitas Serat Centhini terjadi berkat adanya telaah kritis kepadanya yang menyisakan kesan sekaligus kritik terhadap diskursus yang dikandung. Pun berlaku bagi teks-teks sastra Jawa dari kuno hingga modern. Teks yang terjaga oleh sejarah membuktikan ajaran di dalamnya terus berkelindan dengan kondisi (sepanjang) jaman. Tak heran apabila terbangun relasi Serat Centhini terhadap persoalan kesetaraan yang digandrungi terkhusus kaum feminis dan masyarakat plural pada umumnya, hingga hari ini.
Serat Centhini adalah karya bersama beberapa pujangga istana Kasunanan Surakarta –di antaranya Raden Ngabei (Ranggasutrasna) dan Yasadipura II– yang selesai digubah pada 1814 Masehi atau 1229 Hijriah atau 1742 (tahun Jawa). Serat Centhini digubah atas kehendak Sunan Pakubuwana V di masa Ayahanda, Sunan Pakubuwana IV, tepatnya enam tahun menjelang penobatan Sunan Pakubuwana V ketika masih bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom.
Dalam terjemahan Ki Sumidi Adisasmita yang telah dialih bahasakan oleh Drs. Darusuprapta, awal pupuh pertama tembang sinom Centhini Surya Surarjan, tertulis “Sang Putra mahkita Jawa, di wilayah Pulau Jawa, Surakarta Adiningrat, memerintahkan kepada hambanya juru tulis, Sutrasna (R. Ng. Ranggasutrasna) yang dipercaya, menggubah cerita lama, semua ilmu Jawa, dihimpun dalam tembang, supaya tidak membosankan tapi menggembirakan bagi yang mendengarnya.
Jilid pertama Serat Centhini adalah babad Giri yang terdiri dari 87 pupuh. Jilid pertama adalah riwayat kelahiran Sunan Giri hingga menjadi Kanjeng Sunan di Giri (Giri Gajah) yang memerintah Kasuhunan Giri bergelar Prabu Satmaka dan akhirnya diambil menantu oleh Sunan Ampel. Babad Giri dilanjut ketika Kasuhunan Giri runtuh masa Sunan Giri III (Sunan Giri Parapen) oleh serangan pasukan Surabayan (pimpinan pasangan Pangeran Pekik dari Surabaya dengan Kanjeng Ratu Pandhansari adik dari Sultan Agung Mataram).
Serangan Surabayan –laiknya tercatat dalam Serat Centhini jilid I– tidak berhasil meruntuhkan Giri dalam sekali serangan, melainkan melalui beberapa taktik, mengingat semasa Sunan Giri I kasuhunan pun pernah gagal ditaklukkan oleh Majapahit. Taktik damai dan serangan pertama oleh Pangeran Pekik hanya menyisakan kekalahan. Namun akhirnya dibayar tuntas dengan kemenangan menggempur pertahanan Giri di serangan kedua oleh pasukan Surabayan yang telah disatukan kembali strategi perang dan keberaniannya oleh Kanjeng Ratu Pandhansari.
Sementara ‘bumi ini milik laki-laki dan perempuan’ tutur Kyai Faqih Abdul Kodir, begitu pula seluruh bagian kehidupan adalah untuk dan oleh laki-laki sekaligus perempuan. Demikian medan perang untuk Pangeran Pekik dan Kanjeng Ratu Pandhansari, serupa halnya ruang publik meniscayakan panggung untuk laki-laki bersama perempuan membangun tatanan sosial. Lantas keduanya tak sama persis dalam caranya memberikan sumbangsih peradaban. Sebab peradaban dibangun atas hubungan yang ba’duhum awliya ba’din (saling tolong menolong).
Setelah Kasuhunan jatuh, Sunan Giri dan keluarga diberi tempat tinggal dan menetap di Mataram, dengan Endrasena (pedagang muallaf dari China yang diangkat anak Sunan Giri III) gugur di medan pertempuran. Sedangkan dua putra dan satu putri kandung Sunan Giri pergi dari tlatah untuk menjelajah. Mereka terpisah dalam dua kelompok diiringi para abdi (santri Kanjeng Sunan). Raden Jayengresmi (putra pertama) diiringkan santri Gathak-Gathuk dan Raden Jayengsari serta Niken Rancangkapti diiringkan santri Buras.
Keturunan laki-laki maupun perempuan Sunan Giri saling berkelana di tanah Jawa, mencari ilmu, di sampingnya pegangan tata krama ajaran sang Bapa. Tiada semestinya ada dikotomi suatu kelompok harus berdiam dalam ruang domestik, sementara lainnya bebas memerdekakan dirinya. Perempuan, demikian pula laki-laki, adalah subjek sekaligus objek, dimana predikat adalah kunci yang harus keduanya raih –bukan hanya meminta. Pengejawentahan diri adalah laku (kewajiban) bukan melulu perihal pemberian (hak).
Di permulaan pupuh II Jilid 1, Serat Centhinii mulai menuturkan jalan pencarian putra-putri Sunan Giri juga perjalanan Raden Cebolang pada Jilid III. Tentang perjalanan inilah Serat Centhini telah menampakkan bentuknya sebagai Suluk Tambanglaras-Amongraga (nama lain Serat Centhini), dimana suluk dalam pengertian falsafah Jawa diartikan sebagai perjalanan menuju kesempurnaan, berasal dari bahasa Arab ‘fasluk’, Fasluki subula Robbiki zululan, “Dan tempuhlah jalan Rabb-mu yang telah di mudahkan (bagimu).” (QS. 16: 69)
Bagi penulis, pada pembacaan di dua jilid awal (saja), dapat ditemukan begitu berserak bingkai-bingkai mubadalah dari Serat Centhini ini. Mubadalah yang direpresentasikan sepanjang perjalanan putra-putri Sunan Giri dan Mas Cebolang (putra salah satu guru spiritual dalam perjalanan putra Sunan Giri). Mubadalah yang dijumpai tak berupa dogma melainkan terceruk dalam keharmonisan bermasyarakat.
Di bait 4 pupuh II jilid I misalnya, masih mula perjalanan Raden Jayengresmi, tetibanya di hutan Bago bertemu ‘guru’, seorang petapa, yang ternyata Putri Majapahit. Sang putri mengajarkan bermacam geliat binatang kepada Raden Jayengresmi. Pupuh ini menarik dibaca dari perspektif mubadalah. Pun di baitnya yang ke 17, tertulis guru kasidan Raden Jayengresmi yakni Syekh Trenggana, akhirnya moksa. Syekh Trenggana meninggalkan seorang istri dan anak perempuan, Ni Rukhkanti.
Setelah kemoksaan itu, Ni Rukhkanti diajar ilmu martabat tujuh tingkat oleh Raden Jayengresmi. Mubadalah meniscayakan laki-laki maupun perempuan, dari kasta manapun, saling berbagi ilmu bahkan keduanya dapat bersama memberi pengajaran satu sama lain. Saling mengajarkan suatu ilmu, mengingatkan kita kepada HR. Bukhari mengenai kerangka hidup harmoni, Dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya.”
Menuju bait 16 pupuh III jilid I, adalah perjalanan Raden Jayengsari dan Niken Rancangkapti. Raden dan Niken bertemu sepasang guru, Ki dan Nyi Hartati. Ki Hartati mengajarkan tujuh macam cita-cita serta hatungan menyeribu hari. Nyi Hartati mengajarkan Ken Rancangkapti tentang arti jari lima. Sungguh fenomena keagamaan yang jauh dari dehumanisasi. Karena sejatinya agama diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh umat tanpa memandang perbedaan kecuali takwa.
Selain sama-sama mengajarkan ilmu, Ki dan Nyi Hartati tergambar membangun keluarga yang harmonis. Keduanya begitu saling mengasihi. Penafsiran resiprokal Kyai Faqih agaknya sangat sesuai untuk hal ini, terhadap surah Ar Rum (30: 21) dalam terjemahan yang berbunyi “Di antara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untuk kalian semua pasangan-pasangan (pernikahan), agar kalian bisa memperoleh ketenangan dari pasangan tersebut.” Seakan menyepakati konsep mubadalah yang sangat menghargai peran-peran domestik sekalian publik.
Tugas domestik bukan harus dilupakan untuk mencapai kesetaraan. Mubadalah bukan memihak suatu ruang, memberatkan (hanya) sebagian pihak. Mubadalah adalah bagian dari kehidupan manusia, dan kapasitas manusia sebagai hamba, tak berhak meninggikan diri kepada sesamanya. Tak berhak laki-laki menganggap perempuan sebagai inferior. Tak berhak perempuan dipaksa menganggap laki-laki sebagai superior. Keduanya wajib saling menghargai tanpa lengah menyadari peran masing-masing.
Lebih jauh, Serat Centhini Jilid II menyimpan kisah perjalanan Mas Cebolang. Ditemuinya guru bernama Kyai Juru Pujangkara. Kyai Juru berkarib dengan Nyai Cundhamundhing seorang jagal penjual daging dan Nyai Padmacitra seorang juru sungging. Bersama Mas Cebolang, mereka saling berbagi pengetahuan sesuai kecakapan yang dipunyai. Turut serta Nyai Sriyatna menguraikan tentang macam-macam syarat sajian orang punya hajat pengantin dan Nyai Lurah dari dalam keraton datang mengajarkan tentang pranata pernikahan.
Jika persepsi abad 18 terhadap masyarakat Jawa –yang mendudukkan perempuan dalam posisi inferior cum hanya sebagai konco wingking– masih terpelihara, dus perlu telaah lebih jauh mengenai konteks kehidupan masyarakat dalam hibriditas budaya yang muncul di Nusantara. Mengacu pada perkembangan berikutnya, tercatat kehidupan kerajaan membawa pengaruh ajaran sakiyeg sakeka kapti (manusia yang mempunyai kesamaan tanggung jawab).
Memahami kandungan Serat Centhini ini serasa menemukan kedalaman pemikiran Gus Mus tentang saleh ritual dan saleh sosial. Apabila kerajaan Islam di Jawa membawa kontinuitas kultural dalam perjalanannya, yang berupa sintesisme tradisi (keraton) leluhur dengan ajaran pesantren yang ortodoks (Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 2001), akan sangat mungkin terbangun persandingan harmonis antar sesama.
Terlepas dari pengaruh yuridis politik dalam kesejarahan Nusantara, banyak mutiara hikmah yang dapat diambil dari Serat Centhini –sebagai bagian dari teks Jawa– baik segi teologis maupun sosiologis dalam mentadabburkan perspektif mubadalah. Apabila realitas historis dan kultur sosial mempengaruhi bagaimana teks berbunyi, begitu pun relasi kesalingan (mubadalah) dalam masyarakat kita semestinya terpatri. []
*)Tulisan yang sama bisa dibaca di https://neswa.id/artikel/serat-chentini-dan-prototype-mubadalah/