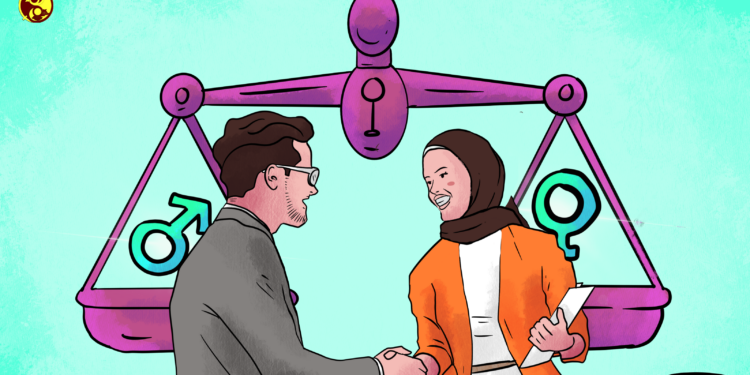Mubadalah.id – Sebelum saya mengulas tentang bagaimana sikap negara dan media dalam memotret politisi perempuan, ada satu pertanyaan yang mengganjal dalam pikiran. Lebih bahagia mana pujian kecantikan dengan pujian kecerdasan?
Pertanyaan ini saya ajukan ketika melihat sebuah postingan di instagram tentang kecantikan dan kecerdasan perempuan. Pembahasan perempuan memang sangat kompleks ketika kita hadapkan dengan budaya yang berkembang di ranah masyarakat. Lihat saja di media sosial.
Instagram misalnya. Berapa banyak akun fanbase yang memotret kecantikan perempuan. Akun-akun kampus cantik seperti UGM cantik, UI cantik bahkan akun santri cantik menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan perempuan di media.
Berkenaan dengan permasalahan ini, Laure Mulvey menjelaskan teorinya yang ia sebut male gaze. Menurut Mulvey, male gaze menawarkan cara pandang seksualitas yang memberdayakan laki-laki namun mengobjektifikasi perempuan.
Perempuan selalu terposisikan sebagai objek pemenuhan hasrat laki-laki maskulin- heteroseksual. Di media, potret perempuan selalu tergambarkan sebagai objek, sehingga perempuan kita tempatkan begitu rendah sebagai pemuas nafsu belaka.
Melihat Teori Male Gaze
Teori ini dapat kita lihat dalam tiga cara yaitu, laki-laki memandang perempuan. Perempuan memandang diri sendiri. Perempuan memandang perempuan lain. Atas dasar ini, maka perspektif gender sangat penting laki-laki dan perempuan miliki, supaya tidak selalu mengobjektifikasi diri sendiri, atau perempuan lain.
Kenyataan ini juga bisa kita lihat bagaimana potret perempuan dalam iklan rokok, yang sebenarnya tidak ada hubungan antara perempuan dengan rokoh dalam scene iklan yang ditampilkan. Di samping itu, berkenaan dengan male gaze ini, berdampak terhadap bagaimana media mencitrakan perempuan.
Dalam iklan-iklan popok, detergen ataupun segala bahan rumah tangga, biasanya yang ditampilkan adalah perempuan. Gambaran iklan ini menjadi salah satu potret bagaimana media menggambarkan perempuan.
Fenomena ini juga turut menjadi salah satu faktor yang membuat budaya patriarki terus mengakar dalam diri masyarakat. Kenyataan ini juga terjadi pada bagaimana media memotret politisi perempuan. Gambaran politisi perempuan di media tidak pernah lepas dari peran domestik ataupun masalah privat yang tampak seksi untuk dikorek oleh media.
Negara yang Memotret Politisi Perempuan
Masalah ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam penelitian Lutfi Basith tahun 2022, ia membagi beberapa kategori negara yang memotret politisi perempuan, di antaranya:
Pertama, negara full demokracy seperti Taiwan, UK, Kanada, Australia, Spanyol, New Zealand, politisi perempuan digambarkan oleh media hampir sama, yakni: sedikit diliput kinerja kepemimpinan dan cenderung seksis.
Kedua, negara flawed demokracy seperti Amerika, Brazil, Belgia, Italia dan Prancis, media meliput politisi perempuan dengan cukup bias.
Ketiga, negara hybrid regime seperti Nigeria, Turki, politi perempuan tergambarkan kurang kredibel.
Keempat, negara authoritarian regime seperti Afghanistan, China, keterwakilan perempuan jarang dan pemberitaan politisi perempuan hampir tidak ada.
Perspektif gender politisi perempuan di negara dengan tipe full democracy, flawed democracy, hybrid regime, dan authoritarian regime adalah sama, mereka dipotret media massa dengan perspektif negatif. Perspektif negatif gender terjadi di 79% negara full democracy, 85% negara flawed democracy, 100% negara hybrid regime dan authoritarian regime.
Namun yang membedakan adalah bahwa di dalam negara dengan tipe full democracy dan flawed democracy terdapat liputan yang positif terhadap politisi perempuan. Meskipun dengan persentase yang kecil, yaitu 21% dan 8%, serta 8% negara dengan tipe hybrid regime ada liputan positif terhadap politisi perempuan.
Peran Media Melanggengkan Patriarki
Berdasarkan penjelasan di atas, Indonesia termasuk negara flawed demokrasi yang masih belum ramah terhadap perempuan. Media Massa menampilkan Politisi perempuan secara negatif, terutama dalam perspektif gender. Di mana hal itu dikemas dalam tiga kategori patriarki, objektifikasi dan stereotip.
Selain itu, media massa kita masih mencitrakan politisi perempuan dengan peran domestik yang tidak terpisahkan. Padahal yang paling penting adalah mengangkat wacana politik yang dibangun oleh politisi perempuan. Masalah ini menjadi masalah klasik yang terus mengakar di Indonesia.
Media turut berpartisipasi dalam pelanggengan budaya patriarki dengan berita yang sangat tidak ramah terhadap perempuan, serta belum sepenuhnya mendukung terhadap wacana politik yang perempuan miliki. Gerakan perempuan adalah gerakan yang terus sustainable. Sebab perjuangan untuk menegakkan ruang yang aman dan ramah terhadap perempuan, adalah perjuangan kemanusiaan yang terus kita lakukan. []