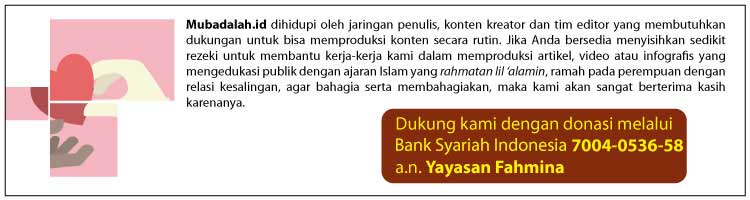Mubadalah.id – Seberapa sering kita menggunakan media sosial, terutama Instagram? Satu jam, tujuh jam, tiga belas jam, seharian penuh, tanpa henti? Dalam laporan Napoleon Cat pada Maret 2024, tercatat ada 90,41 juta pengguna Instagram di Indonesia, hampir sepertiga dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 277 juta, berdasarkan World Population Review per Maret 2024. Kita, para pengguna instagram, adalah bagian dari sepertiga itu.
Saya menggunakan Instagram sejak 2014 dan baru pada 2019 membatasi penggunaannya selama 60 menit sehari dengan pengatur waktu aplikasi ponsel. Waktu melimpah ini saya pakai untuk menyisir berita terkini, berinteraksi dengan teman-teman daring, membagikan a—z kekaryaan, merayakan hidup, membalas komentar, mengikuti war fandom k-pop, dan kadang-kadang mengintip kehidupan gemerlap para selebgram.
Konten-konten yang selebgram bikin mampu menjeda hidup dan membikin senyum merekah. Dwi Handayani misalnya, membagikan keseharian kedua anaknya—Freya dan Ilayya—dengan bungah. Tingkah dua anak lucu itu mampu meletakkan sebentar rasa lelah setelah seharian berjibaku dengan waktu rekat tenggat pekerjaan. Sejak 2021, saya mulai berhenti lama-lama mengamati para selebgram yang terlalu sering endorse produk.
Dari sekian banyak konten yang saya amati dari para selegram, saya paling tertarik pada sudut pandang mereka terhadap satu hal atau suatu masalah. Ada Nadia Alaydrus, seorang dokter yang piawai meramu informasi kesehatan dalam bentuk sederhana sehingga lebih mudah dipahami warganet. Atau, ada Awkrain yang membagikan awareness tentang mental health. Kedua bentuk informasi tersebut memperkaya pengetahuan saya.
Pengaruh Akun Selebgram
Betapa pun ada hal-hal positif yang dapat kita ambil dari mereka, saya tetap mendapat dampak negatif selama bertahun-tahun. Sejak 2016, yang baru saya sadari per 2021, saya berubah menjadi pribadi impulsif. Belanja tanpa henti. Membuka e-commerce dan menambahkan produk di keranjang hampir setiap hari. Saat melacak alasannya, saya sampai pada satu kesimpulan: Iklan-iklan yang berseliweran di akun para selegram telah banyak memengaruhi saya.
Tanpa sadar, saya merasa membutuhkan produk-produk tak penting yang entah kenapa menjadi terasa begitu mendesak untuk dibeli. Fast fashion dinormalisasi, produk-produk receh yang diklaim memudahkan hidup saya beli tanpa henti, dan berbagai macam inovasi makanan yang sejatinya tidak diperlukan tubuh justru terus-menerus dikonsumsi. Kesemuanya terjadi hanya karena saya tak mampu mengendalikan diri.
Kesadaran untuk mengendalikan diri kian menguat ketika saya menyadari begitu banyak sampah yang saya hasilkan hanya karena membeli barang-barang yang kerap disebut-sebut sebagai “racun selebgram” itu. Saat melihat Tasya Farasnya mengunggah lipstik yang ia labeli sebagai produk “Tasya Farasya Approved” misalnya, jari-jemari saya bergerak sendiri, membuka aplikasi, lalu check out dengan riang gembira.
Tak terhitung, berapa kali check out impulsif ini terjadi, sampai pada suatu saat, saya melihat tumpukan bubble wrap menggunung di pojok ruangan. Spontan saya bergumam, “betapa bodoh diri ini, membeli hanya karena teracuni.” Esok harinya, saya mulai unfollow para selebgram yang saya anggap masuk dalam kategori impulsif dan mulai melerai pelan-pelan apa yang menjadi kebutuhan dan sekadar keinginan.
Filterisasi
Keputusan tersebut tak saya sesali sama sekali. Justru, saya meneruskan filterisasi tersebut hingga saat ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendata, sepanjang 2023, ada sekitar 19,56 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia. Data tersedia dari 96 kabupaten/kota. Filterisasi yang saya lakukan memiliki pengaruh kecil sekali. Amat kecil bila tak kita lakukan secara konsisten, dalam skala besar, dan berkelanjutan.
Sampah-sampah yang dihasilkan di Indonesia di antaranya; 41,4% berupa sisa makanan, 18,6% sampah plastik, 11,5% kayu/ranting/daun, dan 10,5% kertas/karton. Angka-angka tersebut menyimpul satu pola: Mayoritas sampah berasal dari limbah rumah tangga dengan proporsi sebesar 39,1%.
Selain berusaha maksimal memotong proporsi sisa makanan, kita wajib menekan yang kedua yakni sampah plastik sebesar 18,6%. Bumi sudah begitu hancur, soal mengurangi sampah, kita tak pantas beralasan apa pun untuk tak melakukannya.
Sampah-sampah plastik dalam total 18,6% itu berasal dari bubble wrap, kemasan plastik, dan kemasan produk yang telah habis. Produk yang mungkin kita beli hanya karena melihat sebuah story. Barang yang mungkin kita beli lantaran ada selebgram yang memberikan klaim tak pasti. Plastik demi plastik dalam berbagai macam bentuk yang kita gunakan sehari-hari.
Sampah plastik tidak bisa terurai begitu saja. Begitu banyak jenis sampah plastik yang baru bisa terurai setelah ratusan tahun. Setiap sampah plastik baru bisa terurai dalam waktu yang berbeda-beda. Sayangnya, meskipun beberapa jenis sampah plastik bisa terurai dalam waktu puluhan hingga ratusan tahun, plastik-plastik tersebut tetap tidak akan hilang begitu saja.
Mikroplastik
Plastik-plastik akan berubah menjadi mikroplastik yakni partikel-partikel plastik kecil yang tidak terlihat mata. United Nations Environment Programme (UNEP) atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat, sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik kemudian banyak dimakan oleh ikan atau hewan ternak. Mereka mengira mikroplastik adalah makanan. Konsumsi yang tak sengaja tersebut berpotensi menyebabkan penyakit.
Mikroplastik bukan satu benda sederhana. Ia mencakup berbagai bahan, ukuran, bentuk, kepadatan, dan warna yang berbeda (Evangelos Danopoulos, Peneliti Mikroplastik Hull York Medical School, Inggris). Mikroplastik primer yang diproduksi berbentuk kecil, kita gunakan dalam benda-benda seperti kosmetik dan cat. Sementara, mikroplastik sekunder dihasilkan dari penguraian bahan plastik yang lebih besar, sebagai misal botol air dan kantong plastik.
Menimbang asal-usul keduanya, mikroplastik sekunder tentu memiliki lebih banyak bentuk ketimbang mikroplastik primer. Sebagai misal, mikroplastik sekunder berbentuk serat yang terlepas dari pakaian sintetis (poliester, dan lain-lain) atau potongan sendok plastik di sungai, danau, atau lautan.
Pada akhirnya, setiap plastik akan menjadi mikroplastik sekunder. Alam memprosesnya menggunakan angin, arus air, dan radiasi UV, memecahnya menjadi potongan-potongan kecil yang semakin kecil dan terus mengecil.
Mikroplastik mengancam kehidupan manusia, terlahir dari plastik-plastik yang kita gunakan sehari-hari. Plastik-plastik yang kita produksi dari keinginan-keinginan tak terkendali. Kita bisa menekan keinginan dengan membeli barang yang memang mendesak digunakan, tidak karena direkomendasikan.
Lagi pula, tidak sulit rasanya memisahkan yang mana kebutuhan dan yang berupa keinginan. Hal-hal yang tak perlu, sesegera mungkin kita hindari. Apa yang selebgram promosikan tidak semuanya kita butuhkan.
Kita bertarung dengan plastik dan mikroplastik. Bertarung dengan para selebgram impulsif. Kita bertarung dengan diri kita masing-masing. Bila mau terlibat dalam gerakan ekofeminisme, mungkin, berhenti mengikuti para selebgram yang membuat kita berlaku impulsif dapat menjadi langkah kecil. Saking kecilnya, kita mungkin ragu, malu, dan enggan melakukannya. []