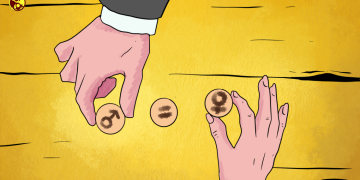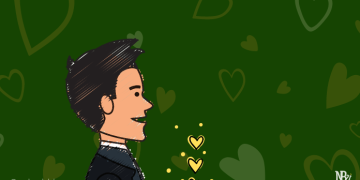Mubadalah.id – Ketika mendengar kabar seorang suami yang menjatuhkan istrinya ke laut dari atas kapal feri, salah satu rekan spontan berkomentar; “wah, ini suaminya sudah tidak tahan diomelin terus tiap hari.” Riuh tawa dan tanggapan serupa kemudian sahut-menyahut. Adegan tersebut awalnya bagai angin lalu sebelum kasus penganiayaan yang kembali ‘melibatkan’ perempuan. Di mana hal itu semakin banyak memunculkan propaganda female-blaming atau pembebanan kesalahan pada perempuan yang sangat kental streotipe ala patriarki.
Layaknya sebuah serial, episode berawal dari pembunuhan ajudan seorang jenderal polisi bintang dua yang kemudian menyusul kasus di atas kapal feri, lalu penganiayaan remaja yang berawal dari masalah pribadi. Namun akhirnya merembet pada banyak hal, termasuk salah satu lembaga negara. Kasus-kasus tersebut tidaklah terkait satu sama lain. Tetapi ada benang merah yang mempertemukan ketiganya, yakni pembebanan kesalahan (berlebih) pada perempuan.
Dalam buku Why Women are Blamed for Everything: Exploring Victim Blaming of Women Subjected to Violence and Trauma (2020), Jessica Taylor menunjukkan bahwa pembebanan kesalahan pada perempuan muncul dari berbagai faktor. Mulai dari mitos stereotipe hingga perilaku, kepercayaan, dan pola pikir masyarakat yang cenderung victim-blaming (hlm. 27). Pembebanan kesalahan inilah yang menurutnya memunculkan dampak berlanjut, yakni self-blaming (hlm. 7 dan 239) atau kondisi di mana perempuan menyalahkan diri sendiri.
Meski buku tersebut fokus pada korban kekerasan seksual yang notabene tidaklah persis sama dengan tiga kasus di atas. Setidaknya tidak terbukti di persidangan, untuk kasus pertama. Ada banyak kesamaan yang membuat ulasannya relevan. Taylor, misalnya, mengatakan bahwa perempuan berada dalam posisi rentan di pusaran kekerasan berbasis sentimen seksual, hubungan asmara dan semacamnya. PC dan AG masing-masing adalah istri dan kekasih pelaku (pleger), sehingga ‘aduan’ keduanya diduga memicu tindakan kriminal.
Gejala Female-Blaming
Sementara itu, perempuan pada kasus kedua adalah istri pelaku yang terlihat tidak menduga akan mengalami kejadian mengejutkan tersebut. Identitas ketiganya seperti menguatkan paparan Taylor bahwa baik girl maupun women sama-sama berada dalam sengkarut sistem patriarki yang kompleks, opresif, dan melegalkan pembebanan kesalahan pada korban, yang sebagian (besar) adalah perempuan. Pembebanan kesalahan ini bahkan tampak lebih berat dibanding eksekutor atapun doenpleger yang dalam ketiga kasus di atas kebetulan adalah laki-laki.
Gejala female-blaming misalnya tampak pada meme yang beredar luas di media sosial. Sebuah meme contohnya, menyiratkan bahwa jika PC atau AG tidak mengadu kepada suami dan kekasihnya masing-masing, dua tragedi tersebut tidak akan terjadi. Meme lain mendaftar akibat dari aduan keduanya yang berdampak luas tidak hanya pada korban, tetapi juga pada beberapa institusi terkait dan masyarakat secara luas.
Kesalahan keduanya, kalaupun pada akhirnya terbukti, seperti jauh lebih besar dibanding pleger atau doenplegder. Sehingga di luar sanksi sosial (dipersalahkan oleh keluarga, teman, termasuk media), mereka didera rasa bersalah luar biasa. Inilah yang oleh Taylor sebut self-blaming dengan indikasi tiadanya penalaran logis bahwa pelakulah yang sepenuhnya bertanggungjawab. Bukan orang terdekat apalagi korban. (hlm. 9 dan 239).
Sementara itu, meski tanpa informasi yang dapat kita pertanggungjawabkan, banyak yang enteng saja berasumsi bahwa kejadian di kapal feri bermula dari kesalahan si istri. Seperti korban rudapaksa yang sering kita salahkan karena gaya berpakaian atau bergaulnya. Komentar spontan semacam ini, seperti sesumbar rekan saya tadi, mencerminkan bagaimana perempuan biasa kita posisikan dalam kasus atau kejadian yang tidak ia inginkan. Mereka seringkali begitu saja kita salahkan tanpa penelusuran yang serius dan perspektif berimbang. Bahkan untuk kesalahan yang tidak mereka lakukan atau justru menimpa mereka.
Membebankan Kesalahan pada Perempuan
Pembebanan kesalahan pada perempuan ini, ironisnya, beriringan dengan permakluman (excuse) kepada laki-laki. Meski siapapun mengamini bahwa ketiga tindakan tersebut tidaklah berperikemanusiaan. Munculnya berbagai pemikiran keagamaan yang dipaksakan kontekstual dengan kejadian tersebut seperti menyatakan sebaliknya.
Ayat yang menceritakan lemahnya tipu daya setan (QS 2: 76), misalnya, kita sandingkan dengan ayat lain yang menegaskan kuatnya tipu daya perempuan (QS. 12: 28) tanpa menyuguhkan konteks atau keterangan lanjutan. Jika perbandingan sembrono ini kita telan mentah-mentah, derajat perempuan tentu berada di di bawah setan.
Apalagi, kalaupun laki-laki yang berperan sebagai eksekutor, ada banyak apologi yang bisa melindunginya. Mulai dari mitos maskulinitas seperti menjaga harkat dan martabat diri, melindungi perempuan yang ‘lemah’, hingga memberi pelajaran kepada korban. Tak pelak, fenomena female-blaming semacam ini merupakan ciri khas ideologi patriarki yang meski bukan tidak kita kaji dan renungkan ulang, tetap berada dalam alam bawah sadar. Di mana sewaktu-waktu dapat kembali mengendalikan pola pikir hingga perilaku.
Asumsi “perempuan selalu benar” yang sangatlah apologetik dan tidak relevan bukanlah argumen yang menopang tulisan ini. Ia tidaklah pantas kita atribusi kepada siapapun, termasuk perempuan. Ukuran benar dan tidak benar pada hakikatnya lebih kita tentukan pada perilaku atau tindakan yang diambil. Bukan siapa yang melakukan. Namun demikian, jika dalam berbagai kasus, termasuk yang memposisikan perempuan sebagai korban, female-blaming masih tetap menggejala, rasa-rasanya banyak anggapan umum atau generalisasi yang perlu kita cerna ulang. []