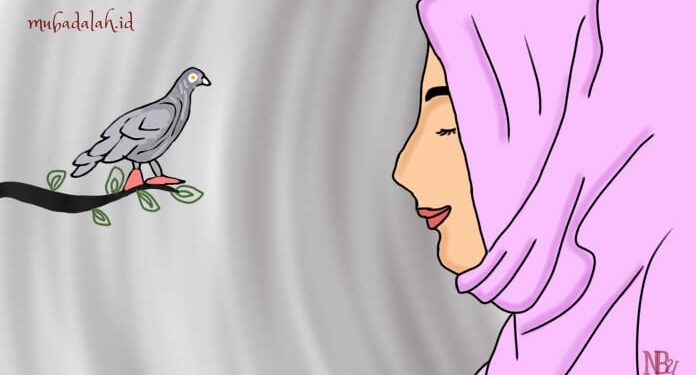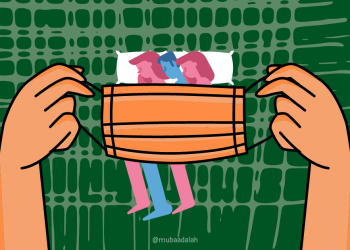Mubadalah.id – Mungkin sekali dua kali kita pernah terbersit sebuah pertanyaan: kenapa yang bisa disebut cantik itu hanya mereka yang putih? Atau setidaknya berkulit mulus dan bening-bening?
Sedari dulu, simbolisasi cantik itu putih dan terang identik dengan keindahan, suci, anggun, menawan, dan perihal baik-baik yang lain. Sebaliknya, hitam dan gelap sering kita tamsilkan sebagai lambang aneka ragam bentuk keburukan.
Petinju legendaris berkulit hitam, Muhammad Ali, bahkan pernah menyinggung secara kritis hal tersebut. Dalam sebuah wawancara ia bertubi-tubi menanyakan:
“Waktu kecil saya tanya ke ibu, bagaimana bisa segala hal yang bagus itu putih? Mengapa Yesus kita gambarkan berkulit putih, berambut pirang, dan bermata biru. Mengapa seluruh murid Yesus, malaikat, paus, Bunda Maria, semua digambarkan berkulit putih?” pantik Ali saat wawancara dengan BBC tahun 1971.
Dan ihwal semacam itu membuka gerbang pada kajian kolonialisme dan paskakolonialisme. Lebih jauh lagi, itu merembet juga hingga ke konsepsi kita tentang kecantikan. Bahwa sosok yang cantik ialah yang berkulit mulus, putih, dan bercahaya. Seolah tidak ada ruang untuk menjadi cantik bagi penduduk yang terlahir berkulit warna lain.
Padahal itu merupakan pemberian secara alamiah (ras). Bukankah itu ganjil dan memancing rasa penasaran? Terutama ketika ribuan, ratusan bahkan jutaan orang berduyun-duyun ‘mengedit’ wajahnya agar menjadi putih.
Mengenai topik ini, ada bacaan menarik. Buku Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional (Marjin Kiri, 2017) karya L. Ayu Saraswati berupaya menelusuri itu. Ia masuk lewat pintu studi kasus di Indonesia.
Mengapa Meneliti Kecantikan?
Bagi Saraswati, manusia itu berorientasi visual. Lagipula, lebih-lebih di zaman serba virtual sekarang ini, organ paling sering diistimewakan dan kita manjakan adalah mata. Karena itu konsepsi menjadi cantik selalu berkaitan dengan peristiwa “melihat” (seeing) dan “terlihat” (being seen).
Saraswati meneliti “kecantikan” ini karena banyak sekali lapis-lapis diskriminasi dan objektifikasi terhadap perempuan. Ada banyak peristiwa perlakuan tidak patut terhadap perempuan “jelek” sebagai “tampilanisme” (look-ism). Saraswati juga membongkar bagaimana “ekspektasi kecantikan merupakan hal yang sistemik” dan bahkan “lebih berbahaya daripada rasisme dan seksisme”.
Itu diperparah karena banyak orang abai, atau tidak sadar bahkan lena akan diskriminasi berdasarkan tampang. Dalam konteks kekinian, banyak curhat di media sosial terkait rekrutmen kerja yang mengedepankan goodlooking Alih-alih kompetensi berdasarkan skill individu. Inilah yang menjadikan riset seputar topik kecantikan penting.
Obsesi Menjadi Putih: Ada Sejak Zaman Baheula
Saraswati secara rinci dan kompleks menyajikan alur kronologis bagaimana “putih” telah menyusup pada konsepsi kecantikan pada bangsa Nusantara. Ia menceritakan alur pergeseran makna dan rujukan “putih” seiring zaman. Menariknya, tidak sebagaimana umum kita pahami, bahwa konsep putih sebagai superior terjadi sejak era penjajahan, Saraswati justru menarik garis lebih jauh ke belakang.
Secara apik ia menelaah karya sastra sebagai lubang intip mengenai kesadaran dan angan-angan kolektif suatu masyarakat. Dan itu dimulainya dari konsep putih dalam epos Ramayana yang legendaris. Epos Ramayana yang diadaptasi oleh bangsa Jawa pada kurun abad ke-9 ini menjadi petunjuk membedakan warna kulit putih dan hitam.
Di mata Saraswati, kulit putih menjadi simbol pujian bagi kejelitaan Sita, kekasih Rama. Dalam karya sastra itu, sosok Sita diagung-agungkan dan terlukis memiliki wajah nan putih, terang bak rembulan, dan bercahaya. Sedangkan figur antagonis, yakni Rahwana, tergambarkan berkulit gelap, berkonotasi buruk dan diilustrasikan sebagai sosok jahat dan pembawa petaka.
Kecantikan Itu Bergeser: Dari Putih Belanda ke Putih Jepang
Bergeser dari abad lawas, Saraswati menyajikan telaah mendalam bagaimana “ideal” kecantikan masa penjajahan terbagi menjadi dua fase: dari Putih Kaukasia (Belanda) menuju Putih Jepang. Dosen bidang Kajian Perempuan di Univeritas Hawai’i ini menerangkan bahwa subjektivitas putih di Indonesia masa kolonial bukanlah semata-mata narasi putih Eropa.
Begitu penjajah baru datang (Jepang), mereka menantang ideal kecantikan putih Eropa dengan menawarkan versi mereka sendiri tentang ideal kecantikan putih Asia. Meski, tetap saja warna putih-lah yang disukai dan dikonstruksikan sebagai “baik”, sementara kulit gelap dianggap tidak dikehendaki (hlm. 98-99).
Ini merupakan imbas kesejarahan, sepanjang abad ke-17 dan ke-18, banyak narasi bernada stereotipe kepada bangsa pribumi Hindia Belanda sebagai pemalas dan dungu. Lebih fatal, “sepanjang periode colonial, warna kulit terang dan putih menandakan status yang lebih tinggi.” Salah satu dampak serius dari itu adalah supremasi kulit putih yang melahirkan berbagai penindasan dan perbudakan.
Kecanduan Pemutih dan Rasa Malu
Penjelasan riset akademis di buku ini cukup kompleks, rumit dan berbumbu banyak analisis canggih perihal kajian interdisipliner (feminis, poskolonialisme dan emotionscape). Kecantikan pasca-kolonial pun berkembang lagi, dan masih menjadikan “putih” sebagai primadona. Bahkan kondisi ini dipropagandakan terus menerus lewat media-media cetak, seperti Poetri Nippon, hingga Poetri Indonesia jang Tjantik Molek.
Di tahap inilah peran pemutih dalam kosmetika mulai menjamur di Indonesia. Jika kita bercermin atau meminjam kacamata dari warga negara lain, sangat banyak sekali orang kulit putih di Eropa yang justru menghindari kosmetik dan sabun muka yang mengandung zat pemutih.
Mereka juga rutin berjemur agar lebih coklat eksotik. Orang-orang kulit putih Eropa mengagumi kecantikan eksotis bangsa Indonesia, juga Amerika Latin. Sementara banyak sekali orang kita yang justru terobsesi menjadi putih seperti mereka.
Ini potret ironis. Terlebih temuan Saraswati menunjukkan bahwa di Indonesia, produk pemutih menduduki posisi tertinggi di antara semua produk industri kosmetik. Unilever Indonesia menghabiskan Rp.97 miliar pada 2003 untuk mengiklankan “satu produk saja” dari pemutih kulit Pond’s (hlm. 178).
Pergeseran Konsep Kecantikan
Bukti lain juga tersebar ke berbagai negara yang mirip. Produk-produk pemutih kulit tersedia di mana-mana di Filipina, Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, India, Arab Saudi, Brasil, Peru, Venezuela, Mexico, Gambia, Senegal, dll. Padahal produk pemutih kulit ini banyak yang diyakini berbahaya secara medis karena kandungan bahan-bahan illegal seperti merkuri atau hidrokinon di atas ambang batas dua persen yang diperbolehkan (hlm. 179).
Terlepas dari itu, riset Ayu Saraswati di sini mempertontonkan kegetiran perempuan yang berlomba-lomba untuk memiliki kulit putih dengan membahayakan diri mereka sendiri. Dalam tulisannya, dari 46 narasumber, hanya 8 yang mengaku tidak pernah mencoba pemutih kulit apa pun. Dalam beberapa pengakuan narasumber juga, tidak sedikit dari mereka yang merasa malu kalau tidak berkulit putih.
Membaca buku ini, bersama dengan realitas terbaru, kita sadar bahwa konsep cantik dan putih sendiri itu bergeser seiring waktu. Dulu dari putih Eropa, lalu Putih Jepang, putih Indonesia, dan mungkin sekarang berkiblat ke Korea Selatan.
Ini juga menyiratkan bahwa konsepsi cantik dan putih selalu berkelindan dengan industri, propaganda, dan relasi kuasa. Perlu kita sadari. Jangan mudah terseret. []