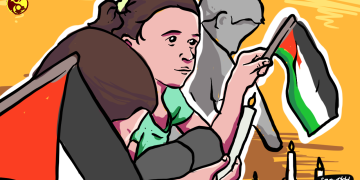Mubadalah.id – Pekat malam masih setia menemani. Dengung orang-orang membaca doa bersama di malam perayaan kemerdekaan terdengar di mana-mana. Hawa dingin malam di musim kemarau tahun ini, tak menyurutkan tekad masyarakat untuk datang dan berkumpul.
Di jalan-jalan dan gang-gang masuk ke kampung yang jauh. Mereka duduk melingkar dan berdoa bersama. Di antara orang-orang yang duduk saling merapat itu, aku bertanya-tanya, kemerdekaan di manakah ia? Karena kemiskinan masih saja setia tak mau beranjak dari rumahku, dan orang-orang di sekitar kampungku.
“Jangan pernah bertanya kemerdekaan di mana Nduk, karena Merdeka tak pernah ada bagi kaum papa.” Ujar Mbah Susno yang duduk di sampingku. Meski bibirnya masih mendaraskan puja-puji dengan lirih. Melantunkan ayat-ayat suci dan selawat pada sang Nabi.
“Lantas untuk apa kita berkumpul dan berdoa bersama jika merdeka tak pernah ada untuk kita?” tanyaku lagi pada si Mbah.
“Setidaknya kita masih mengingat Tuhan, atas berkah kehidupan. Tapi jika bicara kemerdekaan negeri ini, ia ada hanya untuk orang-orang di ibu kota. Entah kota lama yang masih disebut orang dengan sebutan Jakarta, atau kota baru dengan sebutan IKN ibu kota Nusantara.” Ujar Mbah sambil pandangannya menerawang menatap langit-langit malam.
Putus Sekolah
Namaku Dahlia Puspa Indah. Panggil saja Lia. Mungkin orang tuaku menamaiku seperti nama bunga agar sedap dipandang dan indah mewangi. Aku anak pertama dari tiga bersaudara. Adikku semuanya laki-laki masih bersekolah di Tingkat menengah pertama dan sekolah dasar. Bisa kalian tebak, kini aku sudah duduk di sekolah menengah atas.
Setiap kali perayaan kemerdekaan tiba, aku selalu merasa cemas jika merdeka hanyalah kata-kata usang tanpa makna. Sejak aku mampu mengingat, lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana ini, kemerdekaan menjadi sesuatu yang mewah bagiku.
Bapak hanya seorang buruh tani. Sedangkan ibu pedagang sarapan setiap pagi yang penghasilannya tak seberapa. Hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Beruntung, aku dan adik-adik masih bisa bersekolah dengan fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang kadang uangnya malah habis untuk kebutuhan dapur.
Sampai suatu ketika tragedi itu tiba. Bapak ditemukan tak bernyawa setelah mengalami kecelakaan tersambar petir di tengah sawah ketika sedang menggarap lahan milik Pak Haji Samsul. Saat itu aku masih kelas XI sekolah menengah atas di kota kecamatan. Mendadak ibu memintaku berhenti sekolah agar bisa membantunya bekerja mencari penghasilan tambahan.
Terbujuk Rayuan
Sebagai anak pertama, aku tahu punya tanggung jawab untuk menanggung beban keluarga. Ibu yang kehidupannya hanya di sekitar rumah, pasar dan sawah tak punya keberanian untuk pergi bekerja lebih jauh. Akhirnya pilihan ibu jatuh padaku, yang ia anggap sudah bisa dilepas untuk mandiri. Padahal usiaku baru saja menginjak 17 tahun.
Ibu kepincut bujuk rayu Bi Eneng, tetangga desa yang bekerja di ibu kota provinsi. Ia mengaku pada ibu bekerja di tempat mewah dengan gaji besar tapi kerjaan ringan. Hanya membantu bersih-bersih ruangan. Kata Bi Eneng, kerjaan itu cocok untuk anak perempuan seusiaku. Pasti banyak yang suka. Rayuan Bi Eneng terus digencarkan. Hampir setiap hari datang ke rumah menemui ibu.
“Demi adik-adikmu Lia, jangan sampai mereka putus sekolah.” Ujar ibu kembali mencoba membujukku untuk menerima pekerjaan itu. Akhirnya aku luluh juga. Cukup aku saja yang menderita, adik-adikku jangan. Demikian kata-kata yang terus menerus aku tekadkan pada diri, agar tak ada rasa sesal di kemudian hari.
Hari itu pun tiba. Aku berkemas dengan baju seadanya yang dimasukkan ke tas ransel sekolah yang masih aku simpan. Selebihnya kata Bi Eneng akan ia belikan baju di kota. Kamipun berangkat dengan mengendarai kendaraan yang sudah Bi Eneng siapkan. Avanza hitam sudah terparkir di depan rumah.
Terjerumus Pekerjaan Beresiko
Ibuku, adalah perempuan jujur dan lugu yang pernah aku ingat. Tak sekalipun ia curiga pada Bi Eneng, bahkan menaruh kepercayaan 100 persen. Bahwa kepergianku bersama Bi Eneng akan mengubah nasib masa depan keluarga menjadi lebih baik.
Tak pernah terpikir oleh Ibu, bahkan aku sendiri juga tidak, jika kedatanganku ke kota itu membuatku terjebak dalam perdagangan orang dan prostitusi terselubung dengan kamuflase sebagai penyedia layanan jasa spa dan pijat plus-plus. Di mana pelanggannya tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Bahkan ada juga aki-aki yang sudah bau tanah.
Aku menangis tentu saja, teringat almarhum bapak. Merasa berdosa, tapi tak juga ingin menyalahkan ibu. Aku tidak tahu bagaimana caranya agar keluar dari neraka dunia ini. Perasaanku hancur, perih dan pedih. Tubuhku telah rusak, dan aku merasa sudah tak suci lagi.
Tak pernah letih aku berdoa, agar Tuhan memberi jalan. Pintaku satu saja. Aku ingin pulang. Hingga entah ada malaikat dari mana, tiba-tiba datang pelanggan seorang bapak paruh baya yang mengaku bernama Pak Darman. Saat aku masuk ke kamar layanan pijat dengan langkah gontai, dan mata tertunduk enggan, dia hanya menatapku tajam, lalu ia bertanya. “Kamu pasti nggak pengen bekerja di sini?”
Aku bingung mau menjawab apa, hanya anggukan kecil sebagai tanda mengiyakan pertanyaannya. Aku takut untuk bercakap-cakap hal sensitif dengan pelanggan. Takut dilaporkan pada majikan.
“Ya sudah, kamu ikut saya, nanti saya yang bilang ke bos kamu kalau aku suka kamu dan ingin layanan private di rumah. Tenang saya tidak akan melakukan apapun. Saya akan mengantarkan kamu pulang ke rumah orangtuamu.”
Setelah sekian lama akhirnya aku tahu, Pak Darman adalah intel polisi yang kadang-kadang menyamar untuk pura-pura menjadi pelanggan. Atau jangan-jangan sebenarnya petugas berseragam cokelat bagian dari sindikasi perdagangan orang? Entahlah. Aku tak berani menduga-duga. Pak Darman yang baik itu akan membebaskan beberapa perempuan yang merasa tidak nyaman dengan pekerjaan beresiko. Karena ada pula sebagian perempuan yang telah memilih profesi beresiko tersebut sebagai jalan kehidupan.
Makna Merdeka
Setelah aku diantarkan pulang ke rumah, ibu menangisiku tanpa henti. Tentu saja ibu merasa bersalah atas apa yang aku alami. Tapi aku tak menaruh benci apalagi dendam pada ibu sendiri. Justru dari pengalaman ini, aku semakin getol menyampaikan ke teman-teman sebaya agar tak mudah terbujuk rayuan para agen penyalur kerja yang belum jelas, terutama Bi Eneng.
Sindikat perdagangan orang itu ada dan nyata. Dia bergerak seperti sistem yang saling berkelindan antar kepentingan bisnis yang saling menguntungkan, di mana ada permintaan, pasti ada yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Singkat cerita, untuk mengejar ketertinggalan sekolah, aku menyelesaikannya dengan belajar dan lulus dari kejar paket C. Berbekal ijazah kejar paket C aku bekerja menjadi pelayan di mini market terdekat. Pelan namun pasti aku ingin melupakan bagian dari masa laluku yang pernah bernoda.
Meski aku akui, ia tak mungkin hilang begitu saja. Trauma itu tetaplah ada, dan akan menjadi pelajaran berharga, betapa anak perempuan ke manapun langkah kakinya pergi akan rentan menjadi korban kekerasan. Bagiku inilah makna merdeka sesungguhnya. Yaitu merdeka dari segala bentuk kekerasan, kapanpun dan dimanapun.
“Mbah, aku ingin kirim surat untuk Bung Karno dan Bung Hatta.” Kataku pada Mbah Susno usai doa bersama di malam kemerdekaan.
“Apa yang ingin kamu sampaikan Nduk?” tanya Mbah Susno
“Aku ingin tanya, 79 tahun Indonesia sudah merdeka, IKN dibangun dengan begitu megah, tapi kenapa rakyatnya masih banyak yang miskin?”
“Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab Nduk.” Sahut Mbah Susno
Dan aku biarkan angin malam membawa seluruh resahku pada negeri ini. Pada Bung Karno, Bung Hatta, dan para pahlawan lainnya, tentang kisah masa depan anak-anak bangsa yang tak pasti, dan mimpi yang tak sanggup lagi aku jelajahi. []