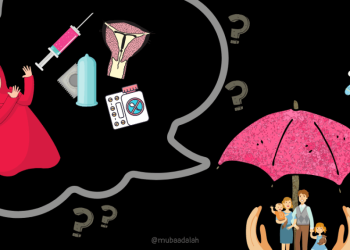“Siapa pasangan idolamu?”
Dalam beberapa kesempatan, saya kerap mendapati pertanyaan itu mencuat begitu saja. Seringkali diutarakan dalam obrolan santai oleh sejawat kepada pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Kadang juga sengaja ditujukan pada saya atau teman-teman lain, sebagai sindirian karena tak kunjung mau berumah tangga.
Tentunya jawaban dari pertanyaan itu adalah gambaran bagaimana kami ingin menjalani kehidupan berumah tangga nantinya. Semacam harapan agar bisa menjalani relasi yang saling mengisi dan saling menghargai satu sama lain.
Pernah salah satu teman menjawab, bahwa pasangan yang diidolakannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah. Singkatnya, dia ingin menjalani relasi sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi dan istrinya dengan suka duka dan perjuangan panjang yang mesti dilalui bersama. Mengingat Khadijah senantiasa menemani Muhammad, bahkan ketika Muhammad berada dalam kekalutan panjangnya menuju Kenabian. Dari Muhammad dan Khadijah setidaknya kita belajar bagaimana relasi kesalingan itu diciptakan.
Kesalingan (mufa’alah) sendiri merupakan bentuk lain dari mubadalah, sebuah konsep relasi antar dua belah pihak yang mengandung semangat kemitraan dan prinsip resiprokal. Relasi kesalingan di sini memang tidak hanya berlaku untuk pasangan suami istri, akan tetapi juga berlaku dalam konteks guru dengan murid, anak dengan orangtua, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan bahkan relasi antara negara dengan rakyatnya (Qadir: 59)
Salah satu pasangan abad ke-20 yang menurut saya bisa dijadikan contoh dalam menjalin relasi kesalingan adalah Aisyah Bintu Syathi’ dengan Amin al-Khuli. Selain relasi suami istri, kesalingan yang dipraktikkan keduanya juga berlaku pada konteks murid dengan guru.
Aisyah bintu Muhammad bintu Muhammad Ali Abdurrahman atau yang lebih familiar dengan nama pena Bintu Syathi’ (Putri Pesisir) adalah seorang pemikir, sastrawan, sekaligus merupakan perempuan pertama yang menjadi ahli tafsir terkemuka.
Lahir pada 6 Nopember 1913, di tengah masyarakat Arab yang masih tradisional, Bintu Syathi’ memiliki perjalanan hidup yang berliku dan keras, terutama ketika harus berhadapan dengan ayahnya sendiri agar bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun dengan keteguhan dan bantuan sang ibu dan kakeknya, Bintu Syathi’ bisa tetap melanjutkan studi dan mendapat gelar Sarjana dan Master pada bidang Studi Bahasa dan Sastra Arab.
Bintu Syathi’ di kemudian hari juga dikenal sebagai seorang emansipatoris, karena semasa hidupnya dihabiskan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, mulai dari hak mendapatkan pendidikan sampai hak untuk ikut berpartisipasi dan perjuangan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam.
Perkenalan pertama Bintu Syathi’ dengan suaminya, Amin al-Khuli berawal di bangku kuliah. Di mana Amin al-Khuli tidak lain merupakan pemikir besar di al-Azhar sekaligus dosen yang mengajar Bintu Syathi’ pada mata kuliah Ulumul Qur’an. Kepakaran Amin al-Khuli dalam bidang tafsir memang tidak bisa disangsikan, karena Amin al-Khuli merupakan sosok pendobrak. Ia merupakan pembaharu dalam metode tafsir tradisional dan menggunakan pendekatan sastrawi dalam menafsirkan al-Qur’an.
Relasi kesalingan pertama yang dapat kita pelajari dari Bintu Syathi’ dengan Amin al-Khuli yakni pada konteks guru dan murid. Sebagai dosen sekaligus suami dari Bintu Syathi’, Amin al-Khulli tidak lantas tampil sebagai sosok yang dominan. Amin al-Khulli selalu membuka ruang diskusi dan bertukar pendapat dengan Bintu Syathi’. Begitu pun sebaliknya, dengan kapasitas dan kecerdasan yang dimilikinya, Bintu Syathi’ tidak segan untuk memberi kritik pada aspek-aspek dalam sastra Arab dan tafsir yang menurutnya tidak memberi ruang pada perempuan.
Dalam hal ini, al-Khuli juga tidak memaksakan pemikiran Bintu Syathi’ selalu sejalan dengannya. Sebagai guru, ia membebaskan muridnya memiliki cara pandang yang berbeda dengannya. Meski demikian tidak bisa disangkal bahwa metode tafsir sastrawi yang diperkenalkan oleh Amin al-Khuli sangat berpengaruh pada penafsiran yang dilakukan oleh Bintu Syathi’, selain juga karena jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang fokus dipelajarinya sejak Sarjana.
Relasi kesalingan kedua yang bisa kita saksikan dari kehidupan Bintu Syati’ dan Amin al-Khuli adalah relasi suami dan istri yang dibangun keduanya selama 20 tahun. Setelah menikah, pasangan ini membuktikan bahwa relasi kesalingan yang mereka bangun, dapat menjadikan keduanya tetap produktif untuk mengeluarkan gagasan dan pemikiran yang luar biasa. Bintu Syathi’ juga tetap mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar doktor dan menjadi perempuan pertama yang menafsirkan al-Qur’an (ushuluddin.com).
Dari pasangan inilah saya belajar bahwa relasi kesalingan benar-benar dapat terwujud, baik dalam perjalanan akademik maupun perjalanan rumah tangga, dan tentunya akan bisa kita temukan dalam konteks yang lain. Dan meski telah terpisah secara dimensional, buah gagasan keduanya tetap bisa kita saksikan dan pelajari hingga detik ini lewat karya. Perjalanan hidup yang dilalui oleh Bintu Syathi’ dengan Amin al-Khulli sendiri juga telah terekam dengan sangat detail dalam novel yang ditulis Bintu Syathi’ berjudul ‘Alaa al-Jisr, ditulis selepas kepergian Amin al-Khulli pada 1960-an. []