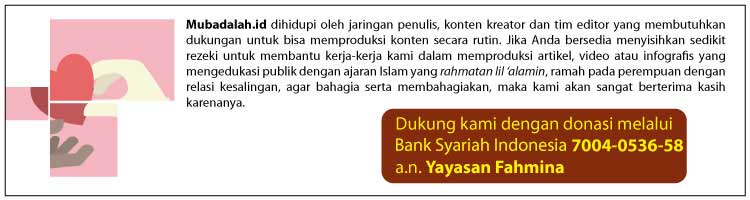Mubadalah.id – Di tengah tekanan sosial dan budaya, keputusan untuk tidak mengkhitan anak perempuan bukanlah hal mudah. Karena sebagian dari masyarakat masih beranggapan bahwa khitan anak perempuan menjadi kewajiban yang harus dilakukan.
Sebab, kalau anak perempuan tidak dikhitan, ia akan tumbuh menjadi perempuan yang liar, nakal dan sulit untuk mengontrol seksualitasnya (hypersex).
Namun, sebagai orang tua baru, saya bersama istri tetap memilih jalan berbeda untuk tidak mengkhitan anak perempuan kami. Keputusan yang kami pilih bukan tanpa alasan, melainkan banyak hal yang kami pertimbangkan untuk tidak mengkhitannya.
Salah satunya adalah kami meng-amini dan percaya dengan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II, yang secara tegas menyatakan khitan perempuan tanpa alasan medis hukumnya haram.
Fatwa inilah yang membuat kami menjadi yakin bahwa dengan tidak mengkhitan putri kami, kami bisa menyelamatkan dia dari beberapa dampak buruk yang akan terjadi. Misalnya disfungsi seksual, komplikasi pada kehamilan dan terutama persalinan, dispareni, nyeri panggul kronis hingga kematian.
Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi dasar, mengapa KUPI mengharamkan khitan perempuan, di antaranya:
Pertama, KUPI menegaskan bahwa khitan perempuan tidak memiliki dasar agama yang kuat. Hadis-hadis yang digunakan untuk melegitimasi praktik ini berstatus dha’if (lemah) atau bahkan tidak valid secara sanad.
Misalnya, hadis tentang Ummu Athiyah yang sering dijadikan rujukan merupakan hadis lemah. Karena dalam praktiknya Nabi Muhammad Saw sendiri tidak pernah mengkhitan putri-putrinya.
Berujung pada Kematiaan
Kedua, dari segi medis, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan, justru berisiko menyebabkan infeksi, pendarahan, disfungsi seksual, hingga kematian.
Penelitian Komnas Perempuan dan PSKK UGM (2017) mengungkap bahwa 4 dari 5 metode khitan perempuan di Indonesia melibatkan pelukaan genital, seperti pemotongan klitoris atau pengikisan uretra. Dampak jangka panjangnya termasuk trauma psikis, nyeri kronis saat berhubungan intim, dan komplikasi persalinan.
Ketiga, bagi sebagian masyarakat khitan perempuan diyakini dapat mencegah anak perempuan menjadi hypersex atau liar. Bahkan mitos serupa ditemukan di Makassar, di mana perempuan yang tidak dikhitan dianggap genit dan tidak sopan. Padahal, klaim ini tidak berdasar ilmiah dan justru mencerminkan pandangan patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek kontrol seksual.
Oleh sebab itu, KUPI mengkritik keras hal ini. KUPI menegaskan bahwa tidak ada korelasi antara khitan dan pengendalian nafsu. Sebaliknya, praktik ini merampas hak perempuan atas tubuhnya sendiri dan melanggengkan kekerasan kepada mereka.
Keempat, menurut KUPI, khitan perempuan sangat bertentangan dengan prinsip maqashid asy-syari’ah. Salah satunya adalah hifzh an-nafs (menjaga jiwa). Sehingga, dari pada mendatangkan kemadharatan (bahaya), lebih baik menghadirkan kemaslahatan bagi anak perempuan dengan menjaga jiwa mereka dari berbagai kekerasan.
Oleh sebab itu, dari empat poin di atas, sebetulnya KUPI lebih menekankan untuk “berbuat baik pada perempuan”, bukan menyakiti mereka. Sehingga Fatwa KUPI di atas dapat menjadi landasan moral dalam melindungi anak perempuan dari berbagai kekerasan.
Bahkan, dengan tidak mengkhitan anak perempuan, saya yakin bahwa saya dan istri telah memilih jalan yang selaras dengan nilai kemaslahatan dan kemanusiaan. []