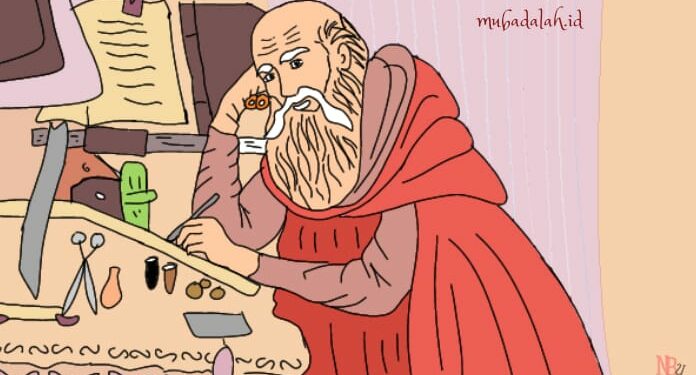Mubadalah.id – Renaisans Eropa merupakan warisan yang kontradiktif. Kita sering menganggapnya sebagai tempat kelahiran modernitas. Namun mereka yang berada di balik layar Renaisans pada dasarnya cukup prihatin dengan girah untuk membangkitkan kembali dunia kuno. Sebagaimana namanya yang berarti ‘kebangkitan kembali’.
Bagi kelompok humanis abad ke-15 dan ke-16, budaya skolastik Abad Pertengahan perlu terisi kembali dengan semangat zaman kuno. Seperti yang dilakukan oleh pendeta berdarah Italia Marsilio Ficino (meninggal tahun 1499) yang pergi “menangkap ikan dengan jaring Platonisme” demi mencari kebenaran Kristen. Giordano Bruno (meninggal tahun 1600) yang mendalami tradisi Mesir kuno dan Helenisme untuk mencari rahasia yang ia yakini sudah lama ada.
Menurut pandangan mereka, gerakan yang mereka lakukan adalah gerakan ke belakang menuju masa lalu yang berupaya mendapatkan kembali mutiara-mutiara kebijaksanaan yang sudah terabaikan saat ini. Mereka tidak berniat melakukan revolusi. Melainkan, sebagaimana tersirat dalam istilah “renaisans”, sebuah kebangkitan—sebuah renovasi .
Namun, terlepas dari semua pengetahuan arkais yang mereka peroleh, kelompok humanis juga memunculkan ide-ide yang pada akhirnya membentuk pandangan dunia yang bertentangan dengan hal-hal yang telah ada sebelumnya.
Ini terjadi karena, menurut beberapa orang, pemahaman kelompok humanis terhadap filsafat kuno sering kali didekontekstualisasikan dengan mendistorsi makna aslinya. Misalnya, dengan mencampurkan Platonisme dengan aliran pemikiran lain yang tidak sejalan, seperti Epikureanisme dan Skeptisisme. Akibatnya, Renaisans secara tidak sengaja memunculkan apa yang sekarang kita sebut sebagai filosofi modern.
Konsep Martabat Manusia
Penekanan modernitas terhadap pengalaman empiris bisa kita bilang merupakan nubuat atas metodologi ilmiah; peralihannya menuju keindahan dunia imanen menandai dimulainya sastra dan seni modern; dan perayaan akan kebebasan manusia—yang dianggap sebagai ciri khas peradaban kuno—menggambarkan liberalisme yang membuahkan hasil berupa Pencerahan.
Mungkin tidak ada contoh paradigmatik dari pembiasan tradisi ini selain ‘Oration on the Dignity of Man’, yang juga terkenal sebagai “the manifesto of the Renaissance,” yang ditulis oleh pangeran sekaligus filsuf Italia Giovanni Pico della Mirandola pada 1486, tepat di usianya yang ke dua puluh tahun.
Manifesto di atas mengartikulasikan konsep martabat manusia dengan memberikan penjelasan tentang manusia yang mengacu pada ajaran Platonisme, Kristen, Hermetik, Kabbalistik, dan Islam. Namun di sisi lain mengarah pada paradigma modernitas dan liberal atas kebebasan individu.
Pesannya kira-kira begini: “Martabat manusia tidak terletak pada bentuk fisiknya yang paling sempurna, melainkan pada potensinya untuk menjadi apa pun yang ia inginkan.” Bagi Pico, kita bisa memilih menjadi malaikat atau iblis, tapi kita akan selalu bermartabat karena kita adalah manusia.
Pandangan tentang martabat manusia terpenuhi dengan makna spiritual yang berdasarkan pada doktrin imago Dei dan hakikat kehendak yang ditahbiskan oleh Tuhan. Namun, nilai sakral yang Pico berikan pada pilihan-pilihan individu tampaknya terlalu condong ke arah sekularisme modern yang mengutamakan aktualisasi diri di atas segalanya, yang menjadi sumber keangkuhan dan sikap eksploitatif manusia terhadap alam dan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, tidak sedikit yang mengatakan bahwa karya tersebut terjebak di antara pandangan dunia pramodern dan pandangan dunia modern, sehingga menimbulkan pertanyaan. Di mana dan bagaimana pandangan Pico tentang martabat manusia yang memunculkan pemahaman kita saat ini? Dan bagaimana filosofinya membantu untuk mengungkapkan perbedaan antara kedua paradigma tersebut?
Yang Membuat Manusia Spesial
Menariknya, Pico membuka ‘Oration’-nya dengan mengutip seorang pemikir Muslim Persia, Ibn al-Muqaffa, yang ketika ditanya apa yang “menurutnya paling membuatnya takjub.” Ia menjawab “bahwa tidak ada yang lebih luar biasa dari manusia.” Pico mengatakan bahwa manusia spesial karena ia bebas dari batasan-batasan spasial, organik, dan kreatif yang hewan lain miliki, sehingga manusia berpotensi dapat menjadi apa pun yang ia inginkan.
Pico della Mirandola membayangkan Tuhan menyatakan kepada Adam bahwa “ketika makhluk lain diciptakan dengan batas-batas, kau bisa menyelami dirimu sendiri tanpa batas.” Kita, kata Pico, seperti bunglon: tidak seperti makhluk lain yang sifat-sifatnya telah ditentukan sebelumnya, kita tidak terbatas pada satu sifat tertentu saja. Pico membayangkan Tuhan memberi tahu kita bahwa kita bisa berubah menjadi apa pun yang kita inginkan:
“Kami telah menjadikanmu makhluk yang bukan berasal dari langit dan bumi. Tidak fana dan tidak abadi, agar kamu, sebagai pembentuk wujudmu sendiri yang bebas dan bangga, membentuk dirimu sesuai dengan wujud yang kamu sukai.”
Kemampuan transmutasi manusia ini, bagi Pico, memiliki dimensi moral. “Adalah kekuatanmu,” lanjutnya. “untuk turun ke bentuk kehidupan yang lebih rendah dan brutal; kau juga akan mampu, melalui keputusanmu sendiri, untuk bangkit ke tingkatan tertinggi yang ilahiah.”
Hal ini menyiratkan bahwa martabat manusia terletak pada kemampuannya untuk memilih. Pico menekankan bahwa manusia memiliki tingkat kebebasan dan potensi yang dapat membawanya lebih dekat pada Tuhan dibandingkan makhluk lain.
Menilik Pemikiran Johann Herder
Kita menemukan gambaran lain tentang pemikiran ini dalam tulisan filsuf Romantisme Jerman abad 18, Johann Herder. Herder juga memandang manusia sebagai makhluk yang unik dan unggul karena manusia relatif bebas dari batas-batas alamiahnya. Senada dengan Pico, ia berpendapat bahwa semua makhluk hidup terbatas pada “lingkup” ekspresi dan pengaruh tertentu, yang ditentukan oleh kapasitas fisik dan sumber daya yang mereka miliki.
Seekor laba-laba, misalnya, “menenun dengan seni Minerva; namun semua karya seninya juga terjalin dalam ruang pemintalan yang sempit.” Sementara itu, manusia tidak terbatasi pada konstruksi sarang laba-laba—dimensinya, bentuknya, atau sutranya—sebaliknya ia memiliki “ruang yang bebas untuk berlatih dalam banyak hal, sehingga ia bisa terus meningkatkan dirinya.”
Bagi Herder, seperti halnya Pico, meningkatkan kualitas diri terus-menerus merupakan cara pemanfaatan kebebasan tertinggi. Kedua pemikir ini selaras dengan upaya penyempurnaan diri dalam Platonisme (dan tentu saja Kristen dan Islam).
Namun, yang unik dari pandangan Renaisans adalah anggapan bahwa martabat manusia terletak pada kehendaknya dan bukan pada pemenuhan teleologisnya. Kita akan bermartabat selama kita menjalani kehidupan yang kita pilih sendiri. Hal ini memberikan prioritas tinggi terhadap aktualisasi diri, atau apa yang Herder sebut sebagai “cerminan diri” (self-mirroring):
“Manusia dapat mencari ruang untuk mencerminkan dirinya sendiri. Ia bukan mesin di tangan alam, ia adalah tujuan dan objek penyempurnaannya sendiri.”
Nilai Kebebasan Manusia
Oleh karena itu, bagi Pico, nilai kebebasan manusia terletak pada kemampuannya untuk mengaktualisasi diri. Karenanya kemampuan ini tidak boleh terbatasi oleh struktur atau sistem yang kita paksakan dari luar dirinya. Pemahaman tentang kebebasan ini—dan implikasi politik bahwa masyarakat tidak boleh membatasi potensinya—merupakan awal dari putusnya hubungan Pico dan Plato. Meskipun Pico mengakui bahwa dia banyak berhutang budi pada filsafatnya.
Bagi Plato, nilai kebebasan manusia bergantung pada perjuangannya demi “Kebaikan”, sehingga menjadi tanggung jawab otoritas politik dan sistem pendidikan untuk menciptakan kondisi yang cocok bagi realisasi kolektif perjuangan tersebut. Hal ini memerlukan penerapan batasan-batasan tertentu (misalnya, melarang hal-hal yang dapat merangsang nafsu). Di mana pada dasarnya merupakan suatu bentuk “kebebasan positif” atau kebebasan untuk mengejar kebaikan dan kebebasan dalam keterbatasan.
Sebaliknya, penekanan Pico terhadap keutamaan sikap untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) sejalan dengan apa yang kita sebut “kebebasan negatif”. Kebebasan dari apa pun yang mengganggu keinginan dan kecenderungan kita, dan juga kebebasan dalam ketidakterbatasan. Ini adalah kebebasan yang mengutamakan keinginan individu dibandingkan kebaikan kolektif, mengecam segala bentuk pengekangan.
Dengan demikian, meskipun Platonisme, Kristen, dan Islam berpendapat bahwa manusia hanya benar-benar bebas dan bermartabat ketika ia memilih kehidupan yang terbai. Yakni, kehidupan yang dapat mengatasi hawa nafsu, di sisi lain kemartabatan dan kebebasan manusia versi Pico bergantung pada kemampuannya mengejar keinginannya dan memilih bentuk kehidupan yang diinginkan.
Jaring Laba-laba Duniawi
Bagi Herder dan Pico, manusia bebas ketika manusia tidak terbatasi oleh parameter jaring laba-laba metaforis dan mampu “menelusuri dirinya sendiri.” Selain itu juga bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Namun dalam pandangan Platonisme, jika kehidupan seseorang terdorong oleh nafsu, ia sebenarnya sedang membuat jaring laba-laba yang menjebaknya dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan menghalanginya dari kebebasan sejati.
Gambaran semacam itu juga muncul dalam Surah al-Ankabūt ayat 41, di mana kita diberitahu bahwa mereka yang hidup untuk hal lain selain Tuhan “diumpamakan seperti seekor laba-laba yang membangun rumahnya sendiri.” Ayat ini mengajarkan bahwa jaring laba-laba ini tidak hanya menjebak kita tetapi juga merupakan “rumah yang paling lemah”, yang terpintal dari sutra duniawi dan bukan dari kebenaran yang transenden.
Pico sendiri pun tidak berniat untuk menghapuskan sisi kerinduan akan sesuatu yang transenden dalam diri manusia. Faktanya, beliau mendorong agar kita juga harus “menutrisi sisi ketuhanan dalam jiwa kita dengan pengetahuan tentang hal-hal ilahi.” Bentuk aktualisasi diri yang paling tinggi, menurut Pico, justru adalah mengaktualisasi bagian yang paling dekat dengan Tuhan: spiritualitas.
Namun, karena Pico melihat bahwa martabat manusia terletak pada potensinya untuk memilih apa pun yang diinginkan, cita-cita transendensi seperti itu menjadi sulit untuk kita gapai. Ketika martabat kita samakan dengan hak untuk “membentuk diri yang merdeka”, maka keharusan untuk mencapai keadaan tertinggi (transenden) rentan dikompromikan; jadi mungkin inilah yang menyebabkan kejatuhan spiritualitas kita di era modern. []