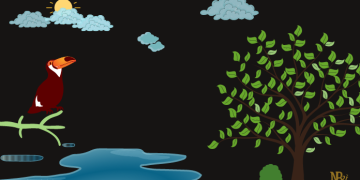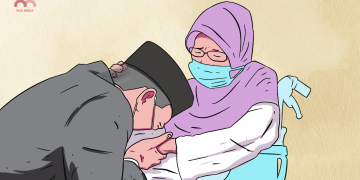Mubadalah.id – Di jagat maya Indonesia yang selalu riuh, sebuah fenomena baru muncul: S-Line trend. Dalam sekejap, linimasa media sosial, terutama TikTok, dibanjiri oleh konten-konten berisi “pengakuan dosa” yang tertandai dengan garis merah di atas kepala. Tren ini, yang awalnya tampak seperti candaan, dengan cepat membelah opini publik dan mengundang perdebatan tentang moralitas, budaya, dan privasi di era digital.
Akar dari tren S-Line ini berasal dari salah satu manhwa webtoon yang berjudul sama, yang kemudian diadaptasi menjadi drama Korea. Webtoon ini mengisahkan tentang dunia di mana garis merah, yang kita sebut S-Line, tiba-tiba muncul di atas orang-orang. Garis merah ini menghubungkan mereka dengan orang-orang yang pernah menjalin hubungan intim dengannya.
Garis ini tidak bisa tersembunyikan dan akan mengikuti ke mana pun seseorang pergi. Sehingga membongkar semua rahasia hubungan seksual seseorang kepada publik. Konsep inilah yang kemudian teradaptasi, atau lebih tepatnya disalahartikan, oleh para pengguna media sosial di Indonesia menjadi sebuah “tren pengakuan dosa”.
Di tangan warganet Indonesia, S-Line bertransformasi menjadi suatu format konten di mana seseorang akan menuliskan “dosa-dosa” atau aib mereka dalam sebuah video. Kemudian mereka timpa dengan stiker garis merah di atas kepala. “Dosa-dosa” yang terakui pun beragam, mulai dari hal-hal sepele. Seperti berbohong kepada orang tua, hingga yang lebih serius seperti pernah melakukan hubungan seks di luar nikah atau bahkan aborsi.
Menabrak Batas Moral dan Budaya
Konten-konten tersebut sering kali diiringi dengan musik yang sedang naik daun dan filter-filter yang menarik, membuat tren ini terasa seperti hiburan semata ketimbang pengakuan dosa yang sakral. Inilah titik di mana tren S-Line mulai menabrak batas-batas moral dan budaya yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.
Dalam bukunya ‘The Moral Landscape’, Sam Harris berargumen bahwa moralitas bukanlah sesuatu yang relatif. Melainkan sesuatu yang dapat terukur secara objektif berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan makhluk hidup. Jika kita menerapkan lensa ini pada tren S-Line, kita akan melihat sebuah paradoks.
Di satu sisi, ada argumen yang mengatakan bahwa tren ini bisa menjadi katarsis bagi pelakunya. Sebuah cara untuk melepaskan beban dosa agar merasa lebih baik. Namun, di sisi lain, kita juga perlu bertanya, kesejahteraan siapa yang sebenarnya sedang kita pertaruhkan di sini?
Apakah pengakuan dosa yang mereka lakukan secara terbuka di media sosial benar-benar akan membawa kelegaan jangka panjang? Ataukah ini hanya akan menjadi sumber penderitaan baru di masa depan, ketika keluarga, pasangan, atau bahkan calon atasan menemukan konten tersebut?
Lebih jauh lagi, tren ini juga mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan menjaga aib, pengakuan dosa secara terbuka di media sosial adalah sebuah anomali. Islam mengajarkan bahwa dosa merupakan urusan pribadi antara seseorang dengan Tuhannya, dan aib adalah sesuatu yang harus tertutupi, bukan kita umbar untuk menjadi konsumsi publik.
Implikasi Tren S-Line
Tren S-Line, dengan demikian, tidak hanya menantang ajaran agama, tetapi juga norma-norma budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat. Ia mengubah sesuatu yang sakral dan privat menjadi sebuah komoditas konten yang diperjualbelikan demi engagement dan popularitas di dunia maya.
Implikasi dari tren ini terhadap privasi juga tidak bisa kita anggap remeh. Di era di mana data pribadi adalah mata uang baru, pengakuan dosa secara sukarela di media sosial adalah undangan terbuka kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yakni untuk mengeksploitasi informasi tersebut. Bayangkan seorang remaja yang, karena ikut-ikutan tren ini, mengakui pernah melakukan sesuatu yang dianggap aib oleh masyarakat.
Beberapa tahun kemudian, ketika ia hendak melamar pekerjaan atau menikah, konten tersebut muncul kembali dan menghancurkan masa depannya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah platform media sosial yang memfasilitasi tren ini? Ataukah individu itu sendiri yang, karena kurangnya literasi digital, tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya?
Cathy O’Neil, dalam bukunya ‘The Shame Machine’, mengupas bagaimana aib dan rasa malu telah menjadi komoditas yang menguntungkan. Tren S-Line, dalam banyak hal, adalah manifestasi dari “mesin malu” ini. Ia mengeksploitasi rasa bersalah dan kebutuhan akan pengakuan untuk menghasilkan konten-konten viral.
Melek Literasi Digital
Para content creator, yang mungkin awalnya hanya iseng, tanpa sadar telah menjadi roda penggerak mesin yang mengubah penderitaan dan aib menjadi tontonan publik. Semakin mengejutkan pengakuan dosanya, semakin besar kemungkinan konten tersebut menjadi viral, dan semakin banyak pula keuntungan yang mereka dapatkan. Baik dalam bentuk followers, likes, maupun popularitas. Namun, keuntungan ini harus terbayar mahal dengan terkikisnya nilai-nilai moral, budaya, dan privasi.
Tren S-Line adalah cerminan dari kondisi masyarakat kita saat ini. Masyarakat yang terobsesi dengan validasi orang lain, yang rela mengorbankan privasinya demi eksistensi di dunia maya, dan yang semakin kehilangan kepekaan terhadap batas-batas moral dan budaya.
Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menghakimi para pelaku tren S-Line tentu bukanlah solusi. Mereka, dalam banyak kasus, adalah korban dari sebuah sistem yang terdesain untuk membuat kita terus-menerus membagikan informasi pribadi tanpa memikirkan akibatnya.
Saat ini yang kita butuhkan adalah gerakan literasi digital yang masif. Di mana tidak hanya mengajarkan tentang cara penggunaan teknologi, tetapi juga tentang etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. []