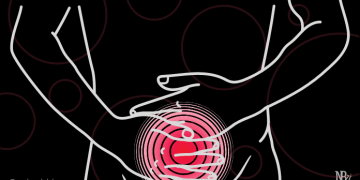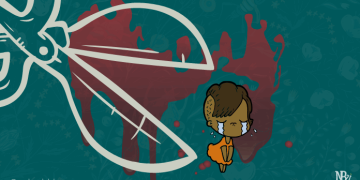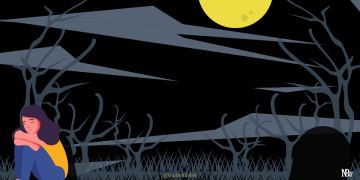“One is not born, but rather becomes, a woman.”
— Simone de Beauvoir
“Cinta dua manusia tidak akan sempurna hingga ia berkata: kau adalah aku.”
— Jalaluddin Rumi
“Ana al-Ḥaqq!” (Akulah Kebenaran)
— al-Ḥallāj
Mubadalah.id – Sejatinya, tulisan ini berangkat dari sebuah pengalaman yang sebelumnya tidak pernah saya duga akan menuntun saya pada sebuah perenungan lintas peradaban.
Perenungan ini muncul ketika saya sedang membimbing skripsi mahasiswa program studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN SATU Tulungagung. Mahasiswa itu menulis skripsi dengan judul “Dari Liyan Menuju Subjek: Representasi Tubuh Yeong-Hye dalam Novel The Vegetarian Melalui Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir.”
Saat mahasiswa tersebut saya minta untuk menjelaskan bagaimana posisi tokoh utama dalam novel, Yeong-Hye, mengalami objektivikasi oleh suami dan ayahnya, ia menjelaskan bahwa dua figur yang patriarkal tersebut (suami dan ayah Yeong-Hye) tidak hanya sekedar mengontrol tubuh Yeong-Hye, tetapi juga mendefinisikan eksistensinya.
Dalam upaya menolak semua itu, Yeong-Hye memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Yakni suatu bentuk resistensi diam yang mendalam dan penuh dengan makna simbolik. Ia sekuat tenaga memilih menjadi subjek atas dirinya, dan bukan sekedar objek dari kehendak orang lain.
Saat mendengarkan paparan mahasiswa tersebut, saya lantas terdiam, dan merenung tentang apakah konsep tentang tubuh, cinta, dan kebebasan ini bisa terbaca lebih dari sekedar konsep filosofis saja?
Dari Bimbingan Skripsi ke Renungan Filsafati
Dalam renungan sekilas tersebut, saya bertanya dalam diri, “apakah hanya Simone de Beauvoir saja yang menawarkan jalan agar seseorang bisa benar-benar menjadi subjek? Apakah dalam khazanah spiritual Islam, kita tidak menemukan semangat yang serupa dari tokoh-tokoh pemikir muslim juga?”.
Maklum, saya kerap kali mengkritisi skripsi mahasiswa AFI yang terkadang pembahasannya kurang menampakkan sisi aqidahnya, atau kurang mencerminkan analisis filsafat Islamnya, dan lebih cenderung ke filsuf Barat. Apakah ini salah? Tentu saja tidak sepenuhnya salah. Hanya saja, AFI perlu menunjukkan pencirinya yang unik sebagai bagian dari keilmuan PTKI, yang tentu berbeda dengan filsafatnya PTU.
Kembali lagi ke renungan saya saat membimbing skripsi mahasiswa. Seketika, saya teringat dengan ungkapan Rumi, yang kerap kali Kyai Husein Muhammad kutip, “Cinta dua manusia tidak akan sempurna hingga ia berkata: kau adalah aku.” Tidak hanya itu, saya juga teringat pada keberanian eksistensial dari al-Hallaj dalam mengatakan “Ana al-Haqq”, yang saya maknai sebagai keberanian dalam meniadakan ego demi kebenaran ilahiah.
Berawal dari itu, saya mulai melihat benang merah. Meski ketiga tokoh tersebut (baik Simone, Rumi, maupun al-Hallaj) memiliki epistemologi dan tradisi yang berbeda, namun ketiganya sejatinya sedang berbicara soal kemanusiaan, subjektivitas, dan juga kebebasan. Ketiganya menolak objektivikasi, baik oleh kekuasaan, norma, cinta yang manipulatif, maupun ego yang membelenggu.
Dalam hal ini, tulisan ini hadir sebagai hasil perjumpaan kontemplatif tersebut. Tulisan ini merupakan sebuah ikhtiar untuk menjembatani antara modernitas, spiritualitas, dan gender dalam satu ruang pemaknaan yang reflektif.
Tubuh: Dimensi Sosial dari Ketubuhan yang Diobjektivikasi
Simone de Beauvoir dalam bukunya yanag berjudul “The Second Sex” mengatakan bahwa perempuan telah begitu lama terdefinisikan oleh laki-laki sebagai “yang lain” (the Other). Tubuh perempuan tidak lagi dimiliki oleh dirinya sendiri, melainkan didikte oleh tatanan patriarkal yang menuntutnya untuk menjadi cantik, tunduk, patuh, dan sesuai dengan norma yang dibuat oleh masyarakat patriarkal.
Yeong-Hye, sebagai tokoh utama dalam novel “The Vegetarian” karya Han Kang, menjadi representasi perlawanan terhadap kontrol atas tubuhnya ini. Keputusannya untuk menjadi vegetarian, sebenarnya bukan hanya sekedar menolak makanan hewani saja, tetapi juga bentuk pemulihan kendali atas tubuhnya yang selama ini diatur, didikte dan dimiliki oleh laki-laki. Tubuhnya menjadi ruang perlawanan baginya.
Tubuh, dalam perspektif feminisme eksistensialis, bukanlah sesuatu yang bersifat netral. Tubuh merupakan medan sosial-politik, tempat di mana kuasa beroperasi. Dalam hal ini, pemulihan subjektivitas atas tubuh merupakan langkah awal untuk menuju kebebasan.
Cinta: Dimensi Emosional dari Kesalingan dan Pengakuan
Sejatinya, tubuh tidak bisa terpisahkan dari cinta. Cinta bisa menjadi alat dominasi jika tidak berlandaskan sikap kesalingan. Hal yang demikian inilah yang ditentang oleh Simone. Dalam pandangannya, cinta yang sejati adalah cinta yang saling mengakui, bukan saling membelenggu.
Jika Simone berbicara tentang pembebasan dari luar, maka Jalaluddin Rumi membawa kita ke pembebasan batin yang lebih mendalam. Dalam sufisme, cinta bukan hanya sebatas afeksi personal saja, tetapi sebuah jalan pembersihan ego.
Maka, di sinilah Rumi berbicara dengan epistemologi yang berbeda, namun tetap sejalan dengan tujuan Simone, objektivikasi. Baginya, cinta merupakan jalan spiritual. Cinta merupakan penyatuan dua jiwa yang saling melihat dan saling menjadi. Rumi menulis di dalam Mathnawi, “Di dalam aku, hanya ada kamu”. Ungkapan ini merupakan suatu bentuk cinta yang tidak menuntut, tidak mengobjektifikasi, tetapi menyatu tanpa menghapus yang dicintai.
Bagi Rumi, dalam cinta sejati, tidak ada penguasaan, juga tidak ada penaklukan. Cinta merupakan sebuah pengakuan atas keberadaan subjek lain sebagai cermin dari diri sendiri. Inilah cinta yang memanusiakan, yang meruntuhkan ego, tetapi tidak menghapus identitas.
Mari kita bandingkan dengan pandangan Simone tentang cinta yang bebas. Simone menolak cinta yang menjadikan perempuan menjadi pasif dan terserap dalam kehidupan laki-laki. Bagi Simone, cinta hanya sah jika kedua belah pihak berdiri sebagai subjek utuh yang saling mengakui.
Dari kedua tokoh ini, kita dapat melihat bahwa antara feminisme eksistensialis dan spiritualitas cinta ala sufi bisa saling menyapa. Simone mengangkat perempuan dari keterasingan sosial, sementara Rumi mengajak jiwa untuk menyatu dalam cinta yang menyadarkan. Keduanya sejatinya menolak cinta sebagai dominasi, melainkan merayakannya sebagai sebuah kesalingan.
Kebebasan: Dimensi Spiritual dari Keberanian untuk “Menjadi”
Simone memandang kebebasan sebagai inti dari eksistensi manusia. Perempuan akan menjadi subjek ketika ia menyadari bahwa eksistensinya tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, menjadi manusia adalah keberanian untuk merumuskan diri—bukan semata menerima label dan norma dari yang lain. Kebebasan sejatinya merupakan keberanian untuk “menjadi”.
Sementara itu, al-Hallaj adalah seorang sufi yang dihukum mati karena ucapannya “Ana al-Haqq” (Akulah Kebenaran). Al-Hallaj justru menempuh kebebasan melalui jalan spiritual. Ia berani menanggalkan ego, membebaskan dirinya dari citra dunia, dan kemudian menyatu dengan Tuhan. Kebebasan yang sejati bagi al-Hallaj adalah ketika tidak ada lagi pemisah antara “aku” dan “Kau”.
Simone mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang merdeka, sementara al-Hallaj mengajarkan kita untuk melebur dalam kehadiran Ilahi dengan cinta. Simone menekankan subjektivitas sebagai tanggung jawab sosial, sementara Al-Hallaj menekankan subjektivitas sebagai jalan spiritual.
Meski demikian, pada dasarnya keduanya sepakat bahwa manusia tidak boleh menjadi objek, baik oleh sistem, kekuasaan, maupun ego yang menindas.
Jembatan antara Modernitas, Spiritualitas, dan Gender
Tatkala feminisme eksistensialis bertemu dengan mistisisme cinta, maka kita dapat belajar bahwa perjuangan perempuan tidak hanya tentang struktur sosial saja, tetapi juga struktur batin. Pembebasan tubuh membutuhkan cinta, dan cinta yang sejati hanya lahir dari pengakuan atas kebebasan subjek yang lain.
Tulisan ini bukan hanya sekedar kolase pemikiran antara Barat dan Timur saja, tetapi menjadi sebuah jembatan—bahwa antara spiritualitas Islam dan feminisme modern bisa saling menyapa dan menguatkan. Tubuh bukan hanya arena dominasi, tapi juga wahana kesadaran.
Cinta bukan hanya sekedar perasaan saja, tetapi bentuk tertinggi dari pengakuan atas subjektivitas. Kebebasan juga bukan sekedar hak sosial saja, tetapi juga pencarian ruhani untuk menjadi manusia yang seutuhnya.
Simone, Rumi, dan al-Hallaj faktanya tidak akan pernah bisa duduk semeja dalam realitas sejarah. Tetapi, pemikiran mereka dapat duduk semeja dalam batin kita yang resah, yang senantiasa merindukan kebebasan, dan yang ingin mencintai tanpa mengobjektifikasi.
Pada akhirnya, menjadi subjek bukan hanya sebuah proyek intelektual saja, tetapi juga laku spiritual. Di dalam ruang kemanusiaan itulah, kita bisa belajar bahwa ungkapan “kau adalah aku” bukan hanya sekedar ungkapan cinta, tetapi juga pengakuan, bahwa setiap jiwa berhak menjadi dirinya sendiri. []