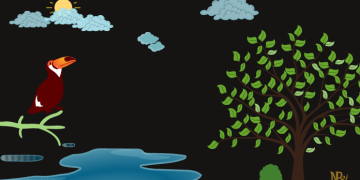Mubadalah.id – Indonesia tidak hanya terkenal sebagai negara maritim karena luas wilayah laut dan banyaknya pulau yang dimiliki. Produksi bahan pangan dalam kuantitas besar dan banyaknya areal pertanian menjadikan Indonesia mendapat julukan pula sebagai negara agraris. Meski demikian, kita tidak boleh jumawa, lantaran jumlah lahan kritis di negara ini cukup besar.
Lahan kritis, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, pengertiannya adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang kita budidayakan atau yang tidak.
Keberadaan lahan kritis ini mengindikasikan adanya degradasi lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi lahan secara massif dan kurang tepat. Lalu pembuangan limbah yang tidak sesuai regulasi, hingga penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan.
Dampak Lahan Kritis
Dampak paling nyata dari lahan kritis adalah penurunan fungsi konservasi dan kapasitas produksi, yang secara langsung maupun tidak langsung, akan berefek negatif terhadap kehidupan ekonomi warga di sekitarnya. Tidak hanya itu, lahan terdegradasi bisa menjadi pemicu terjadinya bencana, mulai dari kekeringan, banjir, tanah longsor, sampai kebakaran ketika lahan tersebut berisi semak belukar kering yang rentan jika tersulut api.
Di akhir tahun 2018, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan kritis tercatat sejumlah 14,01 juta hektar. Sebelumnya di tahun 2014 seluas 27,2 juta hektar dan pada tahun 2009 tercatat berada pada angka 30,1 juta hektar. Walaupun data tersebut menunjukkan adanya tren penurunan, namun angkanya masih terbilang fantastis.
Bahkan, KLHK memperkirakan upaya pemulihan 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia membutuhkan waktu hingga 60 tahun. Prediksi tersebut muncul bukan tanpa dasar. Meskipun telah mereka dukung dengan pendanaan dari APBN, APBD, dan swasta, kemampuan pemulihan lahan kritis hanya 232.250 hektare per tahun. Karena itu, membutuhkan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak, utamanya masyarakat.
Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai regulator, project leader, sekaligus penyokong utama pendanaan melalui APBN dan APBD. Perusahaan swasta bisa berkontribusi melalui support dana, salah satunya dengan program corporate social responsibility (CSR) yang kita orentasikan pada perbaikan lingkungan. Adapun masyarakat dapat mengambil peran sebagai eksekutor di lapangan.
Yang menjadi pertanyaan adalah, apa dasar akademik? Terutama dari diskursus keislaman, yang bisa kita jadikan referensi pemerintah dalam menunjuk warga sebagai “kaki dan tangan” proyek penyelamatan lahan kritis tersebut?
Kontekstualisasi Ihya-ul Mawat
Ihya-ul mawat telah menjadi salah satu bahasan penting dalam bab fiqih muamalat di berbagai literatur kitab klasik. Ihya-ul mawat, secara bahasa, berarti “menghidupkan” kembali lahan yang “mati”. Sejak lama, konsep ihya-ul mawat telah dipraktikkan dan menjadi salah satu instrumen pemulihan potensi tanah yang tidak tergarap.
Dalam hadis riwayat Sayyidah ‘Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:
من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق (رواه البخاري)
“Barang siapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, maka dialah yang paling berhak terhadap tanah tersebut.” (HR. Al-Bukhari)
Dalam kitab At-Tadzhib (hlm. 145) karya Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, kata i’mar (bentuk mashdar dari a’mara) memiliki makna yang sama dengan ihya. Yakni mengambil manfaat, maslahat, dari tanah tersebut, baik dengan menanaminya maupun membangun tempat di atasnya (istishlahuha bi az-zar’i aw al-bina-i).
Ini menunjukkan, ihya-ul mawat bisa kita wujudkan dengan salah satu dari dua cara. Pertama, penggarapan dan konservasi atas lahan yang tidak terawat, terbengkalai, atau bahkan rusak. Baik dari segi unsur fisik, kimia, dan biologinya. Metode pertama ini berorientasi pada aspek produksi pangan dan penyuburan tanah.
Kedua, pembangunan gedung atau sarana yang mempunyai nilai ekonomis. Baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun komersial, seperti pertokoan, penginapan, restoran, dan fasilitas pendukung perputaran roda ekonomi. Metode yang kedua berkenaan dengan penggiatan simpul-simpul perniagaan dan transaksi sejenisnya.
Dalam literatur fiqih klasik, ihya-ul mawat memang melekat dengan tanah yang tak berpemilik. Bahkan, salah satu syarat dari lahan yang “dihidupkan” adalah berstatus bebas dan tidak terikat dengan kepemilikan seorang muslim (an takuwna al-ardhu hurrotan, lam yajri ‘alayha milkun li muslim). Namun, konsep tersebut tidak kemudian dianggap sebagai ketentuan yang bersifat final dan tidak boleh kita utak-atik.
Dalam konteks penyelamatan lahan kritis, terutama yang menjadi milik pemerintah atau negara, konsep ihya-ul mawat dapat kita perkaya dengan menggunakan akad muamalah lainnya. Seperti muzara’ah, musaaqah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah bertindak selaku pemilik lahan kritis, sementara rakyat menjadi penggarap. Dengan cara ini, lahan kritis bisa kita kurangi, lapangan kerja dapat kita perluas. []