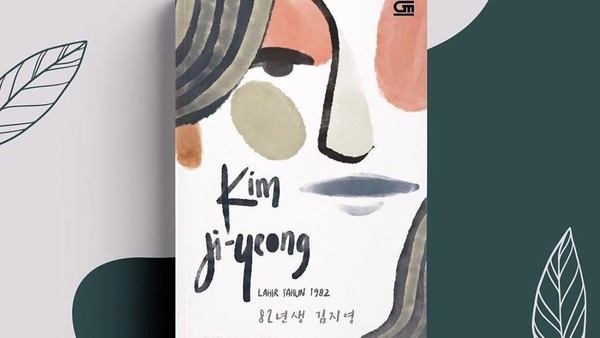Saya meyakini bahwa dalam setiap ketidakadilan pada perempuan, akan selalu ada perempuan yang berani angkat suara–meskipun sangat sedikit. Dalam sejarah bangsa kita, ada begitu banyak contoh perempuan-perempuan pemberani, perempuan-perempuan pendobrak tradisi buruk, perempuan-perempuan cerdas dan peka terhadap ketidakadilan pada kaum perempuan itu sendiri.
Di Jepara, ada Kartini yang berhasil meninggikan derajat kaum perempuan, buah pikirannya dijadikan acuan bagi bangsa ini. Di Minang, ada Rohana Koedoes yang berhasil menyuarakan pendidikan untuk prempuan hingga mendirikan perkumpulan Kerajinan Amai Setia (KAS) di Koto Gadang dan Rohana School.
Sedangkan di Bukittinggi, ada Rasuna Said yang berhasil mendirikan PERMI dan memfokuskan diri pada pendidikan di pelosok-pelosok. Di Sunda, ada Dewi Sartika yang tidak menyukai tradisi dan menyatakan bahwa perempuan tidak boleh bersekolah, hingga akhirnya ia juga mendirikan sebuah sekolah yang bernama Sakola Istri.
Ada begitu banyak contoh tentang perempuan-perempuan berani yang tidak membiarkan dirinya terpojok seperti yang diinginkan orang, adat dan tradisi yang dianut. Jika itu memang buruk, mereka tidak akan segan-segan untuk melawannya.
Dalam fiksi, hal itu juga terjadi. Selalu ada perempuan-perempuan pemberani yang menyuarakan suara-suara perempuan yang tidak berani bersuara. Seperti novel The Pearl That Broke its’ Shell karya Nadia Hashimi, perempuan pemberani itu ditemukan dalam sosok Khala Shaima, Bibi si tokoh utama, Rahima.
Beliaulah yang selalu menggugat anggapan-anggapan buruk orang yang menyatakan bahwa perempuan tidak berhak mendapat pendidikan. Ia selalu mengusahakan semua keponakannya itu untuk bersekolah. Dalam Perempuan di Titik Nol karya Nawal el-Saadawi, sosok Firdaus menjelma menjadi perempuan yang tidak takut dihukum mati. Ketidakadilan yang telah dialaminya membuatnya tidak takut pada apapun.
Novel Kim Ji Yeong juga menunjukkan hal yang sama. Novel ini terkenal karena filmnya yang lebih dulu di-release berhasil merebut hati penonton. Sesaat kemudian lahirlah novelnya. Novel ini sangat sarat akan ketidakadilan. Kim Ji Yeong diceritakan sebagai seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga yang mengharapkan anak laki-laki, Kim Ji Yeong adalah seorang perempuan yang ketika ia mendapat pelecehan dari laki-laki, maka yang disalahkan adalah dirinya.
Kim Ji Yeong adalah seorang mahasiswi yang tidak pernah direkomendasikan dosen untuk magang di perusahaan besar, Kim Ji Yeong adalah karyawan yang tidak pernah dapat promosi meskipun kerjanya baik, Kim Ji Yeong adalah perempuan yang melepaskan semua mimpinya demi mengasuh anak. Dalam arti bahwa ia hidup dalam dunia patriarki yang sangat kental.
Saya tak ingin membahas kehidupan Kim Ji Yeong karena apa yang terjadi pada Kim Ji Yeong adalah apa yang terjadi di sekitar kita, Kim Ji Yeong itu sangat dekat dengan kita. Kim Ji Yeong adalah nenek kita, ibu kita, bibi kita, saudara perempuan kita bahkan kita sendiri.
Kim Ji Yeong adalah perempuan yang memilih diam ketika melihat dan merasakan ketidakadilan itu. Tapi yang menarik dari novel ini adalah bahwa ada sosok-sosok perempuan yang memilih bersuara atas ketidakadilan yang dialami oleh perempuan-perempuan di dalamnya.
Pertama, ibu Kim Ji Yeong, Oh Mi Sok. Meskipun ibu Kim Ji Yeong juga berada dalam sistem patriarki, namun ia sanggup menyuarakan pendapatnya (meskipun cuma kepada suaminya). Oh Mi Sok adalah perempuan yang juga melakukan usaha supaya anaknya bisa sekolah. Oh Mi Sok adalah perempuan yang memberikan ide-ide supaya kehidupan ekonomi keluarganya membaik terus menerus. Tapi setelah usahanya itu, suaminya malah mengklaim bahwa itu semua karena dirinya.
“Aku yang mengusulkan kita membuka restoran bubur. Aku juga yang membeli apartemen ini. Selama ini anak-anak yang mengurus diri mereka sendiri. Hidupmu memang sukses, tetapi bukan atas usahamu sendiri, jadi bersikaplah yang baik padaku dan anak-anak. Kau bau minuman keras. Sebaiknya kau tidur di ruang tamu hari ini.”
“Tentu saja! Tentu saja! Setengahnya berkat dirimu! Kau memiliki rasa hormatku, Nyonya Oh Mi- Sook!”
“Setengah? Bukankah seharusnya 70:30? Aku 70, kau 30.”
Ini mungkin terlihat seperti contoh yang sangat sepele, suara seorang perempuan dalam rumah tangga. Tapi bukankah banyak perempuan yang diam saja ketika perannya diabaikan bahkan ketika sudah mengalami kekerasan sekalipun. Oh Mi Sok memilih bersuara.
Kedua, teman sekolah Kim Ji Yeong yang bernama Yuna. Saat ia di SMP, ada sebuah program makan siang bersama di aula sekolah. Anak-anak harus menghabiskan makanan dalam waktu yang sudah ditentukan. Anak laki-laki mendapat giliran makan dengan nomor urut pertama kali sementara perempuan akan makan jika laki-laki telah selesai makan tanpa ada tambahan waktu.
Jika mereka makan dengan lambat, para guru akan menyuruh mereka menelan makanan dengan cepat sehingga para perempuan harus memakan makanan dengan menjejalkan minuman ke tenggorokan seperti minum obat. Suatu kali, ada seorang guru yang memukul-mukulkan tongkat ke atas piring para perempuan yang makan dengan lambat hingga nasi dan potongan ikan beterbangan ke wajah mereka. Banyak diantara mereka yang menangis sambil mengunyah-ngunyah makanan. Selesai makan, mereka berkumpul di belakang sekolah. Yu-na langsung bilang;
“Ini tidak adil. Rasanya tidak adil apabila kita harus makan sesuai nomor yang sama setiap kalinya. Aku akan meminta nomornya disusun ulang.”
Di tengah budaya diamnya perempuan, bahkan untuk bertanya di dalam kelas saja, masih banyak yang enggan. Yu-na malah ingin mengubah peraturan sekolah. Kim Ji Yeong tidak yakin bahwa Yu-na akan melakukannya. Tapi pada saat rapat kelas diadakan, Yuna benar-benar mengacungkan tangan. Ia benar-benar menyampaikan apa yang ia inginkan. Saat itu, semua ruangan menjadi tegang, Kim Ji Yeong merasa gugup. Tapi semenjak itu, aturan urut makan itu benar-benar diubah secara berkala.
Ketiga, teman Kim Ji Yeong yang tidak ia sebutkan namanya. Ia dicegat di gerbang karena memakai sepatu olahraga. Ia langsung protes kenapa hanya anak laki-laki yang diperbolehkan pakai kaos dan sepatu olahraga. Gurunya menjawab karena anak laki-laki selalu bergerak. Ia benar-benar marah dengan jawaban guru itu.
“Anda pikir anak-anak perempuan tidak suka bergerak? Harus mengenakan rok, stoking, dan sepatu biasa membuat kami merasa tidak nyaman untuk bergerak. Ketika duduk di bangku SD, aku juga suka melompat ke sana kemari, berkeliaran ke sana kemari, dan bermain lompat tali setiap jam istirahat.”
Jawaban itu membuatnya dihukum berjalan sambil berjongkok mengelilingi lapangan. Gurunya menyuruh ia berjongkok sambil memegangi pinggiran roknya agar celana dalamnya tidak kelihatan, tapi yang dilakukannya malah sebaliknya. Karena tidak nyaman, akhirnya guru pengawas menyuruhnya berhenti. Saat itu, temannya bertanya kepadanya kenapa ia tidak memegangi pinggiran roknya. Ia menjawab,
“Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pakaian seperti ini sangat tidak nyaman.”
Sejak aksi protes itu, guru-guru tidak mempersoalkan lagi soal anak-anak perempuan yang memakai kaus lengan pendek ataupun sepatu olahraga.
Keempat, Kang Hye Soo. Setelah Kim Ji Yeong berhenti dari pekerjaannya, ada kejadian di kantornya. Seorang petugas keamanan memasang kamera tersembunyi di toilet wanita. Ia memasang foto-foto karyawan wanita yang diambilnya di situs-situs khusus dewasa.
Saat salah seorang karyawan mengetahuinya, mereka tidak mau melaporkan hal itu pada polisi karena takut. Hanya Kang Hye So lah yang berani melaporkannya pada polisi meskipun atasannya tidak suka karena akan merusak nama baik perusahaannya, tapi Kang Hye So tidak gentar. Ia tetap melaporkan hal itu pada polisi dan polisi akhirnya menyelidiki kasusnya.
Di setiap zaman, di setiap tekanan dan ketidakadilan yang diterima perempuan, harus ada perempuan yang bersuara. Para lelaki tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan perempuan kalau bukan perempuan yang bersuara.
Laki-laki tidak akan tahu bahwa perempuan butuh ruangan menyusui di ruang publik kalau tidak ada perempuan yang bersuara, laki-laki tidak akan tahu betapa tidak nyamannya ruangan kecil yang disebut mushalla untuk perempuan itu kalau perempuan tidak bersuara. Laki-laki tidak akan tahu betapa perempuan butuh didengarkan pengalamannya ketika mendapatkan pelecehan kalau perempuan itu tidak bersuara.
Entah itu akan mengubah keputusan atau tidak, tapi ketika perempuan bersuara, orang-orang akan mulai mempertimbangkannya. Sejarah sudah membuktikan, perempuan-perempuan dalam novel Kim Ji Yeong juga menunjukkan bahwa keputusan untuk bersuara dalam lingkup yang paling kecil sekalipun adalah keputusan yang benar. []