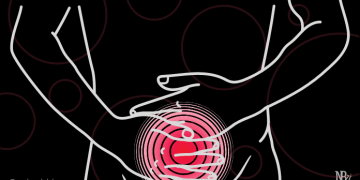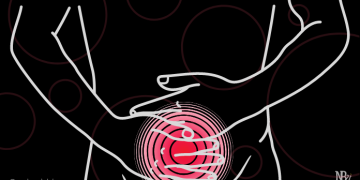“Kenapa wanita sekarang tidak bisa? Sedangkan dulu nenek kita atau buyut kita bisa?” pertanyaan itu meluncur dari seorang laki-laki yang menanggapi pernyataan pemilik akun twitter Meutia Faradilla yang menilai bahwa beban pengasuhan yang berat di pundak ibu menyebabkan kebanyakan dari mereka kepayahan, terlebih ketika perempuan tersebut memiliki banyak anak.
Mubadalah.id – Keresahan Meutia tadi tentu terasa oleh mayoritas kebanyakan perempuan. Sayangnya, kebanyakan perempuan merasa malu dan terbebani ketika harus berbagi apa yang ia rasakan ketika pengalaman fisik perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan hingga menopause. Dan, ketika itu tabu untuk kita bicarakan, akhirnya kesehatan perempuan sendiri lah yang kita pertaruhkan.
Tak pelak, sampai sekarang isu kesehatan perempuan kerap tidak kita prioritaskan oleh pemangku kebijakan, selain karena sebagian besar pengambil keputusan adalah kelompok laki-laki. Selain itu penyebabnya adalah minimnya perbincangan pengalaman perempuan di ruang publik yang membuat tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengalaman fisik perempuan amatlah rendah.
Menstruasi yang Dibicarakan Sembunyi-sembunyi
Salah satu pengalaman fisik perempuan yang kita bicarakan adalah menstruasi. Dalam banyak budaya, perempuan yang mengalami menstruasi kita anggap tidak suci, kemudian perlu kita kucilkan. Efek jangka panjangnya kemudian mengakibatkan banyak perempuan memilih diam saja ketika mengalami haid. Ia merasa malu dan takut terpinggirkan karena hal tersebut.
Kini, dengan konteks era modern seperti sekarang, ketika taka da lagi ancaman untuk ‘dibuang ke hutan’, dan sarana kesehatan jauh lebih baik, perempuan harusnya tidak malu lagi membagikan pengalaman haid yang dialami.
Terlebih berbagi tentang pengalaman menstruasi bisa membantu orang lain di sekitarnya menjadi lebih sadar dan harapannya lebih empatik. Apalagi pengalaman menstruasi tiap perempuan sangatlah berbeda. Sehingga, ketika kesakitan saat menstruasi itu tidak dibicarakan, akhirnya orang awam, bahkan sesama perempuan sendiri bisa menghakimi perempuan lain hanya karena ia sehat-sehat saja ketika mengalami haid.
Ketidaktahuan sesama perempuan mengenai kompleksitas isu ini kian terbuka ketika muncul diskusi mengenai penjualan pembalut reject atau pembalut tak layak jual dari pabrik. Banyak dari mereka mempertanyakan mengapa masih ada perempuan yang membeli pembalut dengan kondisi tidak layak seperti itu.
Jawabannya sederhana: masih banyak perempuan yang tidak memiliki pendapatan cukup untuk membeli pembalut layak.
Lalu, apakah mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka? Bisa jadi mereka sadar, bisa juga tidak. Karena sekali lagi, mereka tidak ada pilihan.
Menunggu Peran Pemerintah
Kondisi ini tentu seharusnya bukan lagi memerlukan solusi tingkat individu, tapi seharusnya sudah berada di wewenang pemerintah, untuk minimal memberikan insentif kepada perusahaan agar dapat menekan harga pembalut agar lebih terjangkau.
Terwujudnya kondisi ideal ini lah memang yang kita harapkan. Namun, sebelum itu dapat kita implementasikan oleh pengambil kebijakan. Sehingga dari kita sesama perempuan sendiri juga harus mengambil inisiatif untuk tidak menganggap bahwa menstruasi itu tabu.
Jangan lagi gunakan istilah-istilah aneh untuk menyebut pembalut. Yakinkan diri bahwa membagi pengalaman menstruasi adalah upaya edukasi skala paling kecil yang bisa kita lakukan.
Sebab tak kita pungkiri bahwa masih banyak individu yang tidak memahami menstruasi itu bagaimana, dan bagaimana payahnya tubuh perempuan ketika haid. Tetangga saya bahkan pernah membawa anak perempuannya ke dokter ketika melihat ia bersimbah darah. Waktu itu ibu sang anak sedang keluar, sehingga si bapak yang panik, tanpa babibu ia mengira anaknya terluka. Padahal, ia mengalami menstruasi.
Pengalaman Fisik Perempuan dan Stigma Sosial
Komentar awam tentang keresahan Meutia di awal artikel ini juga membawa saya berefleksi mengenai pengalaman fisik perempuan lain yang kerap kita abaikan, yakni kehamilan dan melahirkan.
Dalam sejumlah kasus, ketidakpahaman laki-laki terkait kondisi tubuh perempuan sering berujung terjadinya pemerkosaan dalam pernikahan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Hal ini dibuktikan bahwa beberapa kasus perempuan meninggal usai melakukan hubungan badan saat perempuan masih nifas (BBC, 1998).
Selain pemahaman minim mengenai kondisi tubuh perempuan. Sejumlah stigma sosial juga melekat pada perempuan ketika ia berusaha membagikan pengalamannya: dibandingkan dengan generasi dulu, hingga dianggap tidak salehah. Stigma ini bukan hanya kian menegasikan isu kesehatan perempuan, tapi juga kian memperlebar gender gap yang membuat perempuan terus terpojok.
Hal tersebut tergambar jelas ketika berbicara mengenai angka kematian ibu di Indonesia yang masih tinggi. Menurut Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu di tahun 2022 mencapai 183 per 100.000 kelahiran. Di tingkat Asia, kita hanya lebih baik dibandingkan Laos dan Myanmar.
Secara statistik, datanya terus menurun. Namun, tidakkah kita bisa bayangkan bagaimana kondisi zaman dulu? Bisa kita pastikan generasi sebelumnya mengalami hal yang jauh mengerikan, mereka tidak mampu bersuara karena (lagi-lagi) harus terbungkam oleh stigma sosial budaya. Lantas, masihkah kita memilih untuk berdiam saja? []