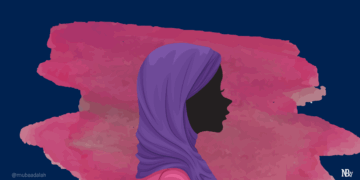Mubadalah.id – Berkenalan dengan sastra pesantren sebenarnya tidak jauh beda dengan berkenalan pada sastra umumnya. Namun semenjak “kelahirannya”, mencari maknanya seperti orang yang menggapai-gapai angin. Gerakan dan karyanya yang banyak—seperti angin, akan tetapi sepertinya untuk mencari definisi yang tepat saja sangat sulit.
Sastrawan pesantren sering kali membawa definisinya masing-masing dengan batasan yang juga beragam. Ada sastrawan pesantren yang menolak batasan dan kriteria, ada juga yang ngotot untuk memiliki batasan demi kemaslahatan sastra pesantren itu sendiri. Maka ketika berkenalan dengan definisi, agaknya tersodor di hadapan kita banyak tangan yang mengaku sastra pesantren.
Badrus Sholeh sendiri mendeklarasikan pada mimbarnya “Sastra Pesantren, Semua Suara Berharga”. Menurutnya, perdebatan antara batas untuk menentukan definisinya sebenarnya hanyalah bentuk dari dialektika yang akan membawa pada sebuah jawaban atas kegelisahan-kegelisahan para pemikir sastra.
Badrus Sholeh ingin semuanya terus mendengarkan perdebatan-perdebatan seperti: Apa beda sastra pesantren dengan sastra islam, sastra qurani, dan sastra profetik? Apakah karya seorang yang bukan santri layak kita sebut sastra pesantren?
Peristiwa semacam ini cenderung memaksa bahwa semua karya sastra yang bertemakan pesantren termasuk dalam kesusatraan pesantren. Pembatasan yang tidak jelas itu sepertinya akan semakin saling terbentur dengan aliran sastra yang bertemakan islam secara garis besar.
Dengan demikian, menjadi beralasan jika Binhad Nurrahmat melayangkan sebuah autokritik terhadap genre sastra ini. Dalam “Gincu Merah Sastra Pesantren”, Binhad menganggap bahwa sastra pesantren hanyalah “gincu” (baca: pelabelan) yang secara serampangan. Pelabelan ini disandangkan kepada karya-karya sastra yang seakan-akan akan membuat sebuah karya menjadi cantik dan memikat. Selebihnya tak mempertimbangkan dari segi estetikanya.
Binhad juga menilai bahwa sastra pesantren hanyalah sebuah sumur yang airnya sering penulis pakai sebagai bahan utama penciptaan karya. Kekayaan tradisi dalam pesantren sering terpakai tanpa melalui proses kesusastraan. Maka bukanlah beda jika sastrawan pesantren yang mengenalkan khasanah tradisi pesantren tanpa menggunakan bahasa sastrawi.
Mencari Sejarah Sastra Pesantren
Tidak ada yang tahu pasti kapan sastra pesantren bermula. Banyak sekali sumber yang menyatakan bahwa hulunya hingga zaman walisongo.
Hal ini menunjukkan bila sastra pesantren yang sering menjadi perbincangan hari ini lebih sering membahas sejarah zaman walisongo daripada merumuskan definisi dan batasan atau posisinya. Dengan demikian, deklarasi-deklarasi seperti sastra profetik dan sastra Islami juga sering dianggap termasuk ke dalamnya.
Jika merujuk pada Prosiding Muktamar Pemikiran Santri Nusantara berjudul “Sastra pesantren di Arena Sastra Indonesia” oleh Rina Zuliana dan M. Mujibuddin SM. Mereka menjelaskan bahwa corak kesusastraan pesantren dalam sejarah mulai berubah pada tahun 2000-an.
Hal ini terlihat dari munculnya karya-karya seperti Perempuan Berkalung Surban dan Mairil. Pada tahun-tahun inilah karya-karya sastra zaman ini lebih tampil sebagai sebuah karya yang membahas sosial budaya kepesantrenan maupun autokritik terhadap budaya buruk pesantren itu sendiri.
Berbeda dengan periode sebelumnya tahun 70-an dengan karya-karya sufistik dari Sutardji Calzoum Bachri, Danarto, bahkan Kuntowijoyo yang beliau sendiri memproklamirkan sastra profetik. Memang pada periode itu sastrawan-sastrawan tidak ramai memperbincangkan tentang kesusastaan pesantren dan justru karya mereka sendirilah yang menjadi wajah dari sastra islam di Indonesia.
Karena historis genre sastra ini sendiri yang tidak jelas sedari kapan adanya, sehingga Rina dan Mujibuddin ini memasukkan sastra islam periode 70-an ini sebagai embrio dari lahirnya sastra-sastra kepesantrenan yang sering diperbincangkan di berbagai diskusi dan simposium akhir-akhir ini.
Hal itulah yang membuat mereka mengklasifikasikan kesusastraan pesantren menjadi dua periode; yaitu klasik dan modern. Klasik di tahun 70-an yang berkutat di ranah-ranah sufistik dan modern di tahun 2000-an yang membahas tentang sosial budaya pesantren.
Sastra Serius vs Sastra Populer
Sepertinya bukan terlalu baru pergulatan diskusi perihal “apakah ini sastra?” di lingkungan kesusastraan. Pun apa yang terjadi dengan polemik terminologis kesusastraan pesantren.
Terlebih dahulu, Rina dan Mujibuddin menemukan bahwa sastra pesantren—seperti arena sastra umumnya—memiliki sub-arena yang saling beroposisi dengan menggunakan teori Strukturalisme Genetik milik Pierre Bourdieu. Gampangnya, dua sub-arena ini adalah satu; sastra serius yang ‘sangat nyastra’ dan dua; kubu sebelah, yaitu sastra populer yang berkarya berdasarkan pasar sastra dan produksi massal.
Jika berdasar pada polarisasi sastra serius dan sastra populer, tempo hari ini pun genre sastra ini lebih menggunakan pijakan sastra ‘sinematik’ dan sastra populer sebagai lahan tumbuh kembangnya.
Tak dapat dipungkiri jika karya-karya seperti Hati Suhita, Perempuan Berkalung Surban, dan Negeri 5 Menara berhasil mencapai legitimasi pasar sastra tahun belakangan. Rini dan Mujibuddin juga menilai perlunya perbaikan dalam literer, estetika, dan stilistika di dalamnya.
Budaya untuk melanjutkan hasil karyanya sebagai suatu komoditas sastra yang memikat dan bergengsi untuk menjadi bahan jual beli bukanlah suatu hal yang baik.
Produk-produknya juga perlu berimbang dengan karya sastra yang berkontestasi secara simbolis, prestise, dan selebrasi artistik non-komersialis. Sehingga sastra pesantren dapat kembali ke zaman Ahmad Tohari, Musthofa Bisri, Acep Zamzam Noor, Danarto, Kuntowijoyo, D. Zawawi Imron atau Sutardji Calzoum Bachri itu. []