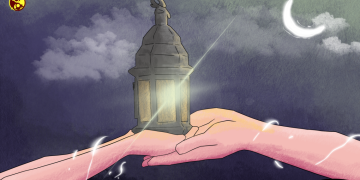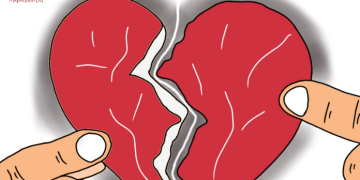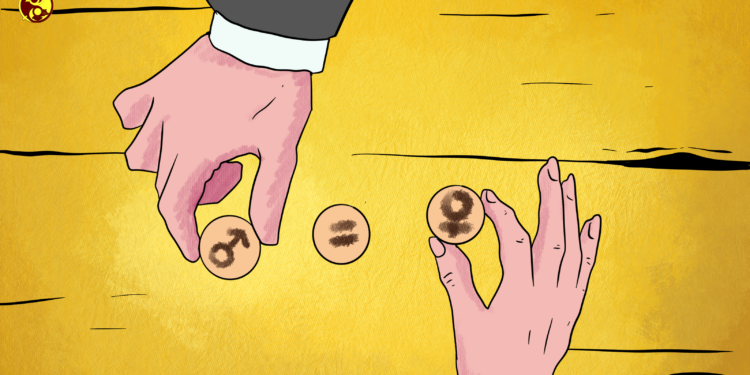Mubadalah.id – Akhir-akhir ini, publik geger dengan beredarnya berita tentang seorang guru besar (profesor) ternama dari kampus terkemuka di Yogyakarta. Dia menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswinya, publik bukan hanya marah—tetapi juga hancur secara moral.
Bagaimana mungkin seseorang yang memegang gelar ‘profesor,’ yang seharusnya menjadi simbol ilmu dan kebijaksanaan, ternyata menjadi predator?
Fenomena kekerasan seksual di dunia akademik ini memperlihatkan kepada kita bahwa kesalehan, jika hanya menjadi kosmetik sosial dan bukan pancaran dari dalam jiwa, akan kehilangan fungsinya sebagai penuntun hidup. Di sinilah kita perlu menggali ulang makna kesalehan. Bukan hanya dalam tataran teoretis, tetapi juga dalam tataran praksis.
Dalam banyak narasi keagamaan dan filsafat, kesalehan kerap kali kita maknai sebagai manifestasi hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Namun, dalam kenyataan sosial, spiritualitas tidak boleh berhenti hanya pada ekspresi simbolik atau ritus ibadah saja. Tetapi harus menjadi kekuatan moral yang menuntun perilaku seseorang dalam menjalankan relasi sosial. Terlebih dalam konteks kuasa seperti relasi antara dosen dan mahasiswa.
Spiritualitas-Bukan Sekadar Teori
Kesalehan yang hanya berwujud simbolik tanpa kita barengi dengan etika perilaku disebut sebagai kesalehan kosong. Di mana seseorang terlihat suci, namun tak mampu membendung hawa nafsu, tak peduli pada penderitaan orang lain, dan sering menjadi alat legitimasi kuasa. Dalam istilah Sufistik, ini adalah bentuk dari riya’, kesalehan palsu yang hanya ingin dipandang, bukan untuk menuntun hidup.
Spiritualitas yang sejati adalah yang transformatif. Yakni yang dapat membentuk karakter, mengontrol nafsu, dan melahirkan kasih. Dalam konteks kekerasan seksual, kita melihat kegagalan spiritualitas seseorang yang seharusnya dapat menjinakkan kekuasaan dan menekan dorongan seksual, tetapi justru terbiarkan liar di bawah legitimasi posisi intelektual.
Sebagaimana dalam Q.S. Al-Ma’un, orang yang mendustakan agama bukan hanya mereka yang tidak salat. Tetapi juga yang menghardik anak yatim dan tidak memiliki kepedulian terhadap orang miskin. Dalam konteks ini, seorang profesor yang intelek dan religius namun melecehkan mahasiswinya telah mendustakan agama, karena ia gagal menjiwai nilai-nilai keadilan dan kasih sayang.
Filsafat memberikan kita alat untuk memahami secara lebih mendalam tentang relasi antara pengetahuan dan kuasa. Michel Foucault, filsuf Prancis, menjelaskan bahwa pengetahuan tidak netral, melainkan selalu terkait dengan kekuasaan (power/knowledge) (Kebung, 2018) (Hidayah et al., 2023).
Jika kita tinjau dengan pemikiran Foucault tersebut, maka dalam dunia akademik, gelar profesor atau guru besar sejatinya bukan hanya sekedar pencapaian intelektual. Tapi juga simbol otoritas yang bisa mengendalikan tubuh, ruang, dan narasi.
Tubuh, Kuasa, dan Moralitas: Sebuah Tinjauan Filosofis
Foucault menyebut bahwa tubuh adalah lokasi di mana kekuasaan bekerja secara halus namun intensif (Mudhoffir & Mudhoffir, 2013). Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh profesor pada perguruan tinggi ternama tersebut, tubuh mahasiswi menjadi objek kekuasaan yang ia paksakan lewat tekanan simbolik. Seperti: nilai, rekomendasi, akses penelitian, dan bahkan ketergantungan akademik. Inilah yang kita sebut “disciplinary power” yang bekerja melalui institusi.
Dalam filsafat Islam, terutama dalam pemikiran etika Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa adab adalah racun (Gunawan et al., 2020). Adab bukan hanya tentang tata krama, tetapi juga tentang kesadaran spiritual dan etika dalam menggunakan ilmu. Seseorang bisa menguasai ilmu farmasi, menjadi pakar kanker, namun jika tidak memiliki adab, maka ia bisa berpotensi menjadi penyakit sosial itu sendiri bagi masyarakat.
Moralitas dalam filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi keberanian untuk melakukan yang baik bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Hal inilah yang hilang dalam kesalehan palsu para pelaku kekerasan seksual, di mana sebenarnya ia tahu bahwa itu salah, tapi menghalalkannya lewat dalih kekuasaan.
Pertanyaan tentang hubungan antara ‘ilm (pengetahuan) dan ‘amal (perbuatan) dalam filsafat Islam sejatinya telah lama menjadi pusat perdebatan. Para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Miskawayh menegaskan bahwa ilmu sejati adalah yang menumbuhkan akhlak, bukan sekedar mengisi kepala.
Bahkan, dalam kerangka tazkiyatun nafs, kesucian jiwa menjadi syarat bagi ilmu untuk memberikan cahaya (nur). Tanpa penyucian jiwa, ilmu bisa menjadi alat penyesatan, sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Jumu’ah ayat 5, bahwa orang yang memikul ilmu tapi tidak mengamalkannya kita ibaratkan seperti keledai yang membawa kitab-kitab.
Potret Disintegrasi Intelektual dan Moral
Fenomena guru besar yang menjadi pelaku pelecehan seksual menunjukkan kegagalan serius dalam mengarahkan epistemologi menuju etika, dan kegagalan dalam menyatukan antara “yang ada” dan “yang seharusnya” dalam eksistensi manusia.
Dengan kata lain, kasus ini menunjukkan potret disintegrasi intelektual dan moral, yakni: cerdas, tapi tidak bijak; tahu banyak, tapi tidak bertanggung jawab. Inilah mengapa integrasi ilmu, iman, dan amal tidak bisa hanya sekadar menjadi slogan di perguruan tinggi, tetapi harus kita upayakan menjadi kesadaran filosofis yang hidup dalam sistem dan individu.
Ada satu pertanyaan mengganggu yang sering kali muncul dalam kasus kekerasan seksual oleh seseorang yang tampak religius adalah, “Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat taat, berbicara tentang Tuhan, bahkan menjadi figur teladan dalam akademik, bisa melakukan tindakan sekeji itu?”. Jawabannya tentu saja tidak sederhana, tapi psikologi agama menawarkan kerangka penting untuk membongkar dinamika jiwa pelaku.
Dalam psikologi agama, kita kenal konsep disonansi kognitif, yakni ketegangan mental yang timbul ketika seseorang memiliki dua keyakinan atau nilai yang saling bertentangan. Misalnya, percaya bahwa pelecehan adalah dosa, tapi tetap melakukannya.
Untuk mengurangi ketegangan semacam ini, seseorang bisa mengembangkan justifikasi internal, seperti: “Saya melakukan ini karena dia menggoda,” atau “Ini bukan pelecehan, hanya kedekatan,” dan lain sebagainya.
Jiwa yang Terbelah: Telaah Psikologi Agama
Lebih dalam lagi, fenomena seperti ini juga bisa kita jelaskan dengan kompartementalisasi jiwa. Yakni seseorang yang memisahkan bagian kehidupan religiusnya dari bagian kehidupannya yang lain.
Sebagai contoh, seseorang di hari Jum’at bisa menjadi imam salat Jumat di masjid, tetapi kemudian bisa berubah menjadi predator di hari Senin. Jiwa yang terbelah ini memungkinkan seseorang mempertahankan citra suci sambil menutupi sisi gelapnya yang tak tersentuh oleh spiritualitas sejati.
Menurut Carl Jung, manusia memiliki bayangan (shadow) dalam jiwanya, yakni bagian gelap yang tidak kita sadari, sering tertekan, tapi tetap mencari saluran ekspresi (Carl & Jung, n.d.). Jika seseorang gagal mengenali dan mengolah bayangannya secara spiritual dan psikologis, maka bayangan itu bisa saja meledak dalam bentuk tindakan yang menyimpang. Spiritualitas yang matang seharusnya dapat membantu seseorang menghadapi dan menundukkan sisi gelap ini, bukan malah menutupinya dengan simbol religius.
Dalam konteks ini, maka kita bisa melihat bahwa pendidikan agama dan moral tidak cukup berhenti pada doktrin atau hafalan saja, tetapi harus sampai pada proses transformasi batin. Yakni mengenali dorongan terdalam, memahami godaan kekuasaan, dan membangun inner control yang kokoh.
Fenomena pelecehan seksual oleh profesor di salah satu perguruan tinggi ternama ini tidak bisa kita lihat sebagai kesalahan personal semata. Namun, hal ini terjadi dalam sebuah ekosistem yang memelihara kekuasaan tanpa akuntabilitas. Dunia akademik sering kali menempatkan profesor atau guru besar di menara gading, menjadikan mereka sosok yang tak tersentuh dan tak bisa kita kritik, apalagi oleh mahasiswa.
Budaya Akademik yang Membungkam
Dalam sistem hierarkis ini, relasi antara dosen dengan mahasiswa tidak hanya sebatas relasi pedagogis. Tapi juga relasi kuasa, di mana salah satu pihak memiliki kontrol atas masa depan akademik dan psikologis yang lain. Sementara dalam budaya yang seperti ini, korban sering kali dipaksa diam, karena takut nilainya rusak, takut terkucilkan, bahkan takut dituduh “menggoda.”
Dalam kasus ini dan beberapa kasus yang terjadi di perguruan tinggi lain, yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya adalah budaya institusional yang defensif. Di mana kampus lebih fokus menjaga nama baik daripada menyelamatkan korban. Alih-alih menindak, lembaga justru melakukan pembungkaman dengan cara-cara halus, seperti: mengaburkan fakta, menunda proses, bahkan memaksa korban berdamai.
Di sinilah perguruan tinggi perlu melakukan reformasi budaya akademik yang menekankan akuntabilitas, keberpihakan pada korban, dan integrasi etika-spiritual ke dalam sistem pendidikan tinggi. Guru besar (profesor) bukan hanya harus hebat secara intelektual, tetapi juga harus tangguh secara moral dan spiritual.
Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru besar bukan hanya sekedar krisis moral individu, tetapi menjadi cermin retak dari sistem pendidikan, spiritualitas, dan filsafat hidup yang gagal menyatu dalam laku sehari-hari. Kesalehan tidak boleh berhenti di lidah atau panggung akademik. Kesalehan harus mengalir dalam tindakan, dalam relasi kuasa. Terutama dalam cara kita memperlakukan mereka yang lemah dan rentan.
Ketika seorang yang bergelar “profesor” atau bahkan “Kyai” sekalipun yang menjadi pelaku kekerasan, maka panggilan untuk melakukan perubahan harus kita suarakan dengan lebih lantang. Nampaknya, kita butuh melakukan redefinisi radikal tentang apa itu “intelektual,” “agama,” dan “kesalehan.”
Saatnya Membumikan Kesalehan dan Menegakkan Keadilan
Seorang cendekiawan sejati bukanlah mereka yang hafal banyak teori. Tetapi mereka yang hidup dalam kesadaran etis dan keberpihakan pada kebenaran. Spiritualitas sejati bukan yang sibuk mencari surganya sendiri, tetapi mereka yang hadir dalam perjuangan melindungi tubuh-tubuh yang digerogoti ketakutan dan ketidakadilan.
Merefleksi dari kasus semacam ini yang sudah mulai marak di perguruan tinggi dan pesantren, kita juga perlu menghentikan budaya mendewakan akademisi dan agamawan. Seolah mereka suci tak tersentuh. Mereka juga manusia, yang bisa keliru dan harus bisa kita tindak.
Mengkritik bukan berarti membenci ilmu, namun sebaliknya, justru mencintainya secara utuh, karena sejatinya ilmu yang membiarkan kejahatan adalah ilmu yang kehilangan jiwanya.
Mari kita tegakkan sistem yang melindungi korban, bukan hanya reputasi. Mari kita bangun spiritualitas yang utuh, yang tidak hanya dengan berpikir secara mendalam, tetapi juga melakukan tindakan nyata, yang mengalir dari zikir ke adab, dan dari salat ke solidaritas.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ash-Shaff, ayat 2-3:
“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.”
Sudah cukup kita menjadi umat yang hanya fasih berbicara tentang moral, tanpa benar-benar membumikan moralitas itu dalam perbuatan. Sudah saatnya membangun kesalehan yang tidak hanya menggugah langit, tetapi juga menyembuhkan bumi. []