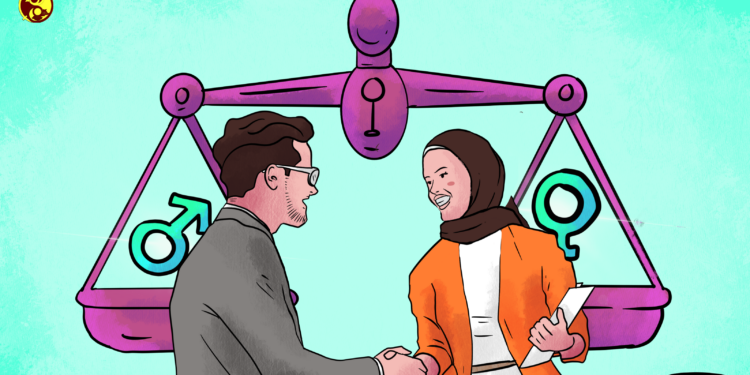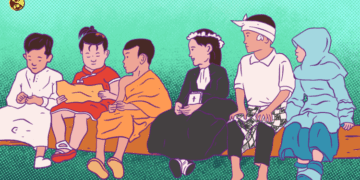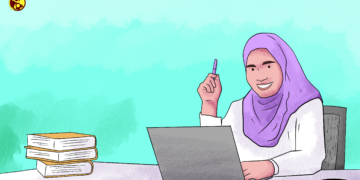Mubadalah.id – “Perempuan tidak diberi akses pendidikan. Itu sebabnya sedikit perempuan yang sekolah, sementara laki-laki banyak.” Argumen seperti itu beberapa kali saya dapati dalam diskusi-diskusi seputar gender dan feminisme. Tentu tidak ada salahnya untuk mempertanyakan, apa benar ruang pendidikan masih tertutup bagi perempuan?
Kalau menengok sejarah, maka boleh kita katakan jawabannya iya. Dalam her-story Nusantara, banyak perempuan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Rahmah El Yunusiyyah, Nyai Khoiriyyah Hasyim, dan perempuan lainnya, yang tampil memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan. Sebab, pada masa mereka, perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kala itu, seakan perempuan dilarang sekolah.
Bagaimana Hari Ini?
Namun itu konteks dahulu, puluhan tahun lalu di era Kartini, Sartika, Rahmah, dan Nyai Khoiriyyah. Lantas, bagaimana dengan konteks saat ini? Apakah perjuangan mereka yang lalu-lalu itu tidak membuahkan hasil? Apakah kondisi pendidikan bagi perempuan saat ini masih sama dengan yang dahulu?
Argumen perempuan sedikit yang sekolah, dalam konteks hari ini, itu perlu kita tinjau kembali. Betapa tidak. Berdasarkan pengalaman, ketika saya ikut diskusi kebanyakan pesertanya perempuan. Di kelas pun begitu, tak sedikit kelas yang mahasiswinya banyak. Coba ke kampus dan lihat sekitar, ada banyak perempuan. Itu artinya, hari ini, sudah banyak kok perempuan yang mendapat akses pendidikan.
Berdasarkan data “Statistik Pendidikan Tinggi tahun 2021”, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa, sepanjang tahun 2021, ada sebanyak 1.227.880 perempuan dan sebanyak 896.345 laki-laki yang masuk perguruan tinggi dalam negeri. Jadi, berdasarkan data malah perempuan yang lebih banyak mengakses pendidikan tinggi daripada laki-laki.
Kehidupan yang Makin Setara Gender
Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, argumen bahwa perempuan tidak mendapat akses pendidikan yang setara dengan laki-laki sudah menjadi agak keliru. Ini bukan berarti gerakan pendidikan bagi perempuan itu agenda mengada. Tidak. Sebab, meningkatnya angka perempuan yang bisa sekolah hari ini, tidak lepas dari gerakan para perempuan yang memperjuangkan pendidikan bagi kaumnya.
Perubahan konteks ruang dan waktu ini perlu kita pahami. Meski dalam buku-buku seputar gender dan feminisme yang kita baca mengatakan perempuan sedikit yang sekolah, perempuan tidak mendapat akses, perempuan tidak bisa bercita-cita. Itu konteks ruang dan waktu saat buku itu ditulis.
Boleh jadi realitas kehidupan sudah berkembang ke arah yang lebih baik. Semakin setara gender. Seperti hari ini di Indonesia, rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan perempuan sudah banyak yang berpendidikan, sudah mendapat banyak akses, dan sudah bisa bercita-cita.
Wacana Feminisme pun Ikut Berkembang
Dalam perkembangan kehidupan menjadi lebih setara gender, wacana feminisme pun harus ikut berkembang. Jadi, bukan berarti suatu masyarakat makin setara gender lantas gerakan feminisme tidak perlu lagi. Justru wacana feminisme harus ikut berkembang sesuai konteks ruang dan waktu.
Untuk memahami perkembangan wacana feminisme ini, misalnya kita pakai contoh ukuran pemberdayaan perempuan dari Kemenpppa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) soal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
Berdasarkan kacamata itu, kalau akses pendidikan bagi perempuan terpenuhi, bukan berarti upaya mewujudkan masyarakat adil gender selesai. Kita melangkah ke PR selanjutnya adalah soal partisipasi.
Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, narasi kesetaraan gender tidak melulu berputar pada wacana lama soal membandingkan akses pendidikan laki-laki dan perempuan. Sebab, hari ini, sudah semakin banyak perempuan yang mendapat akses pendidikan. Bahkan berdasarkan data tahun 2021 malah sudah perempuan yang lebih banyak sekolah di perguruan tinggi.
Seharusnya narasi feminisme zaman now-nya adalah, memang sih sudah banyak sarjana perempuan, namun apa itu selaras dengan kesempatan partisipasi perempuan di ruang publik? Jadi, kita menaikkan narasi wacananya ke level selanjutnya.
Contoh lain misalnya dalam hal pemerintahan. Perempuan mendapat akses kuota 30% di parlemen. Aksesnya sudah ada, maka wacana feminisnya berkembang menjadi, sudah maksimalkah partisipasi perempuan memenuhi akses 30% itu? Bagaimana kontrol perempuan dalam partisipasi kuota 30%?
Dan, apakah para perempuan di parlemen sudah benar-benar mewakili (memberi manfaat) bagi para perempuan Indonesia? Ya, jangan-jangan hanya jadi formalisasi 30% saja dari elit politik yang berkepentingan, kan?
Jadi narasi dalam wacana feminisme tidak stagnan. Itu berkembang menyesuaikan konteks capaian dalam setiap ruang dan waktu peradaban.