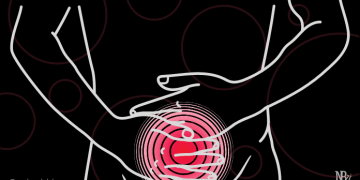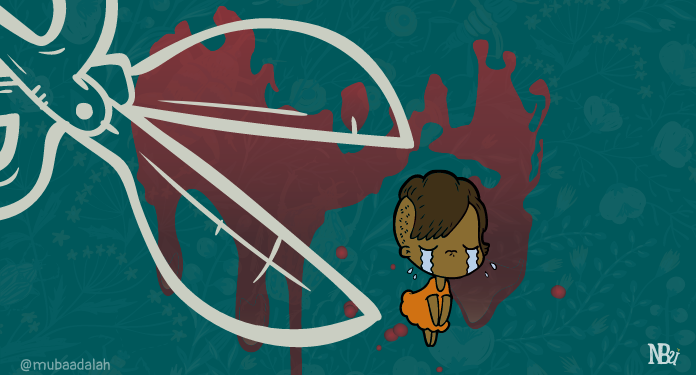Mubadalah.id – Pernah lihat remaja perempuan disunat? Atau minimal, bisa bayangin nggak, perempuan yang sudah akil-baligh, dan mungkin ada yang badannya bongsor seperti orang dewasa, itu disunat? Jujur saja, ngeri membayangkannya. Pertama, harus berani tahan malu karena area paling privat di tubuhnya harus terlihat orang lain.
Kedua, harus berani menahan sakit luar biasa, karena dilakukan saat usianya sudah remaja. Tapi rasa ngeri yang saya rasakan itu, nyatanya bukan bayangan. Karena ada sebuah flyer khitan massal perempuan, baru saja beredar beberapa hari ini. Flyer ini bersumber dari panitia pelaksana peringatan 1 Abad sebuah pesantren serta haul ke-81 sang pendirinya, di daerah Tuban, Jawa Timur.
Panitia membuka kuota 250 orang untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki jumlahnya hanya 10. Jumlah yang tidak imbang itu, semakin bikin tanda tanya. Bukankah yang disunnahkan untuk dikhitan itu laki-laki? Tapi kenapa untuk laki-laki slotnya hanya sedikit? Kenapa praktik tersebut kita lakukan secara massal? Dan, berapa rata-rata usia perempuan yang akan kita sunat?
Sebuah skripsi yang diterbitkan UIN Walisongo Semarang berjudul Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban: Kajian Living Hadis, yang Durrotun Isnaini An Nabilat tulis di tahun 2019, menjawab rasa penasaran saya kenapa flyer tersebut beradar.
An-Nabila secara gamblang mengungkapkan, bahwa tradisi di balik khitanan massal perempuan di pesantren tersebut sudah berlaku sejak puluhan tahun lalu, yakni sejak pertama kali Haul mereka gelar. Khitanan massal mereka gagas sebagai bentuk tasyakur para pihak yang ingin mengisi peringatan dengan hal-hal baik dan bermanfaat, yang salah satunya dengan khitan.
Sebagaimana pihak pesantren tersebut yakini, khitan perempuan mereka lakukan karena alasan syariat. Yakni mendasari pandangannya pada Mazhab Syafi’i yang mewajibkan perempuan dikhitan. Melengkapi hadis yang mengisahkan sahabat Ummu Athiyah, yakni seorang dukun sunat di zaman Rasul yang beliau minta untuk tidak melakukannya pada perempuan secara berlebihan.
Praktik yang Masih Berlanjut
Alasan lainnya, pihak pesantren meyakini bahwa manfaat kesehatan juga akan perempuan dapatkan jika dikhitan. Seperti syahwat yang terkontrol sehingga tidak mudah terjerumus dalam zina. Wajah jadi berseri-seri, menambah kenikmatan hubungan seksual yang berdampak pada keharmonisan rumahtangga.
Bahkan mereka percaya akan memudahkan proses pembersihan area vagina. Walhasil, praktik yang sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun lalu di pesantren tersebut, terus berlanjut hingga saat ini, yang dieksekusi oleh dukun sunat.
Namun, bagaimana nasib para perempuan yang mereka sunat tersebut? Apakah keputusan berkhitan itu murni mereka sadari? Jika membaca utuh riset An Nabila dalam skripnya, motivasi para santri putri untuk mereka khitan tidak semuanya murni dari keinginan pribadi. Melainkan bentuk ta’zhim atau rasa hormat pada para pembimbing dan pengasuh pesantren. Merasa tidak enak jika melanggar aturan pondok, atau bahkan ada yang hanya sekadar ikut-ikutan teman.
Secara rinci An Nabila menulis, para santri mereka beri pemahaman mengenai praktik ini. Di mana mereka lakukan sebagai wujud mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga anjuran Nabi Ibrahim as. Mereka juga menganggap khitan perempuan mempunyai banyak manfaat kesehatan.
Selain motif lain seperti ingin mengikuti peraturan pesantren, melaksanakan arahan dari pengasuh pesantren, atau ada juga yang melakukannya karena ikut-ikutan temannya sendiri. Selain itu ingin menjadikan kenangan bahwa dia pernah mengikuti khitan perempuan massal di pesantren tersebut.
Menurut An Nabila, para santri putri umumnya mengetahui sunat perempuan mereka lakukan saat usianya masih kecil atau mungkin masih bayi. Sedangkan praktik khitan perempuan mereka lakukan di usia sudah remaja bahkan dewasa. Mereka baru mengetahuinya saat mereka sudah menjadi santri di sana.
Fatwa Darul Ifta Mesir
Apa yang kita sebut sebagai pandangan syariat oleh para pihak yang setuju pada praktik khitan perempuan, nyatanya juga harus kita hentikan dengan alasan syariat. Darul Ifta Mesir tahun 2007 mengeluarkan fatwa melarang khitan perempuan.
Tindakan ini bahkan masuk kategori haram dan bisa terpidana karena ada bahaya secara medis dan psikis. Demikian pula hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan bahwa khitan perempuan tidak ada manfaatnya dan sebaiknya kita tinggalkan.
Tahun 2022 Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan pandangannya, dengan menyatakan bahwa melindungi perempuan dari pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis, adalah wajib hukumnya.
Dalam konteks khitan perempuan, mendudukkan persoalan organ tubuh perempuan, dalam hal ini adalah vagina, tentu saja sangat kita perlukan merujuk pada pendekatan medis. Bila para pihak yang meyakini khitan perempuan itu kita lakukan dengan alasan membuang sedikit atau melukai sedikit sesuatu berbentuk tudung klitoris, maka pihak medis menampik tegas hal ini.
Sebab vagina perempuan bersifat terbuka dan tidak ada satupun kulit yang menutupi area alat kelamin perempuan. Hal ini memudahkan perempuan saat membersihkan vaginanya. Tidak seperti laki-laki yang dianugerahi kulit/kulup yang menutupi area penis, sehingga sangat perlu untuk kita potong/sunat/khitan.
Pentingnya Mediasi
Lantas bagaimana menyikapi fakta flyer di atas? Karena dari uraian An Nabila dalam skripsnya, sejatinya praktik khitanan massal tersebut hendak memunculkan makna sosial, makna budaya, dan makna religius.
Melakukan napak tilas sebuah peringatan dengan kegiatan positif, sangatlah kita anjurkan dari sudut pandang manapun. Terlebih hal baik tersebut bukan hanya baik untuk kalangan internal, melainkan maksudnya bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Namun jangan lupa bahwa jangan sampai tindakan yang kita lakukan sejatinya malah berdampak negatif karena kurangnya informasi, minimnya kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menerima berbagai pandangan. Tentu saja mediasi menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Praktik yang sangat tidak tubuh perempuan perlukan bahkan melukai ini, mestinya harus kita hentikan.
Tetapi, menghilangkan niat baik memelihara tradisi juga bukanlah hal yang bijaksana. Sehingga, pihak penyelenggara bisa saja tetap mempertahankan tradisi ini dengan betul-betul mempertimbangkan khitan perempuan untuk tidak lagi mereka adakan.
Mungkin bisa mereka ganti dengan banyak kegiatan lain yang jauh lebih bermanfaat dan benar-benar kita butuhkan. Minimal untuk para santri putri, dan secara lebih luas lagi, untuk masyarakat luas di sekitarnya.
Dari riuhnya hiruk-pikuk praktik sunat perempuan yang tidak pernah selesai ini, tentu yang paling esensi segera kita lakukan adalah mendengar suara perempuan itu sendiri. Utamanya mereka yang menjadi ‘obyek’ sunat: Apakah perempuan sebagai pemilik tubuhnya sendiri menangguk manfaat besar?
Apakah perempuan sebagai pemegang otoritas atas tubuhnya, yang akan menjalankan fungsi sosial dengan alat reproduksinya itu sepanjang hayat, benar-benar kita dengar keinginannya? Di sinilah tugas kita semua berada. []