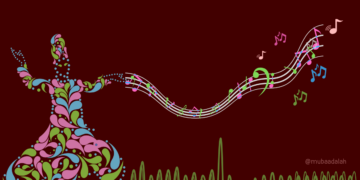Mubadalah.id – Hati Suhita menambah deretan novel pesantren yang berhasil menembus dunia perfilman. Film yang ditayangkan di bioskop sejak 25 Mei kemarin mendapat respons yang positif dari masyarakat. Bahkan baru tujuh hari sejak penayangan film ini, melihat twitter Kharisma Starvision, Film Hati Suhita telah menyerap 257.075 penonton.
Sekilas Film Hati Suhita
Sudah banyak media yang memberikan ulasan terkait film Hati Suhita. Secara sekilas film yang Starvision adaptasi dari novel dengan judul yang sama milik Khilma Anis ini menggambarkan tradisi pernikahan di pesantren. Menjadi hal yang lumrah dalam tradisi kepesantrenan bahwa putra kiai akan dinikahkan dengan putri kiai lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga trah dan supaya dapat melestarikan kehidupan pesantren ke depannya.
Namun lagi-lagi di era sekarang dengan kebudayaan yang semakin berkembang perjodohan seperti itu dapat kita katakan relevan atau kurang relevan. Relevan karena memang prinsip kafa’ah (sekufu) masih memegang perang penting dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.
Namun juga bisa kita katakan kurang relevan karena di era milenial ini setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Lagi-lagi semua kembali kepada bagaimana komunikasi yang terbangun di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Belajar dari Film Hati Suhita
Meskipun Khilma Anis dengan kerendahan hatinya mengatakan bahwa film tersebut bukan film bergenre pesantren, namun film ini tetap menggambarkan bagaimana kehidupan pesantren yang sarat dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Justru melalui sastra yang telah tervisualisasikan ini, nilai-nilai yang pesantren ajarkan seperti adab, birrul walidain, dan khidmah kepada guru akan lebih mudah tersampaikan kepada audiens.
Begitupun nilai-nilai perspektif mubadalah yang tersirat dalam film tersebut. Dalam artikel berjudul “Adakah Nilai-Nilai Perspektif Mubadalah dalam Novel Suhita”, Karimah Iffia Rahman menyebutkan tiga nilai perspektif mubadalah seperti prinsip mitsaqan ghalidha, hunna libasun lakum wa antum libasun sahun, dan muasyaroh bil ma’ruf. Tentu masyarakat, bahkan yang awam sekaligus akan lebih mudah memahami pesan tersebut melalui visualisasi yang menarik nan apik.
Sastra sebagai Media Dakwah
Dalam tulisan ini saya tidak ingin memberi banyak ulasan tentang Film Hati Suhita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sudah banyak media yang menceritakannya. Yang menarik bagi saya bahwa Hati Suhita sebagai bagian dari karya sastra telah berhasil menjadi media dakwah.
Merujuk dari M.S Nasarudin Latif bahwa dakwah adalah setiap aktivitas, baik lisan maupun tulisan yang mengajak, menyeru, serta memanggil manusia supaya beriman dan taat kepada Allah berdasarkan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah.
Jika melihat pengertian tersebut, setiap individu dapat melaksanakan kegiatan dakwah. Dakwah tidak hanya kita pahami dengan aktivitas ceramah di atas podium maupun masjid-masjid, namun dapat menjelma melalui berbagai macam cara, termasuk melalui karya sastra. Dakwah melalui karya sastra pun terasa lebih luwes, lentur, tidak membosankan, dan mampu menyentuh emosional audiens.
Geliat Sastra Pesantren di Indonesia
Sejarah menunjukkan bahwa dunia sastra sebagai bagian dari lingkup kesenian turut memegang peran penting dalam proses islamisasi di Indonesia. Betapa banyak karya sastra yang lahir dari rahim ulama terdahulu sebagai upaya untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat.
Di masa Wali Songo kita akan mengenal karya sastra bernafaskan Islam seperti Suluk Sunan Bonang, Suluk Kalijaga, Suluk Sunan Giri, dan Wasita Jati Sunan Geseng. Karya sastra tersebut murni tulisan tangan yang Beliau tulis dengan nuansa tasawuf yang kental. Selain itu juga terdapat karya sastra sebagai bentuk akulturasi dengan budaya sebelumnya seperti Serat Dewa Ruci, Jamus Kalimasodo, Jaka Sumantri (ketiganya ini karya Sunan Kalijaga), Jaka Klinting (karya Sunan Kudus) dan Pajajaran (karya Sunan Gunung Jati).
Tidak berhenti di situ, para ulama, kiai, pujangga, bahkan para raja banyak yang menelurkan karya sastra di era Mataram Islam. Serat Surya Raja misalnya, ditulis oleh Hamengkubuwono II yang mengisahkan tentang Sunan Kalijaga sebagai guru spiritual wangsa Mataram Islam.
Pada awal masuknya Islam di Indonesia, karya sastra yang ada sering kali memuat nilai-nilai tasawuf. Namun nilai-nilai yang mereka ajarkan juga menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu tanpa menghilangkan substansi dari ajaran Islam.
Selain itu juga terdapat relasi yang kuat antara pesantren dengan keraton. Bahkan terdapat suluk yang menyebutkan bahwa para putra raja hendaknya menjadi santri terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat melalui kekuatan politiknya. Hal itu tertulis dalam Suluk Wringin Sungsang karya Sunan Kalijaga.
Pada dekade selanjutnya pun banyak pujangga jebolan pesantren. Ronggowarsito misalnya, cicit Yasadipura I ini dulu pernah nyantri di pesantren Gebang Tinatar Tegalsari di bawah asuhan Kiai Ageng Muhammad Besari. Ia kemudian menjadi pujangga besar Jawa yang melahirkan karya sastra masyhur bercorak mistik Jawa-Islam seperti Serat Kalatidha, Sabdajati, Sabdatama, Jaka Lodhang, dan Wedharaga.
Pesantren dan Tradisi Kesusastraan
Dalam tradisi kepesantrenan sendiri sastra kerap kali menjadi media pembelajaran. Para ulama terdahulu meringkas materi-materi keagamaan dalam bentuk syi’ir sehingga mempermudah para santri dalam belajar.
Adanya pembelajaran berbasis syi’iran, mulai level dasar seperti Aqidatul Awam, Ngudi Susilo, Alala hingga yang level atas seperti Alfiyah menjadi metode yang hingga kini masih kita temui di pesantren. Bahkan hal tersebut menjadi ciri khas yang jarang kita temui di tempat lainnya.
Adalah sebuah keniscayaan jika produk-produk didikan pesantren pun banyak yang bergelut di bidang sastra. Ada yang menjadi cerpenis, novelis, maupun penyair. Lihat saja KH Mustofa Bisri, Cak Nun, Candra Malik, Najhaty Sharma, maupun Khilma Anis. Mereka tidak hanya berkarya, melainkan juga menyelipkan nilai-nilai keislaman dengan sentuhan halus melalui karya sastranya.
Dalam artikel berjudul Treading The Footsteps of Wali Songo as The Shaper of Islam Nusantara Tradition, Siti Muliana dan Muhammad Nasruddin menyebutkan bahwa salah satu strategi islamisasi yang Wali Songo lakukan adalah melalui budaya popular. Tentu budaya popular di masa silam dengan masa sekarang sudah jauh berbeda. Jika dulu budaya popular yang berkembang melalui suluk dan pewayangan maka sekarang sudah berkembang ke dunia novel dan perfilman.
Sebuah Refleksi
Hati Suhita yang berhasil difilmkan ini menjadi nafas segar bagi dunia pesantren. Biasanya kerap kali santri terkesan sebagai pribadi yang kolot, konservatif, dan tidak modern. Namun Hati Suhita mampu menunjukkan bahwa santri dapat go nasional, bahkan internasional dengan karya sastranya. Memang stigma-stigma seperti itu harus kita patahkan dengan bukti nyata.
Selain itu pesantren hendaknya juga menjadi lingkungan yang memberikan “kebebasan” – tentu dalam batas wajar – untuk mengembangkan kreativitas para santri. Potensi-potensi yang santri miliki hendaknya tidak dikekang hanya karena berpatokan dengan metode lama.
Alangkah baiknya jika potensi tersebut dapat tersalurkan, terfasilitasi, dan terarahkan sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi semua pihak, terlebih bagi eksistensi dari Islam itu sendiri.
Sedikit pesan bagi para santri dan diri saya sendiri, Belajarlah, berkaryalah, lakukan apa yang dapat kamu lakukan dan jadilah Khilma Anis versi dirimu sendiri! Sekian. []