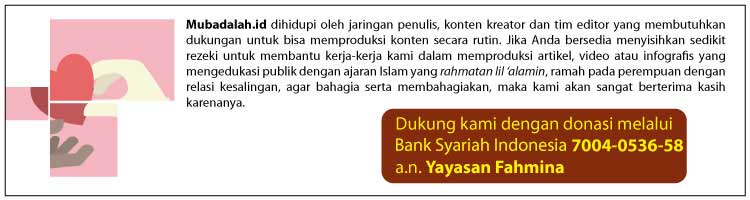Mubadalah.id – Perdebatan di sekitar pemahaman atau memperebutkan makna teks merupakan perdebatan yang sangat klasik. Ia muncul sejak awal Islam bahkan sejak manusia mulai berfikir dan berkebudayaan. Perdebatan itu telah melahirkan sekte-sekte, aliran-aliran pemikiran keagamaan bahkan ideologi-ideologi. Pada dimensi fiqh, dikenal dua aliran besar, ahl al-hadîts dan ahl al-ra’y. Aliran pertama cenderung lebih tekstualis (harfiah) dan mempercayai sumber berita, sementara yang kedua lebih rasionalis dan lebih melihat kandungan berita.
Ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu disampaikan orang: Apakah teks harus diterima menurut arti lahirnya atau bisa di-ta’wîl (tafsîr)? Apakah hukum-hukum yang terdapat dalam teks bisa dirasionalkan atau tidak (hal al-ahkâm mu’allalah bi ‘illah am lâ)? Apakah akal bisa bertentangan dengan wahyu? Bagaimana jika bunyi teks berlawanan dengan logika atau dengan realitas, mana yang harus diprioritaskan? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu saja dijawab dengan pandangan yang beragam dan dengan argumentasinya masing-masing.
Sesungguhnya kedua aliran tersebut tidak jauh berbeda dalam semangat dan tujuannya. Semuanya sepakat bahwa hukum-hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dan menegakkan kemaslahatan (kesejahteraan) manusia. Kita menemukan paradigma ini pada semua ahli fiqh Islam. Menegaskan pandangan gurunya [Imâm al-Haramain al-Juwainî], Imâm al-Ghazâlî dalam al-Mustashfâ’, misalnya, mengemukakan bahwa kemaslahatan sebagai tujuan syari’ah.
Pandangan dan pendirian mereka yang beragam tersebut sesungguhnya merupakan akibat dari perbedaan pemahaman atau pemaknaan mereka atas teks-teks al-Qur’ân maupun Hadits Nabi saw. Tidak seorang muslimpun yang ingin menafikan al-Qur’ân dan Hadits Nabi saw. Sebab menafikan keduanya mengakibatkan ia kehilangan identitasnya sebagai muslim.
Terkait dengan hal ini, Prof. Dr. Husein al-Dzahabî mantan Menteri Waqaf Mesir dan Guru Besar Universitas al-Azhar pernah mengatakan: “Kebenaran Agama adalah apa yang ditemukan manusia dari pemahaman kitab sucinya sehingga kebenaran agama dapat beragam dan bahwa Tuhan merestui perbedaaan cara keberagaman umat manusia atau apa yang kemudian disebut dalam ajaran Islam sebagai “tanawwu’ al-‘abadah”. Jika ini dapat dipahami niscaya tidak akan timbul kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan…” (lihat: Agama dan Pluralitas Bangsa, P3M, 1991, hlm. 40).
Lalu dari mana dan mengapa orang berbeda-beda dalam memaknai teks? Untuk menjelaskan hal ini, adalah menarik untuk mengemukakan pandangan Fârûq Abû Zaid dalam bukunya Al-Syarî’ah al-Islâmiyah baina al-Muhâfizhîn wa al-Mujaddidîn (Syari’ah Islam antara tradisionalis-konservatis dan modern) bahwa “keberagaman interpretasi atas teks-teks keagamaan adalah refleksi sosio-kultural mereka masing-masing”. Fârûq mengatakan: “Anna Madzâhib al-Fiqh al-Islâmy laisat siwâ in’ikas li tathawwur al-hayâh al-Ijtimâ’iyyah fî al-‘Alam al-Islâmy”. (hlm. 16).
Perebutan pemaknaan atas teks pada akhirnya harus disudahi melalui mekanisme yang paling baik dan sejalan dengan perintah al-Qur’ân; ‘musyawarah’, dan cara-cara yang demokratis, bukan dengan jalan sendiri-sendiri apalagi dengan menggunakan kekerasan, membunuh, termasuk membunuh karakter orang.