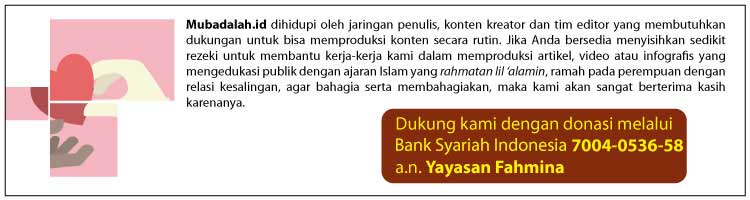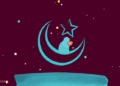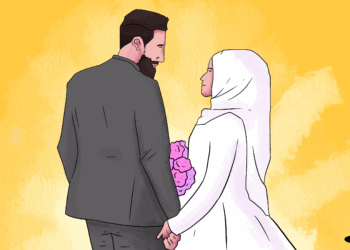Mubadalah.id – Banyak dari kita hidup dengan asumsi bahwa dunia ini telah berjalan menuju keadilan. Kita merasa telah cukup inklusif, cukup sadar, dan cukup adil. Namun setelah membaca buku Disabilitas dan Narasi Ketidaksetaraan karya Muhammad Khambali, saya menyadari bahwa anggapan itu keliru. Dunia, sayangnya, belum seadil itu dan kita belum sesadar itu.
Buku ini bukan hanya sekadar kumpulan esai tentang disabilitas. Ia adalah seruan, ajakan, dan juga semacam tamparan bagi siapa pun yang selama ini hidup dalam privilese sebagai individu non-difabel. Dengan bahasa yang lugas, sesekali puitis, sesekali meledak dalam kemarahan yang terpendam, buku ini mengangkat berbagai isu seputar disabilitas yang sering kali kita abaikan, atau bahkan tak pernah kita anggap penting.
Membongkar Mitos “Normal”
Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah kritik terhadap konsep “normal”. Masyarakat modern kerap membangun sistem sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan budaya dengan standar-standar tertentu yang kita anggap wajar dan ideal.
Sayangnya, standar ini seringkali hanya merujuk pada kondisi tubuh dan kemampuan mayoritas, alias non-difabel. Akibatnya, siapa pun yang berbeda menganggapnya “tidak normal”, “cacat”, atau bahkan “masalah”.
Khambali mengajak kita untuk mempertanyakan: apakah “normal” itu fakta atau konstruksi? Siapa yang menetapkan batasan “normal”? Dan apa dampaknya bagi mereka yang hidup di luar kategori itu? Buku ini tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi juga menunjukkan bagaimana kata-kata semacam “normal”, “berkebutuhan khusus”, dan “istimewa” bisa menjadi alat kekuasaan yang secara halus menyingkirkan dan menindas.
Ableisme: Diskriminasi yang Diabaikan
Salah satu kekuatan buku ini adalah keberaniannya untuk menyebut dan membedah ableisme, yaitu sistem kepercayaan dan praktik sosial yang menempatkan kemampuan tubuh dan pikiran non-difabel sebagai patokan utama dalam kehidupan bermasyarakat.
Ableisme membuat kota tidak ramah kursi roda, membuat kelas tidak ramah pada siswa dengan gangguan belajar, dan membuat media hanya menampilkan difabel sebagai objek rasa kasihan atau inspirasi semata.
Esai-esai dalam buku ini menunjukkan bagaimana ableisme menjelma dalam wujud yang kasat mata: trotoar yang tinggi, bangunan tanpa lift, toilet tanpa pegangan tangan. Tapi ia juga hadir dalam hal yang lebih subtil: kurikulum sekolah yang tidak mempertimbangkan gaya belajar neurodivergent, atau bahasa yang eufemistis yang justru menghapus identitas difabel.
Inklusi yang Sering Timpang
Inklusi adalah kata yang sering kita pakai untuk menunjukkan niat baik. Tapi di tangan Khambali, kata ini juga dibongkar dan ia kritisi. Ia menunjukkan bagaimana inklusi, dalam praktiknya, kadang hanya menjadi cara halus untuk “memasukkan” difabel ke dalam sistem yang tidak pernah benar-benar kita rancang untuk mereka. Inklusi sering kali hanya sebatas “akses masuk”, bukan “perubahan sistem”.
Misalnya, menyediakan lift atau ramp di sekolah belum tentu berarti inklusi jika materi ajar, cara mengajar, dan lingkungan sosial tetap diskriminatif. Inklusi sejati seharusnya menantang sistem yang sudah ada, bukan sekadar memberi ruang agar yang berbeda bisa “ikut” asal tidak mengganggu.
Suara dari Pinggir: Perspektif Difabel dalam Esai
Yang membuat buku ini begitu kuat adalah cara pandangnya yang datang dari dalam. Khambali, sebagai pengajar pendidikan khusus, menulis tidak hanya sebagai akademisi. Tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang memahami disabilitas secara langsung. Ia tidak menulis dari menara gading, melainkan dari jalanan kehidupan sehari-hari, dari kelas-kelas tempat ia mengajar, dan dari perenungannya sebagai manusia.
Kita diajak untuk mendengarkan pengalaman difabel, bukan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek yang punya suara, agensi, dan hak untuk kita dengar. Salah satu kutipan dari buku ini yang paling menggugah berbunyi, “Pada mulanya adalah kata, selanjutnya diskriminasi.” Kalimat ini merangkum bagaimana bahasa bisa menjadi alat kekerasan simbolik yang membuka pintu bagi diskriminasi sistemik.
Sebuah Refleksi Dari Pembaca
Sebagai pembaca, saya tidak hanya diajak memahami isu disabilitas dari sudut pandang teoritis atau aktivisme, tetapi juga diajak merenung secara pribadi. Buku ini menuntut pembacanya untuk bercermin, bertanya, bahkan merasa tidak nyaman. Dan itu baik. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kita sedang belajar.
Selain itu, apresiasi khusus layak kita berikan kepada desain sampul buku ini yang begitu sarat makna. Elemen bahasa isyarat dan tulisan Braille bukan hanya ornamen estetis, tapi simbol nyata dari upaya inklusivitas. Desain ini, karya Viona Daisy, menjadi bukti bahwa inklusi bisa dan harus menyentuh seluruh aspek kehidupan, bahkan pada detail sekecil tampilan sampul.
Di sisi lain, buku ini juga tidak serratus persen sempurna. Beberapa bagian terasa repetitif, mungkin karena bentuknya yang berupa kumpulan esai. Ada juga kesalahan teknis kecil seperti typo dan pemenggalan kalimat yang bisa diperbaiki di cetakan selanjutnya.
Namun kekurangan ini tidak mengurangi nilai penting dari pesan yang tersampaikan. Sebaliknya, kekurangan itu justru mengingatkan kita bahwa perjuangan kesetaraan tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kejujuran dan keberanian untuk terus melangkah.
Menutup dengan Harapan
Sebagaimana yang Khambali tuliskan, kesetaraan mungkin tampak fana, tak nyata, sulit tergapai. Tapi ia bukan mustahil. Kesetaraan, seperti senja, selalu bisa kita kejar. Dan perjalanan menuju sana kita mulai dari hal-hal kecil: dari membaca buku ini, dari mengubah cara kita berbicara, berpikir, dan bersikap.
Kita tidak perlu menunggu menjadi ahli untuk mulai peduli. Kita hanya perlu berani melihat dari pinggir, tempat di mana suara-suara yang selama ini terbungkam, mulai berbicara.
Buku ini tidak memberikan semua jawaban. Tapi ia memberikan sesuatu yang lebih penting: yaitu kesadaran. Dan dari kesadaran itu, semoga lahir perubahan. []