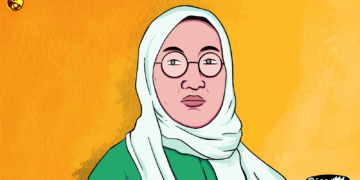Mubadalah.id – Sudah menjadi tradisi di Indonesia, bahwa pada setiap ‘Hari Pahlawan’ selalu diwarnai dengan wacana ‘pangusulan’ gelar pahlawan nasional, bagi mereka yang dianggap memiliki jasa perjuangan dalam membela bangsa dan negara. Seperti yang terjadi di Blora, Jawa Tengah baru-baru ini.
Di tengah peringatan Hari Pahlawan pada 10 November yang lalu, terdapat usulan agar Pocut Meurah Intan diberi gelar sebagai Pahlawan Nasional. Usulan ini disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang saat itu sedang berziarah di makam Pocut Meurah Intan, pada Selasa, 9 November 2021 yang lalu.
Potjut Meurah Intan adalah salah satu pejuang perempuan yang ditemukan dalam laporan Belanda. Disebutkan dalam laporan kolonial ‘Kolonial Verslag’ pada tahun 1905, bahwa hingga awal tahun 1904,ia adalah satu-satunya tokoh dari kesultanan Aceh yang belum menyerah dan mempertahankan sikap anti-Belanda. Bahkan setelah suaminya menyerah kepada Belanda, dia memutuskan untuk berpisah dan mendesak ketiga putranya yang bernama Muhammad, Budiman dan Nurdin untuk tetap melanjutkan pertempuran.
Menurut catatan sejarah, perjuangan Pocut Meurah dalam melawan Belanda terjadi pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Setelah berhasil menghindari penangkapan, Pocut Meurah Intan melakukan perlawanan dengan cara bergerilya. Akhirnya ia ditangkap di markas mereka di Padang Tiji. Pocut Meurah Intan lalu diasingkan di Kabupaten Blora hingga akhir hayatnya. Makamnya berada di kawasan makam Tegalsari, Desa Tempurejo, Kabupaten Blora. Di makamnya tertulis bahwa ia meninggal pada 20 September 1937.
Di Indonesia, pemberian gelar Pahlawan nasional, diberikan pada mereka yang meninggal dunia karena berjuang melawan penjajahan, juga pada mereka yang semasa hidupnya menghasilkan prestasi atau karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan pahlawan nasional masih menimbulkan banyak polemik, khususnya yang berkaitan jumlah pahlawan nasional perempuan yang dinilai masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan. Dari 191 jumlah keseluruhan pahlawan nasional, hanya terdapat lima belas orang pahlawan nasional perempuan. Jumlah ini menunjukkan bahwa pemilihan pahlawan nasional di Indonesia masih diwarnai bias gender.
Tidak hanya sampai disitu, polemik terkait gender dalam pemilihan pahlawan nasional terlihat pada nama-nama hanya berjumlah lima belas itu, dianggap belum mewakili para pejuang perempuan lainnya. Kebanyakan dari mereka hanya tercatat dalam cerita-cerita yang berkembang di masyarakat daerahnya masing-masing, sehingga tidak tercatat dalam publikasi sejarah nasional.
Sebut saja, Potjut Meurah Intan, yang merupakan salah satu pejuang perempuan yang turut serta terjun ke medan perang dengan mempertaruhkan nyawanya melawan penjajah, namun tidak mendapat gelar pahlawan nasional.
Penulisan sejarah mengenai tokoh-tokoh pahlawan ini memunculkan pola dasar kepahlawanan perempuan. Para pahlawan perempuan ini selalu digambarkan sebagai seorang prajurit yang berani, cantik, biasanya janda dengan latar belakang bangsawan dan ditakdirkan untuk mati sebagai martir.
Pola kepahlawanan seperti ini banyak terdapat dalam buku-buku sejarah ‘mainstream’ diterbitkan dari tahun 1950 hingga 1980-an.Dengan kata lain, penonjolan pada kisah-kisah romantis dari beberapa tokoh terpilih menjadi satu-satunya titik rujukan sejarah bagi para pejuang perempuan Aceh secara umum.
Dalam sejarah ‘mainstream’ negeri ini, kita mengenal tiga nama tokoh pahlawan perempuan Aceh yang dijadikan sebagai pahlawan nasional. Mereka adalah Malahayati, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia. Kisah ketiga tokoh ini sama-sama ditransmisikan oleh orang Belanda.
Kisah Malahayati diketahui lewat sebuah karya fiksi yang berhubungan dengan sejarah Aceh yang diterbitkan pada tahun 1935 yang ditulis oleh Marie Van Zeggelen, kisah Tjoet Nja Dhin diketahui lewat novelis Belanda, Madelon Székely-Lulofs dan Tjoet Meutia yang kisahnya disampaikan oleh Jurnalis perang Zentgraaff. Narasi ketiganya serupa, yakni adanya penekanan pada kebangsawanan, kesempurnaan fisik, dan peran gendernya sebagai seorang istri dari tokoh laki-laki berpengaruh.
Padahal jika ditelusuri, masih banyak pejuang perempuan Aceh anti-Belanda yang hidup di abad kesembilan belas lainnya namun sangat sedikit dinarasikan dalam historiografi Aceh maupun Indonesia, seperti misalnya Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, Pocut Meuligo, Teungku Fakinah dan Teungku Cutpo Fatimah.
Selain itu, masih banyak juga para pejuang perempuan yang ‘anonim’ terlibat dalam perang melawan Belanda. Kebanyakan dari mereka berasal dari desa dan jauh dari lingkaran eksklusivisme kebangsawanan aceh. Zentgraaff melaporkan bahwa ada ratusan dan mungkin ribuan perempuan Aceh yang aktif terlibat dalam perang. Dia menjelaskan bahwa para perempuan ini memilih untuk pergi berperang dari pada tinggal berdiam diri di rumah.
Bukti arsip dari para pejuang perempuan semacam ini juga dapat ditemukan di telegram Belanda yang dikirim dari Aceh ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa. Mereka menyebutkan para perempuan desa ini bersenjatakan rencong dan kerap menyerang pasukan marsose kolonial, menyembunyikan senjata dan amunisi, bahkan melakukan penyamaran dengan pakaian pria berwarna hitam. Para perempuan anonim ini, yang namanya tidak tercatat dalam sejarah Indonesia, mengambil bagian dalam perjuangan bersama pejuang laki-laki dan sesama perempuan.
Dalam Sejarah mainstream, narasi mengenai kepahlawanan perempuan didominasi oleh mereka yang berasal dari kalangan bangsawan, berada dibalik nama besar suaminya. Sementara yang berada di luar lingkaran itu, biasanya dilupakan oleh sejarah, seperti kasus para pejuang perempuan yang anonim ini. Bukti partisipasi dalam perang oleh perempuan anonim diungkapkan oleh pengamat Belanda pada abad ke-19, tetapi mereka tidak pernah diberi perhatian yang sama dengan perempuan bangsawan Aceh yang namanya masuk dalam jajaran pahlawan nasional.
Kita memang tidak mengetahui secara pasti tentang latar belakang ratusan atau ribuan perempuan yang diperhatikan oleh Zentgraaff. Namun, belum terlambat untuk mencari sejarah anonim ini. Narasi ini mungkin saja dapat kita temukan pada koleksi jurnal, surat, koran-koran, dan laporan Belanda yang tersimpan dalam Arsip Nasional Belanda, mengingat masa pendudukan Belanda yang cukup lama di Aceh memungkinkan untuk mereka mendokumentasikan hal ini. Bagaimanapun, kejayaan Aceh di masa lalu tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan perempuan sebagai pejuang bahkan pemimpin perang. []