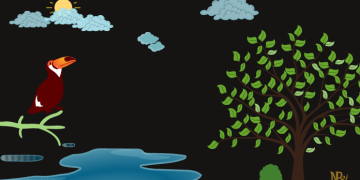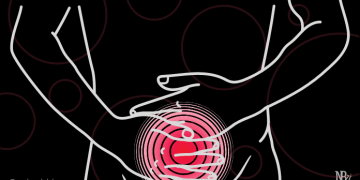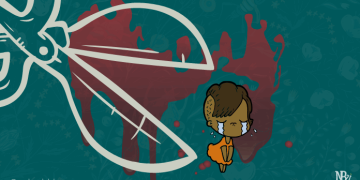Mubadalah.id – Suasana lebaran Idulfitri masih terasa hingga hari ini. Hampir semua umat muslim menyambut hari kemenangan ini dengan penuh bahagia dan haru.
Namun meski begitu, masih hangat diingatan kita bagaimana Ramadan 2024 dipenuhi dengan warna warni keberagaman agama. Mulai dari perbedaan penentuan tanggal 1 Ramadan, trend War Takjil antara Muslim dan Non Muslim, sampai pada perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri.
Dari semua fenomena di atas sepertinya kita lebih luwes dalam menerima perbedaan penentuan tanggal 1 Ramadan, begitu juga dengan trend War Takjil. Namun dalam menerima perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri, kita mesti banyak belajar lagi.
Bagaimana tidak, kemarin ketika Jama’ah Aolia menetapkan bahwa Hari Raya Idulfitri jatuh pada tanggal 5 April 2024 atau pada tanggal 25 Ramadan Nahdlatul Ulama (NU). Sebagian besar umat muslim meresponnya dengan penuh kebencian dan mencaci maki mereka. Bahkan tidak sedikit yang melabelinya sesat dan menyimpang dari ajaran Islam.
Hal ini semakin panas ketika Mbak Banu sebagai sesepuh Jama’ah Aolia menyampaikan bahwa penetapan tersebut didasari karena beliau telah melakukan “Tilpun langsung pada Allah”. Bagi sebagian umat muslim ini sangat aneh dan tabu. Maka dari itu, mereka merasa yakin untuk mengatakan bahwa Jama’ah Aolia itu sesat.
Tabayyun
Jika kita maknai lebih dalam, sebagai seorang muslim yang hidup di Indonesia, kita mestinya lebih luwes dalam menerima segala bentuk perbedaan dan keragaman dalam beragama. Lebih dari itu, sebagai muslim yang baik, mestinya kita juga mengutamakan tabayyun, atau menelusuri terlebih dahulu apa maksud dan makna yang terkandung dalam istilah “tilpun Allah” itu.
Untuk mengetahui hal tersebut, tentu saja kita harus bertemu dan berkenalan secara langsung dengan jama’ah Aolia ini. Karena tidak mungkin kita bisa memahami sesuatu yang kita anggap bereda, tetapi kita tidak mau legowo untuk mengenal siapa mereka dan apa makna yang terkandung dari ajaran yang mereka yakini.
Inilah mengapa sikap toleransi dan memahami keyakinan berbeda itu sangan penting. Supaya tidak mudah berprasangka buruk dan melabeli orang yang berbeda sebagai kelompok sesat dan menyimpang.
Mengenal Mbah Banu
Sebagaimana yang aku sampaikan di atas, kita memang sangat perlu mencari terlebih dahulu informasi segala hal yang kita anggap berbeda. Sehingga dari informasi tersebut kita bisa mengetahui lebih dalam siapa mereka, apa nilai yang diyakini oleh mereka dan bagaimana car akita bersikap atau merespon perbedaan tersebut.
Karena itu, daripada sibuk komentar negatif ke Jamaah Aolia dan Mbah Banu, mari kita mengenal terlebih dahulu, siapa itu Mbah Banu.
Dari beberapa sumber yang aku baca di internet, Mbak Banu memiliki nama asli Raden Ibnu Hajar, beliau lahir di Pekalongan, pada 28 Desember 1942. Ia tumbuh dan besar di di Solotiyang, Maron, Purworejo.
Kemudian seperti yang ditulis di website suara.com. Mbah Banu sempat berkuliah di Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, ia memutuskan drop out (DO) atau keluar pada semester akhir. Tidak diketahui pasti apa alasan Mbah Banu memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
Sementara itu, dalam proses belajar ilmu agama, Mbah Banu secara langsung belajar pada ayahnya yaitu Kiai Soleh bin KH. Abdul Ghani bin Kiai Yunus. Kiai Soleh merupakan murid dari Mbah Kholil Bangkalan.
Dari sumber-sumber informasi tersebut, ternyata Mbah Banu dan keluarganya itu merupakan orang yang berpengetahuan. Karena itu, menurut saya tidak mungkin Mbah Banu menyesatkan jamaahnya sendiri, pasti ada cara dan pendekatan khusus yang Mbah Banu lakukan dalam melakukan penetapan Hari Raya Idulfitri tahun 2024.
Respon Para Tokoh di Indonesia pada Istilah “Tilpun Allah”
Ibu Lies Marcoes, seorang peneliti dan aktivis kemanusiaan dalam salah satu unggahan di Facebook pribadinya menyampaikan bahwa, kata “tilpun langsung”, yang dipakai oleh Mbah Banu dalam bahasa Antropologi agama merupakan metafora agar yang mendengarnya mengerti. Bukankah setiap manusia yang pernah berdoa pada hakekatnya melakukan “tilpun langsung” kepada Tuhan sesembahannya.
Senada dengan hal itu, Kiai Marzuki Wahid, Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) juga ikut merespon hal tersebut. Menurutnya, kita tidak bisa memahami telpon di sini sebagai telpon menggunakan handphone (HP) atau alat komunikasi lain. Karena Allah jelas bukan makhluk, yang bisa kita telpon dengan HP atau sejenisnya.
Menurut Kiai Marzuki, makna telpon di sini bukanlah makna hakikat. Tetapi berupa majaz di mana “Tilpun Allah” bisa bermakna berdoa atau berzikir. Persis seperti apa yang sering kita lakukan sehari-hari.
Hanya saja bahasa dan cara penyampaiannya berbeda, lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Lies, mungkin istilah tersebut dipilih Mbah Banu supaya memudahkan kita dalam mengerti apa yang dimaksud oleh Jama’ah Aolia.
Menanggapi Perbedaan dengan Bijak
Dari yang disampaikan oleh Ibu Lies Marcoes dan Kiai Marzuki Wahid. Aku jadi belajar bahwa dalam merespon dan menanggapi perbedaan dalam cara beragama. Kita tidak perlu hebah, apalagi marah-marah. Justru kita harus mulai belajar untuk bijak dan juga santai dalam beragama.
Sehingga, perbedaan apapun tidak menjadi masalah, apalagi menimbulkan ujaran kebencian. Bukankah ini juga yang selalu Nabi Muhammad Saw teladankan, beragama dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih. Bukan dengan mencaci, menghardik, marah, apalagi memandang yang berbeda sebagai kelompok sesat dan menyimpang.
Lagi pula, bukankah Hari Raya Idulfitri itu adalah hari kemenangan, kegembiraan dan kebahagiaan? Masa hari kemenangan mau kita rusak hanya karena perbedaan cara menentukan tanggal 1 Syawal.
Karena itu, mari beragama dengan asik dan santuy. Hargai dan hormati setiap pandangan yang berbeda. []