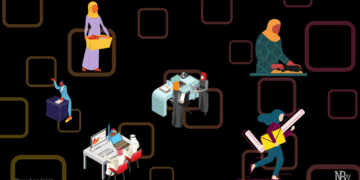Mubadalah.id – Hadis populer yang berbunyi, “Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya” (HR. Tirmidzi & al-Hakim), sering dikutip untuk menegaskan otoritas mutlak suami atas istri.
Padahal, konteks kemunculan hadis (asbab al-wurud) itu adalah respons Nabi saw terhadap Mu‘adz bin Jabal yang ingin bersujud kepada beliau. Meniru tradisi umat lain kepada pemuka agamanya. Tafsir yang mengabaikan konteks ini menjadikan hadis tersebut sebagai palu gada untuk melanggengkan relasi kuasa dalam rumah tangga. Apalagi bertambah dengan tafsir surat Annisa ayat 34.
Narasi tersebut bukan hanya ada di Islam. Bibel, misalnya, juga memuat seruan serupa. “Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan” (Efesus 5:22). Maka tak mengherankan bila gagasan kesetaraan dalam pernikahan sering dianggap menyimpang—sebuah gagasan yang dianggap melawan arus utama dan mengguncang tatanan yang selama ini kita anggap sakral, terutama oleh kelompok konservatif.
Sederet Tantangan
Ketika sudah memiliki kesadaran berbasis gender, pasangan bukan berarti sudah selesai dengan praktik kesetaraan. Setelah akad, masih ada sejumlah tantangan berbasis gender yang bisa menjerumuskan pasangan ke dalam pernikahan tradisional.
Banyak pasangan, terutama istri, akan terseret ke dalam pola relasi yang ditentukan oleh konstruksi gender tradisional ketika tinggal bersama orang tua atau mertua yang masih memegang teguh pola lama.
Dalam situasi seperti itu, ruang negosiasi menjadi sempit. Sehingga pasangan sulit berkelit dari nilai-nilai konservatif. Oleh sebab itu, tinggal terpisah dari keluarga asal bisa menjadi pilihan strategis untuk membuka kemandirian dalam pengelolaan rumah tangga.
Keputusan untuk memiliki anak juga sering kali menarik pasangan masuk kembali ke pola lama. Tekanan sosial-kultural, harapan keluarga besar, serta narasi pengasuhan tradisional. Di mana perempuan otomatis mereka anggap lebih siap mengurus anak. Sehingga mengikis peluang untuk membangun peran yang setara. Maka, penting untuk membicarakan visi pengasuhan bahkan sejak sebelum menikah.
Stereotip Gender dalam Keluarga
Budaya populer pun masih akan turut andil memperkuat stereotip gender dalam keluarga. Narasi tentang sifat laki-laki yang rasional dan perempuan yang emosional atau pria kerja di luar dan perempuan di rumah terus direproduksi. Lantas menciptakan pembenaran bahwa kesetaraan bukanlah hal yang alami. Dalam konflik rumah tangga, narasi ini sering menjadi alasan untuk menolak pembagian tugas domestik secara adil.
Bagi sebagian suami, kesetaraan bisa mereka anggap sebagai ancaman terhadap konsep kejantanan/maskulinitas. Aktivitas domestik seperti memasak atau menidurkan bayi dianggap akan menggerogoti kejantanan. Apalagi menyaksikan tetangga yang setiap saat bisa mancing atau main futsal, tanpa terbebani tugas domestik dan parenting.
Selanjutnya, ketika istri mulai mengusulkan relasi yang setara, respons yang muncul kerap berupa penolakan pasif-agresif. Diam, defensif, mengkritik, bahkan merendahkan gagasan itu dengan membawa-bawa dalih agama. Dalam sejumlah kasus, agama menjadi tameng untuk mempertahankan ketimpangan, bukan sebagai jalan menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.
Pernikahan yang Setara
Sejumlah tantangan di atas perlu kita mitigasi, terutama sebelum akad terjadi. Pernikahan yang setara berarti menolak dominasi atau otoritarianisme atas nama jenis kelamin. Prinsip kesetaraan berperan melindungi orang dari berbuat zalim sekaligus menjadi korban dari kezaliman. Dengan prinsip ini, suami akan terlindung dari sikap tangan besi seperti Firaun, dan istri akan terlindungi dari kemungkinan menjadi korban KDRT.
Kesetaraan dalam hubungan adalah kebutuhan fitri untuk menjaga kesehatan jiwa kedua belah pihak. Relasi yang setara adalah kunci hubungan yang mesra. Prinsip mubadalah adalah tawaran nyata relasi yang berkeadilan.
Tentu, menggeser paradigma seperti ini berarti menggoyahkan identitas lama tentang maskulinitas dan feminitas. Namun, keberanian generasi muda untuk menegosiasikan ulang peran gender justru menandai harapan baru bagi pernikahan setara yang sakinah. []