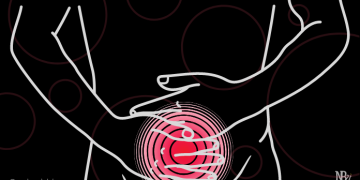Mubadalah.id – Kerentanan berlapis adalah ketidakadilan nyata yang dialami oleh perempuan difabel yang menjadi korban kekerasan. Namun, perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual sering kali menjadi isu yang terabaikan dalam wacana sosial. Salah satu kasus yang belakangan ini menjadi pembicaraan publik adalah kasus Arini, perempuan penyandang disabilitas asal Riau yang menjadi korban kekerasan seksual.
Marah, kecewa, kesal, dan sedih, rasa itu melebur dan mengaduk emosi ketika melihat video yang memberitakan Arini dan ayahnya di Instagram. Dalam video tersebut mereka berjalan meninggalkan kantor polisi dengan wajah lelah dan hampir putus asa yang tergambar dari raut keduanya.
Pihak kepolisian mengabaikan mereka ketika berusaha mencari keadilan atas tindak kekerasan seksual yang menimpa Arini. Saat itu, pihak kepolisian berdalih bahwa tidak ada polisi wanita yang sedang bertugas untuk menangani pelapor perempuan. Sehingga pihak aparat enggan memproses laporan. Ini sungguh alasan yang tidak masuk akal, bahkan cenderung aneh. Saya bisa membayangkan bagaimana kepolisian itu acuh dengan kasus-kasus yang bahkan mereka tidak bisa menilai bahwa kasus itu adalah krusial.
Podcast Denny Sumargo sebagai Ruang Bercerita
Akhirnya beberapa waktu lalu, Denny Sumargo mengundang Arini dan Ayahnya untuk menceritakan semua kronologinya. Podcast diawali dengan cerita ayahnya tentang kondisi Arini. Arini mengalami demam hingga kejang pada usia 10 bulan, karena itu ia seperti lumpuh total.
Lalu di usia 13 tahun mulai belajar jalan lagi, kemudian di usia 15 sudah bisa berjalan sendiri meski masih mengalami kesulitan jika berjalan di jalanan becek, berbatu atau jalan tidak rata. Setiap langkah Arini bukan hanya sekedar gerak tubuh, tetapi merupakan simbol keteguhan dan perjuangan.
Dengan suara yang lirih dan mata yang sesekali tampak kebingungan Arini bercerita tentang kejadian memilukan yang ia alami. Tentang bagaimana ia dimanipulasi dan diberikan janji-jani, mendapatkan kekerasan seksual, hingga ditelantarkan oleh Puji.
Awalnya mereka berkenalan melalui Facebook. Kemudian ketika Arini keluar rumah untuk membeli snack, Puji datang dan mengajak Arini pergi ke hotel dengan janji akan dinikahi. Sesampainya di hotel, Puji melakukan tindak kekerasan seksual terhadap Arini. Dengan situasi tersebut ditambah kondisi yang dialami, Arini tidak cukup kuasa untuk melawan Puji.
Berselang hari Arini meminta kejelasan pertanggungjawaban kepada Puji, berharap Puji akan menepati janjinya. Tetapi jawaban yang ia dapat hanya “nanti”. Arini malah dikejutkan dengan kenyataan bahwa ternyata Puji telah menikah dan memiliki satu orang anak.
Kemudian, tanpa ada rasa bersalah Puji meninggalkan Arini di sebuah SPBU, tanpa kejelasan. Tindakan ini sungguh sudah terlampau tidak terpuji untuk dilakukan oleh seorang manusia. Kasus ini cerminan bahwa kerentanan perempuan difabel berkelindan dengan beberapa faktor, yakni gender dan disabilitas.
Interseksionalitas
Kelindan dan persinggungan identitas yang ada dalam diri Arini melahirkan adanya kerentanan berlapis. Kompleksitas pengalaman yang dipengaruhi oleh persimpangan identitas tidak bisa dipahami menggunakan satu kacamata saja.
Maka untuk membaca kasus ini konsep interseksionalitas dapat memberikan pemahaman untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana layer-layer identitas seseorang saling bersinggungan dan mempengaruhi pengalaman kehidupan mereka.
Kimberlé Crenshaw memperkenalkan konsep interseksionalitas pertama kali pada tahun 1989. Ia menawarkan lensa analisis yang kuat untuk memahami bagaimana berbagai bentuk ketidakadilan sosial saling terkait dan dapat mempengaruhi kesejahteraan individu maupun kelompok.
Dalam sudut pandang interseksionalitas, kita tidak bisa memahami identitas sosial seseorang secara terpisah. Tetapi identitas dalam diri seseorang adalah hasil dari persimpangan dan interaksi yang rumit antar beberapa identitas dan latar belakang, seperti gender, ras, kelas, agama, dan disabilitas. Belakangan ini, seiring dengan perkembangan zaman, akses teknologi informasi digital juga menjadi salah satu dimensi dalam analisis interseksionalitas.
Dengan menggunakan konsep interseksionalitas memungkinkan kita untuk mengidentifikasi layer identitas yang multidimensi. Selain itu, dengan konsep ini dapat menambal sulam jarak atau disparitas yang barangkali belum terisi oleh analisis yang berfokus dalam satu dimensi saja.
Pendekatan interseksionalitas juga membuka potensi untuk menggali dinamika kekuasaan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Dalam konteks kasus Arini, kita harus membacanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor identitas yang berinteraksi dalam pembentukan pengalaman Arini.
Kerentanan Berlapis Perempuan Disabilitas
Faktor pertama yang harus penting kita gali adalah dimensi gender dan disabilitas. Karena sebagai perempuan penyandang disabilitas, Arini tentu mengalami pengalaman yang sama sekali berbeda dengan perempuan non-disabilitas. Dari sudut pandang gender, perempuan masih menjadi korban lebih banyak ketimbang laki-laki.
Dalam laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tercatat bahwa per tahun 2025 ada 26.367 jumlah kasus kekerasan seksual yang masuk dalam laporan. Dengan rincian 22.541 korban perempuan dan 5.570 korban laki-laki.
Merujuk data ini dapat kita pahami bahwa dalam masyarakat yang patriarkal masih melihat perempuan sebagai pihak yang lebih lemah, alih-alih sebagai subjek penuh kehidupan. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan.
Kemudian dimensi disabilitas. Dimensi ini, melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang lebih mudah untuk dimanipulasi. Dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan bisa melawan atau mengungkap kekerasan seksual yang menimpanya. Dalam pandangan ableisme, penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai individu yang tidak memiliki kontrol penuh atas tubuh dan suaranya.
Maka dengan pandangan itu lahirlah asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melaporkan atau bahkan menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan. Asumsi ini yang kemudian membuat penyandang disabilitas kurang, bahkan tidak diperhatikan haknya dalam perlindungan hukum.
Antara Status Sosial, Keterbatasan Teknologi, dan Akses terhadap Keadilan
Selain dimensi gender dan disabilitas, status sosial juga menjadi peran penting dalam proses memperjuangkan keadilan untuk Arini. Arini dan ayahnya bukan hanya menghadapi sistem yang mengabaikan korban perempuan penyandang disabilitas, tetapi juga menghadapi ketimpangan akses keadilan.
Hal ini terbukti ketika aparat tidak responsif dan hanya memandang remeh apa yang Arini alami. Mereka enggan memproses hukum dengan alasan tidak adanya polisi wanita. Bisa saja ini menjadi lain cerita jika Arini berangkat dari kelas sosial menengah keatas. Aparat akan lebih sigap memprosesnya.
Dimensi lain yang menjadi hambatan adalah Arini belum memiliki akses penuh terhadap teknologi digital. Dalam ceritanya, Arini menyebutkan bahwa ia membuka media sosial di gawai temannya ketika berkenalan dengan Puji, karena ia tidak memiliki gawai sendiri.
Barangkali jika Arini telah memiliki akses penuh dalam bermedia sosial, kemudian dia speak up, keadilan akan lebih cepat ia dapatkan. Karena akhir-akhir ini kita banyak menemui, aparat akan lebih cepat memproses kasus-kasus jika telah viral di media sosial. No viral, no justice.
Dari kasus Arini, kita dapat mempelajari bagaimana pentingnya memahami suatu kasus dengan konsep interseksionalitas. Melihat identitas yang multidimensi, yakni gender, disabilitas, dan status sosial bukan sebagai identitas yang terpisah. Tetapi identitas yang saling silang hingga dapat menimbulkan kerentanan yang berlapis-lapis. Maka, memperjuangkan keadilan dan perlindungan yang setara bagi semua individu, penting untuk mempertimbangkan berbagai dimensi identitas dalam dirinya. []