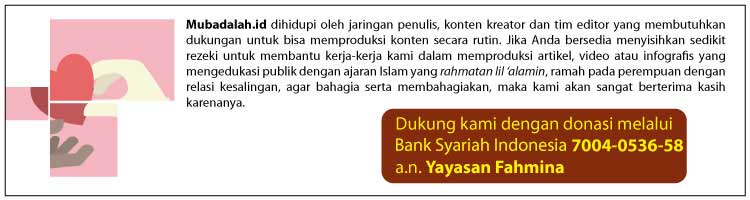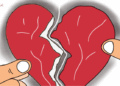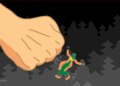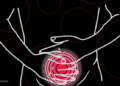Mubadalah.id – Salah satu indikator kualitas hidup di sebuah negara bukan hanya terletak pada gedung-gedung pencakar langit atau kecepatan internetnya, tapi pada bagaimana negara tersebut memperlakukan warganya yang paling rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Di titik ini, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah. Dan jika mau jujur, tak perlu menengok jauh-jauh ke Skandinavia untuk belajar soal isu disabilitas. Cukup tengok tetangga sendiri, Malaysia. Ya, kita perlu belajar dari Malaysia.
Statistik yang Bikin Terdiam
Jumlah penyandang disabilitas di Malaysia sekitar 640 ribu jiwa. Pemerintah Malaysia mengalokasikan anggaran sebesar RM1,25 miliar atau sekitar Rp4,1 triliun untuk mendukung kelompok ini. Itu artinya, satu penyandang disabilitas “di-backup” negara dengan dana sekitar Rp6,4 juta per tahun.
Bandingkan dengan Indonesia: 23 juta jiwa penyandang disabilitas, tetapi hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar. Ini bukan salah ketik. Rp3 miliar. Kalau dibagi rata, artinya satu orang hanya mendapat sekitar Rp130 per tahun, lebih murah dari ongkos parkir.
Ini bukan sekadar angka. Ini gambaran dari prioritas negara. Anggaran adalah cermin dari keberpihakan. Dan dari cermin ini, kita bisa bertanya dengan getir: apakah Indonesia sungguh-sungguh menganggap penyandang disabilitas sebagai bagian penting dari warganya?
Tunjangan dan Bantuan yang Terstruktur
Malaysia memiliki skema yang jelas dan terstruktur. Difabel yang bekerja berhak atas tunjangan EPOKU (Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya) sebesar RM450 per bulan. Bagi difabel yang tidak bisa bekerja, tersedia bantuan RM150 per bulan. Mahasiswa penyandang disabilitas bisa menerima bantuan pendidikan dan biaya hidup hingga RM5.000 per tahun.
Sementara itu di Indonesia, bantuan seperti ini terasa sporadis dan penuh ketidakpastian. Banyak kisah soal warga yang mengajukan alat bantu dengar, tapi tidak kunjung menerima meski sudah dua tahun menunggu. Bahkan ada kasus bantuan kursi roda justru dikirim ke warga tunanetra, salah sasaran yang menandakan sistem pendataan dan distribusi kita masih sangat berantakan.
Lebih menyedihkan lagi, ada kasus di mana seorang difabel yang sebelumnya rutin menerima bantuan sosial, tiba-tiba berhenti tanpa alasan yang jelas. Saat ditanya ke dinas sosial, jawabannya hanya “masih dalam proses.”
Delapan bulan kemudian, prosesnya belum juga rampung. Dalam sistem, namanya masih tercantum sebagai penerima. Namun bantuannya tak kunjung datang. Dana bantuan seperti menguap di udara, atau mungkin tersedot ke arah yang tak pernah sampai pada yang berhak.
Pajak dan Insentif: Malaysia Lebih Peka
Di Malaysia, membeli alat bantu disabilitas bisa diklaim sebagai tax relief. Artinya, warga negara yang difabel atau keluarga yang merawat difabel bisa mendapatkan potongan pajak karena pengeluaran ini. Fakta Ini bukan hanya soal insentif ekonomi, tapi bentuk nyata pengakuan negara terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
Di Indonesia? Tak banyak insentif semacam ini. Kalau pun ada, belum kita ketahui secara luas dan sangat jarang diterapkan secara efektif. Seringkali warga malah harus membayar mahal untuk fasilitas atau alat bantu, tanpa subsidi atau keringanan sedikit pun.
Layanan Publik: Infrastruktur vs Praktik
Kalau hanya melihat papan petunjuk braille di halte atau elevator di gedung pemerintahan, mungkin kita bisa bilang: “Oh, Indonesia sudah ramah difabel.” Tapi coba tanya pengalaman nyata dari pengguna kursi roda atau teman Tuli.
Banyak dari mereka mengatakan bahwa layanan publik kita masih belum benar-benar inklusif. Fasilitas ada, tapi tidak terawat. Pendampingan ada, tapi tidak ramah. Bahkan sering kali, penyandang disabilitas diperlakukan seolah-olah mereka beban.
Cerita lain datang dari Malaysia. Saat seorang ibu pengguna kursi roda transit di bandara, staf bandara langsung memberi prioritas penuh. Bahkan ketika anaknya salah antre paspor, petugas langsung minta maaf karena tidak menyadari keberadaan kursi roda. Bandingkan dengan di Indonesia, di mana kadang penyandang disabilitas harus memohon-mohon bantuan, atau lebih buruk lagi: dianggap mengganggu antrean.
Penting untuk kita tegaskan: ini bukan soal kasihan. Kita harus berhenti memandang difabel sebagai objek belas kasihan. Mereka bukan “yang kurang beruntung” yang butuh sedekah. Mereka adalah warga negara yang sah, yang punya hak setara untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat.
Inklusi bukan berarti “boleh ikut asal tidak merepotkan.” Inklusi berarti “harus ada, dan diberi ruang yang setara.” Dalam banyak kesempatan, Indonesia masih gagal memahami prinsip ini. Seolah-olah, cukup dengan menambahkan ramp di pinggir gedung, maka semua masalah selesai. Padahal inklusivitas bukan cuma soal fisik, tapi soal cara pikir, budaya, dan sistem.
Birokrasi Tanpa Hati
Kisah tragis lainnya, seorang yang semula menerima bansos tiba-tiba tidak mendapatkannya lagi. Setelah delapan bulan menghubungi dinas sosial, jawabannya masih, “dalam proses.” Padahal, dalam sistem, namanya masih tercatat sebagai penerima. Lalu, ke mana uangnya? Atau jangan-jangan, dana tersebut menguap ke kantong yang lain?
Ironisnya, para pejabat kita malah sibuk memperkaya diri. Lihat saja berapa anggaran untuk fasilitas mewah anggota DPR atau pejabat kementerian. Saat difabel masih berjuang mendapatkan bantuan kursi roda atau alat bantu dengar, para elite sibuk naik mobil dinas baru dan rapat di hotel berbintang.
Isu ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal kemauan. Mau tidak negara ini mengakui bahwa difabel bukan beban, tapi bagian dari bangsa yang harus kita beri hak setara? Bahwa inklusivitas bukan berarti “boleh ikut asal tidak merepotkan”, melainkan berarti “harus hadir sebagai bagian dari sistem”?
Kita perlu belajar dari Malaysia, bukan hanya dari segi kebijakan, tapi dari nilai yang diusung mengenai empati. Di sana, difabel tidak dipandang sebagai penghalang pembangunan. Mereka dipandang sebagai warga negara penuh yang berhak atas pendidikan, pekerjaan, dan martabat.
Saatnya Kita Serius
Indonesia perlu meninjau ulang seluruh pendekatan terhadap isu disabilitas. Mulai dari pendataan yang benar, sistem bantuan yang transparan, hingga pelayanan publik yang sungguh-sungguh ramah dan empatik. Ini bukan soal kasihan. Ini soal keadilan.
Setara mungkin fana. Tapi bukan berarti tak bisa kita perjuangkan. Mari mulai dari sini, dari keberanian untuk mengkritik, dari kejujuran untuk bercermin, dan dari kemauan untuk berubah.
Jika Malaysia bisa, mengapa kita tidak? []