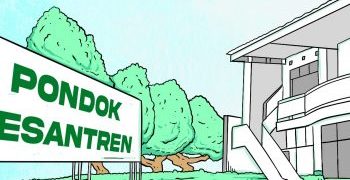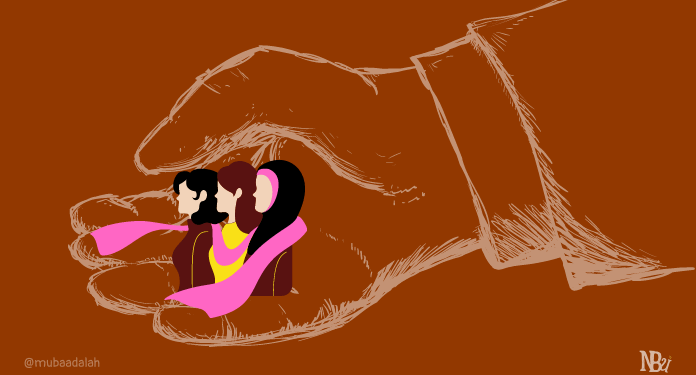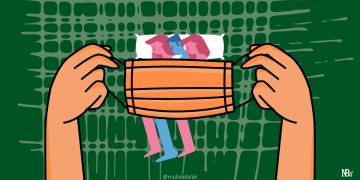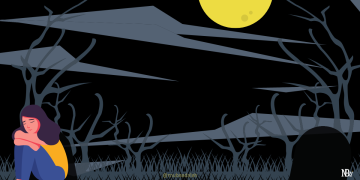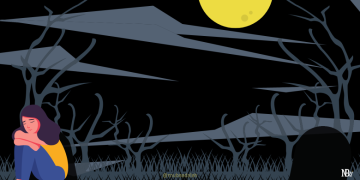Mubadalah.id – Sahnya UU TPKS tampaknya tidak memberi efek jera terhadap predator-predator kejahatan seksual. Bagaimana tidak, kasus kekerasan seksual yang bermula dari budaya seksisme ini kian mengkhawatirkan. Tidak hanya melibatkan kalangan masyarakat biasa. Bahkan juga melibatkan oknum-oknum dari institusi yang seharusnya memberi perlindungan dan bantuan kepada masyarakat.
Kasus pemerkosaan yang pelakunya merupakan oknum dokter di RSHS Bandung. eks Kapolres Ngada NTT yang memperkosa anak di bawah umur bahkan menjual vidionya di website pornografi luar negeri. Akademisi yang melakukan pelecehan seksual. kasus-kasus kekerasan seksual lainnya yang melibatkan institusi agama hingga kasus femisida yang kian berlalu lalang.
Tagar Indonesia darurat pelecehan seksual pun ramai bersiliweran. Harusnya ini menjadi peringatan besar bagi kita semua. Bahwa di mana pun, kapan pun dan siapa pun bisa menjadi korban kekerasan seksual.
Hadirnya undang-undang TPKS menjadi angin segar bagi kita semua bahwa adanya payung hukum yang berpihak terhadap korban. Tetapi penegakan hukum tanpa lingkungan sosial yang berperspektif gender jelas tidak memberi efektifitas nyata dalam memperjuangkan ruang ramah dan aman untuk bersama.
Ngomong-ngomong soal kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan rantai kekerasan tertinggi femisida dan kekerasan seksual. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini?. Ya, kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan ruang ramah dan aman bagi bersama.
Kita semua bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan dan kita semua bertanggung jawab untuk membangun sistem sosial yang berpihak terhadap korban. Aku, kamu, kalian, mereka, pemerintah, pelayan publik dan semuanya bertanggung jawab untuk itu.
Ketika Data Berbicara
Bicara Kekerasan seksual akan selalu menjadi topik yang aktual. Bagaimana tidak, kasus yang terjadi hampir setiap saat ada bahkan mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Mengutip data dari catahu komnas perempuan ada sekitar 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024.
Angka ini mengalami kenaikan signifikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 dengan angka 401.975 kasus. Berdasarkan bentuk kekerasannya persentase kekerasan seksual mencapai 26,94%, kekerasan psikis 26,94%, kekerasan fisik 26,78% dan kekerasan ekonomi 9,84%.
Merujuk pada ringkasan eksekutif komnas perempuan yang rilis pada 8 Maret 2025, data dari mitra catahu, kekerasan seksual menjadi kekerasan tertinggi yang diadukan yang menembus angka 17.305 kakus, kemudian kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565.
Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.
Tingginya kasus kekerasan yang menimpa perempuan terutama kekerasan seksual menunjukkan substansi hukum saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Bicara pencegahan kekerasan seksual Kita harus melihat akar permasalahan lebih jauh mengapa kekerasan seksual terus terjadi.
Dalam bukunya Luka-luka Linimasa, Kalis Mardiasih menjelaskan bahwa kekerasan seksual yang terjadi secara terang-terangan tidak terjadi begitu saja secara tiba-tiba.
Piramida Kekerasan Seksual
Ada fenomena menarik di mana kekerasan ini membentuk piramida dengan dasarnya normalisasi atau pewajaran perilaku merendahkan. Ini bisa kita lihat dalam candaan yang bernuansa seksisme. Jika kita masih menganggap candaan yang merendahkan orang lain sebagai hal yang lucu. Inilah titik kita sedang menormalisasi kekerasan dalam hal yang paling abstrak.
Tingkatan kedua dari piramida ini adalah merendahkan tubuh atau seksualitas orang lain yang ini mencakup pelecehan seksual. Misalnya catcalling atau pun penyebaran konten seksual tanpa persetujuan dan lain sebagainya. Lalu puncak tertinggi dari piramida kekerasan seksual itu sendiri adalah kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan seperti pemerkosaan.
Normalisasi candaan dengan nuansa budaya seksisme menjadi salah satu akar kekerasan seksual, karena hal ini akan membentuk budaya yang mentoleransi pelecehan dan meremehkan pengalaman korban.
Ketika komentar atau lelucon yang merendahkan perempuan dianggap wajar atau bahkan lucu, maka batas antara interaksi yang pantas dan tindakan yang melanggar semakin kabur. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan berbasis gender.
Candaan seksis, misalnya, kerap kita anggap hal sepele. Kalimat seperti “dasar perempuan, baperan” atau “pantes jadi sekretaris, cantik sih” mungkin terdengar biasa. Tapi justru dari situ bibit kekerasan mulai tumbuh.
Ketika masyarakat mentolerir dan menertawakan lelucon yang merendahkan, mereka secara tidak sadar sedang menyuburkan kultur yang membungkam pengalaman korban dan membenarkan dominasi satu gender atas gender lainnya.
Seksisme: Sistemik dan Mengakar
Budaya seksisme tidak berhenti pada candaan. Ia menjelma dalam berbagai bentuk: dari peraturan berpakaian yang hanya menyasar perempuan, cara media membingkai berita kekerasan seksual, hingga sistem pendidikan yang minim edukasi soal kesetaraan dan relasi kuasa. Semua ini adalah bagian dari seksisme yang sistemik.
Ketika perempuan menjadi korban, pertanyaan pertama sering kali adalah “dia pakai baju apa?”, “kenapa pergi malam-malam?”, atau “kenapa tidak melawan?”. Sementara pelaku justru sering terlindungi, dicarikan alasan, bahkan dimaklumi karena “khilaf”, “laki-laki wajar”, atau “dia punya masa depan”.
Seksisme juga tampak dalam minimnya ruang aman untuk menyuarakan kekerasan. Banyak korban tidak melapor karena takut disalahkan, direndahkan, atau dianggap mempermalukan keluarga. Dalam banyak kasus, institusi pendidikan atau tempat kerja malah memilih bungkam atau berdamai demi menjaga “nama baik”. Akibatnya, korban terpaksa menanggung luka sendirian, sementara pelaku bebas mengulang pola kekerasannya.
Perlu kita sadari bersama bahwa kekerasan seksual bukan hanya soal satu pelaku yang harus kita hukum, tapi sistem yang perlu kita benahi. Bukan hanya soal korban yang butuh perlindungan, tapi soal masyarakat yang perlu berani menyuarakan ketidakadilan. Dan tentu, bukan hanya soal pengesahan Undang-undang TPKS, tapi soal perubahan budaya yang harus kita perjuangkan bersama. []