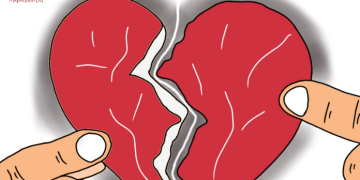Mubadalah.id – Lagi dan lagi, kasus kekerasan seksual kembali terjadi di pesantren. Polresta Pati menerima aduan terjadinya pelecehan seksual oleh seorang oknum pimpinan pesantren di Kecamatan Jakenan, Pati, pada Sabtu (2/8/20205).
Pesantren sebagai tempat aman bagi kasus pelecehan seksual seakan telah menjadi lagu lama. Apakah sebenarnya pokok penyebab masalah klasik ini?
Bila ditelisik, akarnya tak lain ialah dhawuh kiai. Dhawuh, atau yang mungkin bisa dimaknai sebagai instruksi (order), merupakan terma yang sangat lazim ditemui di dunia pesantren.
Siapa saja yang pernah merasakan didikan pesantren pasti tak asing dengan kata ini. Ushul fiqh barangkali menempatkan dhawuh sebagai perintah (amr).
Sementara, menurut kaidah, amr berarti suatu kewajiban yang berasal dari seseorang dengan derajat lebih tinggi kepada seorang yang berposisi lebih rendah (from the sublime to the ridiculous).
Ringkasnya, ada kecenderungan “memaksa” dan “subordinatif” di dalam dhawuh.
Posisi dhawuh kiai
Sebagai institusi yang sentralistik, dhawuh kiai menduduki posisi paling sublim, kompulsif, sekaligus subordinatif di lingkungan pesantren. Hampir-hampir, tak akan pernah ada kata “tidak” untuk dhawuh kiai macam ini.
Berbekal dominasi dan sentralitas kuat dalam mengontrol segala kehidupan santri, seorang kiai dapat memberikan dhawuh apa saja—mestinya hal yang baik saja—kepada para santrinya.
Tentu, belum ada sejarahnya—dan mungkin tak akan pernah ada sejarahnya—santri membilang “emoh” terhadap dhawuh tadi.
“Apalagi sampai mendemo—wujud penolakan, ke-emoh-an—seperti di kampus-kampus,” ujar seorang Gus yang juga politisi sebuah partai hijau.
Adopsi prinsip agama
Sebagai sebuah ketaatan, semestinya tak ada yang salah dari prinsip order maupun acceptance dari sebuah dhawuh. Terlebih, agama yang dogmatis juga berakar dari dhawuh Tuhan.
Tuhan merupakan sosok the most sublime yang punya citra ideal untuk memberi dhawuh sebagai guideline kehidupan bagi “domba-domba-Nya” di muka bawana.
Dhawuh-Nya itu lantas mengalami ramifikasi menjadi larangan (nahy) dan anjuran (nafl). Praktik yang berlangsung di pesantren selaku lembaga pendidikan keagamaan sedikit banyak mengadopsi model dhawuh tuhan ini.
Peran tuhan selaku order giver beralih tangan ke lengan kyai, sementara nasib order receiver bersalin tangan kepada santri atau anak didik. Praktis, jelas gamblang bagaimana subordinasi itu bekerja.
Paradigma profetik pasif
Interpretasi dhawuh sebagai sumber penggerak dalam melakukan tindakan biasanya berakar dari pandangan pasifisme profetik. Nabi Muhammad SAW beroleh posisi sebagai figur pasif yang selalu menanti wahyu.
Ia senantiasa submisif kepada wahyu dalam mengambil setiap tindakan seremeh-temeh apapun. Wahyu (inspiration) yang bersumber dari Sang Pewahyu, yakni Allah SWT, merupakan order tertinggi yang berdiri sebagai pedoman yang mengikat sekaligus final.
Terlebih, Ummul Mukminin Sayyidatina ‘Aisyah r.a. menyebut kepribadian sang Nabi juga sebagai wahyu. Putri Abu Bakar Ash Shiddiq ini berujar “Kana khuluquhu al Quran”—perangai sang Nabi ialah Quran.
Kritik paradigma
Paradigma yang demikian jelas problematis. Menempatkan Nabi sebagai sosok pasif tanpa intuisi dan inisiatif berarti secara tidak langsung telah mencerabut sosok Nabi dari sisi kemanusiaannya (basyariah).
Nabi Muhammad SAW, sebagaimana umat Islam meyakinkininya, memang sosok yang ekstraordinari (khash). Menurut kaidah ushul fiqh, sesuatu yang ekstraordinari berarti tunggal.
Namun, sekalipun Nabi bersifat khash, ia tetaplah manusia yang semestinya juga menyandang sesuatu yang umum menyemat pada manusia biasa (ordinary people).
Sebagaimana kabar sejarah, perlu pengakuan jujur bahwa Nabi pernah berbuat salah, luput, dan khilaf selaku insan yang mahal al khatha’ wa an nisyan. Misalnya saja, Sang Nabi sempat beroleh teguran lewat Surat An Naba’ ayat 1.
Setidaknya, perihal ke-ordinari-an Nabi bisa ditinjau pada ayat terakhir Surat Al Kahfi. Allah SWT memerintahkan sang Nabi untuk mengabarkan tentang ke-ordinari-annya bersama ke-ekstraordinari-annya.
Kurang lebih, ayat itu memungkinkan untuk beroleh arti begini, “Kabarkanlah, wahai Muhammad! Sesungguhnya aku ini hanyalah orang sejenis kalian yang diistimewakan oleh wahyu yang disampaikan kepadaku…”
Pendeknya, Nabi dalam konteks sosial, bukanlah sosok yang over-extraordinary. Ia tetaplah manusia, sekalipun tak seperti manusia kebanyakan (basyar laa kal basyar).
Nabi bukan seorang pasifis yang sekadar menanti wahyu. Ia tetap menggunakan kemanusiaannya untuk menyikapi segala realitas kehidupan. Sementara Nabi merupakan figur yang terjaga (ma’shum), kita sekalian adalah sebaliknya.
Lantas, apakah kita akan bersikap lebih otoritatif dengan dhawuh-dhawuh ketimbang Sang Nabi? []